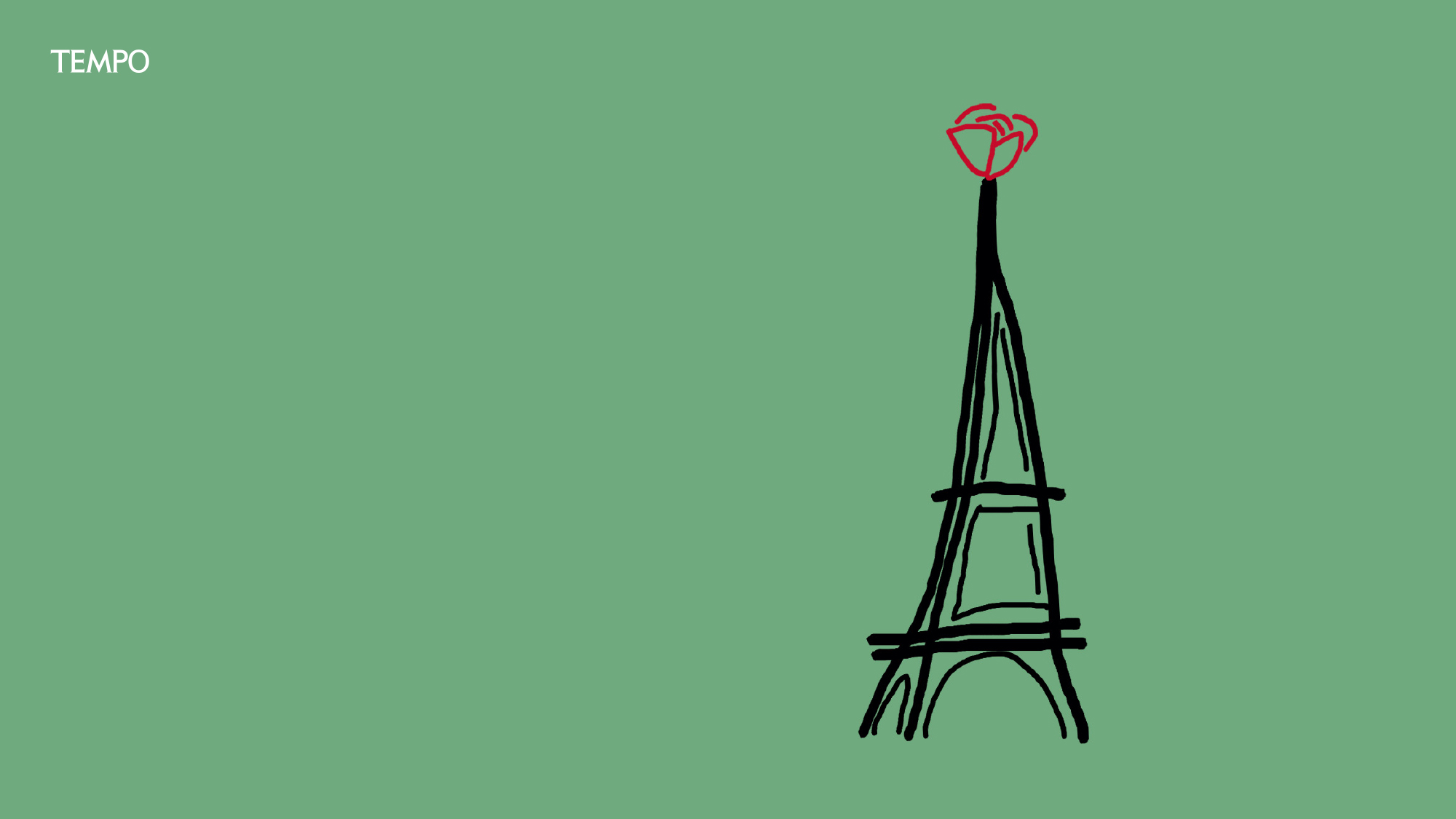Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
RAMBUT gondrongnya biasa dijepit rapi dan ditutup topi rimba. Ia pun menyandang tas punggung dan berpakaian senyaman mungkin untuk mencari nisan-nisan dan kompleks permakaman. Bukan makam dan nisan biasa, pencariannya diarahkan ke nisan makam kuno orang keturunan Tionghoa. Berbekal peta kuno Belanda atau informasi yang diperoleh dari koleganya, ia akan mengunjungi suatu permakaman.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kebahagiaan besar bila ia berhasil menemukan makam dan nisan-nisan yang diinginkan. Kadang ia harus menerobos semak belukar yang menutupi makam dan nisan atau blusukan ke tempat permakaman umum hingga masuk gang-gang dan rumah orang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Philipus Dellian Agus Raharjo akrab dipanggil Pippo Agosto. Biasanya ia akan blusukan mencari nisan atau makam-makam kuno Tionghoa di sekitar Semarang bersama sahabatnya, Bram Luska. Jika menemukan makam yang diinginkan, mereka akan membersihkan, mencatat, dan mendokumentasikannya. Tak lama kemudian biasanya ia akan mengunggah temuan tersebut di media sosial.
Pippo boleh dikatakan sebagai detektif makam kuno Tionghoa. Dia mulai aktif blusukan tiga tahun lalu. Aktivitasnya ini berawal dari ketidaksengajaan. Saat itu ia sedang mengunjungi mausoleum atau ruang permakaman keluarga Thio Sing Liong, warga Semarang yang memiliki usaha ekspor-impor. Mausoleum itu berada di Jalan Sriwijaya, Kota Semarang. Makam di dalamnya berbalut marmer utuh yang didatangkan langsung dari Genoa, Italia.
Menurut Pippo, makam keluarga itu tergolong baru. Dia memperkirakan makam dibangun pada abad ke-20. Kondisinya juga megah dan terawat karena keturunan keluarga yang dikebumikan di sana masih ada. "Waktu itu saya belum mencari makam kuno. Hanya jalan-jalan lihat makam yang unik," tuturnya.
Pippo lantas mengunggah kunjungannya di mausoleum itu di media sosial. Unggahannya tersebut kemudian mempertemukan Pippo dengan Bram Luska. Bram meminta Pippo menemaninya kembali mengunjungi mausoleum tersebut.
Saat itu Bram mengatakan menemukan batu nisan bertulisan aksara Cina di Tlogorejo, Kota Semarang. Bram lalu meminta Pippo mengidentifikasi batu nisan temuannya tersebut. "Karena dia tidak bisa membaca, saya yang diminta membacanya," ucap Pippo kepada Tempo, Kamis, 23 Februari lalu.
Dari situlah kemudian keduanya rutin berburu, blusukan mencari makam tua di Kota Semarang. Aktivitas itu rutin dilakukan hampir setiap pekan di sela-sela kesibukan Pippo mengajar privat semua mata pelajaran untuk siswa sekolah dasar-sekolah menengah pertama dan bahasa Jepang untuk siswa sekolah menengah atas. Mereka pun mendatangi sejumlah wilayah berdasarkan peta lawas zaman Belanda atau informasi yang mereka miliki dari budayawan Tionghoa bernama Irawan. Sejumlah daerah pernah mereka datangi, seperti wilayah Semarang barat di Kelurahan Simongan sekitar Kelenteng Sam Poo Kong. Sementara itu, di wilayah Semarang timur, mereka mengunjungi Kedungmundu.
Selama hampir tiga tahun berburu, Pippo mengaku telah menemukan ratusan makam kuno. "Kalau bong atau makam hampir seratus. Kalau bongpay atau batu nisan lebih dari seratus," ujarnya. Makam itu dia temukan di pinggir jalan, perkampungan, permakaman tua, dan lainnya.
Ia tertarik menelusuri jejak nisan-nisan kuno ini karena penasaran mengetahui sejarah para leluhur keturunan Tionghoa yang tinggal dan meninggal di Semarang. Dari tulisan di nisan, Pippo mengetahui kapan mereka dimakamkan serta marga yang mengindikasikan dari dinasti apa dan dari mana mereka berasal. Ia menduga mereka yang dimakamkan ini adalah para pendatang yang merupakan loyalis Dinasti Ming yang melarikan diri karena situasi pergolakan sosial-politik di negerinya.
Pippo mengatakan kemampuannya membaca aksara Cina berawal ketika ia duduk di bangku kuliah. Saat mengenyam pendidikan teknobiologi di Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, dia banyak membaca buku berbahasa Jepang. "Waktu saya kuliah biologi ada dosen memberi materi dari buku Jepang. Mau tak mau saya harus kursus," katanya.
Sunguh kebetulan, huruf-huruf di nisan masih bergaya tradisional sehingga memudahkannya membaca dan mengidentifikasi informasi pada bong dan bongpay tersebut. "Jadi belum disederhanakan. Itu sama persis dengan kanji Jepang, cuma cara bacanya yang beda," ucap pria yang juga mengajar di Sanggar Bocah, sebuah sanggar belajar menggambar, ini.
Ia menjelaskan, nama Pippo Agosto ia sandang bukan karena fan pemain sepak bola Italia, Filippo Inzhagi. Ia mengaku senang sepak bola, tapi tidak terlalu fanatik. Nama itu ia dapat karena dulu pernah belajar sebentar di Serikat Misionaris Xaverian yang kebanyakan pastornya dari Italia.
Nama Pippo Agosto sebenarnya hanya sebutan di media sosial. Berasal dari nama Philipus Dellian Agus Raharjo, Philipus menjadi Filippo, lalu dalam bahasa sehari-hari menjadi Pippo. “Agus jadi Agosto,” katanya. Pria ini mengatakan, selama blusukan di makam kuno, ia tak mempedulikan hal-hal aneh atau mistis. Ia justru merasakan ada keunikan makam kuno di Bergota yang ternyata tidak dimuat dalam peta zaman Hindia Belanda. “Saya tanyakan juga kepada Profesor Claudine Salmon, tapi belum ada jawaban,” tuturnya.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo