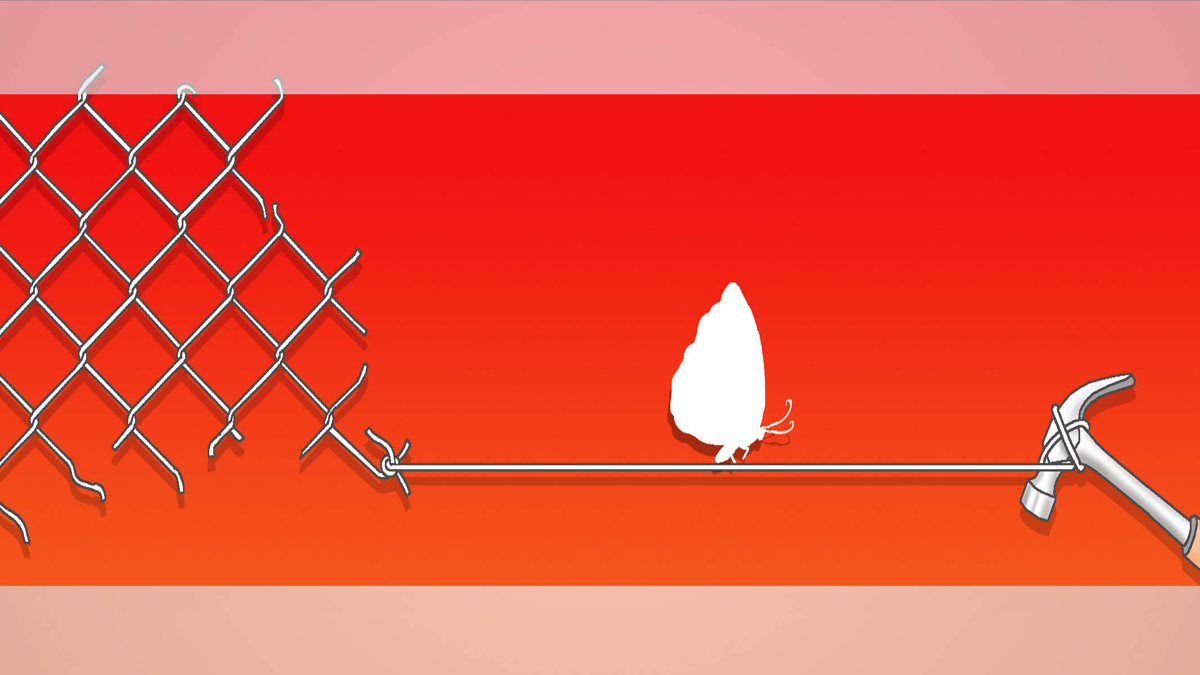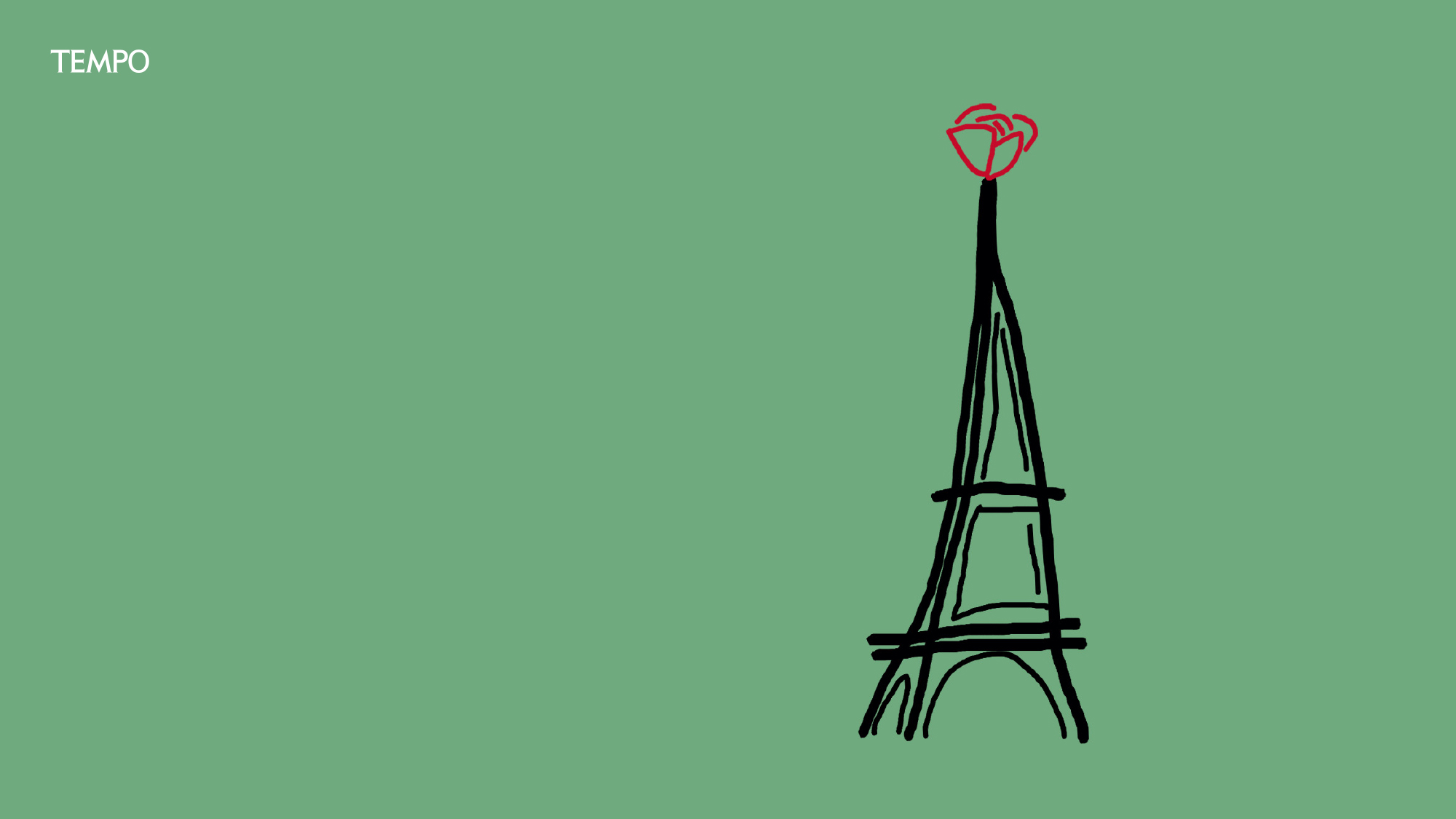Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Gerwani dikecam karena tak mengkritik poligami Presiden Sukarno.
Ada dilema dalam gerakan perempuan dengan kompromi politik.
Banyak aktivis yang belum memahami politik nasional 1965.
SELAIN badan-badan propaganda Angkatan Darat, pihak yang dengan segera memvonis Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) terlibat dalam aksi kejam terhadap para jenderal di Lubang Buaya justru Kongres Wanita Indonesia (Kowani). Belum tuntas pemerintah Sukarno melakukan investigasi terhadap Gerakan 30 September (G30S) pada 29 Oktober 1965, Majelis Permusyawaratan Kowani sudah mengeluarkan Gerwani dari keanggotaan organisasi payung tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Keputusan ini diikuti dengan pemecatan Hurustiati Subandrio sebagai Ketua Koordinator Kowani sekitar Maret 1966. Alasan yang dikemukakan Kowani, setelah Surat Perintah Sebelas Maret terbit, suami Hurustiati, Wakil Perdana Menteri Subandrio, juga dianggap terlibat dalam G30S sehingga ia ditahan bersama sejumlah menteri dalam Kabinet Dwikora. Permufakatan Kowani dengan tentara makin bulat ketika Mayor Jenderal Soeharto hadir dalam pembukaan kongres luar biasa organisasi tersebut pada 30 Mei 1966 dan menyampaikan pidato arahan untuk meraih dukungan penuh kaum perempuan dalam menegakkan pemerintah Orde Baru.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sejak kapitulasi Kowani kepada tentara, jejak berharga Gerwani dihapuskan dari lintasan sejarah gerakan perempuan. Tak kalah tragis, Kowani pun kehilangan sukma kepeloporannya sebagai badan pengayom organisasi-organisasi perempuan independen dan “rumah aman” bagi para pejuang perempuan nasionalis. Gerwani ditampilkan dalam narasi resmi sebagai organisasi siluman yang tak jelas asal-usulnya. Para aktivis pendirinya diingkari oleh aktivis-aktivis perempuan lain. S.K. Trimurti pun, yang bersahabat dengan sesepuh Gerwani seperti Sri Panggihan dan Umi Sardjono, tidak leluasa menceritakan perjalanannya dengan tokoh-tokoh ini dalam memoarnya. Padahal, dengan Umi, misalnya, ia melahirkan Gerakan Wanita Indonesia Sedar (Gerwis), cikal-bakal Gerwani, dan mendidik kader-kader utamanya dalam Barisan Buruh Wanita sejak zaman kolonial.
Walaupun tidak pernah dinyatakan secara terbuka, dapat diduga bahwa pengingkaran sumbangsih Gerwani terhadap pergerakan perempuan terjadi akibat tekanan luar biasa dan penyebaran ketakutan akan tuduhan “terlibat G30S/PKI”. Di masa operasi penumpasan G30S, tuduhan itu tidak main-main. Taruhannya bisa nyawa atau penghidupan sehari-hari. Namun, kalau kita perhatikan dengan saksama pernyataan-pernyataan para aktivis perempuan yang menghujat Gerwani, kita dapat menangkap bahwa prasangka terhadap Gerwani tidak dibangun di atas bidang kosong. Sepanjang pemerintahan Sukarno memang ada ketegangan dan perselisihan di antara organisasi perempuan. Perbedaan pilihan strategi, rivalitas politik, dan “komunisto-phobia” mewarnai interaksi mereka dengan aktivis-aktivis Gerwani. Persoalannya, pada 1965 terjadi lompatan penyimpulan yang janggal dan fatal dari perselisihan sehari-hari ke hujatan yang mematikan satu pihak.
Salah satu isu yang sering diungkap sebagai pangkal ketegangan Gerwani dengan organisasi perempuan lain adalah penolakan Gerwani mengecam poligami yang dilakukan Sukarno. Gerwani dianggap mengkhianati perjuangan gerakan perempuan untuk menghapus poligami yang berlangsung sejak awal abad ke-20. Sebagian aktivis, terutama dari Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari), menganggap Gerwani terlalu dipengaruhi oleh PKI. Pendapat ini boleh jadi benar karena sejak PKI di bawah pimpinan D.N. Aidit memilih jalan parlementer, Sukarno membantu PKI menghadapi kekuatan-kekuatan antikomunis yang terus berusaha menyingkirkan partai tersebut dan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dengannya.
Tapi, dari perbincangan saya dengan sejumlah aktivis Gerwani, ada soal lain yang membuat mereka enggan berhadap-hadapan dengan Sukarno. Kebanyakan dari mereka lahir dan besar dengan pidato-pidato Sukarno yang tidak pernah alpa menekankan bahwa “wanita Indonesia adalah muka mutlak daripada Revolusi Indonesia” (amanat Presiden Sukarno dalam pembukaan Kongres Kowani X, 24 Juli 1964). Bagi mereka, Sukarno bukan hanya presiden, tapi juga guru yang menumbuhkan rasa berbangsa dan mengajarkan tata cara berwarga negara.
Yang patut diingat, pilihan Gerwani tidak mengecam Sukarno sama sekali tak menyurutkan langkah organisasi ini untuk memperjuangkan Undang-Undang Perkawinan, yang menolak poligami. Demikian pula PKI dan ormas pendukungnya, yang memberlakukan larangan selingkuh dan poligami. Salah satu kisah yang menjadi model adalah Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra tidak segan-segan memecat tokoh ternama seperti penyair A.S. Dharta dan pelukis S. Sudjojono karena poligami.
Bahkan Aidit secara terbuka, dalam perhelatan umum Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia yang juga dihadiri Sukarno, menyatakan poligami telah menghambat kemajuan bangsa. Anehnya, Ketua Perwari Armistiani Soemarno Sosroatmodjo tetap berhubungan erat dengan Sukarno sampai akhir pemerintahannya. Dia menjalankan perintah Sukarno menggalang sukarelawan dan menjadi komandan Tenaga Inti Sukarelawati di Jakarta Raya untuk mendukung operasi Trikora dan Dwikora. Dari ingatan mantan Sekretaris Jenderal Gerwani, Kartinah Kurdi, mereka tetap bekerja sama dengan organisasi-organisasi perempuan lain, termasuk Perwari, sampai “Gestok pecah”.
Saya mengamati aktivis-aktivis perempuan di masa itu sebenarnya tidak asing dengan dilema yang dihadapi Gerwani. Mereka hafal kisah tragis Kartini yang harus memilih antara kecintaan terhadap ayahnya dan kelanjutan cita-cita besarnya. Sejak Kongres Perempuan Indonesia pertama, sumber ketegangan utama antarorganisasi perempuan adalah masalah poligami.
Seperti halnya Gerwani, sebagian dari mereka menolak berhadap-hadapan dengan para patron atau patriark yang sudah memungkinkan mereka berorganisasi sebagai perempuan. Ini bukan pertama kalinya gerakan perempuan harus menjalankan kompromi politik yang menunda kemajuan proyek emansipatoris mereka. Semangat persaudarian (sisterhood) yang hendak mereka bangun melalui sekian banyak kongres dan aksi bersama berulang kali terguncang oleh kebutuhan “politik nasional”. Seandainya operasi militer antikomunis 1965-1966 tidak terjadi, mungkin mereka akan melanjutkan perdebatan tentang pilihan-pilihan strategi yang tepat untuk menjadikan kepentingan perempuan sebagai kepentingan nasional.
Dalam sebuah pertemuan dengan sejumlah mantan aktivis Gerwani dari Jawa Tengah di forum Lingkar Tutur Perempuan di Solo pada September 2005, terjadi diskusi yang hangat dengan aktivis-aktivis feminis masa kini tentang pentingnya memperjuangkan pembebasan perempuan dari belenggu patriarki.
Salah satu tema yang mencuat berkisar pada apa yang dimaksud dengan perempuan berpolitik. Sebagian mantan aktivis Gerwani merasa bahwa mereka sedikit sekali paham tentang yang disebut “politik nasional” di masa mereka aktif. Mereka mempercayai saja pemimpin Gerwani dalam hal penentuan arah kebijakan nasional. Pada akhir diskusi muncul pertanyaan dari mereka, “Seandainya kami lebih paham politik nasional pada 1965, apakah kami akan lebih siap menghadapi gempuran terhadap kami?” Sampai hari ini, pertanyaan tersebut belum terjawab.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo