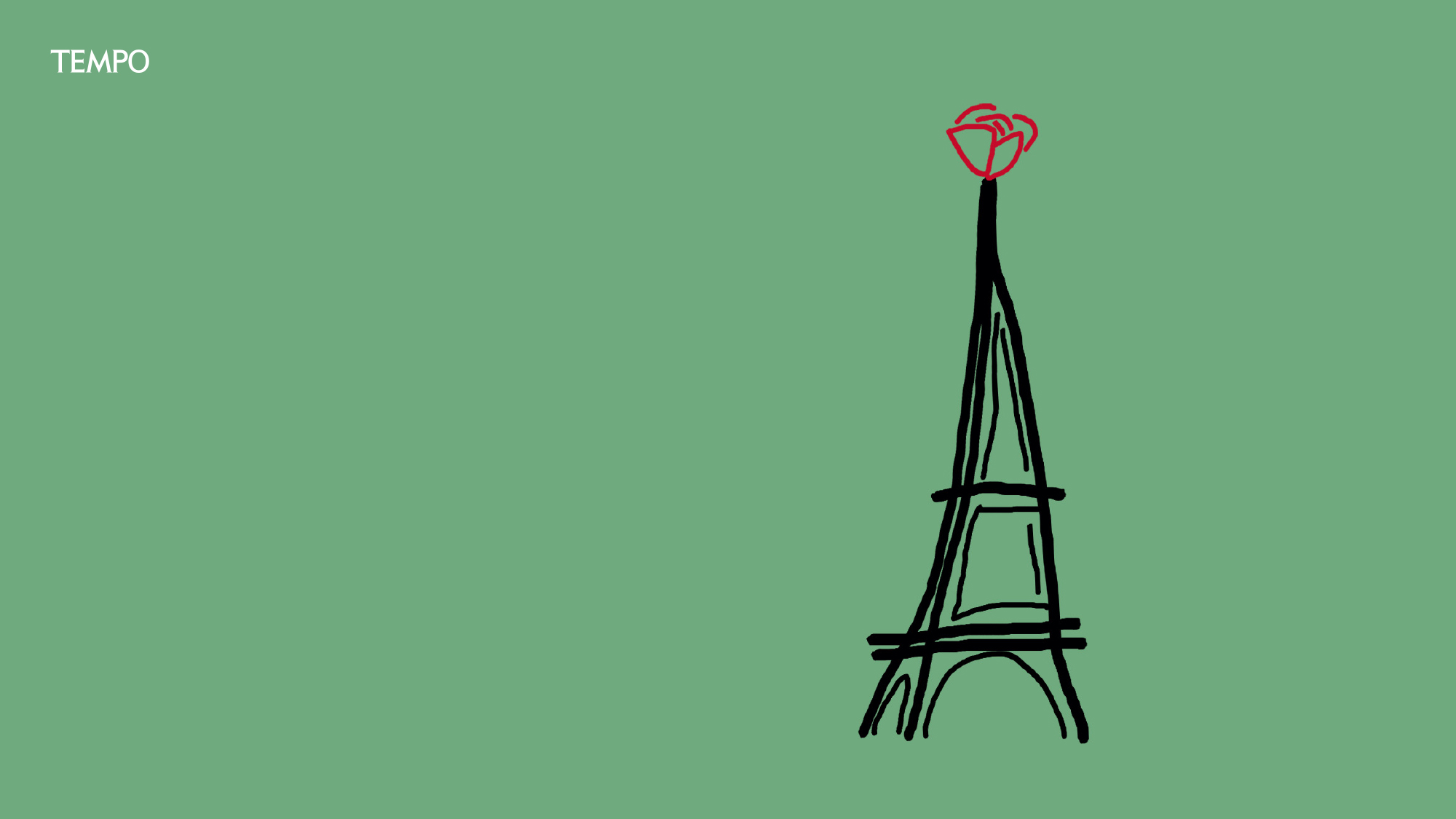Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Wawancara Ayu Utami dengan Lakhdar Brahimi.
Menyoal keberagaman.
Mendorong Bhinneka Tunggal Ika.
DELAPAN puluh tahun silam, Hamid Algadri, kakek Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, berpidato untuk mendukung pembebasan Afrika Utara. Kemerdekaan Indonesia adalah inspirasi bagi negara-negara yang pada 1950-an masih terjajah. Lakhdar Brahimi muda datang ke Jakarta sebagai wakil pelajar muslim Aljazair dan berguru tentang perjuangan kemerdekaan. Kelak ia menjadi diplomat ternama dan utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pelbagai negosiasi perdamaian. Berikut ini petikan wawancara Ayu Utami dengan mantan Menteri Luar Negeri Aljazair tersebut di kediamannya di Paris.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Apa dukungan yang diberikan Indonesia bagi perjuangan Aljazair dulu?
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pada 1953, anggota parlemen Hamid Algadri berpidato meminta pemerintah dan rakyat Indonesia mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa Afrika Utara. Ini bahkan sebelum perang kemerdekaan kami. Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung berdampak sangat besar di seluruh dunia. Di Bandung kami belum jadi anggota, belum merdeka, tapi kami punya perwakilan sebagai pengamat dan memberi pidato juga. Ada satu kalimat dari komunike Bandung, bahwa negara-negara Asia-Afrika mendukung kebebasan bangsa Aljazair. Itu besar sekali dampaknya. Itu mendorong moral bangsa kami, dan membuka mata dunia bahwa sesuatu terjadi di Aljazair. Kemudian Indonesia mengirim senjata, saya kira. Delegasi militer terwujud pada 1960 ke Tunisia dan Maroko untuk mengawasi perbatasan dan melihat bagaimana mereka bisa membantu, dan mereka mengirim beberapa senjata.
Anda melihat hubungan Hamid Algadri dari Partai Sosialis Indonesia dengan Mohammad Roem dari Masyumi. Apakah situasi kebinekaan di Indonesia menginspirasi Anda?
Awalnya perhatian kami terpusat pada problem kami sendiri. Kami sangat gembira dengan inisiatif Hamid Algadri. Suatu panitia dibentuk untuk mendukung Aljazair. Ketuanya Mohammad Natsir dari Masyumi, sekretaris jenderalnya Hamid Algadri, Partai Sosialis, ada Pak Kasimo dari Partai Katolik, dan perwakilan semua partai. Sukarno dan Indonesia secara umum adalah sumber solidaritas di antara negara dan bangsa yang pernah atau masih dijajah.
Adakah nilai-nilai yang Anda simpan dari masa itu sampai sekarang?
Ada banyak sekali hal. Duduk di sini, di posisi kita sekarang, dengan perang di Ukraina, polarisasi yang makin hari makin nyata, saya takjub bahwa rakyat Indonesia tidak menyerahkan dua hal yang sangat penting yang mereka punyai: Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Kamu tahu, lima dasar serta persatuan dalam perbedaan ini adalah yang kita butuhkan sekarang. Itu dimulai di Indonesia, dan dikembangkan menjadi sepuluh prinsip negara Non-Blok. Dunia sangat membutuhkannya. Perpecahan hari ini berbeda, tapi mungkin lebih berbahaya daripada yang terjadi pada 1950-an.

(Dari kiri) Rosihan Anwar, mantan duta besar Aljazair Lakhdar Brahimi, dan mantan Menteri Luar Negeri Ali Alatas, di Jakarta, April 2006. Dok. Tempo/Yosep Arkian
Pada 2000, terbit “Brahimi Report”, dokumen yang dianggap sangat penting dalam operasi pemelihara perdamaian PBB. Apakah Anda puas dengan pelaksanaan rekomendasi laporan itu?
Tidak terlalu. Pertama, laporan itu adalah anak dari kegagalan gawat PBB di Rwanda dan Srebrenika. Di Rwanda terjadi genosida, padahal PBB berjaga di sana. Di Srebrenika, kota kecil di bekas Yugoslavia, Bosnia, 8.000 pemuda dibantai, dan PBB ada di sana. Maka pertanyaannya: apakah PBB sungguh bisa menjadi pemelihara perdamaian, atau haruskah kita berhenti membayangkan peran apa pun dari PBB? Kofi Annan yang punya pemikiran ini. Mulanya ia menerbitkan dua laporan, tentang Srebrenika dan tentang Rwanda. Lalu kami berpikir untuk sedikit menilai ulang bagaimana PBB bisa menjadi lebih baik sebagai pemelihara perdamaian, dan itulah laporan kami. Kami tak menduga bahwa semua orang ternyata menyambutnya. Usaha penerapannya memang sedikit sulit. Tapi jangan lupa, PBB adalah milik anggotanya. Para birokrat melayani pemilik PBB, yakni negara-negara anggotanya.
Indonesia, sejak merdeka, harus memutuskan menjadi negara Islam atau tidak. Indonesia memilih tidak. Tapi tegangan antara Islamisme dan sekularisme selalu merupakan arus bawah. Ini juga terjadi di Aljazair dan kebanyakan negara mayoritas muslim. Apakah tegangan ini akan memudar atau berlanjut di masa depan?
Sangat sulit untuk menganalisis itu dengan layak. Tapi yang saya bisa katakan adalah kita harus mengakui bahwa pandangan ekstrem Islam—“Islam adalah jawaban”—bukan hal baru. Pandangan ini ada dari dulu. Dalam pergolakan kemerdekaan, ada yang berkata bahwa mereka tidak berjuang untuk bendera, mereka berjuang untuk Islam. Tapi saya kira mayoritas muslim, yang taat pada agamanya, tetaplah berkata: kami mau membangun negara modern. Dan saat kami memperkenalkan sosialisme, mereka bilang bagus, kita akan punya sosialisme. Kita harus tidak melupakan itu. Motif solusi Islam itu muncul lagi. Indonesia beruntung, karena ada organisasi Islam yang kuat, yang bersikap moderat: Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Banyak negeri tidak punya kesempatan itu. Saya kira, jika saya bisa kembali ke kenyataan bahwa Indonesia tidak menjual dirinya kepada asing sepenuhnya, saya ingin melihat Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, angkat suara bukan hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri, untuk berkata bahwa inilah Islam.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul "Dunia Membutuhkan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila". Wawancara lengkap Lakhdar Brahimi akan ditayangkan di LIFEs, Jumat, 11 Agustus 2023