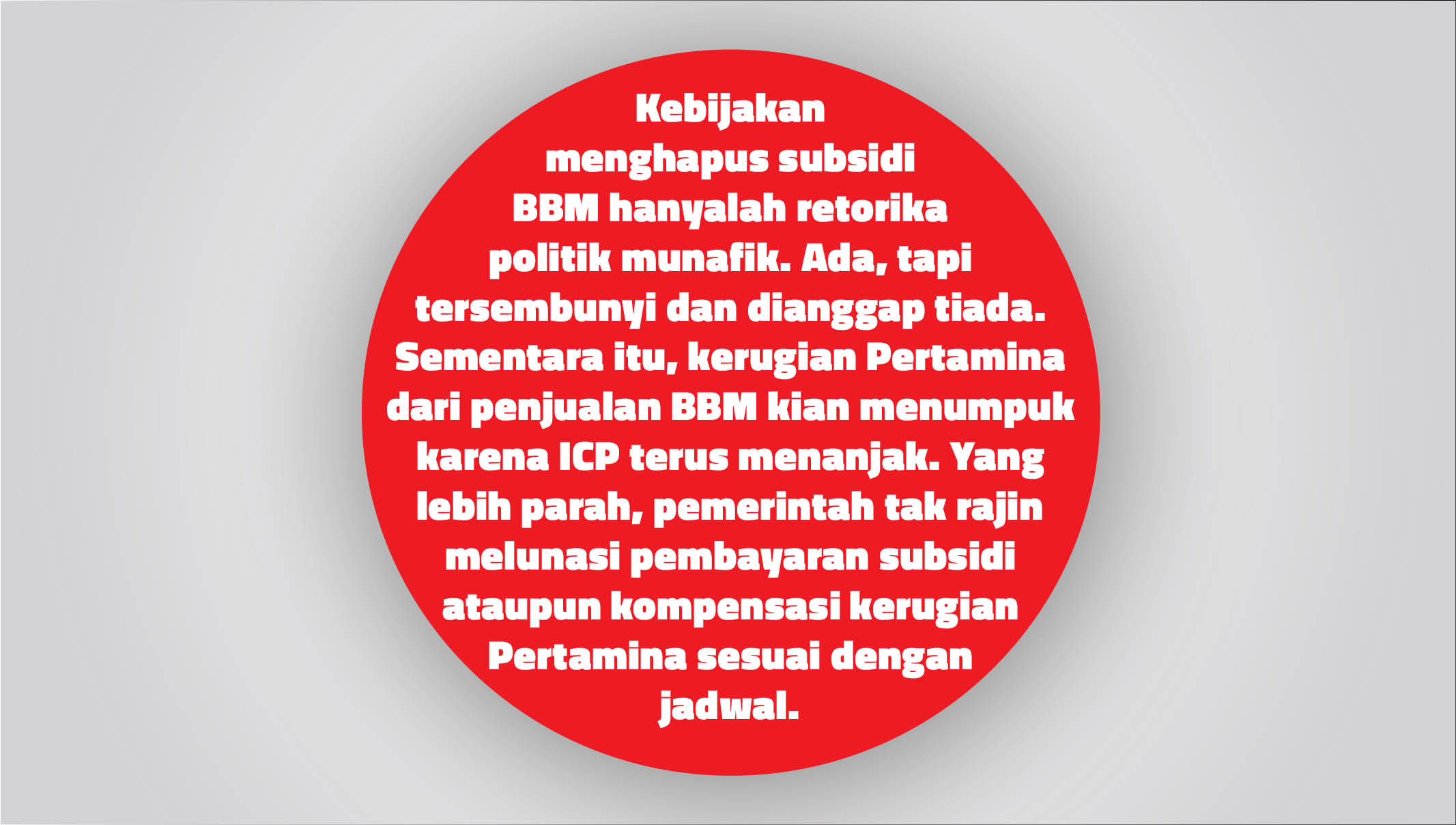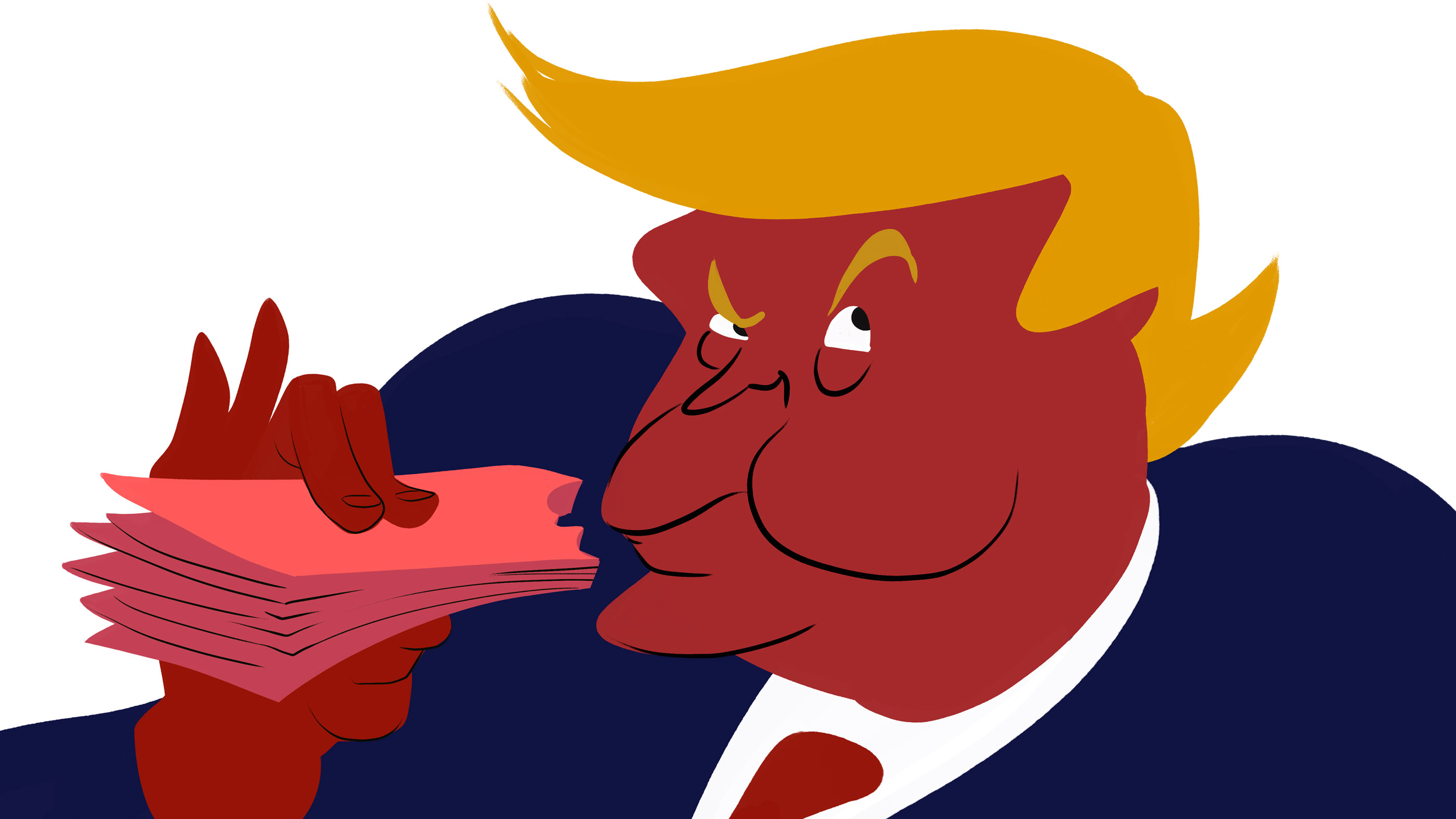Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Harga BBM selalu jadi pemoles wajah kepentingan politik Jokowi.
Kebijakan populis demi citra menyimpan beban triliunan rupiah yang makin menggunung.
Risiko meningkat jika solusi sederhana terus diabaikan.
SYAHDAN, pada 2015, Presiden Joko Widodo mencabut subsidi bahan bakar minyak. Daripada untuk menomboki subsidi yang lebih menguntungkan pemilik mobil pribadi, pemerintah lebih baik memakai uang negara buat keperluan yang lebih mendesak. Banyak orang angkat jempol, memuji kebijakan itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sebetulnya, situasi saat itu memang memungkinkan pencabutan subsidi. Harga minyak sedang murah-murahnya. Sempat bertengger di level US$ 61,86 per barel pada Mei 2015, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian crude price (ICP), yang menjadi patokan harga minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ataupun untuk menghitung harga eceran BBM, terus merosot hingga US$ 27,49 per Januari 2016.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Jadi sebetulnya tanpa subsidi pun harga BBM saat itu sudah murah. Namun politikus yang sedang berkuasa tentu tak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk mendongkrak citra. Mereka gencar memoles kebijakan itu dengan narasi politik yang keren: subsidi dicabut untuk membiayai pelbagai proyek infrastruktur yang lebih bermanfaat buat rakyat.
Narasi itu mulai menghadapi tantangan yang sebenarnya ketika kemudian ICP pelan-pelan merambat naik, terutama semenjak 2019. Karena resminya tak ada lagi subsidi, harga jual BBM seharusnya ikut naik seiring-sejalan dengan kenaikan ICP. Realitasnya, praktis tak ada penyesuaian harga BBM yang berarti. Pemerintah tak pernah mengizinkan PT Pertamina (Persero) menaikkan harga eceran BBM untuk transportasi sesuai dengan harga pasar. Singkat kata, Pertamina harus menjual BBM dengan menanggung rugi.
Begitulah, subsidi BBM sebetulnya tidak pernah hilang. Subsidi itu kini cuma “tersembunyi” dalam pembukuan Pertamina, beralih rupa menjadi kerugian korporasi milik negara. Pemerintah memang berjanji menanggung sebagian kerugian itu. Tapi bukan dengan memberi subsidi, melainkan kian tersamar, sebagai kompensasi bagi Pertamina. Subsidi BBM yang masih transparan tersisa dalam APBN hanyalah subsidi tetap untuk solar, yaitu sebesar Rp 1.000 per liter, yang bahkan turun lagi menjadi Rp 500 per liter pada 2021.
Walhasil, tahun demi tahun Pertamina mengambil alih tanggung jawab pemerintah sebagai penyokong harga BBM agar tetap rendah. Kebijakan menghapus subsidi BBM hanyalah retorika politik munafik. Ada, tapi tersembunyi dan dianggap tiada. Sementara itu, kerugian Pertamina dari penjualan BBM kian menumpuk karena ICP terus menanjak. Yang lebih parah, pemerintah tak rajin melunasi pembayaran subsidi ataupun kompensasi kerugian Pertamina sesuai dengan jadwal. Tunggakannya terus menggunung. Per akhir Februari 2022, tagihan Pertamina kepada pemerintah untuk subsidi dan kompensasi selama 2019-2022 mencapai Rp 99,4 triliun.
Invasi Rusia ke Ukraina membawa kisah ini sampai ke babak yang menentukan. Pasar global terguncang hebat, harga minyak melambung tinggi. ICP per Februari 2022 mencapai US$ 95,72 per barel. Kerugian dari penjualan BBM makin besar. Hal ini membuat arus kas Pertamina dari aktivitas operasi perusahaan makin surut, kering, bahkan minus. Menjelang akhir Februari 2022, posisi arus kas operasional Pertamina minus US$ 1,87 miliar.
Problem finansial Pertamina tentu berdampak langsung pada pengadaan BBM dan kecukupan stoknya. Tak ada cara lain, Pertamina harus mencari pinjaman untuk belanja persediaan. Dalam keadaan sekarang, ketika bunga di pasar global sedang naik dan likuiditas mengetat, ongkos berutang kian mahal. Tambahan beban bunga bisa membuat kondisi finansial Pertamina memburuk. Pada gilirannya, peringkat utangnya bisa merosot. Beban finansialnya makin berat.
Solusi cepat masalah ini sebetulnya sederhana: pemerintah mengakhiri politik munafik subsidi BBM. Jika harga minyak sudah sedemikian tinggi, dan pemerintah tak sanggup atau tak mau menanggung subsidi, harga jual BBM ya harus naik seturut harga pasar, dengan segala konsekuensinya.
Jika tidak, krisis BBM bisa meletus karena tipisnya persediaan. Antrean panjang orang berburu BBM akan terasa sangat ironis jika bersisian dengan baliho-baliho kebulatan tekad mendukung Jokowi untuk 2024, yang kini bertebaran di banyak tempat.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo