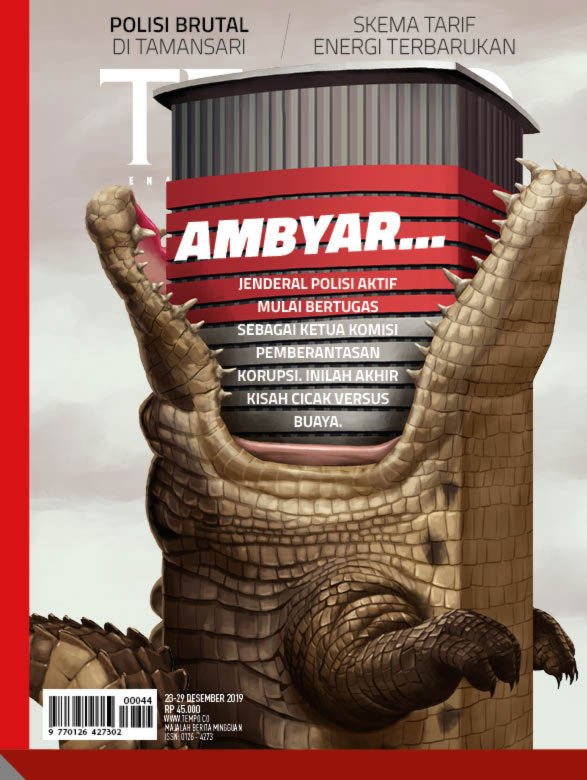Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Opera Gandari dipentaskan untuk ketiga kalinya. Sutradara Melati Suryodarmo memberikan tafsir baru, lekat dengan pengalaman personal sebagai perempuan.
Opera Gandari dipentaskan untuk ketiga kalinya. Sutradara Melati Suryodarmo memberikan tafsir baru, lekat dengan pengalaman personal sebagai perempuan.
Opera Gandari dipentaskan untuk ketiga kalinya. Sutradara Melati Suryodarmo memberikan tafsir baru, lekat dengan pengalaman personal sebagai perempuan.
DARI puncak perancah yang menjulang di panggung, suara parau Christine Hakim menyela keheningan. Rambut abu-abu Christine tergerai. Di pangkuannya, terjurai sehelai kain putih yang sembirannya terus-menerus ia telusuri dengan jari-jemari. “Ia yang tak ingin melihat dunia, sore itu menengok ke luar jendela buat terakhir kalinya....” Demikian Christine membuka Opera Gandari di Graha Bhakti Budaya, Jakarta Pusat, 15 Desember lalu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Di bawah Christine, di kaki perancah, berturut-turut hal terjadi. Soprano Bernadetta Astari maju ke sudut kanan. Lalu masuk kelompok paduan suara Batavia Madrigal Singer berkostum warna-warni tanah dari dua sisi panggung dalam formasi barisan sambil bergantian merendahkan badan. Yang terakhir muncul adalah enam penari dari Studio Plesungan berbalut kain cokelat. Di ceruk depan panggung, tak begitu kelihatan oleh penonton, pengaba Peter Veale dari Ensemble Musikfabrik Jerman memandu 20-an pemusik Jakarta Modern Ensemble memainkan komposisi Tony Prabowo. Perekat mereka semua adalah libretto yang bersandar pada sajak “Gandari” oleh Goenawan Mohamad.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Opera itu berkisah tentang Gandari, istri si buta Destarastra, ibu seratus Kurawa yang mengguncang kerajaan dewa-dewa dalam epos Mahabharata. Karena kebutaan suaminya dan bertubi-tubi kepedihan atas kematian anak-anaknya, Gandari memutuskan berpaling dari dunia dengan mengikatkan sehelai kain hitam menutupi matanya. Ini adalah kisah pada lima hari sebelum ia menutup mata karena cinta dan duka. Namun, meski panggung sering kali ramai oleh penampil yang masuk silih berganti, tak benar-benar ada Gandari di atas panggung malam itu.
Pentas ini merupakan yang ketiga kalinya Opera Gandari dipanggungkan sejak 2014. Sebelumnya, Opera Gandari dipentaskan di Teater Jakarta di bawah arahan Yudi Ahmad Tajudin dan di Frankfurt, Jerman, dengan koreografer Cina, Su Wen-Chi. Kali ini seniman pertunjukan Melati Suryodarmo yang menjadi sutradara. Oleh Melati, Gandari tak dihadirkan dalam satu sosok pelakon, melainkan menjadi napas yang menjelma dalam setiap unsur tari, suara, bunyi, dan cahaya di atas panggung. “Saya menghindari penokohan Gandari. Tak ada Gandari yang utuh, yang bisa terpegang di satu ruang,” kata Melati.
Maka penonton dapat menemukan Gandari pada Christine Hakim yang menceritakan kabar kematian Dursasana, putranya, di Padang Kuru lalu darahnya disauk untuk membasuh rambut Drupadi. “Darah anakku,” ujar Christine, datar saja, kontras dengan hiruk-pikuk musik dan lampu yang berganti warna semerah darah. Bisa juga pada penari perempuan yang diseret dan disepak hingga terguling-guling, yang memeluk diri sendiri rapat-rapat lalu menggelepar. Gandari juga mewujud dalam nada-nada yang dilantunkan Bernadetta, yang sepertinya menyanyikan kata-kata, tapi makin didengar, makin kita tak mampu menangkap makna dari yang sedang ia nyanyikan. Hanya nada-nada tinggi yang mengisi ruang, menyentuh kekosongan.
Ketiadaan Gandari yang tunggal itu dimungkinkan karena sajak Goenawan memang bukanlah sebuah narasi utuh tentang Gandari. Teks itu adalah tangkapan-tangkapan tak runut yang membentuk imaji tentang Gandari. Ketika membuat komposisi untuk opera ini pada 2013, Tony Prabowo juga mendekatkan musiknya pada bentuk kolase. Yang kerap terdengar adalah piano yang dibunyikan patah-patah, dentang tunggal tiba-tiba, atau kersik tajam seperti daun kering saling menggesel. Penyanyi kor juga tak jarang hanya menyanyikan suku kata seperti pada adegan mendekati akhir ketika mereka membisikkan a/ir/su/rut/ca/ha/ya/se/pa berganti-gantian hingga bergema. “Ada struktur besar yang diisi oleh ide tentang bunyi, warna, dan tekstur dengan motif saling terkait,” kata Tony, yang mengerjakan komposisi ini selama satu setengah tahun. Untuk pentas ketiga ini, Tony menambah beberapa bagian dalam komposisinya.

TEMPO/Nurdiansah
Meski dikunci oleh libretto Goenawan dan komposisi musik Tony Prabowo, Melati menemukan banyak celah untuk bereksperimen. Melati menawarkan cara pandang baru tentang Gandari, yang biasanya dicitrakan sebagai perempuan suci dan ibu yang rela berkorban untuk suami dan anak-anaknya. Melati mengaku sangat dipengaruhi oleh pengalaman pertamanya membaca kisah Gandari saat masih kanak-kanak melalui berjilid-jilid komik Mahabharata oleh R.A. Kosasih. Digambarkan, Gandari melahirkan segumpal daging, menendangnya hingga pecah menjadi gumpalan-gumpalan kecil, yang masing-masing kemudian berubah menjadi bayi berjumlah seratus. “Ingatanku tentang Gandari sangat sederhana, yaitu ekspresi marahnya saat menendang gumpalan daging itu,” ujar Melati.
Karena itu, Gandari, bagi Melati, lebih dari sekadar perempuan setia. Dia juga menyimpan dendam dan amarah karena tak berdaya. Kita melihat para penari terpelanting, jatuh-bangun, atau menggapai-gapaikan tangan ke atas seolah-olah ingin mengambil sesuatu tapi tak mampu. Melati juga meminta direktur artistik Jay Subiyakto menghadirkan struktur dengan tangga di atas panggung. Tangga itu menjadi simbol kekerasan hati Gandari untuk mencapai sesuatu tapi sering kali tertahan oleh nasibnya sebagai perempuan. Kemudian Melati meminta Christine Hakim sebagai narator karena, pada pentas-pentas sebelumnya, aktor laki-laki yang mengisi peran ini. Christine, tentu saja, tampil menonjol meski baru pertama kali tampil di panggung teater. Sedikit yang patut disayangkan adalah ekspresi Christine kurang kentara terlihat karena tata cahaya jarang menyorot langsung ke wajahnya.
Melati juga “meledek” keganjilan kisah kematian Dursasana, putra Gandari, yang konon dapat dikalahkan oleh Bima hanya karena campur tangan dua arwah kembar, Tarka dan Sarka. Caranya mempertanyakan plot itu adalah dengan menghadirkan dua perempuan pembawa lentera bergaun merah yang bergerak dengan canggung di atas panggung pada adegan pemakaman Bhisma. “Mereka perempuan biasa, bukan penari. Saya khusus mencari perempuan kembar satu telur dan meminta mereka bergerak bebas di panggung,” kata Melati.
Kehadiran para perempuan itu menjadi salah satu cara Melati menyuarakan pertanyaan-pertanyaan pribadinya tentang menjadi perempuan dan menjadi ibu. Pertanyaan yang belum tentu akan terjawab sebagaimana pada adegan terakhir ketika semua penampil riuh merangkak-rangkak kian ke mari di atas panggung, tapi pada akhirnya terkulai sambil melihat ke atas, “Dan dari langit tak ada lagi apa-apa.”
MOYANG KASIH DEWIMERDEKA
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo