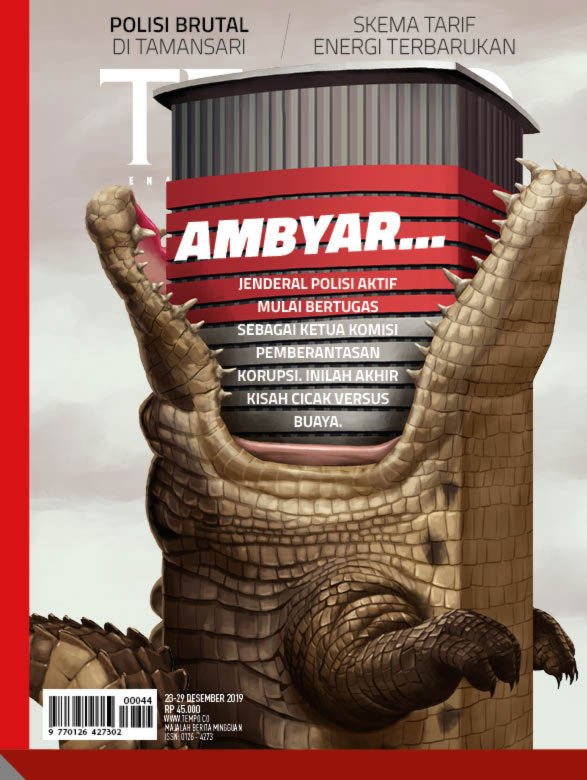Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
DEMAM kemaestroan melanda medan seni rupa Indonesia sejak dulu. Seniman dan karyanya selalu menjadi yang paling penting atau menerima paling banyak lampu sorot, meskipun tidak salah. Seniman atau perupa seperti selalu merasa mendapat amanat untuk terus meladeni spirit progresivitas, selalu merasa bisa melampaui dan menerobos batasan. Padahal progresivitas memerlukan pertukaran pengetahuan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Seni rupa kita selalu berupaya memberikan jawaban dengan sedikit usaha untuk mengajukan pertanyaan,” ujar Hendro Wiyanto saat memberi sambutan untuk pameran yang dikuratorinya, “Mengingat-ingat Sanento Yuliman (1941-1992)-Pameran Karya dan Arsip”, di Galeri Cipta II, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 12 Desember lalu. Minimnya kebutuhan untuk bertanya merujuk pada eksistensi kritik seni yang jumlah produknya jauh tertinggal jika dibandingkan dengan inisiasi penyelenggaraan peristiwa seni rupa, seperti pameran.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kita bisa bertanya berapa jumlah tulisan atau ulasan pameran di media massa setiap minggu. Apakah itu sekadar laporan singkat-padat dari wartawan atau ulasan komprehensif dan mendalam dari seorang pengamat seni rupa? Berapa jumlah jurnal seni rupa di Indonesia? Berapa jumlah skripsi, tesis, dan disertasi yang diciptakan para lulusan perguruan tinggi seni rupa? Berapa jumlah penelitian ataupun publikasi tentang karya seniman di luar katalog pameran dan independen dari pendanaan senimannya sendiri ataupun kolektor?
Pada titik inilah pameran “Mengingat-ingat Sanento Yuliman”, yang diselenggarakan pada 12 Desember 2019-15 Januari 2020, menjadi penting. Pameran ini memperlihatkan ratusan arsip tulisan kritik seni rupa dan kebudayaan Sanento, yang aktif berkarya pada 1970-1990-an. Arsip-arsip itu terhimpun dari koleksi keluarga serta diperoleh dari institusi pengarsipan, seperti Perpustakaan Nasional Indonesia, Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin, dan Perpustakaan Seni Rupa Institut Teknologi Bandung.
Sanento Yuliman (1941-1992) adalah salah satu kritikus terbaik yang pernah dimiliki oleh seni rupa Indonesia. Dedikasinya terhadap kritik dan kajian seni diawali ketika ia memilih jalur skripsi ketimbang jalur karya seperti kebanyakan temannya di Departemen Seni Rupa ITB pada 1968. Setelahnya, tulisan Sanento rutin mengisi rubrik seni rupa dan kebudayaan di banyak media massa Tanah Air.
Sanento dikenal sebagai kritikus yang telaten mencatat kecenderungan dari tiap periode seni rupa di Indonesia beserta konteks kebudayaan, sosial, dan politik yang melatarinya. Sebagai kritikus--terutama seni lukis--ia mempercayai bahwa seni lukis Indonesia hidup dan berkembang dari banyak pengaruh. Hal ini menghindarkan Sanento dari penilaian yang cupet dan terburu-buru dalam membaca gejala artistik tertentu. Kelebihan ini juga membuatnya mampu menyelesaikan sebuah buku berjudul Seni Lukis Indonesia Baru: Sebuah Pengantar, yang diterbitkan oleh Dewan Kesenian Jakarta pada 1976. Terbitan ini secara cermat dan komprehensif merangkum perkembangan seni lukis Indonesia sejak pra-kemerdekaan hingga 1970-an yang masih kerap dirujuk para peneliti seni rupa dan dijadikan diktat kuliah di sejumlah perguruan tinggi seni rupa di Indonesia.
Melalui arsip-arsip Sanento, pameran ini menunjukkan kepada kita jalan sunyi kritikus dan pranata kritik seni rupa di Indonesia. Jika pameran ini tidak terlaksana, dokumen-dokumen itu mungkin hanya akan teronggok dan berdebu di rak-rak penyimpanan. Arsip tulisan Sanento yang mayoritas terpublikasi di media massa menggarisbawahi ungkapan Bambang Bujono yang dikutip oleh Hendro Wiyanto dalam catatan kuratorial bahwa kritik seni rupa Indonesia sekadar “numpang indekos” di media massa.
Sampel keterkucilan dunia kritik seni ini bisa dilanjutkan jika kita melihat naskah-naskah kunci Sanento yang dipamerkan, misalnya skripsi yang menandai kelulusannya di Departemen Seni Rupa ITB berjudul “Beberapa Masalah dalam Kritik Seni Lukis Indonesia” (1968) dan disertasi berjudul “Genese De Le Peinture Indonesienne Contemporaine: Le Role De S. Sudjojono (Asal Mula Seni Lukis Kontemporer Indonesia: Peran S. Sudjojono)” (1979) yang menandai kelulusan studi doktoralnya di Ecole des Hautes en Sciences Sociales, Paris. Kita bisa sekadar memperhatikan judul dan tahun pembuatannya untuk menilai betapa signifikannya dua publikasi ini. Namun hingga kini keduanya belum pernah diterjemahkan dan diterbitkan, yang membuatnya hanya beredar di kalangan amat terbatas.
Peran kritik seni rupa dan kritik pada bidang seni lain adalah mendorong pertukaran pengetahuan. Dalam pameran, melalui arsip-arsip Sanento ini kita bisa melihat sejumlah konteks yang menaungi eksistensi kritik seni rupa di Indonesia. Misalnya kecenderungan seniman yang takut dikritik. Kritik seni masih dipahami hanya menonjolkan keburukan-keburukan. Pengalaman dikritik (jelek) oleh kritikus sepertinya bisa menghadirkan trauma yang mendalam.
Yang menarik, pameran ini menampilkan beberapa pernyataan kritik Sanento yang penting. Sanento piawai dalam menampilkan contoh kritik seni rupa yang jeli dalam menawarkan kosakata untuk mendefinisikan kecenderungan baru atau inovasi yang dicapai perupa. Ia menerjemahkan dalam bahasa yang mudah. Misalnya dalam tulisan Sanento berjudul “Perspektif Baru” pada 1975 ada pernyataan demikian: “Dapatkah kita katakan bahwa dalam pameran ini kita sedang diperkenalkan pada pengalaman kesenian baru, di mana perasaan akan kekonkretan merupakan aspek dasar yang meresapi kualitas pengalaman itu…”.
Diksi “kekonkretan” merujuk pada penggunaan benda sehari-hari dalam karya seniman Gerakan Seni Rupa Baru. Kecenderungan baru ini diyakini Sanento pada seni-seni yang tidak terkucil yang langsung menyapa audiens dalam benda sehari-hari yang konkret. Saya meyakini bahwa diksi “kekonkretan” juga dipakai Sanento untuk mengiringi istilah ready made (benda pakai) dan found object (benda temuan) yang saat itu ramai muncul dalam diskursus seni rupa di Eropa Barat dan Amerika Serikat.
Di bagian lain, kita akan menemukan arsip-arsip yang secara sepintas tidak berhubungan dengan karier Sanento sebagai kritikus seni rupa, yaitu sejumlah reproduksi karikaturnya di tabloid Mahasiswa Indonesia, media pelantang aktivisme bagi Angkatan 66 yang kritis terhadap orde Sukarno. Kritik-kritik Sanento melalui karikaturnya tidak terjebak pada penyerangan pribadi kepada tokoh, melainkan kepada fenomena yang memicu pergolakan situasi ekonomi, politik, dan sosial pada masa itu.
Selain karikatur dan karya-karya ilustrasi dalam sebuah lini masa besar yang memuat riwayat hidup Sanento di awal ruang pamer, disebutkan pula jika ia punya renjana dalam dunia sastra. Puisi berjudul “Laut” (1968) dan esai berjudul “Dalam Bayangan Sang Pahlawan” (1968) memperoleh penghargaan dari majalah sastra Horison. Saat mahasiswa, Sanento juga aktif bergiat dalam dunia teater. Ia sempat terlibat menjadi pengurus majalah budaya anak muda Aktuil.
Selain menampilkan arsip, pameran ini menghadirkan beberapa lukisan Sanento serta buku teori seni dan bacaan lain yang menjadi referensi bagi aktivitas menulisnya. “Mengingat-ingat Sanento Yuliman” juga menampilkan rekaman suara dari diskusi-diskusi yang melibatkan Sanento sebagai pembicara. Presentasi sejumlah arsip dan karya ini memadai dalam menampilkan sosok Sanento yang bersegi-segi, yang masih jarang diketahui khalayak seni.
Kritik seni (rupa) agaknya masih akan menempuh jalan sunyi di tengah ingar-bingar peristiwa seni rupa kontemporer belakangan ini, seperti secara klise diungkapkan melalui penghadiran mesin ketik Sanento yang terkucil diabaikan para pengunjung saat pembukaan pameran. Terbatasnya ruang publikasi untuk kritik seni, keengganan seniman untuk dikritik, peran kurator, dan otoritas pasar bisa menjadi beberapa sebab makin tidak dibutuhkannya lagi profesi kritikus seni (rupa).
CHABIB DUTA HAPSORO, KURATOR SENI RUPA
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo