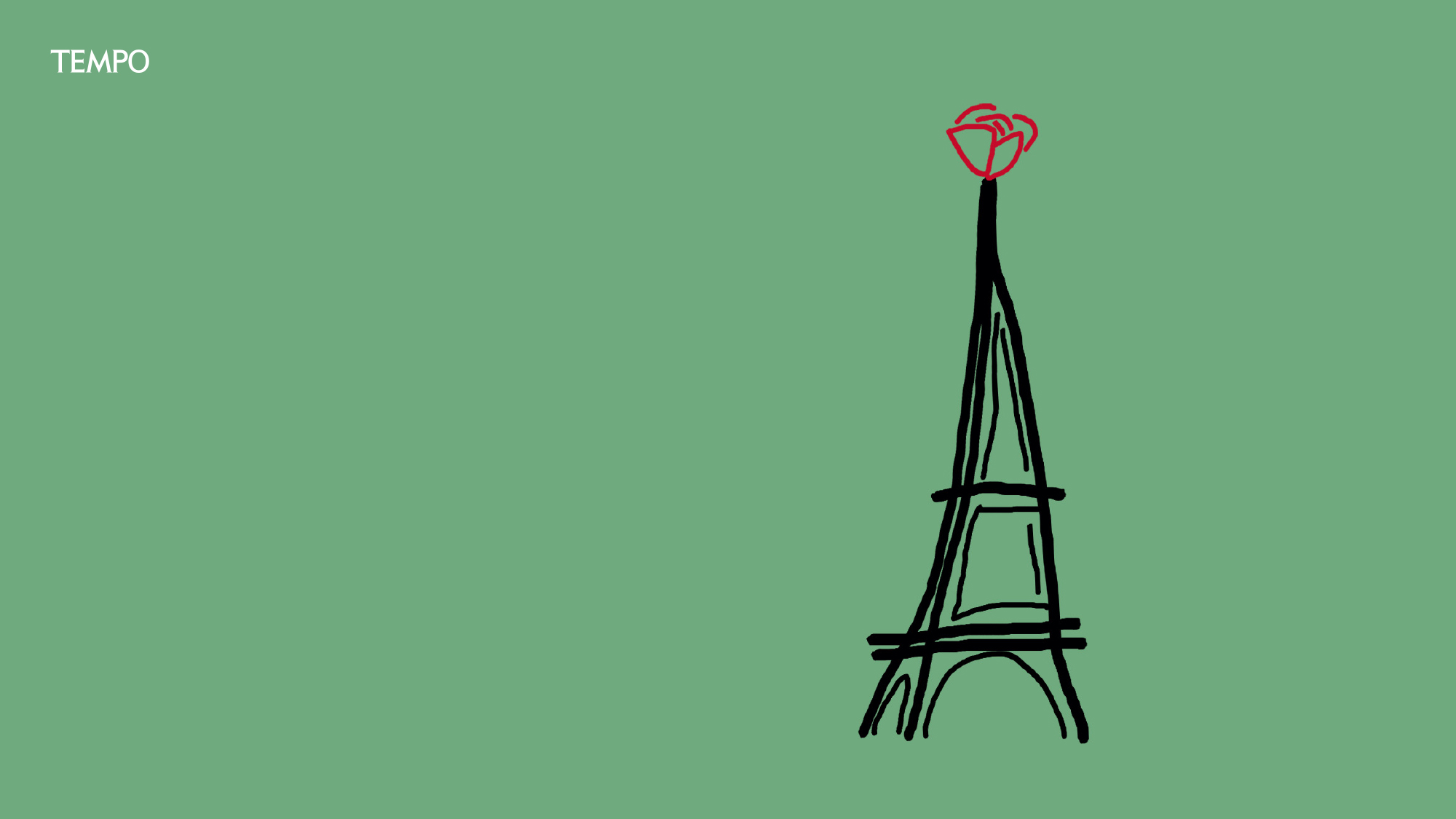Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“JAKET kulit tanpa lengan, kuping ditindik, sepatu bot Docmart (Dr. Martens). Kerumunan massa itu banyak sekali yang berbaju hitam,” kata Giri Nugroho, 41 tahun. Setelan itu jauh dari kesan menakutkan bagi Giri remaja. Justru tampak trendi baginya. Bisa jadi karena ia terbiasa merekam pemandangan itu saban akhir pekan. Dulu, tiap Ahad, Giri dan belasan kawan sebayanya biasa pergi menonton pergelaran musik bawah tanah (underground). “Kami ke (Gelanggang Olahraga) Saparua,” ujarnya saat dihubungi, Kamis, 1 Juli lalu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Rombongan bocah sekolah menengah pertama ini pergi sejak pagi hingga petang menjelang. Tumpangannya gratis: mobil bak terbuka yang dicegat di jalan raya sekitar Kiaracondong, area rumah mereka. Di perjalanan tertampar angin Bandung yang dingin, di Saparua hawa sejuk adalah hal yang muskil. Tujuh ribu manusia bersesakan di dalamnya, menyanyikan lagu-lagu cadas yang dibawakan bergantian oleh puluhan musikus yang unjuk gigi di panggung kecil. Terbawa melodi keras dan vokal penuh energi dari kelompok musik idola, para penonton tak jarang berloncatan, saling bertabrakan. Moshing menjadi atraksi biasa di sana. Kalau sudah kelewat sumpek, barulah Giri keluar dari gelanggang untuk menangkap udara segar.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini


Acara musik di GOR Saparua Bandung. Film Gelora: Magnumentary of Gedung Saparua
Kenangan itu membuat Saparua punya tempat sendiri bagi Giri. Bahkan kini dia menjabat Kepala Sub-Bagian Urusan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, yang mengharuskannya bersentuhan dengan gelora tersebut. “Salah satu tugasnya memelihara kebersihan dan keamanan Gelora Saparua bersama puluhan petugas lapangan,” ucapnya.
Gelora Saparua adalah legenda. Menurut Ridwan Hutagalung dari Komunitas Aleut, yang aktif menggali sejarah Kota Bandung, Belanda menjadikan area Saparua sebagai lapangan olahraga untuk publik pada 1910. Sebutannya ketika itu Nederlandsch-Indische Athletiek Unie (NIAU). Baru pada 1961, pemerintah memoles ulang kawasan seluas 25.400 meter persegi ini. Gedung Saparua, yang seluas 1.267 meter persegi, dipermak menjadi tempat pertandingan bola voli dan bulu tangkis dalam hajatan Pekan Olahraga Nasional kelima.
Namun, dalam perkembangannya, lebih banyak seniman yang lahir di sini ketimbang olahragawan. Pada 1980-an, Saparua menjadi wadah beragam pentas kesenian. Di sana tak hanya digelar konser band cadas, tapi juga genre musik lain. Saparua pun menjadi tempat pembacaan puisi penyair W.S. Rendra. Di sana pula sejumlah band beraliran black metal kerap membuat atraksi eksentrik. Misalnya ritual memanggil arwah sembari membakar kemenyan yang mencekam suasana. “Itu sering dilakukan band dari Ujungberung, seperti Sacrilegious,” ujar Ridwan.

(Dari kiri ke kanan) Gitaris Burgerkill Eben, Vokalis Rocket Rockers Aska, Sutradara Alvin Yunata, Creative Director Cerahati Edy Khemod, dan Vokalis Superglad Buluks, saat gala premiere Film Dokumenter “Gelora: Magnumentary Of Gedung Saparua di Grand Indonesia, Jakarta, 6 Juni 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis
Peran itulah yang menjadi jantung cerita film dokumenter Gelora: Magnumentary of Gedung Saparua, yang tayang perdana pada pertengahan Juni lalu di sejumlah kanal streaming. Proyek gagasan Rich Music ini disutradarai Alvin Yunata, gitaris band rock Teenage Death Star yang juga mantan vokalis Harapan Jaya. Dalam film yang digarap selama tiga bulan ini, sejumlah musikus yang punya sejarah panjang dengan Saparua menjadi narasumber. Mereka di antaranya Sam Bimbo; vokalis Seringai, Arian13; mantan vokalis Pure Saturday, Suar; manajer Burgerkill, Dadan Ketu; dan gitaris Burgerkill, Ebenz.
Alvin memilih Saparua sebagai subyek film dokumenternya karena gelanggang olahraga itu punya peran besar bagi pergerakan musik independen dan industri kreatif. Selama aktif di yayasan pengarsipan musik Irama Nusantara, dia menemukan, sejak 1960-an, gelora ini sudah menjadi tempat pentas keroncong konkurs dan Aneka Nada, band Sam Bimbo. Bahkan, menurut risetnya, diketahui area Saparua sudah menjadi lokasi kegiatan musik pada 1930-an. “Film ini menjadi jurnal yang mencatat lahirnya generasi yang mengusung kolektivitas, adanya ruang pergerakan bagi perkembangan musik underground,” ujarnya, Selasa, 29 Juni lalu.
Alvin sendiri menjadi saksi bagaimana penggemar musik dari beragam genre terhubung dan terbentuk menjadi komunitas kuat di Saparua, baik fan musik metal, alternatif, maupun punk rock. Menurut dia, jiwa kebersamaan antarmusikus dan dukungan penggemar yang membuat Saparua kuat sebagai sebuah ekosistem. Komunitas di dalamnya pun berjejaring dan punya solidaritas tinggi.
Alvin pun mendapat energi dan inspirasi dari gedung ini hingga akhirnya ia bersalin posisi dari penonton menjadi penampil. “Gue pertama kali datang ke Saparua saat SMA. Ketika itu Arian (sekarang vokalis Seringai) masih di band Puppen dan manggung di sana. Gedung itu lambat-laun mempengaruhi gue, memberi pemikiran di luar normatif,” tuturnya.
Direktur Kreatif Cerahati, Edy Khemod, menambahkan, proyek atas inisiatif dari pihaknya, Arian, dan Roni Pramaditia ini ingin menyuguhkan dokumentasi momen bersejarah di Bandung. Selama ini, dokumentasi itu belum banyak ada. Keberadaan gelora sendiri vital mengingat ketika itu banyak hal yang serba terbatas. Internet masih menjadi fasilitas yang eksklusif, begitu pun media sosial. “Semangatnya adalah kolektivitas dan kemandirian. Musisi patungan sewa tempat dan saling bantu antarteman. Dengan keterbatasan pun musisi bisa tetap solid sebagai komunal,” ujar Khemod, yang juga penggebuk drum Seringai.

Penonton konser musik punk di Bandung, September 2007. Dok. TEMPO
Sam Bimbo, yang pada awal 1960-an membentuk Aneka Nada bersama adiknya, Atjil, dan Guruh Sukarno Putra, menyebutkan konser perdana grupnya berlangsung di Saparua. Ketika itu, mereka tampil bersama band top asal Jakarta, Eka Sapta. Konser pertama di Saparua itu digelar mandiri oleh kedua band pada 1963. Setelah itu, Saparua mulai dilirik grup musik lokal sebagai opsi tempat pentas.
Salah satunya vokalis Seringai, Arian Arifin alias Arian13, yang ketika itu menggawangi Puppen. Dalam wawancara via Zoom, Selasa, 29 Juni lalu, Arian menyebutkan, satu hari bisa ada 20-30 band yang tampil di Saparua pada 1990-an. Jumlah penonton ajang mingguan ini pun selalu membeludak. Bahkan, pada satu waktu, karcis pernah terjual 7.000 lembar. Itu hampir dua kali lipat kapasitas Gelora Saparua, yang hanya 4.000 orang. “Bandung dingin, tapi Saparua selalu ‘panas’,” ujarnya, lalu tergelak. Fasilitas Saparua yang terbatas, baik dari segi audio maupun pencahayaan, tak menjadi perkara besar. “Malah kami makin teruji untuk main di tempat yang seadanya.”

Penampilan band Koil saat konser dalam acara musik metal di halaman GOR Saparua Bandung, Jawa Barat, Maret 2010. TEMPO/Prima Mulia
Gitaris Burgerkill, Aries Tanto alias Ebenz, membenarkan anggapan bahwa kondisi Saparua sejatinya tak mendukung sebagai arena konser musik. Band yang biasa tampil di sana pun, termasuk Burgerkill, menyadari itu. Namun mereka cuek dan nyaman saja. “Karena kami enggak punya opsi lagi soal tempat pentas. Jadi kualitas audio tak kami pikirkan,” katanya, Selasa, 29 Juni lalu.
Pengamat musik Bens Leo menyebutkan film dokumenter garapan Alvin penting karena menyuguhkan Saparua sebagai gelora dengan atmosfer yang kondusif bagi band independen. Namun ia menyoroti film ini tak memberi gambaran lebih spesifik tentang Saparua. Misalnya bagaimana waktu itu personel grup punk rock yang hendak manggung datang berombongan menumpang mobil angkutan umum (angkot) bersama keluarganya. Di angkot, dandanan mereka sudah lengkap. Pun anak-anaknya dipoles mirip gaya panggung si bapak. Yang juga tak kalah menarik tapi belum tersaji di film adalah momen lahirnya toko pakaian alias distro. “Dulu musikus gelar lapak di luar gelora. Jual kaset dan pernak-pernik band mereka,” ucapnya, Ahad, 27 Juni lalu.
Hal itu dibenarkan musikus Iman Rahman Angga Kusumah alias Kimung. Ia menyebutkan, di luar panggung, musikus dan penonton berkenalan dan mengobrol. Pedagang kaset dan zine pun laris manis menjajakan produk bikinan mereka sendiri. Yang membuat Kimung terkesan, penonton Saparua tetap guyub walau mereka menggemari genre musik yang berbeda. “Saya pun kadang datang pagi untuk menikmati suasana ramai dan karya band underground,” ujar Kimung, yang dulu bermain sebagai pembetot bas Burgerkill.

Penampilan band dalam pertunjukan musik Rock Session di Gedung Gelora, Jalan Saparua, Bandung, pada 1980. Dok. TEMPO/Yudhistira Anm Massardi
Sayangnya, peran Saparua tenggelam setelah tak lagi diperuntukkan sebagai ruang pertunjukan, 20 tahun lalu. Adapun pada 2019, Gelora Saparua ditata ulang. Namun prosesnya terhenti sementara karena pandemi Coronavirus Disease 2019. “Karena tergolong bangunan cagar budaya, bentuk bangunannya tidak diubah,” kata bekas Kepala Biro Umum Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Iip Hidajat. Status pengelolaan Saparua pun berubah-ubah, dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Kota Bandung, hingga kini di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
•••
DI luar Bandung, kawasan gelanggang olahraga juga memegang peran penting bagi perkembangan “skena” musik lokal. Selain Bulungan (Jakarta), ada Kridosono (Yogyakarta), Manahan (Solo, Jawa Tengah), dan Pulosari (Malang, Jawa Timur). Sebelum dirobohkan untuk menjalani renovasi pada 2018, Gelora Manahan Solo juga populer sebagai tempat konser. Tak hanya menjadi tempat konser band terkenal seperti Dewa, Efek Rumah Kaca, dan Navicula, Manahan juga biasa menjadi panggung musikus lokal tiap Ahad pagi. “Ada dua-tiga panggung dengan genre musik berbeda. Walau suaranya saling tabrak, kami tetap menikmati,” tutur gitaris Seven Souls, Fitrian Siswa Angkasa, 38 tahun.
Menengok peran Manahan, vokalis band metal Down for Life, Stephanus Adjie, berharap gelora itu akan berbekal akustik ruangan yang mumpuni setelah direnovasi. Ia merujuk pada Madison Square Garden di New York dan arena olahraga lain di Amerika Serikat serta Eropa yang punya kualitas akustik keren yang mendukung pentas musik. “Gedung olahraga itu idealnya multifungsi,” ujarnya.
Gelora Pulosari di Malang bahkan pernah ditahbiskan sebagai barometer rock. Penonton Malang dikenal sangat antusias terhadap jenis musik itu. Siapa pun grup musik Indonesia jika tampil di situ antara 1970-an dan 1980-an harus berhati-hati. Sebab, bila performa mereka jelek, bisa-bisa menimbulkan “kerusuhan”. Usman Mansur, 70 tahun, ingat, tiap hendak menuju Pulosari untuk menonton pertunjukan musik rock, ia berkumpul dulu di kawasan Kayutangan (sekarang Jalan Basuki Rahmat), Kota Malang. Dari situ, ia berangkat berombongan ke Pulosari, yang berjarak sekitar 3 kilometer, dengan berjalan kaki.

Gedung Gelora Saparua di Bandung, Jawa Barat, 2 Juli 2021. TEMPO/Prima mulia
Usman mengenang, bersama rombongan Kayutangan yang dipimpin lelaki bernama Sugeng, ia ikut menjebol pintu Pulosari demi bisa menonton gratis pergelaran musik. Menurut Usman, bila band yang tampil di Pulosari tak memuaskan selera mereka, tak jarang Sugeng bertindak nekat. Melempar kursi lipat ke panggung, misalnya. Pernah juga saking sukanya mereka kepada penampilan AKA dan The Rollies, kedua band itu dipaksa memperpanjang durasi tampil. “Konser The Rollies yang seharusnya rampung jam 12 malam akhirnya baru kelar jam 2 pagi,” ucapnya. “Kalau ada musisi yang main jelek atau fals di Pulosari akan diteriaki, ‘Mudhun, mudhun (Turun, turun)!’,” ujar Ketua Museum Musik Indonesia Hengki Herwanto, yang pada masa itu menjadi jurnalis majalah musik Aktuil. Walhasil, kata dia, sejumlah band luar Malang menjadi minder tampil di Pulosari.
Ovan Tobing, yang dulu kerap menjadi pembawa acara di Pulosari, membenarkannya. Vokalis Ogle Eyes, (almarhum) Micky Jaguar, pernah dilempari telur busuk, tomat, dan batu oleh penonton. Pada 1980-an, saat God Bless tampil di Pulosari, terjadi keributan. Ovan, yang sebetulnya hanya menonton, melompat ke panggung dan menenangkan penonton. Karismanya membuat penonton Malang tidak sampai berbuat kekisruhan. Vokalis God Bless, Achmad Albar alias Iyek, mengakui Pulosari sebagai kawah candradimuka dan tempat uji nyali kelayakan kualitas grup rock Tanah Air. Salah satu konser yang juga diingat bagi penggemar musik rock Malang pada 1980-an adalah konser Genesis Night bersama Cockpit Band Jakarta. Konser itu betul-betul memuaskan dahaga para penggemar Genesis di sana. Waktu itu vokalis Cockpit, (almarhum) Freddy Tamaela, sampai heran menyaksikan anak-anak Malang begitu hafal lagu-lagu Genesis. Tiap lagu yang ia nyanyikan diikuti bersama-sama oleh penonton Gelora Pulosari.

Penampilan lady rocker Silvia Sartje di GOR Pulosari, Malang, pada 1973. Repro Koleksi Museum Musik Indonesia
Menurut Hengki, walau Pulosari adalah tempat olahraga, arena berkapasitas 3.000 penonton itu punya kualitas akustik yang lumayan. Di sana juga digelar festival band yang menampilkan musikus lokal, seperti Avia, Tornado, dan Elvira. Lady rocker Sylvia Saartje juga disambut baik di Pulosari. “Aku dimenangkan zaman. Tinggal di Malang yang penontonnya kritis,” katanya. Hingga medio 1990-an, Pulosari masih rajin menggelar pentas musik. Termasuk festival musik pada akhir 1997, yang menghadirkan musikus Bandung tempaan Gelora Saparua: PAS Band, Burgerkill, dan Forgotten. Sayangnya, itu menjadi pentas musik terakhir di Pulosari. Pemerintah Kota Malang semula menyebutkan bakal merenovasi area itu. Namun, belakangan, di sana justru dibangun toko swalayan.
Vokalis Seringai, Arian13, menyebutkan, masih perlu atau tidaknya keberadaan panggung gelora di sejumlah daerah sebagai wadah kreatif para musikus mesti dikembalikan lagi kepada anak muda zaman ini. “Mungkin generasi sekarang sudah enggak butuh (gelanggang olahraga) karena mereka terbiasa mendengarkan musik streaming. Standar penonton akan kualitas pentas juga pasti lebih tinggi karena sudah merasakan pertunjukan musik di tempat-tempat yang lebih megah daripada gelora. Jadi tergantung anak muda sekarang. Mereka masih butuh gelora enggak?”
ISMA SAVITRI, ANWAR SISWADI (BANDUNG), EKO WIDIANTO (MALANG), DINDA LEO LISTY (SOLO)
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo