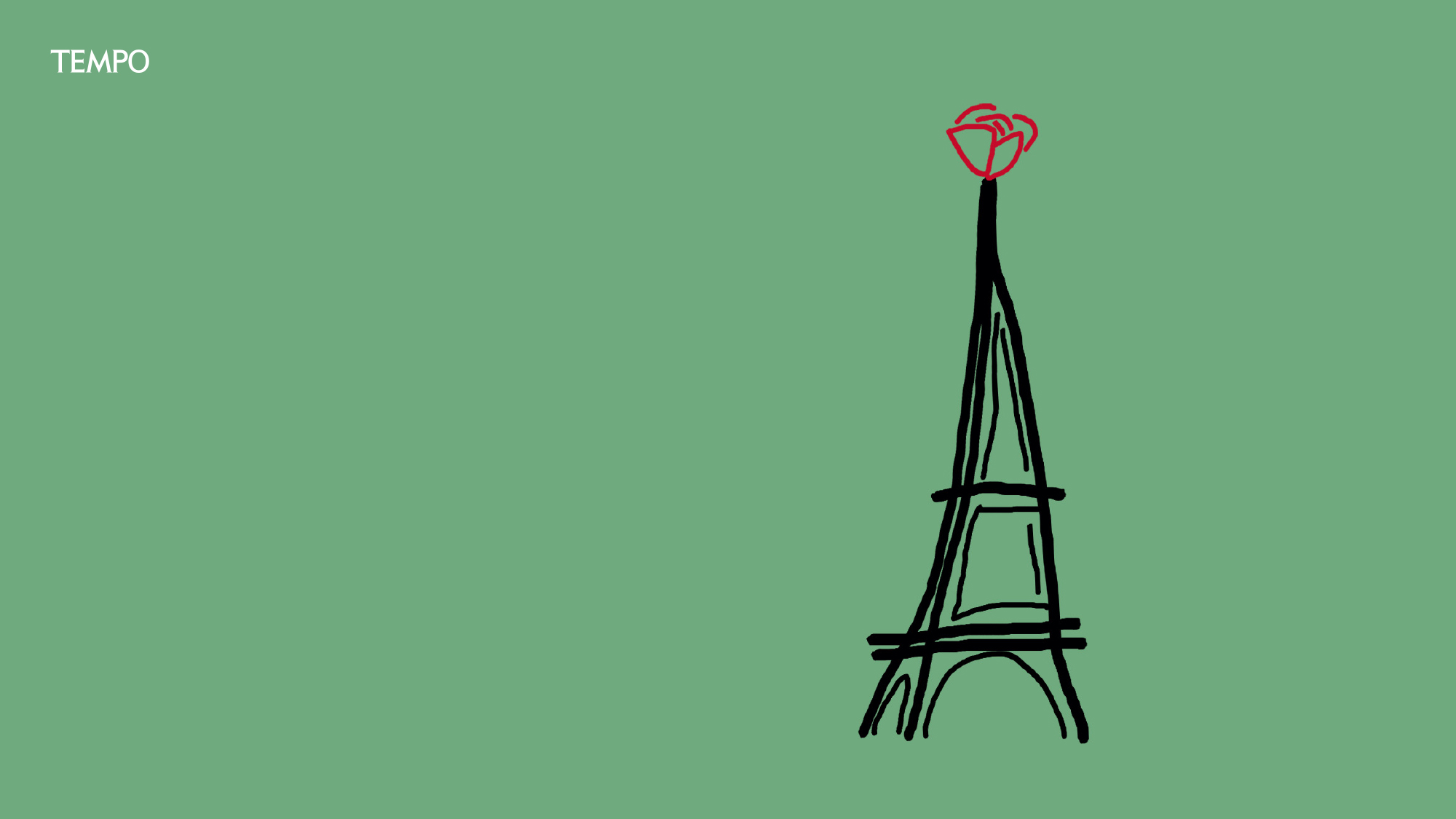Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Perjalanan Muhibah Budaya Jalur Rempah di wilayah barat di tujuh titik persinggahan, dimulai dari Jakarta. Titik persinggahan berikutnya adalah Belitung Timur, Dumai, Sabang, Melaka, Tanjung Uban, dan Lampung, lalu kembali ke Jakarta.
Melibatkan setidaknya 150 anggota Laskar Rempah yang merupakan anak muda pilihan dari berbagai provinsi.
Menyusuri jejak Jalur Rempah di setiap titik persinggahan, menggali budaya dan tradisi masa lampau.
PERJALANAN Muhibah Budaya Jalur Rempah kembali berlangsung pada 5 Juni 2024. Perjalanan melalui jalur laut bersama KRI Dewaruci ini dimulai dari Jakarta, menyusuri tujuh titik jejak Jalur Rempah di kawasan barat Indonesia di sepanjang Pulau Sumatera hingga Melaka di Malaysia yang dulu merupakan episentrum perdagangan rempah. Menyinggahi kota bandar di masa lalu yang menjadi kota kosmopolitan di zamannya. Tempo diundang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengikuti perjalanan ini dengan rute Dumai-Sabang-Melaka-Tanjung Uban.
•••
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
PAGI-PAGI, dari dek bawah dan belakang kamar terdengar cukup kencang sebuah lagu yang tak asing. “Surat kabar sore dijual malam. Selepas isya melangkah pulang. Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu. Demi satu impian yang kerap ganggu tidurmu. Dipaksa pecahkan karang lemah jarimu terkepal…,” begitulah sepenggal syair lagu “Sore Tugu Pancoran (Si Budi Kecil)” milik Iwan Fals. Saya masih agak terkejut dengan suasana santai pagi itu di sebuah kapal Tentara Nasional Indonesia. Hari berikutnya, lagu pop dangdut Jawa yang berkumandang, mungkin untuk mengobati rasa kangen para anak buah kapal.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pagi kedua yang cerah dalam pelayaran bersama Kapal Perang Republik Indonesia atau KRI Dewaruci selepas dari Pelabuhan CT-1 Dumai. Wilayah ini dulu adalah bagian dari Kerajaan Siak. Kapal masih memutari Pulau Rupat, Riau, menuju perairan Sumatera Utara. Saya bangun terlalu dini, pukul 03.30, salah melihat jam, mungkin tubuh juga masih dalam proses adaptasi. Setengah jam kemudian, saya bergegas mandi. Setelahnya, sembari menunggu pagi, saya balik ke tempat tidur, kasur terbawah dari tiga tingkat. Untuk keluar-masuk “kolong”, kepala harus merunduk dan tubuh dimiringkan dulu. Saat saya tidur, kaki saya tumpangkan pada dua tas besar yang saya letakkan di ujung kasur busa. Tapi, jika kedua lutut saya menekuk, hanya tersisa tak kurang dari satu jengkal kasur dengan alas di atasnya. Saya dan para penumpang lain pun “bersahabat” dengan bayi dan kecoak remaja yang sering hilir-mudik di lipatan kasur.
Kapal legendaris buatan 1953 yang pernah berkeliling dunia dan dikomandani Letnan Kolonel Laut Rhony Lutviadhani ini merupakan kapal latih taruna Angkatan Laut hingga kini. “Kapal ini masih dipakai oleh taruna, terutama untuk berlatih tentang navigasi alam dan layar. Pelajaran navigasi menentukan kelulusan seorang taruna,” ujar Letkol Rhony saat ditemui di anjungan kapal, Selasa, 18 Juni 2024. Biasanya para taruna mempelajari praktik dari teori yang didapatkan di bangku akademi selama sekitar tiga bulan.
Kapal ini membawa rombongan Laskar Rempah dan undangan Batch 2 Kayumanis dari program Muhibah Budaya Jalur Rempah (MBJR) 2024. Program MBJR digagas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2020. Kementerian mulai bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut pada tahun berikutnya. Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid mengatakan pelayaran MBJR bermula dari refleksi terhadap kenyataan sejarah Indonesia sebagai negara maritim. Program ini berupaya memperkenalkan dan menelusuri kembali jejak sejarah kemaritiman Indonesia. “Lebih dari itu, kita memiliki banyak praktik tradisional yang berkaitan dengan kemaritiman dan semua itu harus kita lestarikan,” ucap Hilmar dalam pelepasan rombongan, Sabtu, 8 Juni 2024.

Para anggota Laskar Rempah Kayumanis berolahraga di Geladak H KRI Dewaruci saat program Muhibah Budaya Jalur Rempah 2024. Tempo/Dian Yuliastuti
Pada 2022, KRI Dewaruci mengantarkan para anggota Laskar menyusuri jejak Jalur Rempah ke Indonesia bagian timur, menuju titik 0 di Banda Neira, Maluku. Pada tahun ini, Muhibah Jalur Rempah menyusuri jalur barat dengan tujuh titik singgah, yakni Jakarta-Belitung Timur-Dumai-Sabang-Melaka-Tanjung Uban-Lampung, hingga kembali ke Jakarta selama 8 Juni-17 Juli 2024. Tempo mendapat undangan mengikuti perjalanan darat dan pelayaran selama 18 hari mulai 17 Juni hingga 7 Juli 2024.
Dalam pelayaran tahun ini diadakan program singgah di luar negeri, yakni di Melaka, Malaysia. “Program ini tidak hanya mempromosikan kekayaan budaya Indonesia, tapi juga memperkuat diplomasi budaya dengan negara-negara sahabat. Untuk pertama kalinya pelayaran MBJR akan berlabuh di Malaysia melalui titik Melaka,” tutur Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Irini Dewi Wanti.
•••
SETELAH menyantap sarapan, rombongan berjalan ke luar ke geladak H, tempat berkumpul utama. Mulai pukul 10.00, rombongan bersiap mendapat materi dari para pakar. Mereka diundang untuk memberikan bekal selama di kapal. Beberapa anak buah kapal (ABK) dengan sigap memasang tenda peneduh. Begitulah kegiatan selama tiga hari di kapal. Di sela-sela pembekalan (bisa pagi, siang, atau sore), para anggota Laskar Rempah biasanya berlatih koreografi untuk penampilan mereka di titik singgah. Selain materi tentang sejarah dan budaya rempah, pengetahuan seputar kemaritiman, KRI Dewaruci, dan tradisi di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut diberikan oleh para perwira di kapal.
Hari itu, di sisi kanan dekat sekoci, beberapa ABK dari Bagian Bahari tampak menggelar terpal putih. Terlihat Sersan Dua Budi tengah menjahit bagian terpal itu dibantu Sersan Satu Kusnadi, salah satu awak yang paling lama mengikuti KRI Dewaruci berkeliling dunia. Menjahit tenda atau terpal menjadi kegiatan yang beberapa kali dijumpai beberapa hari ke depan. Dari Kusnadi diketahui bahwa semalam pelayaran dihadang badai.

KRI Dewaruci berlayar membawa Laskar Rempah Batch II saat tiba di Pelabuhan Tanjung Bruas, Malaka, Malaysia, 30 Juni 2024. Antara/Virna Puspa Setyorini
Belum 24 jam KRI Dewaruci berlayar, saat memutari Pulau Rupat, ombak makin terasa menggoyang kapal. Rupanya, selepas tengah malam, badai datang menerpa. Goyangan kapal sedikit terasa dari tempat tidur di kamar rombongan perempuan yang terletak di bawah tiang Arjuna. Kamar ini terkena dampak guncangan paling kecil. Angin dan hujan memperlambat laju kapal yang biasanya mencapai 8-9 knot. Kapten Rahmad Widodo, perwira jaga laut yang tengah bertugas piket saat itu, mencatat angin bertiup kencang dari arah barat laut-utara dengan kecepatan 38 knot. Badai berlangsung hingga menjelang pukul 3 dinihari.
“Semalam kecepatan kapal turun sampai 3,5 knot, tinggi gelombang 2,5-3 meter,” kata Kapten Rahmad kepada Tempo di anjungan pada Kamis pagi, 20 Juni 2024.
Seusai badai itu, kapal melaju tenang dan lancar. Menikmati makan siang pada hari kedua di kapal, kebetulan saya mendapat giliran bersantap di ruang komandan. Wah, bikin penasaran. Bersama dua anggota Laskar Rempah, penulis dari Tribunnews masuk ke ruangan yang diisi sofa cokelat tua berbentuk L di dua sudut dengan meja kayu yang memiliki penahan.
Foto Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut terpampang pada dinding di sebelah ukiran kayu bergambar Bima yang bertarung melawan seekor naga dan di hadapannya Dewa Ruci duduk dengan tenang. Beberapa plakat ditempelkan pada dinding. Sebuah bel untuk memanggil ada di meja komandan. Piring ditata rapi dengan segelas air putih di samping piring. Rupanya, komandan KRI tidak hadir saat itu. Kami ditemani beberapa perwira. Salah satunya Letnan Satu Daud, Kepala Departemen Logistik. Sayur bening bayam-labu yang dipadukan dengan lauk ayam goreng, tahu bacem, sambal, dan kerupuk di siang itu sungguh terasa segar dan nikmat sekali.

Suasana perkampungan Portugis di wilayah Ujong Pasir, Malaka, Malaysia. Tempo/Dian Yuliastuti
Menjelang sore, ombak perlahan meninggi selepas perairan wilayah Sumatera Utara. Memasuki perairan Aceh hingga Selat Malaka, ombak benar-benar mengguncang kapal disertai angin kencang. Para ABK dan anggota Laskar yang menunaikan salat Jumat di geladak harus berupaya menyeimbangkan posisi. Di tengah ombak yang tinggi ini, beberapa anggota Laskar berteriak kegirangan dan kemudian berlari ke arah haluan di kiri dan kanan.
Ah, rupanya segerombol lumba-lumba tampak menyertai kapal. Mereka berenang dengan lincah. Tiga-empat ekor di antaranya berenang agak jauh. Ada pula yang mepet ke lambung kapal di bagian haluan. Beberapa ekor yang berenang agak jauh kadang meloncat dengan lincah saat dipanggil-panggil. Tapi ombak yang menyertai pelayaran ini membuat banyak anggota Laskar dan beberapa undangan muntah. Geladak agak sepi karena mereka teler dan turun ke lambung. Setelah puas mengambil foto dan video dengan dibantu seorang ABK, saya pun turun. Kepala saya terasa sedikit pening karena anggukan haluan yang cukup kencang diguncang ombak. Segera saya mengoleskan minyak angin, mereguk minuman herbal saset, lalu tidur sebelum mual dan muntah. Beberapa ABK memberikan tip agar tidak masuk angin dan mabuk laut. “Makan. Bagaimanapun kondisinya, perut tidak boleh kosong,” ucap Sersan Dua Ropingi dari Bagian Kesehatan.
Urusan makan menjadi kebiasaan baru selama pelayaran. Pukul 06.00 adalah jam sarapan, tapi hidangan sudah tersedia pada pukul 05.30. Para penanting—anggota Laskar yang membantu menyiapkan makanan dan piring—akan berseru agar semua segera bangun dan bersantap pagi. Jam sarapan dibatasi. Biasanya selewat pukul 07.30 makanan sudah dibereskan. Setiap orang juga wajib mencuci piring yang berlogo TNI AL dan menumpuknya di panci besar. Sayur tumis kangkung kacang panjang, terung, dan bobor daun singkong sering menemani nasi yang disiapkan enam juru masak. Sesekali ada sayur bening bayam-labu. Soto dan rawon juga beberapa kali disajikan. Standarnya, setiap pagi ada lauk telur (dadar), lalu siang daging (ayam) dan malam ikan (tongkol).
Jika anggota rombongan melewatkan jam makan, kurang cocok dengan lauk yang disajikan, atau masih merasa lapar, ada kantin yang menyediakan mi instan dan camilan, juga bakso. Kami menyebutnya “bakso samudera”. Makanan ini sering kali baru tersedia sore-malam. Pada pukul 10.00 dan 16.00, biasanya disajikan makanan ekstra. Kopral Kepala Rudji Antoro yang mengatur dan memasak menu santapan ini yang berupa bubur kacang hijau yang legit dan wangi pandan dengan perpaduan jahe dan kayu manis, santan mutiara dicampur potongan agar-agar, juga rebusan kacang dan ubi, pisang keju, serta roti goreng meses.
Makanan untuk semua anggota rombongan dan anak buah kapal harus direncanakan secara matang di bawah komando Kepala Departemen Logistik. Ada Letnan Satu Daud yang mengatur urusan ini. Menjelang keberangkatan, dia dan anak buahnya menghitung kebutuhan logistik. Bukan hanya makanan, logistik bahan bakar dan air, termasuk urusan administrasinya, diperhitungkan. “Untuk makan, kami perkirakan satu orang 0,5 gram per individu sekali makan. Dikalikan jumlah orang dan hari perjalanan, ketemu jumlah yang harus dibawa atau disediakan,” ujarnya.

Bekas benteng yang dikenal sebagai A Famosa, di depan Bukit Melaka. Tempo/Dian Yuliastuti
Biasanya bahan kering yang awet seperti beras, bumbu, dan makanan darurat instan seperti roti gabin, daging, dan ikan kaleng serta kopi dan susu sudah disediakan pada saat keberangkatan. Ada beras yang bisa dipesan untuk satu bulan atau hingga tiga bulan jika memungkinkan. Adapun stok bahan makanan basah seperti sayuran, buah, telur, daging, dan ikan harus disesuaikan. Di titik perhentian, biasanya Rudji akan berbelanja bahan basah—setidaknya satu pikap sekali berbelanja.
Daud menjelaskan, bahan makanan kering bisa disimpan di suhu ruangan. Adapun sayuran-buah disimpan di ruangan dengan suhu 15 derajat Celsius. Sedangkan daging dan ikan harus disimpan dalam suhu minus 11 derajat Celsius. Dia mesti memantau penyimpanan dan mesin, juga enam juru masaknya. “Kalau ada perubahan suhu, harus segera lapor ke bagian mesin,” ucapnya. Dia juga mengurusi bahan bakar mesin dengan kebutuhan 43 ton. Untuk sekali perjalanan 24 jam, kapal membutuhkan 3 ton solar.
Hal penting yang juga harus diawasi adalah air. Kapal ini mampu membawa 75 ton liter air untuk perjalanan kurang dari lima hari. Penggunaannya harus dihemat untuk urusan kebersihan—mandi, cuci piring, cuci baju, dan makan-minum. Air dialirkan hanya pada waktu-waktu tertentu, seperti saat pagi (subuh) dan sore. Selebihnya air ditampung di beberapa drum untuk berwudu dan mencuci piring. Jika pelayaran berlangsung lebih dari tiga hari, biasanya penggunaan air dikurangi agar masih ada stok. Dalam pelayaran yang panjang, jika persediaan menipis, prioritas utama penggunaan air adalah untuk logistik. Apalagi saat itu kapal mengangkut setidaknya 130 orang.
Mandi di tengah pelayaran tentu tak bisa seenaknya. Semua anggota rombongan diminta menghemat air. Untuk mengeringkan tubuh, semua anggota rombongan mendapat lap sintetis. Tersedia kamar mandi untuk anak buah kapal serta anggota Laskar laki-laki dan perempuan. Untuk ABK dan anggota Laskar laki-laki, terdapat dua kamar mandi dan tiga toilet untuk buang air besar di geladak J. Untuk anggota Laskar perempuan, tersedia dua kamar mandi dan toilet di geladak yang sama. Kamar mandi ini juga digunakan oleh para perwira.
Setiap bak mandi tak selalu penuh dengan air setelah digunakan untuk mandi. Jika penuh, bak mandi itu bisa menampung tak sampai 1 meter kubik air. “Sayang, enggak tega pakai air banyak-banyak,” tutur Debby Loekito, penulis yang ikut bersama rombongan. Saat kapal berlabuh, di hotel, ia puas bisa mandi dengan lebih baik. Dalam urusan mandi, anggota rombongan harus bertenggang rasa dan antre. Agar tak antre, ada yang langsung mandi saat subuh, lalu tidur lagi. Ada juga yang antre setelah matahari naik dengan risiko air tinggal sedikit. Urusan kebersihan menjadi satu hal yang mengkhawatirkan saat menstruasi.
Penghematan juga bisa dilakukan saat berwudu untuk salat yang dijamak dan qosor—dilakukan saat salat zuhur-asar dan magrib-isya. Salat subuh, magrib, dan Jumat biasanya dilakukan di geladak utama secara berjemaah. Agak menantang ketika ombaknya sedikit tinggi. Saat angin berembus kencang, terutama pada waktu salat magrib dan subuh, para anggota jemaah perempuan kesulitan karena mukena mereka sering terangkat lantaran tertiup angin. Bacaan surat juga tak terdengar. Arah kiblat yang kerap berubah selalu diumumkan. Misalnya hijau 150 berarti menyerong ke kanan haluan arah 120 derajat atau merah (penunjuk ke kiri) 150 derajat. Pernah juga terlihat ada perubahan arah yang bertolak belakang. Jadilah kami beramai-ramai mengangkat sajadah. Salat zuhur dan asar biasanya dilakukan di dekat ruang tidur atau di Salon. Yang terakhir ini bukan ruang untuk berdandan, melainkan ruangan buat menerima tamu.
Ruangan itu cukup luas, berukuran sekitar 9 x 4 meter dengan empat jendela dan berkarpet merah. Dua sofa cokelat gelap berbentuk L, masing-masing dengan meja berukir, mengisi ruangan itu. Foto Presiden dan Wakil Presiden RI serta Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut terpampang pada dinding kayu. Lukisan Bima bergelut dengan naga disaksikan Dewa Ruci juga dipasang. Foto-foto lawas tentang pembuatan dan perjalanan KRI Dewaruci, beberapa plakat penghargaan, serta miniatur Dewaruci juga menghiasi ruangan itu. Ruangan ini bisa menampung tiga orang yang hendak bersalat. Ihwal arahnya, patokannya tentu kompas di telepon seluler.
Kehilangan sinyal seluler dan Internet menjadi hal lumrah di tengah laut. Sinyal biasanya muncul saat mendekati daratan. Saat itu semua orang segera bergegas ke geladak atau lorong geladak J. Para anggota Laskar lekas mengunggah konten mereka, para ABK menghubungi anggota keluarga, dan beberapa jurnalis pun mengirim berita. Sering pula, ketika mereka sedang berselancar di dunia maya, tiba-tiba sinyal kembali hilang. Jika sudah begitu, biasanya mereka duduk-duduk di geladak menjemput senja. Ada pula yang kembali tidur dan lanjut mengetik. Saat senja tiba, peluit akan berbunyi. Ada perintah berdiri sempurna menghadap arah bendera di atas anjungan. Itulah waktu penurunan bendera Merah Putih yang dikibarkan sejak pagi. Setelah itu, azan magrib berkumandang. Orang-orang bergegas mengambil air wudu.
Memasuki ujung Pulau Sumatera, mendekati Pulau Weh, Aceh, ombak masih cukup tinggi. Arusnya juga kuat. KRI Dewaruci berhasil melaluinya dan melego jangkar menjelang subuh. Kapal tiba di teluk yang dikelilingi pulau. Kapal semula bersandar agak jauh dan sedikit miring. Jangkar seperti tak bisa “makan”—istilah para ABK bahwa jangkar sudah menancap kuat. Angin terlalu kencang berembus sehingga akhirnya kapal bergerak merapat ke dermaga dengan dipimpin langsung oleh komandan. Kapal kembali ke Sabang, Aceh. Kapal ini pertama kali singgah di Sabang dalam perjalanan muhibah keliling dunia pada 16 Maret 1964. Dewaruci membawa 110 awak saat itu.
Sampai di dermaga pagi, semua orang tak boleh keluar dari kapal hingga esok untuk penyambutan. Jadilah rombongan seperti orang yang dikarantina. Padahal lambung kapal sudah menempel pada beton dermaga. Malamnya, Nasrul Hamdani dan Miftah Roma, dua narasumber dari Medan dan Aceh, memesankan kopi Gayo dan kopi sanger, yang diantarkan oleh kolega mereka ke kapal. Jadilah malam itu sebagian undangan menikmati kopi bumi Aceh.
Setelah empat hari tiga malam, anggota rombongan tak sabar mencuci baju. Mencuci dengan mesin hanya dibolehkan untuk awak kapal. Itu pun dilakukan saat buang sauh. Sedangkan anggota rombongan baru bisa mencuci baju saat mendarat, misalnya dengan mencari penyedia jasa cuci ketika singgah di Sabang dan menggunakan mesin cuci koin tatkala berlabuh di Melaka. Beruntung ada penyedia jasa mesin cuci koin 24 jam karena mencuci baru bisa dilakukan saat malam, seusai kegiatan. Setidaknya dibutuhkan waktu satu setengah hingga dua jam, tergantung banyaknya cucian. Saat berada di Sabang, tiba-tiba rombongan harus checkout dari hotel, padahal masih ada cucian pakaian dalam. Jadilah cucian itu diangkut basah-basah dan dikeringkan dengan dicantolkan pada tongkat di kamar di bawah penyejuk udara.
•••
DI Sabang, rombongan disambut pejabat setempat dengan tradisi peusijuek—penaburan seperti tepung tawar. Komandan kapal dan beberapa anggota rombongan menjadi perwakilan. Sebuah pertunjukan kolosal garapan sutradara Fauzan Santa dan penulis naskah Azhari Aiyub berjudul Pasar Abad 17 disuguhkan. Sangat menarik. Puluhan seniman teater dari Banda Aceh dan Sabang dilibatkan. Pertunjukan ini seperti mesin waktu yang membawa gambaran abad ke-16, ketika bandar Kesultanan Aceh Darussalam menjadi bandar penting untuk perdagangan rempah. Bandar ini digambarkan berada di persimpangan rute dagang Asia dengan Eropa, yang menjadi rantai pasokan komoditas seperti rempah, kain, emas, gajah, dan budak.
Fauzan dan Azhari mendiskusikan konsep, improvisasi aktor, dan struktur cerita. Azhari merapikannya dengan narasi yang ia gali dari berbagai dokumen dan hasil riset serta beberapa buku bacaan tentang sejarah Aceh, rempah, dan Kesultanan Aceh pada abad ke-16 hingga ke-17. Beberapa bagian novelnya ia nukil untuk naskah ini. Pertunjukan itu seperti memperlihatkan betapa bandar Aceh menjadi tempat yang kosmopolitan.
“Pertunjukan ini seperti mesin waktu, ada keterlibatan penonton keluar-masuk, sehingga penonton bisa masuk langsung ke dimensi dan lingkungan masyarakat yang berbeda sesuai dengan cerita yang dibangun,” kata Fauzan. Di Dermaga CT-1 Sabang, terdapat belasan gubuk. Belasan orang menggelar lapak dagangan. Ada pula lapak permainan catoe rimung (catur harimau). Beberapa orang berdandan seperti pedagang Turki, India, Eropa, dan Cina. Lagak mereka agak congkak. Sejumlah saudagar perempuan tampak dipayungi pengawal mereka.
Sementara itu, beberapa penjaga pasar berteriak-teriak mengusir para pengemis yang mengais rezeki dari para saudagar. Saat itu cerita memperlihatkan lelang merica dan budak. Seorang pria dengan kostum merah menyala menjadi pelelangnya. “Hari ini kita kedatangan banyak pedagang asing untuk melihat merica terbaik di Aceh Darussalam. Kita mulai. Kami buka dengan harga 40 dirham Aceh atau 1.000 dolar Spanyol. Hati-hati, jaga uang Anda,” ucapnya.

Adegan lelang rempah dan budak dalam pertunjukan "Pasar Abad 17", di Pelabuhan BPKS Sabang, Aceh. Tempo/Dian Yuliastuti
Setelah itu, rombongan menikmati perjamuan tradisi idang meulapeh dan pembuatan kuah beulangong, sayur berbahan daging, nangka, dan pisang muda yang kaya rempah, sajian kuliner asli Bumi Rencong yang merupakan artefak budaya rempah.
Dari Sabang, rombongan menyeberang ke Banda Aceh esoknya. Sejumlah tempat dikunjungi, antara lain Museum Aceh, Gunong Sari, dan Pendopo Gubernur Aceh yang merupakan situs bersejarah. Di Museum, selain melihat peta perjalanan jejak Jalur Rempah, rombongan bisa menyaksikan aneka keramik, salinan manuskrip Sulalatus Salatin, juga lonceng Cakra Donya. Lonceng kapal ini adalah artefak yang tersisa dari masa kejayaan Kerajaan Samudera Pasai, hadiah Laksamana Cheng Ho dari Kerajaan Cina kepada Kerajaan Pasai pada 1414. Tempo juga menyinggahi makam Sultan Iskandar Muda yang berada di dekat Museum Aceh dan Pendopo Gubernur—bangunan peninggalan Belanda.
Di masa Pangeran Perkasa Alam, yang dikenal sebagai Sultan Iskandar Muda, menurut sejarawan Universitas Negeri Malang, Jawa Timur, Daya Negri Wijaya, ia tidak memperbolehkan monopoli dan mengizinkan perdagangan bebas. “Semua orang boleh berdagang di Aceh dan kondisi Aceh makin baik. Menjadi Aceh yang kosmopolitan pada 1606,” ujarnya dalam pembekalan di KRI Dewaruci. Saat itu konon rempah-rempah didatangkan ke Aceh, terutama lada, meski kualitasnya tidak sebaik rempah Sumatera bagian selatan dan barat Jawa.
Daya membeberkan koneksi dan kondisi Aceh serta Melaka dari kronik-kronik yang ditulis rohaniwan Portugis. Catatan ini berasal dari arsip di Portugal pada abad ke-16 hingga ke-17. Salah satunya catatan Dom Joao Ribeiro Gaio yang menjadi Uskup Melaka (1578-1601) dan Kapten Melaka (1587-1588) yang mengisahkan serba-serbi Aceh serta strategi penaklukannya dalam teks dan konteks “Roteiro das Cousas Do Achem: Fontes Primordiais Do Seculo XVI Sobre Achem Os Portos Da Costa Norueste De Samatra”.
Daya, doktor lulusan Universidade do Porto, Portugal, menjelaskan bahwa saat itu tercatat Sultan Salehudin menyerang Melaka dengan 2.000-3.000 personel pasukan pada 1537, tapi dapat dikalahkan oleh Portugis dan dilengserkan pada 1538. Aceh dan beberapa kerajaan bawahannya menyerang Melaka lagi pada 1547. Lalu Aceh dan Aliansi Islam (Ottoman) kembali menyerbu Melaka pada 1568. Penyerangan terjadi lagi pada 1572 oleh Aceh tanpa menunggu bantuan dari Jawa. Aceh kembali menggempur Melaka dan gagal pada 1575. Serangan Aceh pada 1583, Daya menambahkan, membuat risau Kapten Melaka Roque de Mello. Dia lalu meminta bantuan Luis Monteiro Coutinho untuk menangkal serangan Aceh. “Tapi kapalnya dibakar dan dia ditawan bersama 12 orang Portugis lainnya,” katanya. Sempat melarikan diri ke Pidie tapi kemudian kembali ditangkap, Coutinho dieksekusi di Aceh dengan disaksikan dua orang Portugis, Diogo Gil dan Tomas Pinto.
Dari Sabang, rombongan menuju Melaka setelah menyusuri rute awal. Kapal melego jangkar tak jauh dari Tanjung Bruas, pelabuhan di Melaka, sehari sebelum penyambutan. Di kejauhan, pelangi muncul tepat saat rombongan merayakan ulang tahun Komandan KRI Dewaruci dengan acara potong tumpeng. Agak siang, beberapa anak buah kapal berbaju selam sibuk di dekat palka. Rupanya, baling-baling kapal terlilit jaring nelayan. Beberapa awak kapal, termasuk dua penyelam, turun membereskan lilitan itu.
Esoknya, di Tanjung Bruas, rombongan disambut Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid. Di Muzium Rakyat, diselenggarakan acara penyambutan oleh Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono, serta anggota Executive Council Pelancongan, Warisan, Seni, dan Budaya Melaka Datu Wira Abdul Razak bin Abdul Rahman. Mereka sekaligus membuka pameran arsip dokumen dan foto tentang rempah di tenda di depan museum, tak jauh dari kawasan pusat sejarah Melaka yang ramai oleh beragam turis. Keterangan arsip dokumen dan foto hanya tersedia dalam bahasa Indonesia.
•••
MELAKA adalah kota tua dengan jejak masa lalu yang masih kental. Pengunjung kota ini seperti diseret ke ruang dan waktu pada masa lampau. Di kawasan kota tua bisa dijumpai bangunan-bangunan kuno khas Eropa. Tak jauh dari Muzium Rakyat, terdapat replika Istana Sultan Melaka. Tapi replika ini konon jauh lebih kecil dari aslinya. Menurut keterangan pemandu wisata, istana yang asli tiga kali lipat lebih luas dan tujuh kali lipat lebih tinggi dari bangunan ini. Tak jauh dari replika gedung istana bercat cokelat tua ini, terdapat sepotong gerbang bekas benteng yang dikenal sebagai A Famosa atau pintu gerbang Santiago. Tersusun dari batu laterit dari Pulau Upeh, Pulau Jawa, dan Pulau Panjang—masih kokoh, berwarna tembaga dan putih, terdapat relief di bagian atasnya—benteng ini dibangun oleh Alfonso de Albuquerque pada 1511.
Di belakang benteng, terdapat jalan berundak menuju bukit yang dinamai Bukit Melaka yang sebelumnya dikenal sebagai Bukit St. Paul saat dikuasai Belanda pada 1641. Sebelum Belanda datang, saat Portugis menguasai Melaka, bukit ini dikenal dengan nama Nossa Senhora do Oiteiro dan Monte Dalimaria. Portugis datang pada 1510 dan menaklukkan Melaka pada 1511.
“Di situlah sebenarnya letak istana dan kompleks tempat tinggal para pembesar, tapi kemudian dihancurkan. Di kemudian hari dibangun gereja, menjadi Gereja St. Paul,” ucap B.H. Ahmad Sabri, sang pemandu. Ia menuturkan, benteng saat itu pasti tebal karena kerajaan baru bisa ditaklukkan setelah 10 hari. Tak jauh dari Stadthuys di samping masjid juga ada sebuah bekas benteng dengan beberapa meriam. Menariknya, terdapat dua sisi benteng yang berbeda zaman. Satu bidang dibangun di era Portugis, satu bidang lagi pada zaman Belanda. Juga ada sebuah kincir air dari era Kesultanan Melaka.
Dari atas bukit, kita bisa memandang Kota Melaka hingga birunya Selat Malaka di kejauhan. Di puncak bukit itu, terdapat bangunan yang dikenal sebagai Gereja St. Paul dengan patung Xavier, pendeta Prancis bertangan buntung, di depannya. Mulanya tempat bukan gereja, melainkan kapel Persatuan Jesuit. Setelah 1753, aktivitas keagamaan di sana berhenti, lalu tempat ini dipakai sebagai pekuburan. Di dalam dan sekitar reruntuhan bangunan, terdapat banyak batu nisan besar, seperti di Museum Wayang dan Museum Prasasti di Jakarta.

Suasana di kawasan titik nol Malaka, Malaysia. Tempo/Dian Yuliastuti
Masih menurut pemandu, gerbang benteng yang sesungguhnya ada di menara jam besar di depan Stadthuys dan Gereja Chris Melaka (dibangun Belanda pada 1753) yang bercat merah bata. A Famosa pada era Portugis awalnya adalah kubu pertahanan yang dibuat untuk menangkal berbagai serangan yang kemudian dihancurkan Belanda. Benteng ini dibuat di atas bekas masjid Melaka. Di masjid biasanya juga terdapat nisan para sultan. Tapi semuanya dimusnahkan. Sultan Alaudin atau Sultan Mahmud tewas ditikam sehingga mengakhiri era Kesultanan Melaka.
Turun dari bukit dari sisi yang lain, ada Stadthuys yang dijadikan Muzium Sejarah dan Etnografi. Di sinilah segenap artefak, arsip, dokumen, dan foto tentang sejarah Melaka digelar. Termasuk yang cukup menarik adalah mata uang dari timah berbentuk hewan seperti kura-kura, buaya, dan ayam. Materi ditata berdasarkan masa penguasaan bangsa Barat, dari Portugis, Belanda, Inggris, hingga kembali ke Belanda.
Di bagian belakang terdapat Galeri Laksamana Cheng Ho, yang sepi, tak banyak dikunjungi orang. Di samping bangunan terdapat patung Cheng Ho. Galeri ini berisi narasi hubungan Kesultanan Melaka dengan beberapa dinasti Cina, dari Dinasti Tang (618-907), Song (960-1279), Yuan (1279-1368), hingga Ming (1368-1643).
Hubungan baik dimulai dari hubungan dagang dari lawatan Yin Ching pada 1403 dan politik dengan pengiriman utusan Raja Cina Yung Lo. Laksamana Cheng Ho melawat ke Melaka dua kali, memperingatkan Kerajaan Ayuthia, negeri Thai, agar tidak mengganggu Kerajaan Melaka. Raja Parameswara membalasnya dengan kunjungan ke Cina beserta 500 pedagang dan kerabat istana, juga dua kali lawatan lain. Hadiah emas, perak, sutra, porselen, dan uang diberikan kepada Parameswara.
Di museum itu ditampilkan berbagai teks narasi, surat dari Dinasti Ming, daftar waktu lawatan Sultan Melaka, keramik, dan peralatan tembaga, juga replika beragam kapal Cheng Ho. Ada biografi Cheng Ho, juga rute dan seri pelayaran serta jejak kunjungannya di Malaysia dan tempat lain di dunia, termasuk di Indonesia. Di Jalan Hang Jebat, tak jauh dari Jalan Jonker yang terkenal, terdapat Muzium Budaya Cheng Ho, museum pribadi yang didirikan oleh Tan Ta Sen, Presiden Masyarakat Internasional Cheng Ho. Ia pernah diberi penghargaan oleh Borobudur Writers & Cultural Festival. Museum ini juga menyimpan berbagai informasi dan artefak tentang Cheng Ho.
Saya juga menyempatkan diri mampir ke perkampungan Portugis di wilayah Ujong Pasir, tak sampai 5 kilometer dari area kota tua Melaka. Sebuah patung Kristus bercat putih kokoh dengan kedua tangan terentang. Tak jauh dari perempatan tempat patung itu berada, terdapat rumah-rumah keturunan Portugis, yang sering disebut Serani. Ada pula replika rumah tradisional yang pertama kali disediakan untuk warga Serani saat mereka ditempatkan di Ujong Jurong pada 1930-an. Di hadapan rumah tradisional itu, berdiri sebuah kapel bercat putih dengan patung Maria di sisi depan kiri dihiasi bunga aster berwarna merah dan putih.
Sayangnya, museum di sana tutup. Saat diintip dari jendela kaca, museum seperti tak terawat. Agak ke belakang, terdapat deretan kantin. Di sanalah para Serani membuka restoran boga bahari ala Portugis. Saya berjumpa dengan seorang perempuan Indonesia yang mengaku bernama Rahma, asal Sampang, Madura, Jawa Timur, yang sudah 27 tahun bekerja di sana. Ia bekerja pada pasangan keturunan Portugis yang mempunyai restoran bernama Joan & El Chicco’s.
Selepas dari Melaka, rombongan bertolak ke Tanjung Uban, Kepulauan Riau, dalam pelayaran 22 jam saja. Rombongan turun di Pelabuhan Lanal Bintan di Tanjung Uban. Pulau Penyengat dan Tanjungpinang menanti untuk dieksplorasi. Di Tanjungpinang, Raja Farul, pemandu kami dari Komunitas Kelompok Sadar Wisata Pulau Penyengat, menyambut dengan gurindam sembari meminta rombongan membayangkan betapa sibuknya pelabuhan Sri Bintan Pura pada abad ke-16 hingga ke-17. Pelabuhan yang dulu ramai di era perdagangan rempah. Kami menyusuri sebuah ruas jalan bernama Jalan Gambir yang masih hidup dengan transaksi ekonomi. Jalan ini dulu adalah pusat perdagangan gambir. Tak jauh dari Tanjungpinang, di daerah Senggarang, konon terdapat gudang-gudang gambir.
Menurut Anastasia Wiwik, sejarawan Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, pada 1687, kota-kota di sepanjang Sungai Johor dan Riau, yang merupakan bagian dari Kerajaan Johor, menjadi pusat perdagangan seperti keterangan Gubernur Melaka Thomas Slicher dalam suratnya ke Batavia pada Mei 1687. Pasang-surut ekonomi terjadi. Wiwik mengatakan Riau kembali berjaya saat pemerintahan Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah pada 1722. Sultan Sulaiman juga menggerakkan penanaman gambir. Riau pun menjadi salah satu pusat perdagangan yang penting dan menentukan di Asia Tenggara. Pusat perdagangan di Pelabuhan Riau yang terletak di Ulu Sungai Carang menjadi tempat transaksi. Meski tidak memproduksinya, masyarakat Riau mampu menyediakan komoditas itu.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Dian Yuliastuti melaporkan dari Dumai, Sabang, Melaka, dan Tanjungpinang.