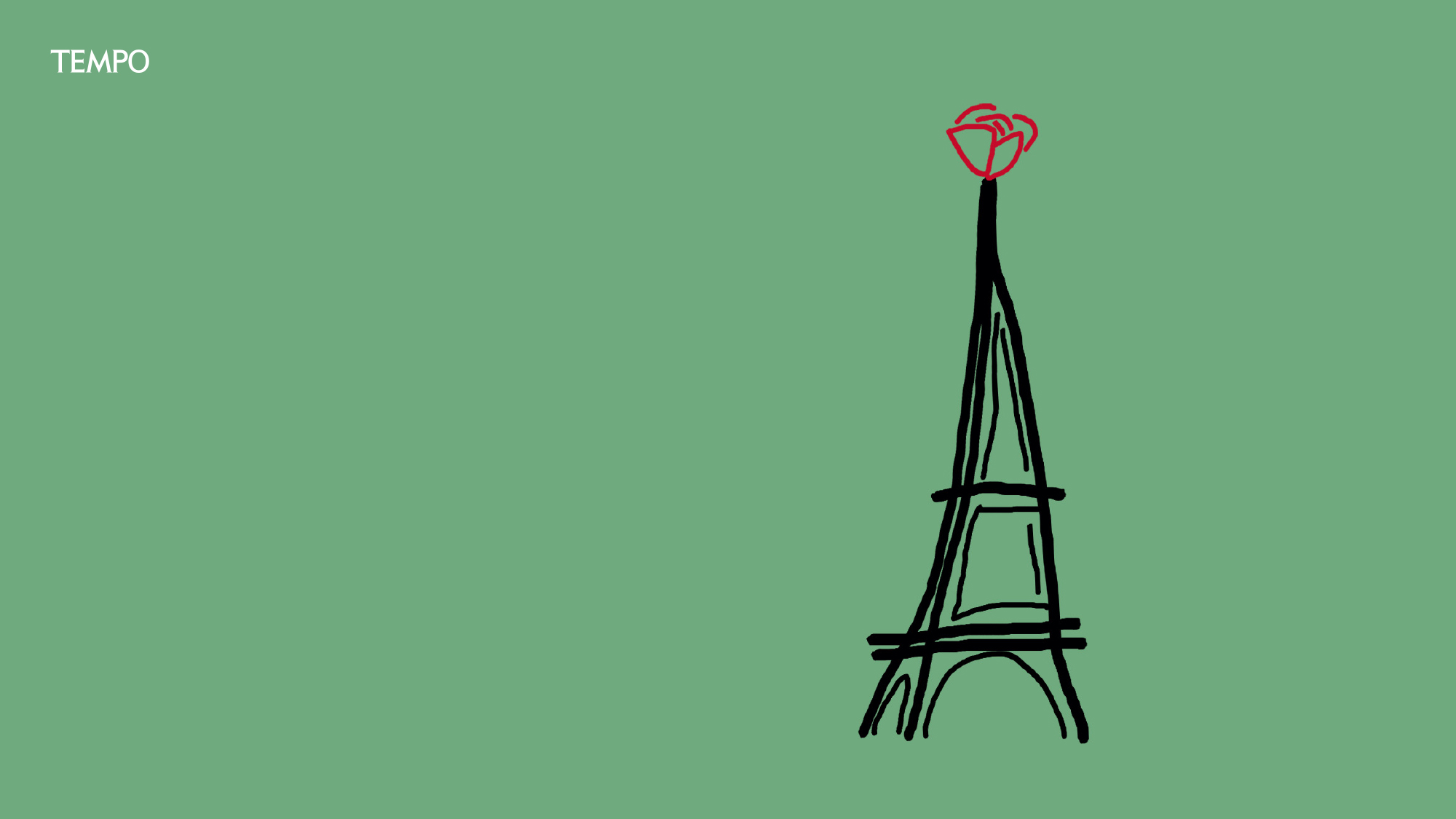Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“[T]he new autocrats come to power not with bullets but with laws….”
~ Kim Lane Scheppele, 2018
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
PELURU dan tendangan sepatu lars telah berganti dengan kata-kata yang diberi lambang kekuasaan. Pada masa lampau, raja dan penjajah mengusir orang miskin dan mengambil tanah mereka dengan serdadu dan senjata. Saat ini mereka cukup datang ke kantor pertanahan dan membuat sertifikat dengan payung peraturan yang ia buat sendiri, lalu menggunakan aparat bersenjata yang bisa mereka perintahkan untuk mengambil tanah itu. Hasilnya sama, alatnya berbeda.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Tentu saja, narasi di atas hanya bisa terjadi saat penguasa memang ingin mengambil kepentingan sebesar-besarnya dari kekuasaan yang dimilikinya. Penguasa seperti ini visi kepemimpinannya bukan moralitas politik, melainkan akumulasi kekayaan dan kekuasaan. Sayangnya, inilah yang terjadi dalam sepuluh tahun belakangan.
Dalam negara hukum, hukum negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dibuat oleh orang-orang yang punya otoritas. Tapi gagasan negara hukum sebenarnya berdiri pada landasan moral publik. Ia berpijak pada hak asasi warga negara dan pembatasan kekuasaan sehingga pembentukan hukum dipagari secara ketat oleh proses yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel. Maka semua proses pembentukan undang-undang harus terbuka agar ada deliberasi yang cukup. Hal ini diperlukan agar ide yang disokong dengan alasan dan data terkuat yang dipilih menjadi muatan sebuah undang-undang. Begitu pula hakim, jaksa, dan advokat terikat oleh prosedur ketat sebelum bisa membuat putusan.
Apa lacur, penguasa yang culas tahu persis proses yang ketat itu penghalang yang harus mereka hancurkan agar bisa makin berkuasa dan bermodal. Karena itulah pertama-tama mereka akan meruntuhkan segala institusi dan prosedur yang bisa membuatnya akuntabel. Begitu institusi bisa dibajak, hukum bisa dibentuk menjadi apa saja dengan mudah.
Bagi kekuasaan tanpa moral, penghalang yang harus dihancurkan pertama kali adalah kekuatan penyeimbang dalam lembaga legislatif. Tak sulit meredakan oposisi di sana di tengah situasi umum partai politik yang elitis dan berlaku seperti kartel. Kursi menteri dan jabatan strategis menjadi alat tukarnya. Transaksi ini menarik bagi partai-partai karena jabatan tak hanya mengandung status sosial, tapi juga akses terhadap penggunaan anggaran. Sejak 2014 sampai sekarang, ada empat menteri yang terbukti melakukan korupsi dan satu menteri yang tengah menjalani proses pengadilan.
Kekuatan oposisi dari luar kekuasaan formal juga harus dilumpuhkan agar tak berisik mengkritik dan mengungkap kebenaran. Pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, tak sedikit aktivis yang diajak bergabung ke pemerintahan, yang akhirnya membuat mereka tak lagi bersuara lantang. Di sisi lain, mereka membungkam aktivis, jurnalis, dan kelompok-kelompok prodemokrasi yang menolak tunduk dan kukuh mengkritik dengan kekerasan fisik, serangan digital, dan kriminalisasi.
Penjaga akuntabilitas berikutnya yang harus dibajak untuk membuat kekuasaan tak diganggu gugat adalah penegak hukum. Kepolisian, kejaksaan, dan hakim agung punya sejarah panjang dalam kebobrokan sistem penegakan hukum Indonesia sejak Orde Baru. Maka kepentingan-kepentingan bisa bertemu dengan mudah.
Komisi Pemberantasan Korupsi juga tak luput dari radar kekuasaan. Pada 2019, upaya menghancurkan KPK dilakukan dengan dua langkah: merevisi Undang-Undang KPK dan memasukkan pimpinan bermasalah. KPK tak lagi independen dan tidak bisa bekerja efektif karena konflik internal yang terbangun dari kekacauan organisasi. Belakangan, KPK juga kerap digunakan untuk tujuan menghajar lawan politik sehingga Koran Tempo menyebutnya dalam editorial sebagai “Komisi Politisasi Korupsi”.
Di sisi lain, Mahkamah Agung sebagai kekuasaan yudikatif yang terpisah dari eksekutif seharusnya dijaga independensinya dalam konstitusi. Namun korupsi hakim dan petugas pengadilan lain, ditambah pengawasan yang minim, menimbulkan situasi yang menguntungkan untuk siapa saja yang punya uang dan kekuasaan.
Yang terakhir adalah dirobohkannya Mahkamah Konstitusi. Baru pada masa pemerintahan Jokowi seorang hakim bisa diganti di tengah masa jabatan karena putusan yang dibuatnya. Penggantian ini salah secara prinsip karena melanggar independensi kekuasaan kehakiman dan ilegal lantaran melanggar undang-undang. Tapi Jokowi melegalisasinya dengan keputusan presiden. Hari ini, undang-undangnya akan segera diganti untuk melegalkan praktik yang salah itu. Tak berhenti di situ, hubungan perkawinan menciptakan situasi konflik kepentingan yang luar biasa antara Jokowi dan mantan Ketua MK, Anwar Usman.
Moda operasi kekuasaan seperti ini banyak muncul di berbagai belahan dunia. Para pembelajar hukum menyebutnya “autocratic legalism”, yaitu penggunaan hukum untuk melegitimasi tindakan-tindakan yang otokratik atau kekuasaan nirkontrol (Corales, 2015; Scheppele, 2018). Fenomena legalisme otokratik terjadi, antara lain, di Hungaria, Venezuela, Rusia, dan Turki. Pembajakan institusi-institusi secara legal dilakukan agar kekuasaan tak lagi bisa diawasi—dari demokrasi menjadi otokrasi. Studi komparasi di negara-negara tersebut menunjukkan pola yang sama: perubahan konstitusi untuk membuat hukum tertinggi itu longgar bagi penguasa. Biasanya, ujungnya adalah menghapus periode kekuasaan.
Sepuluh tahun terakhir, cara pandang legalistik memang kuat. Apa saja yang sudah diberi cap sebagai hukum seakan-akan menjadi kebenaran, meskipun akal budi dan kemanusiaan kita mengatakannya itu salah. Pada periode kedua Jokowi, penguasa memasuki “masa panen” legalisme otokratik.
Setelah akuntabilitas kekuasaan roboh, mudah saja membuat undang-undang secepat kilat dan tanpa partisipasi bermakna, seperti Undang-Undang Cipta Kerja, revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Undang-Undang Ibu Kota Negara. Begitu pula dengan hukum dalam bentuk putusan pengadilan. Sebut saja putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Jokowi, menjadi calon wakil presiden. Juga putusan Mahkamah Agung yang membuat Kaesang Pangarep, anak bungsu Jokowi, bisa menjadi calon gubernur.
Pemerintah Jokowi juga membuatkan perangkat legal bagi mekanisme penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu secara non-yudisial tanpa upaya mengungkap kebenaran. Sementara itu, berbagai pelanggaran HAM masih terus terjadi atas nama pembangunan, seperti penggusuran dengan kekerasan. Bentuk pelanggaran HAM lain dalam proses penegakan hukum juga kerap terjadi, seperti penyiksaan dalam penegakan hukum, salah tangkap, dan pengabaian laporan. Tagar #percumalaporpolisi dan #noviralnojustice di media sosial menjadi simbol perlawanan terhadap penegakan hukum yang tak berfungsi itu.
Kerusakan hukum bisa dilihat dalam dua wilayah: korupsi dan pelanggaran hak asasi. Keduanya dilakukan secara sistemik dengan menggunakan kekuasaan negara (state capture), dalam bentuk produk hukum. Tapi yang dirusak oleh pemerintahan Jokowi sebenarnya bukan hanya institusi-institusi hukum, melainkan juga bangunan negara hukum kita.
Yang menyedihkan, cukup banyak warga yang tak menyadari semua kerusakan itu. Pendidikan kewarganegaraan kadung mencekoki kita dengan gagasan bahwa warga negara yang baik harus mematuhi tindakan yang dilakukan dengan landasan hukum atau oleh orang yang punya otoritas berdasarkan hukum, tanpa kritik. Tak menjadi soal apakah hukum itu adil dan apakah hukum tersebut ternyata berdampak buruk. Keabsahan menjadi landasan kebenaran.
Kelas menengah di kota besar pada umumnya tak memahami perusakan negara, karena yang mereka lihat dan rasakan adalah kemegahan pembangunan. Pemerintahan Jokowi yang populis sangat tekun mengolah informasi dan memelihara pendengung sehingga sebagian besar warga juga tak menyadari kerusakan hukum yang tak terlihat secara kasatmata. Scheppele (2018) menulis: “How many people can really see this until they themselves need constitutional protection and find themselves defenseless? By then it is too late.”
Negara hukum pada prinsipnya adalah soal hak asasi manusia dan pembatasan kekuasaan. Dalam sepuluh tahun terakhir, keduanya diobrak-abrik. Hukum hanya dilihat sebagai alat penguasa dalam memperbesar kekuasaan dan mengakumulasi kekuasaan untuk elite. Penguasa culas menggunakan hukum sebagai tameng bagi segala tindakannya.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo