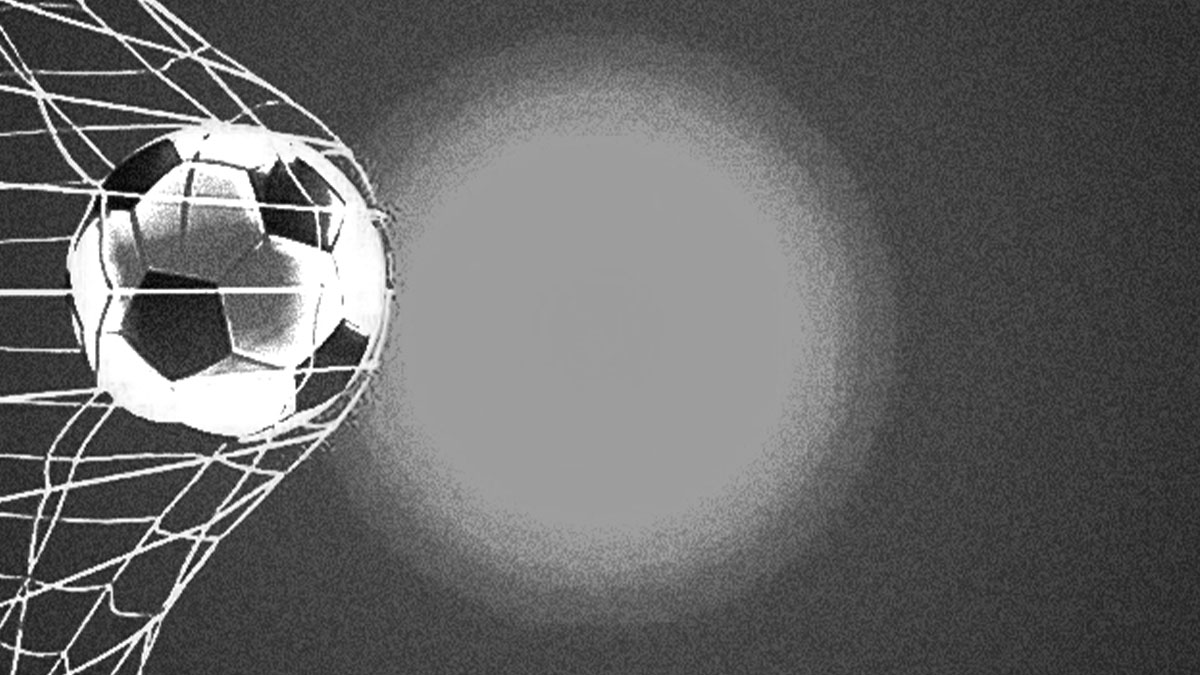Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
YANG membedakan Mohammad Hoesni Thamrin dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional lain dalam soal sepak bola, bahkan dibanding Soeratin sekalipun, adalah ketajamannya melihat (lapangan) sepak bola sebagai medan perang perebutan ruang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Michael Charles Williams menggambarkan betapa sulitnya kaum pergerakan radikal di Banten. Mereka terpaksa sembunyi-sembunyi dan menyaru di acara hajatan dan selamatan atau pura-pura nonton film di bioskop padahal sedang berkoordinasi. Pertandingan sepak bola di kampung juga kerap dimanfaatkan untuk menggelar rapat. Kadang malam hari mereka berkumpul di tengah lapangan sepak bola yang gelap gulita (Communism, Religion, and Revolt in Banten, 1990, halaman 168).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

M.H Thamrin bukan anggota gerakan radikal (nonkooperatif). Dia memilih jalur kooperatif dengan memasuki Dewan Kota dan Volksraad. Namun ia juga menyadari persoalan ruang tersebut karena kota-kota besar masa itu, termasuk Batavia, memang dirancang untuk melayani, sekaligus mencerminkan diskriminasi rasial khas kolonial.
Tak lama setelah membeli bangunan di Gang Kenari pada 1927, Thamrin menghibahkannya untuk dipakai sebagai ruang pertemuan segala bangsa, terutama untuk agenda politik emansipasi kaum pergerakan. Gedung di Kenari (kini menjadi Museum M.H. Thamrin) menjadi antitesis dari ruang-ruang eksklusif seperti societeit atau perumahan elite di Menteng, yang pembangunannya diprotes Thamrin, yang tak hanya melanggengkan diskriminasi rasial, tapi juga menyumbat mobilitas orang Betawi di tanahnya sendiri.
Langkah Thamrin membeli lapangan di Laan Trivelli pada 1931 dan memugar lapangan di Petojo menjadi stadion bagi kaum bumiputra (terutama Voetbalbond Indonesische Jacatra atau VIJ) berlatih dan bermain sepak bola pada 1936 menjadi penegasan atas tajamnya kesadaran dia ihwal pentingnya merebut atau menciptakan ruang yang aksesibel, inklusif, dan demokratis bagi warga bumiputra.
Sulitnya kaum bumiputra bermain bola di tempat yang layak tidak hanya dialami VIJ di Jakarta, tapi juga bond sepak bola bumiputra di berbagai kota, misalnya Persib di Bandung, dan negeri-negeri jajahan lain. Kaum bumiputra meresponsnya secara tipikal: mulai dengan mengorganisasi diri dengan membuat bond sepak bola, lalu berusaha menciptakan ruang sendiri untuk bermain bola.
Front de Libération Nationale dalam riwayat pergerakan kemerdekaan Aljazair, misalnya, memaksimalkan tim-tim sepak bola bumiputra, seperti Mouloudia Club Algérois, untuk menajamkan identitas antikolonial. Kegilaan Rabah Zerari muda terhadap sepak bola hanya bisa dialihkan oleh agenda pembebasan Aljazair dari penjajahan Prancis. Kelak, setelah menjadi pemimpin gerilya berjulukan Commandant Azzedine, ia menyatakan dalam memoarnya bahwa “olahraga adalah sekolah nasionalisme bagiku dan lapangan sepak bola adalah medan perang pertamaku”.
Bandingkan dengan LONA di Sumatera Barat. Kesebelasan tersebut rupanya menjadi cawan petri bagi kecambah kaum radikal di Pariaman. LONA lantas menjadi organ antikolonial bawah tanah bernama Barisan Merah, yang bersama Sarikat Djongos, Sarikat Itam, dan lain-lain, menjadi bagian tak terpisahkan dari radikalisasi kaum komunis Sumatera Barat yang meledakkan perlawanan bersenjata pada Januari 1927 di Silungkang (The Communist Uprising of 1926-1927 in Indonesia, 2009, halaman 147-164).
Thamrin menjadi khas karena tindakannya dalam membangun ruang baru itu bisa dibilang koheren dengan fokus utamanya sebagai politikus dan perwakilan masyarakat Betawi. Thamrin nyaris tak pernah berhenti membicarakan, memprotes, hingga mengusulkan berbagai isu dan solusi mengenai ruang yang adil bagi warga bumiputra.
Biografi Thamrin yang paling luas karya Bob Hering (Mohammad Hoesni Thamrin: Membangun Nasionalisme Indonesia, Hasta Mitra, 2003) memuat daftar panjang persoalan ruang yang dikemukakan Thamrin di Dewan Kota: sesaknya pondokan kaum miskin di pinggiran kota, buruk dan sempitnya jalan kampung, hingga perkara penerangan jalan. Di Volksraad, ia menentang tujuan sosiopolitik Indo-Europeesch Verbond untuk mendapatkan tanah bagi golongan minoritas Indo Eropa.
Kesadaran dan ketajaman Thamrin dalam melihat problem ruang itu membuatnya sampai memikirkan sempit dan dangkalnya saluran air sehingga ia mengusulkan program pengerukan dan pendalaman saluran. Ia bahkan memikirkan ruang bagi orang mati: memprotes diskriminasi rasial mengenai biaya kepemilikan makam di Batavia.
Bisa dipahami jika Thamrin pernah dengan sadar mengutip utuh deskripsi koleganya di Dewan Kota, V.J. van Marle, tentang Batavia yang menggunakan analogi spasial (cetak miring dari saya): “Batavia masih seperti lukisan dengan pigura bagus… sementara kampung-kampung terwakili pada kanvas tak berharga.”
Berbeda dengan tokoh-tokoh lain yang geraknya berpindah-pindah kota bahkan negara, Thamrin lahir, tumbuh dewasa, berkiprah, bahkan meninggal dan dimakamkan di kota yang sama. Riwayat itulah yang memungkinkannya menyadari pentingnya—dengan merujuk pada konsep Lefebvre—“hak atas kota” secara konsisten.
Sebagai magnet penarik massa, karena begitu cepat disukai berbagai kelas sosial, sepak bola menjadi isian (content) yang menarik bagi ruang-ruang baru yang dicoba diciptakan Thamrin. Ia meletakkan sepak bola sebagai penggerak emansipasi di dalam dan melalui ruang-ruang yang spesifik (lapangan sepak bola).
Sepak bola modern sebagai permainan yang dilahirkan bangsa kulit putih (sastrawan Argentina, Jorge Luis Borges, menyebut sepak bola sebagai “dosa bangsa Inggris yang sukar dimaafkan”) diambil alih kaum pergerakan menjadi “senjata makan tuan”. Sepak bola sebagai olahraga beregu yang memungkinkan bentrok fisik sangat cocok untuk menggambarkan kekontrasan, sekaligus konflik, antara “kaum sini” dan “kaum sana”. Kategorisasi “sana” dan “sini” ini memudahkan usaha mempertebal identitas “kami” sebagai—dengan mengutip Medan Prijaji—“bangsa jang terprentah”. Melalui “kaum sana” dan “kaum sini” serta “kami” itu, persatuan menjadi lebih mungkin diusahakan.
Membentuk Front Nasional di Volksraad serta bergabung dengan Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia, Partai Indonesia Raya, dan koalisi besar Gabungan Politik Indonesia menjadi sekelumit usaha Thamrin menjahit persatuan kaum nasionalis moderat yang mengalami kesulitan setelah Gubernur Jenderal Bonifacius Cornelis de Jonge (1931-1936) mengambil haluan ultrakonservatif. Pembelaannya terhadap para tokoh yang ditangkap dan dibuang (seperti Sukarno) membuatnya sentral dalam merawat keterhubungan antara barisan kooperatif dan nonkooperatif.
Dalam statusnya sebagai satu dari sekian banyak tokoh berhaluan kooperatif itu, Thamrin dinilai R.G.A.Z. Kiewiet de Jonge sebagai anggota Volksraad “paling kiri”; sehingga Cornelis de Jonge mengaku sangat senang jika ia bisa melihat Thamrin dibuang ke Banda atau tempat lain—sesuatu yang tak bisa ia lakukan karena Thamrin terlalu “kompeten dan cerdik” (Bob Hering, 209-210).
Saat ruang-ruang di dalam negeri itu terasa kian tersumbat, ia memperluas ruang penjelajahan dengan membangun kontak dengan Jepang. Sepak bola, lagi-lagi, menjadi bagian ikhtiar Thamrin memperluas ruang tersebut. Pada 1936, ia menjadi bagian dari inisiatif mengirim delegasi seratusan orang ke Jepang, di dalamnya termasuk tim sepak bola yang berada di bawah naungan PSSI (Soerabaijasch Handelsblad, edisi 1 Agustus 1936). Saat itu konflik antara PSSI dan federasi sepak bola orang kulit putih (NIVU) mulai meruncing dan memuncak dalam urusan pengiriman tim Hindia Belanda ke Piala Dunia 1938.
Ruang politik yang ia coba perluas hingga ke Jepang itu memicu pemerintah kolonial memperlakukannya sebagai tahanan rumah pada 6 Januari 1941. Lima hari kemudian, karena sakit yang tak tertangani dengan patut tersebab statusnya sebagai tahanan rumah, ia mengembuskan napasnya yang terakhir.
Seseorang yang terus berusaha memperluas ruang-ruang gerak kaum bumiputra itu mencapai momen final justru saat ruang geraknya seketika dihabisi hanya sesempit rumahnya sendiri.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo