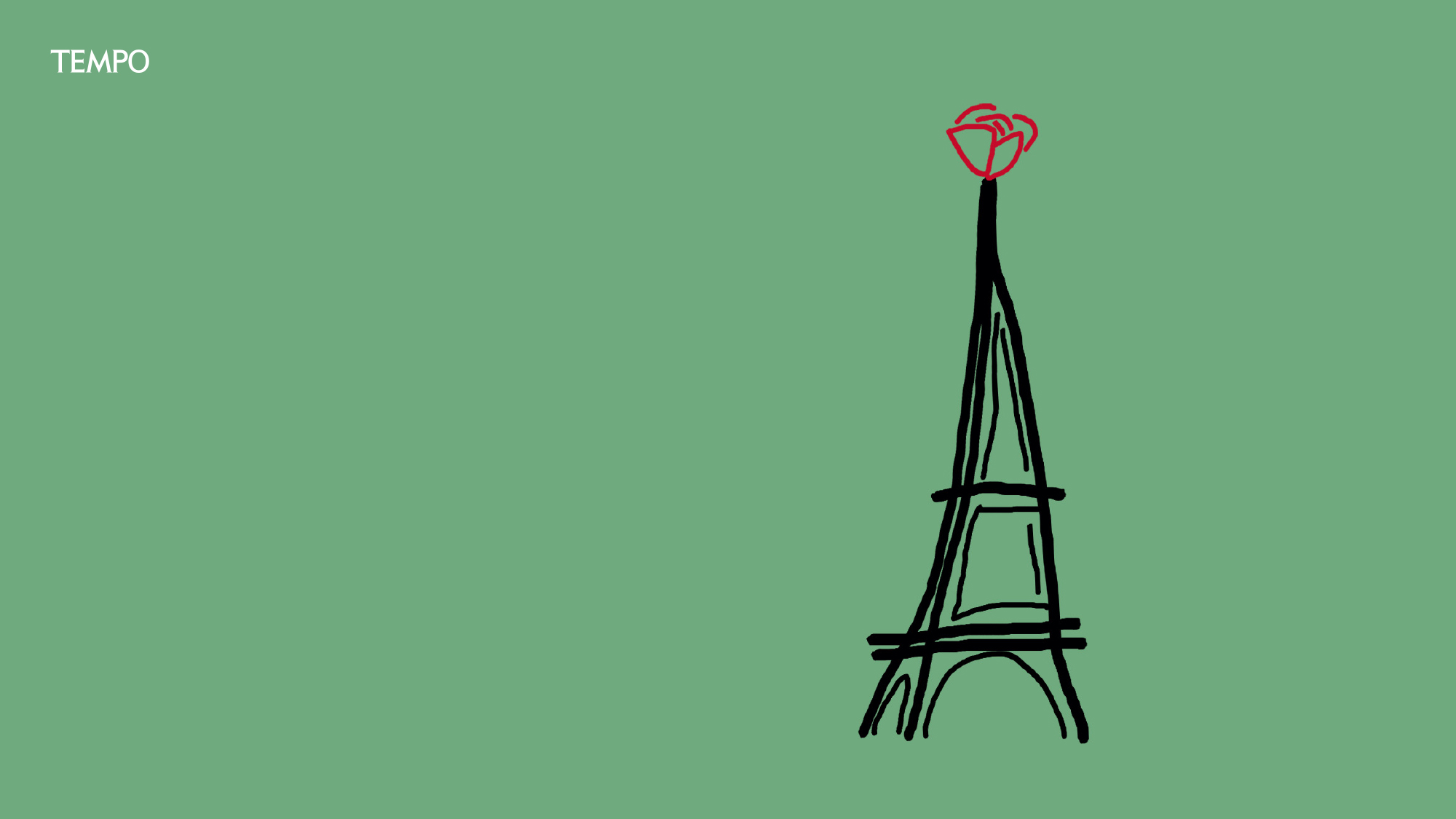Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Semua jari tanganku sampai ada bekasnya untuk rapid test, padahal baru sebulan masuk Indonesia,” kata Nova Ruth Setyangingtyas, melalui sambungan telepon, 1 Oktober lalu. Musikus asal Malang, Jawa Timur, itu tertawa kecil. Tak semata karena mesti berkali-kali menjalani tes cepat pengujian Covid-19, tapi lantaran Nova selama beberapa bulan terakhir tinggal di lautan. Rumahnya adalah kapal sepanjang 18 meter bernama Arka Kinari, yang artinya bertahan hidup di dalam kapal. Bahtera berumur 73 tahun itulah yang membawanya pulang kampung ke Indonesia, setelah lebih dari setahun mengarungi samudra. “Aku tetap harus rapid test. Padahal di lautan kan sebenarnya enggak ketemu siapa-siapa kecuali ikan.”
Nova tak sedang bertamasya. Arka Kinari membawanya menjelajahi lautan sejak bertolak dari Pelabuhan Rotterdam, Belanda, 23 Agustus tahun lalu. Bersama Arka Kinari, musikus hip-hop itu menjalani mimpinya: menyebarluaskan pesan untuk menjaga bumi, bijaksana dengan sampah, dan mengasihi lautan. Misi itu dia rawat bersama sang suami yang musikus sekaligus komposer asal Amerika Serikat, Grey Filastine. Mereka disokong tim relawan yang ikut serta dalam pelayaran: Benjamin Blankenship, Claire Fausat, Sarah Payne, Titi Permata, I Made Bradley, dan Tommy Panjang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Arka Kinari berlayar di Atol Pasifik, 24 Agustus lalu. Grey Filastine
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Benjamin adalah kapten armada Arka Kinari merangkap pemain tambahan di pentas musik Grey dan Nova. Bukan hanya dia yang merangkap jabatan. Claire yang seorang pelaut juga merangkap manajer panggung. Begitu pula anggota kru lainnya, sebagian besar punya peran dalam setiap pertunjukan musik Nova dan Grey. Kadang mereka bermain musik, tapi ada kalanya unjuk gigi pentas teatrikal. Adapun Titi, yang dulunya aktivis lingkungan, adalah manajer proyek Arka Kinari. “Kami betul-betul gotong-royong. Selama di kapal pun saya sering bertugas memasak dan beres-beres,” ujar Nova.
Tim Arka Kinari masuk ke perairan Indonesia melalui Sorong, Papua Barat, pada 1 September lalu. Di sana mereka sempat melempar sauh dan menghabiskan waktu lebih dari sepekan lamanya. Selama di Sorong, Nova dan kawan-kawan sempat menggelar konser mini. Baru kemudian mereka menyentuh titik lain seperti Banda Neira (16-23 Agustus), Selayar (27 September-3 Oktober), Makassar (5-10 Oktober), dan Benoa (20-31 Oktober). Perjalanan mereka rencananya akan ditutup di Surabaya pada 7 November 2020.
Dalam perjalanan antarlokasi, ada kalanya tim Arka Kinari mampir ke satu daerah, seperti Gili Gede, Nusa Tenggara Barat, yang mereka datangi setelah bertolak dari Makassar. Keberangkatan itu berkesan bagi Nova, karena saat di Makassar kapal mereka terlebih dulu diberkati oleh para bissu yang dipimpin Puan Mattoa Bissu. Berjumpa dan berinteraksi dengan masyarakat setempat menjadi satu hal yang diharapkan Nova dan Grey. “Pengalaman perjalanan ini lebih mengena. Karena ditempuh lewat jalur laut, saturasi perbedaan budaya antardaerah jadi terasa berbeda,” kata Nova.

Kru Arka Kinari, (dari kiri) Sarah Payne, Ben Blankenship, Claire Fauset, saat berlayar di Samudera Pasifik, Juni lalu. Grey Filastine
Di Indonesia, awak Arka Kinari mulai beradaptasi dengan kenormalan baru. Mereka meminimalkan paparan virus dengan tak menggunakan bus maupun taksi. Walau tak bisa dimungkiri, pandemi ini menggerus ambisi Nova dkk. Rencana awalnya, di titik yang disinggahi, mereka akan menggelar pertunjukan musik di kapal sembari menyebarkan pesan soal lingkungan. Namun pandemi memaksa mereka untuk menyusun ulang rencana. Rencana pentas di Pelabuhan Makassar, misalnya, beralih menjadi gig kecil di Benteng Rotterdam.
Di sela-sela konser mereka, Nova dan awak Arka Kinari sekaligus mengkampanyekan sejarah soal jalur rempah Nusantara. Gerakan yang diinisiasi Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu melebur dalam setiap kunjungan Nova dan Grey di berbagai daerah di Indonesia, dari Sorong hingga Surabaya. “Jalur rempah ini juga penting bagi kami, karena di situ juga ada transaksi ilmu dan budaya—hal yang beberapa tahun terakhir terus kami selami dan upayakan,” ujar Nova.
•••
Nova dan Grey adalah seniman yang karyanya selama ini berfokus pada alam dan budaya. Belasan tahun terakhir, keduanya berkeliling dunia untuk tur, yang sebagian besar perjalanannya dilakukan lewat jalur udara. Hal itu menurut Grey membuatnya gelisah dan terus berpikir soal metode tur yang koheren dengan pesan-pesan kelestarian lingkungan yang selama ini mereka gembar-gemborkan. Harapannya ketika itu sederhana. Mereka ingin bepergian dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Sampai kemudian, Grey dan Nova terpikirkan tenaga angin dan sebuah pertunjukan musik yang disokong panel surya.
Menurut Grey, rencana itu terus berubah sejak 15 tahun lalu. Mereka sempat terpikir menumpang bermusik di kapal kargo atau membeli kapal tradisional suku Bugis, pinisi. Namun, pada akhirnya, sebuah kapal layar tua berbobot 45 ton itulah yang dipilih. Ide itu dipatenkan dengan merilis album “An Emergency Exit from the Anthropocene”, yang dianggap Grey merepresentasikan misinya dan sebuah petualangan bahari. Kapal pun menjadi panggung sekaligus platform penyampai pesan. Ia mengibaratkan pelayarannya dengan slow food, alias gerakan untuk menikmati penganan secara perlahan sekaligus mempromosikan kuliner lokal. “Jadi yang akan kami jalani ini adalah tur lambat,” ujar dia, 13 Oktober lalu, saat singgah di Gili Gede.

Tim Arka Kinari saat berada di Makassar. Isman Alwi
Karenanya, tergesa-gesa tak ubahnya pantangan dalam perjalanan mereka. Grey menjelaskan, bergerak lambat sejatinya membuat mereka bisa lebih menyelami tur ini, menjangkau tempat-tempat terpencil, dan menghabiskan waktu untuk belajar, baik dengan diri sendiri maupun warga lokal yang mereka temui selama perjalanan. Namun Grey menegaskan mereka tak sedang merayakan sejarah kemaritiman, melainkan berupaya menghidupkannya kembali dengan unsur kebaruan. Salah satu caranya adalah menggunakan sistem energi terbarukan di kapal mereka yang uzur.
Grey pun berharap cara mereka bisa menjadi solusi alternatif di masa mendatang. “Masa depan yang rendah karbon akan memusatkan Indonesia di persimpangan jalan yang menghubungkan Asia dan Timur Tengah dengan Afrika, juga Eropa. Saya pikir cara ini membantu kita untuk berhenti merusak bumi, tak lagi mengekstraksi minyak dan batu bara, sekaligus menguatkan lagi hasil bumi yang berharga, yakni rempah-rempah yang dimiliki Indonesia dalam jumlah melimpah,” kata dia.
Untuk membiayai mimpi yang mahal ini, Grey bahkan menjual rumahnya di Seattle, Amerika Serikat. Uang tambahan mereka dapatkan dari kampanye dan saweran publik di Kickstarter dan Patreon. Namun perjalanan dengan Arka Kinari tak selamanya mulus. Grey mengatakan rute terpendek dari Eropa ke Indonesia sebenarnya bisa melalui Terusan Suez, Mesir. Sayangnya, rute ini kurang aman karena adanya perompak Somalia dan perang saudara di Yaman. Rute terpendek kedua adalah jalur kolonial Belanda di Afrika Selatan. Tapi opsi ini pun urung dipilih karena ancaman badai, sedangkan kapal Arka Kinari belum teruji dan krunya pun belum berpengalaman di laut lepas.

Arka Kinari saat berlabuh di Raja Ampat, Papua, September lalu. Grey Filastine
Walhasil, tim kapal yang dinakhodai Benjamin memilih rute paling aman, walau sangat panjang. Sejak bertolak dari Pelabuhan Rotterdam pada Agustus 2019, mereka singgah di Prancis, Portugal, Maroko, Kepulauan Canary, Cape Verde, Tobago, Grenada, Aruba, Venezuela, Kolombia, Panama, Kosta Rika, Meksiko, Hawaii, sejumlah atol Pasifik yang tidak berpenghuni, dan Guam. Kapal ini baru merapat ke Indonesia setelah lebih dari setahun berlayar, tepatnya pada 1 September. “Kami mengubah Arka Kinari menjadi mesin yang tangguh untuk bertahan hidup,” ujar Grey.
Dalam perjalanan itu, salah satu yang menyenangkan tim adalah saat menjelajahi pulau terpencil dan berkenalan dengan warganya. Bahkan sebagian dari orang yang baru mereka temui itu sempat bergabung sebagai kru. Seperti seorang pelaut Prancis, koki asal Portugal, dua perempuan Inggris yang disebut Grey terampil melakukan banyak hal, juga seorang anak muda Indonesia di Guam yang andal dalam kelistrikan. Adapun momen merapat ke daratan dan mendapati Internet selalu mereka jadikan kesempatan untuk mengurus navigasi dan membenahi persoalan teknis di kapal.
Virus corona tentu menjadi batu sandungan dalam rencana yang sudah dirapikan tim Arka Kinari sejak bertahun-tahun lalu. Saat meninggalkan Meksiko pada 21 Februari, awak Arka Kinari sebenarnya sudah tahu soal pandemi corona. Namun mereka baru merasakan dampaknya enam pekan setelah itu, saat hendak masuk ke Hawaii. Dari informasi di radio, Grey dkk mendengar sejumlah negara di Kepulauan Pasifik mengisolasi wilayahnya. Begitu pun Indonesia, sudah ada larangan bagi penumpang armada laut untuk masuk ke negara ini. Di tengah ketidakpastian ini, hal gawat lain muncul: visa Amerika sebagian kru hampir habis.
Grey mengatakan selama berbulan-bulan ketika itu mereka dalam kondisi tidak nyaman. Kapal sempat melewati atol Johnston—bagian teritori Amerika, yang pernah menjadi tempat uji coba dan gudang senjata kimia dan biologis. Ketika itu, kapal sudah meminta izin untuk mendarat, tapi tak ada respons. Arka Kinari lalu mendekati Pulau Marshall, yang sayangnya ditutup. Mereka akhirnya mendarat sebentar di sebuah pulau kosong. Saat itu, kata Grey, mereka berupaya keras untuk segera masuk ke Indonesia sebelum awal Juli. Pertimbangannya, karena kala itu diperkirakan akan terjadi badai, sementara mereka butuh segera mencapai daratan untuk berlindung.

Tim Arka Kinari menjalani rapid test saat tiba di Pulau Selayar, Sulawesi Selatan, 1 Oktober lalu. Raditya M Fadilla
Namun rencana itu tak bisa diwujudkan. Arka Kinari belum bisa merapat ke Indonesia, sehingga akhirnya terlebih dulu memutar ke Guam. Mereka tinggal di sana selama 40 hari sembari menunggu visa Indonesia para awak beres diurus. Harapannya, bila kapal mereka akhirnya diperbolehkan masuk ke Indonesia, jarak tempuhnya pun tak akan terlalu jauh.
Di tengah keruwetan itu, Nova berupaya keras bernegosiasi dengan pemerintah dan mencari cara agar timnya bisa segera masuk ke Nusantara. Ia lalu mengontak Titi Permata, kawannya yang dulu bekerja sebagai aktivis lingkungan untuk Sinode Gereja Protestan di Maluku Utara. Titi kemudian menjadi Manajer Proyek Arka Kinari. Ialah yang kemudian turut menjembatani urusan perizinan, hingga akhirnya kapal mereka bisa bergerak ke Papua Barat setelah terkatung-katung lebih dari sebulan lamanya.
Saat urusan perizinan mulai terang, tantangan datang dari alam. Badai mulai datang hingga sang kapten mesti berstrategi agar kapal mereka bisa tetap melaju. Malang bagi tim Arka Kinari, mesin mereka saat itu justru bermasalah sehingga sempat kehabisan bahan bakar. Untung saja, kata Grey, mereka diselamatkan kapal tanker besar Cina yang menjatuhkan solar dan makanan dengan tali ke Arka Kinari. Namun sumbangan itu hanya mengamankan mereka selama beberapa hari. Krisis berlanjut dengan badai yang melumat salah satu layar kapal. “Sekarang kejadian itu jadi terasa lucu. Tapi ketika dulu terjadi, kondisinya betul-betul mengerikan,” ujar Grey.
Pengurusan dokumen juga menjadi benang kusut dalam perjalanan Arka Kinari. Walau para syahbandar dan pejabat lokal disebut Grey kompeten, urusan administratif sempat mengganjal langkah mereka. Seperti saat di Raja Ampat, Papua. Karena kurang satu tanda tangan dalam kelengkapan dokumen, di Raja Ampat mereka sempat ditolak. Hal itu tak hanya mengganggu rencana pertunjukan Arka Kinari, tapi juga menghambat laju mereka kembali ke laut lepas melalui terumbu karang Raja Ampat. Karena terlambat berangkat, malamnya mereka sempat digoyahkan badai yang nyaris melempar Arka Kinari.
Titi Permata menyadari bahwa bergabung dengan tim Arka Kinari bukan pekerjaan gampang. Ia sendiri langsung bergumul dengan pekerjaan rumah yang sukar karena mesti memastikan kapal itu berlabuh ke Indonesia dan bisa menggelar pentas. Padahal, dalam situasi pandemi, bisa menggelar pertunjukan musik semacam hal mustahil. Saat dihubungi Nova pada Maret lalu, Titi sedang tinggal di rumahnya di Salatiga, Jawa Tengah, sementara Grey dan Arka Kinari masih berada di laut lepas.

Tim Arka Kinari tiba di Pulau Selayar, Sulawesi Selatan, 1 Oktober lalu. Raditya M Fadilla
Ia pun mulai mendekati pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan pertimbangan kemanusiaan para awak kapal. Pendekatan Titi menemui titik terang setelah Kementerian menawarkan Arka Kinari untuk terlibat dalam gerakan Jalur Rempah. Dibantu promotor Yayasan Lintas Batas, Grey dan Nova akhirnya bisa menggelar pentas walau tak sebesar yang digagas. “Kami melakukan itu dengan dana yang terbatas. Sebab, para sponsor yang semula siap belakangan mengundurkan diri karena pandemi. Namun, karena semua yang bekerja di kapal ini adalah sukarelawan, kami bisa beradaptasi dengan itu,” kata Titi.
Bagi Nova, tantangan bahkan sudah datang sebelum petualangannya dengan Arka Kinari dimulai. Ia mengaku sempat takut melaut dalam jangka waktu lama, karena cemas akan kondisi di samudra yang serba tak pasti. Apalagi ada mitos bahwa perempuan tak boleh turun melaut. “Tapi akhirnya saya percaya saya bisa. Nenek saya orang Bugis. Masak saya tidak bisa sekuat beliau?” ujarnya. Begitu pun Grey, yang menganggap proyek ini melebihi harapannya, baik dalam hal baik maupun buruk. “Arka Kinari ibarat kehidupan yang dinamis. Titik terendahnya lebih buruk dari apa pun yang pernah saya alami dalam hidup. Tapi titik tertingginya melampaui apa pun yang dapat saya bayangkan,” kata dia.
ISMA SAVITRI
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo