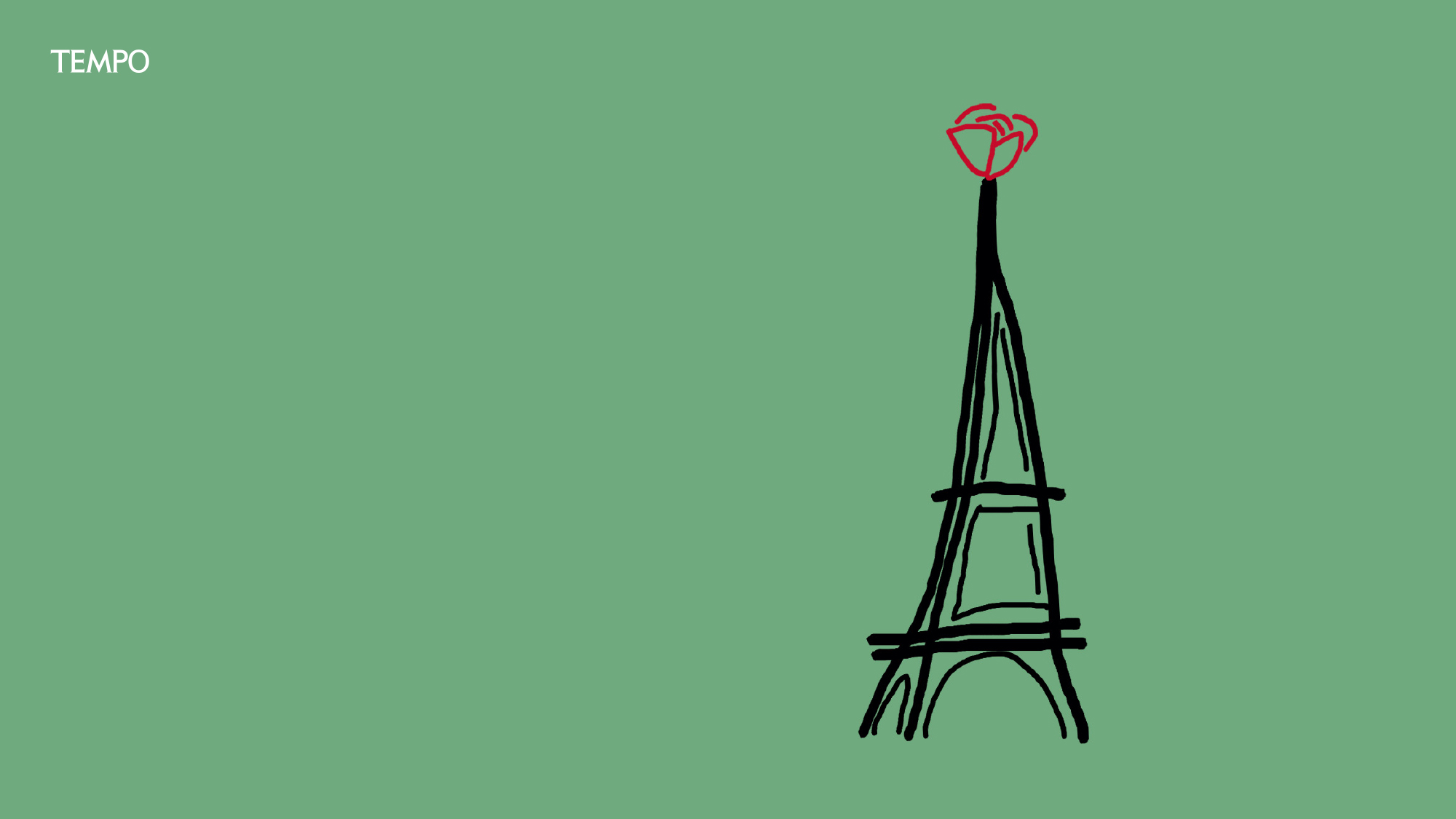Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Malaikat Kecil dari Pasuruan
Sejak kecil, Ernest terbiasa hidup berpindah. Akrab dengan Max Havelaar sejak bangku sekolah dasar.
Saya dilahirkan di kota kecil Jawa Timur, Pasuruan, pada 8 Oktober 1879," tulis Ernest Franois Eugne Douwes Dekker dalam daftar riwayat hidup singkat yang dia tulis saat mendaftar di Universitas Zurich, September 1913.
Tidak disebutkan latar belakang keadaan dia terlahir di kota sebelah tenggara Surabaya itu. Yang jelas ayahnya, Auguste Henri Edoeard Douwes Dekker, agen di bank kelas kakap Nederlandsch Indische Escomptobank, memang sering pindah rumah. Dari buku Het Leven van E.F.E. Douwes Dekker karya Frans Glissenaar disebutkan, kakak perempuan dan abangnya, Adeline (1876) dan Julius (1878), lahir saat keluarga tinggal di Surabaya. Adiknya, Guido, lahir pada 1883 di Meester Cornelis, Batavia—sekarang Jatinegara, Jakarta Timur. Dari sana, keluarga Auguste pindah ke Pegangsaan, Jakarta Pusat.
Di tubuh putra Pasuruan tersebut bersemayam darah campuran. Auguste memiliki darah Belanda dari ayahnya, Jan (adik Eduard "Multatuli" Douwes Dekker), dan dari ibunya, Louise Bousquet. Ibu Ernest, Louisa Neumann, lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, dari pasangan Jerman-Jawa. "Bisa jadi percampuran darah ini mempengaruhi saya," tulis Ernest. "Mungkin petualangan saya pun berawal dari mereka."
Seperti darah yang mengalir di nadinya, sejak kecil Ernest dijejali pengetahuan dari berbagai belahan dunia, termasuk menguasai bahasa Inggris. Guido mengatakan masa kecil Douwes Dekker bersaudara ditemani buku The Monkey's Frolic. Meski buku terbitan 1823 ini memiliki versi bahasa Belanda, Louisa memilih membacakan keluaran asli yang berbahasa Inggris. Buku 17 halaman ini menceritakan petualangan Pug si monyet dan Puss di kucing yang doyan iseng dan bikin onar. Setiap halaman dilengkapi gambar berwarna. Tulisannya memiliki rima, seperti kalimat penutup di halaman pamungkas: To show that no malice or envy he knew, He shook hands with Pug, and each party withdrew. "Kami tidur ditemani buku ini dan bangun dengan buku ini di sisi ranjang," ujar Guido, yang dikutip Paul W. van der Veur dalam The Lion and the Gadfly.
Rumah pialang saham di Batavia tersebut memiliki sejumlah hewan piaraan dan ternak. Mulai kuda, kancil, burung, sampai ikan di akuarium. Ernest kecil kebagian tugas mengawasi mereka saat sang ayah tidak di rumah. Pada 22 Mei 1889, dia menulis surat kepada ayahnya—dipanggil Paatje—yang berada di luar kota. Dia mengabarkan betapa cengengnya si bontot Guido, bandelnya Julius yang berkuda sambil hujan-hujanan, dan binatang peliharaan yang aman terkendali. Beberapa hari berikutnya, Adeline juga mengirim surat. Kepada ayahnya, si sulung menuliskan Ernest yang, jika sedang bekerja, ibarat malaikat. "Tapi seperti setan saat tidak ada pekerjaan," tulisnya. Dari kumpulan surat keluarga itu tecermin tabiat tiap anggota Douwes Dekker bersaudara. Adeline bersikap seperti ibu sekondan, Julius seorang pemberani tapi sembrono, Ernest paling cerdas, dan Guido paling cengeng.
Ernest mengenyam pendidikan dasar di Europeesche Lagere School Batavia. Sekolah yang beroperasi sejak 1817 ini hanya menerima anak-anak Eropa dan Indo, hasil kawin campur yang diakui oleh sang ayah. Pengecualian diberikan kepada Achmad Djajadiningrat, putra bangsawan Banten, yang bisa bersekolah di sana berkat rekomendasi penasihat pemerintahan Hindia-Belanda, Snouck Hurgronje. Djajadiningrat—yang terdaftar atas nama Willem van Bantam—jadi teman Ernest di sekolah lanjutan, dan kemudian menjabat anggota Volksraad atau Dewan Rakyat.
Di masa belajar tujuh tahun ini, Ernest berkenalan dengan Max Havelaar. Novel terbitan 1860 yang bercerita tentang eksploitasi Belanda terhadap rakyat di wilayah jajahannya itu menjadi bacaan wajib di sekolah dan bahan diskusi di rumah. Saat Ernest sepuluh tahun, ayahnya menyebar pamflet yang membantah tudingan Max Havelaar sebagai tulisan ngawur. Sang ayah juga menampik rumor bahwa Eduard Douwes Dekker sakit jiwa. Semua orang mengenal Ernest sebagai keturunan penulis besar tersebut dan sering dibanding-bandingkan dengan Groot Oom-nya. Itu membuatnya gerah. "Saya jauh di bawahnya," tulis Ernest pada 1912. "Namun saya lebih idealis daripada Sang Martir dari Lebak itu."
Pada 1892, keluarga Auguste hijrah ke Surabaya. Ernest dan Julius mendaftar di Hogere Burger School, sekolah tingkat atas. Di sana, mereka tercatat sebagai siswa kelas pertama dengan nomor induk 574 dan 573. Sama seperti di tingkat dasar, maktab ini khusus untuk anak-anak Eropa. Saat itu, menduduki bangku sekolah lanjutan merupakan anugerah. Di antara 35 juta penduduk Hindia-Belanda, cuma 91 ribu warga keturunan Eropa yang berhak masuk sekolah lanjutan, yang hanya ada di Batavia, Semarang, dan Surabaya. Jumlah murid gabungan tercatat 669 Eropa, 13 pribumi, dan 4 Timur Jauh. Lulusan per tahun antara 1900 dan 1904 adalah 40 Eropa dan 1 pribumi.
Tahun berikutnya, mereka kembali ke tanah Betawi dan masuk HBS Gymnasium Koning Willem III. Sekolah yang dikenal dengan KW III ini berlokasi di Weltevreden, sekitar Gambir, Jakarta Pusat, sekarang. Mengutip P.F. Dahler—adik kelas Ernest—Glissenaar menuliskan Ernest tidak menyukai duduk di kelas untuk mendengarkan guru mengajar. "Dia suka membolos," kata Dahler. Namun bakatnya sebagai penulis terlihat di masa sekolah lanjutan ini. Saat 14 tahun, Ernest menulis Gedenkboek van Lombok, Buku Peringatan Lombok. Tulisan itu bercerita tentang Ekspedisi Militer Belanda untuk memadamkan huru-hara di Lombok akibat dominasi Bali terhadap warga muslim di sana. Ernest mendapat pujian pertama sebagai penulis. "Kau, anakku, akan menjadi seorang penulis," ujar ibunya.
Masa ini juga yang mungkin mempengaruhi pemikiran Ernest ke depan. Glissenaar mengatakan Ernest mengalami diskriminasi di sekolah. Sebagai Indo alias setengah Eropa, sekolah memperlakukannya sebagai murid kelas dua, di bawah Eropa murni. Hal itu juga dialami murid pribumi, antara lain Mas Darna Koesoema, teman sekelas yang jadi karibnya seumur hidup.
Dalam riwayat singkat, Ernest menulis lulus HBS pada 1898. Nilainya 2 atau bagus. Penilaian menggunakan skala 1-5, dengan terbaik 1 dan terburuk 4, sedangkan 5 tidak lulus. Catatan pribadi itu tidak menyebutkan dia pernah mengulang kelas. Kurikulum HBS berdurasi lima tahun, meski siswa yang membutuhkan enam tahun—seperti Ernest—untuk menyelesaikan studi juga lumrah, mengingat standar penilaian yang muluk.
Saat itu, belum ada perguruan tinggi di Hindia-Belanda. Siswa yang ingin menempuh perguruan tinggi harus merantau ke Belanda atau negara lain di Eropa. "Karena ayah tidak punya uang, saya pada usia 18 tahun mencari penghidupan sendiri," ujarnya. Penyesalan ini menghantui Ernest sampai hari tua.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo