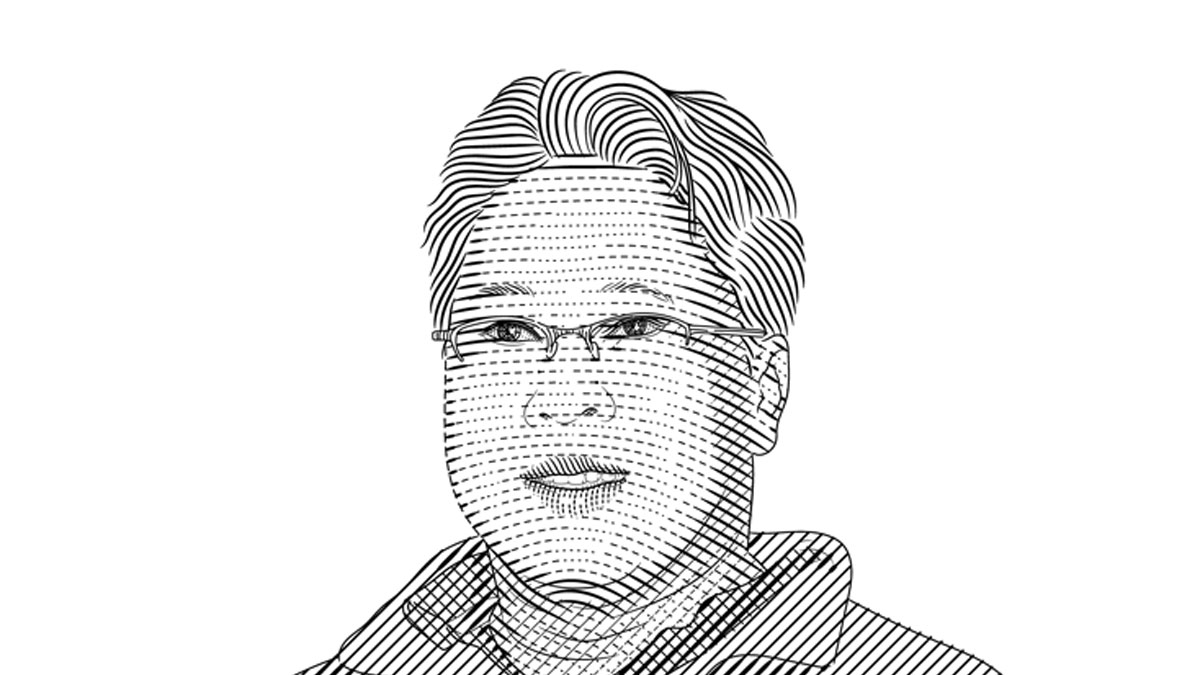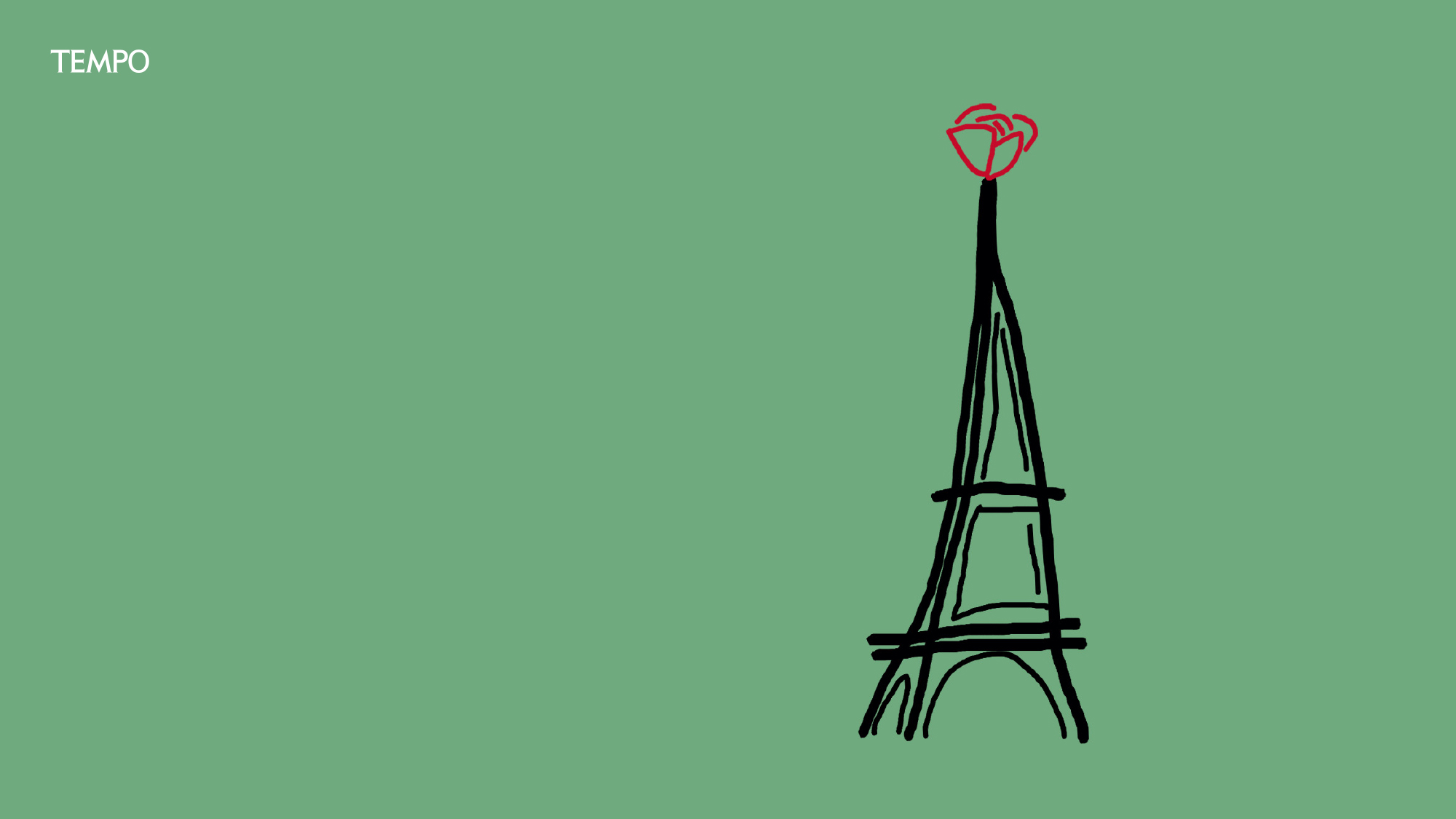Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Buah pikiran Soedjatmoko tentang pembangunan Indonesia yang masih muda.
Menurut dia, pembangunan Indonesia harus dibimbing ilmu pengetahuan.
Ia menganjurkan teknologi madya, membangun dari desa, tak tergiur investasi dan utang luar negeri.
SOEDJATMOKO mengatakan sejarah tidak boleh ditulis untuk menghasilkan mitos. Ia seorang teknokrat, yang mengagumi Hok Gie, dan dengan serius membaca Kant, Hegel, serta Merleau-Ponty. Ia berbeda dengan teknokrat masa kini, yang dengan encer mengalir bersama populisme-otoritarian. Karena itu, Soedjatmoko pasti setuju atas gagasan bahwa melalui sejarah, kita bisa belajar bagaimana intelektual di satu zaman mengambil sikap terhadap kekuasaan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
George Kahin dan Milton L. Barnett, dalam majalah Indonesia volume 49, meringkas secara tepat siapa Soedjatmoko. Dari faktor-faktor utama yang membentuk wataknya, ada beberapa elemen yang tampak sangat menonjol, yakni refleksi mistik Jawa, bacaannya yang luas tentang sejarah Barat dan filsafat politik, serta nasionalisme intuitifnya. Kahin dan Barnet mencatat peran penting Sutan Sjahrir, mentor yang membentuk pendirian politik kritis Soedjatmoko serta memberi merek sosialisme demokratis (sosdem); lalu Ratmini, istrinya (mereka menikah pada 1957) yang memelihara perspektif kemanusiaannya, memberinya jangkar emosional yang kuat, dan terkadang membuatnya menertawai diri sendiri.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Soedjatmoko lahir pada 1922 dan wafat pada 1989. Setelah menamatkan pendidikan di HBS Surabaya, ia lanjut ke Sekolah Kedokteran di Jakarta. Pada 1943, bersama Sjahrir ia ikut membangun perlawanan terhadap pendudukan Jepang. Setelah Indonesia merdeka, pada 1946 ia bekerja di Kementerian Informasi pimpinan Amir Sjarifuddin. Ia mendirikan jurnal Het Inzicht (Insight) yang kontra terhadap propaganda media yang disponsori Belanda, Het Uitzicht (Outlook).
Pada 1947, Soedjatmoko juga ikut mendirikan terbitan sosialis Siasat dan pada 1952 ia mendirikan koran Partai Sosialis Indonesia (PSI), Pedoman. Pada 1961-1963, ia pergi ke Amerika Serikat untuk menjadi dosen tamu di Cornell University. Setelah kepulangannya ke Indonesia, ia dicekal hingga akhir pemerintahan Sukarno pada 1965.
Soedjatmoko merasakan tekanan yang kuat pemerintah Sukarno terhadap Sutan Sjahrir yang berujung pada pembubaran PSI dan penelantaran Sjahrir hingga kematiannya di Zürich, Swiss, pada 1966. Mengenai kematian Sjahrir, ia menulis: Ini adalah kehilangan yang mengerikan. Kehidupannya serta cara sakit dan kematiannya sangat jelas mengingatkan saya pada aspek kehidupan yang tragis, khususnya manusia dalam politik.
Selama sepuluh tahun, sejak 1967, Soedjatmoko menjadi penasihat pribadi Menteri Luar Negeri Adam Malik. Setelah itu ia menjadi Duta Besar untuk Amerika Serikat hingga 1971. Sekembali dari Amerika, ia bekerja sebagai penasihat Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk bidang budaya dan sosial hingga diangkat menjadi Rektor Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa di Tokyo (1980-1987).
Soedjatmoko bukan intelektual publik yang menggebu mengajak orang bertindak langsung untuk mentransformasi masyarakat. Ia cenderung menjadi teknokrat yang mempercayai ilmu pengetahuan sebagai dasar pengambilan keputusan dan kebijakan negara. Ia dengan lugas menekankan bahwa ilmu-ilmu sosial memiliki peran yang sangat penting dan banyak kegagalan pembangunan terjadi sebagai akibat pengabaian terhadap ilmu-ilmu sosial.
Dari rumusan itu jelas bahwa ia berupaya keras mendamaikan sikap intelektual yang rigid dengan tujuan-tujuan pragmatis dari pembangunan di masa awal tumbuhnya Orde Baru. Bagi suatu bangsa yang baru lepas dari kekacauan, kata dia, pembangunan adalah kemestian, tapi ia mesti dibimbing oleh pengetahuan.
Sebagaimana kebanyakan intelektual di zaman itu, Soedjatmoko juga dikejutkan oleh ekstase kekerasan di masa awal Orde Baru. Kenyataan ini mendorongnya menganjurkan pandangan politik yang lebih akomodatif terhadap pembangunan Soeharto. Soedjatmoko tahu persis bahwa pembangunan adalah satu-satunya resep yang mesti ditempuh untuk mengupayakan perubahan, tapi di saat yang sama sedari awal ia juga sadar dan khawatir unsur-ideologi kekerasan neofasis melekat kuat di dalamnya.
Karena itu, ia merumuskan triadik dari apa yang disebutnya sebagai “Teori Demokrasi untuk Pembangunan” yang menggabungkan perubahan, tatanan, dan keadilan. Menurut dia, perjuangan untuk hak-hak politik, yang merupakan perjuangan masyarakat yang bebas dan demokratis, tidak akan ada artinya kecuali didasarkan pada keamanan negara dan bangsa.
Bagi dia, demokrasi, hak asasi, dan kebebasan diperlukan, tapi dalam konteks negara yang sedang berubah ia mesti diperjuangkan selaras dengan perubahan dan tatanan. Dari sini bisa kita simpulkan, dari segi gagasan, ia memang tidak semaju Amartya Sen yang di pertengahan 1990-an menandaskan bahwa pembangunan mesti inheren sebagai kebebasan. Namun ia tidak sekonservatif para ideolog pembangunan Orde Baru yang memposisikan pembangunan nasional boleh dilakukan dengan menunda dan menindas kebebasan.
Dari segi ini, teknokrasi Soedjatmoko adalah teknokrasi yang kritis. Ia membuktikannya dalam surat kepada Presiden Soeharto pada 1969. Surat itu ia maksudkan untuk mengabarkan kritik dan penolakan kaum muda di Belanda terhadap rencana bantuan untuk Indonesia melalui lembaga bantuan internasional Inter-Governmental Group on Indonesia.
Kepada Soeharto, Soedjatmoko menganjurkan: “Tidak tepatlah untuk melihat kecaman-kecaman di antara golongan muda itu sebagai buatan pihak komunis atau pihak New Left saja.… Soal tahanan politik dan lambannya reformasi politik, inilah yang dalam pandangan golongan muda menentukan ‘image’ Indonesia…. Hanya tindakan konkret di Indonesia akan dapat mengubah pandangan negatif ini”.
Surat itu menunjukkan kejujuran seorang intelektual yang memandang kritik sebagai hal yang legitim dan tidak boleh distigmakan sebagai buatan komunis sebagaimana kebiasaan pejabat Orde Baru. Lebih jauh ia menyarankan Soeharto, bila menginginkan Indonesia baik di mata dunia, memperbaiki kondisi hak asasi manusia dan mereformasi politik dengan menyelenggarakan pemilihan umum yang baik.
Soedjatmoko bukan seorang kritikus yang advokatif, tapi jelas ia intelektual humanis yang berani. Dari segi ini, ia mewarisi kekhawatiran-kekhawatiran Sutan Sjahrir akan tampilnya populisme dan nasionalisme yang berlebihan dan membutakan mata. Keberanian itu ia tunjukkan dalam seminar nasional sejarah di Universitas Gadjah Mada pada 1957.
Dia berpendapat, sebelum “Sejarah Indonesia” ditulis, banyak penelitian harus dilakukan. Dia takut akan reaksi yang terlalu nasionalistis terhadap konstruksi sejarah Indonesia, yang sebelumnya berpusat pada Eropa, mendorong panggilan cepat-cepat untuk memobilisasi suatu versi sejarah baru dengan risiko melayani tujuan politik langsung. Dengan begitu, sejarah tunduk di bawah kepentingan nasional, mitos, dan propaganda.
Dalam suratnya kepada Milton L. Barnett, ia menulis, “Saya harus berkonsentrasi untuk mencoba melindungi studi sejarah dari tuntutan nasionalisme yang grasa-grusu.” Harus ada kewaspadaan besar, ucap dia, terhadap “bahaya kebutuhan akan mitos nasional baru dan kebutuhan akan cara pandang yang kurang-lebih seragam tentang masa lalu kita, yang akan mendorong kita mengadopsi satu sudut pandang tertentu sebagai versi resmi sejarah Indonesia” (Kahin dan Barnett, Indonesia, 1990).
Ihwal mengapa kita perlu berhati-hati terhadap nasionalisme, ditulisnya pada 1965: “Sekalipun nasionalisme merupakan tenaga modernisasi, belum tentu ia merupakan pemutusan hubungan dengan weltanschauung masyarakat agraria tertutup” (Etika Pembebasan, LP3ES, 1988). Anjuran untuk membedakan sejarah dari kreasi mitos, propaganda, dan justifikasi nasionalis adalah satu pernyataan paling berani dalam sejarah intelektual Indonesia. Apalagi pernyataan itu diucapkan dalam periode ketika kekuasaan politik Indonesia memposisikan negara, sejarah, dan nasionalisme sebagai satu kesatuan.
Dengan kata lain, pandangan-pandangannya terhadap sejarah, nasionalisme, pembangunan, dan politik dilatari oleh humanismenya. Itu sebabnya ia dengan tegas mengatakan sejarah menjadi penting hanya jika manusia sadar bahwa hanya manusia yang dapat membuat sejarah. Soedjatmoko mempertahankan sikap intelektual sebagai teknokrat-kritis di masa kering otoritarian Orde Baru. Bertolak belakang dengan teknokrat masa kini yang tanpa malu-malu menanggalkan pendirian keilmuannya di bawah populisme.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo