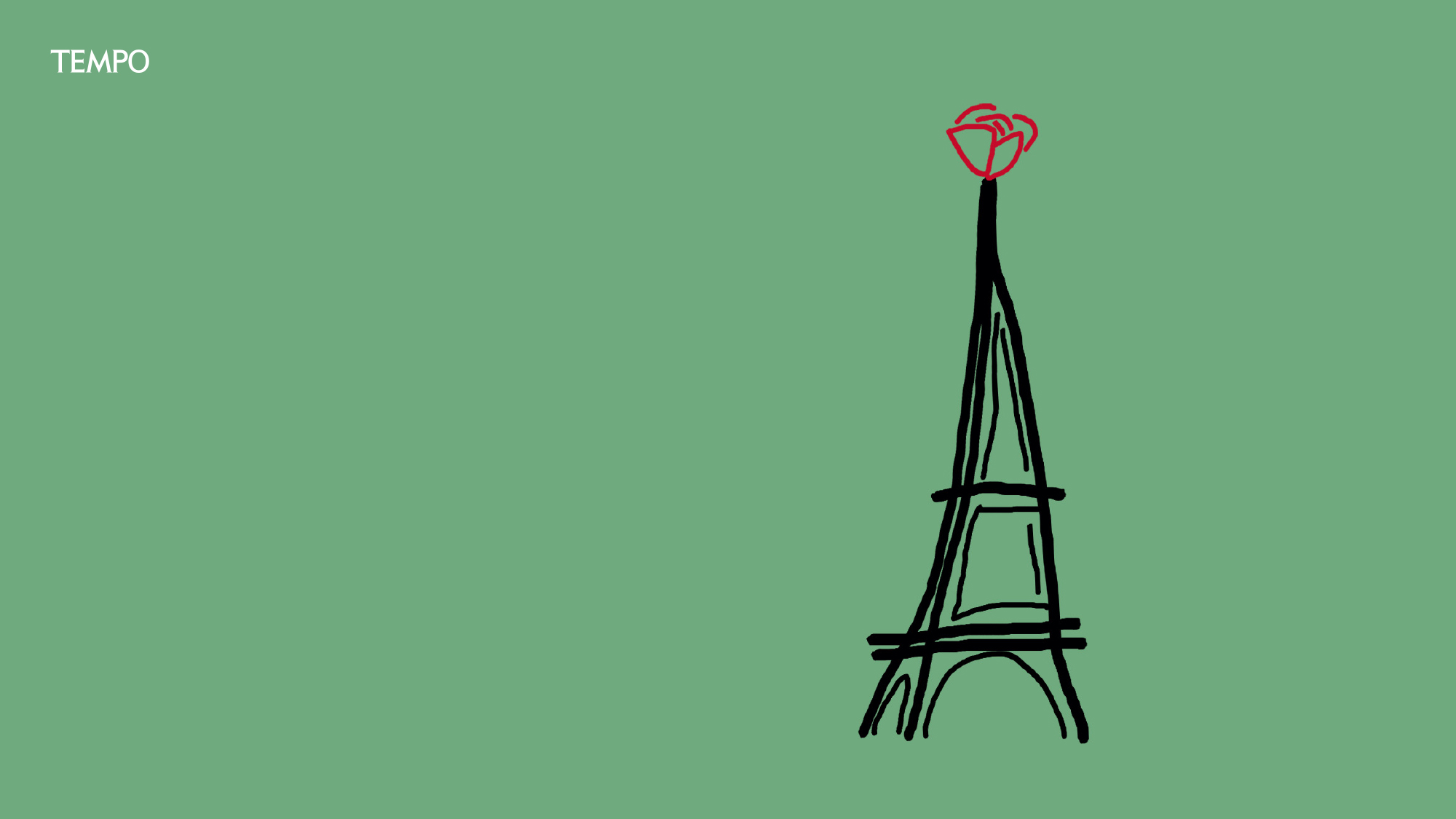Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Minggu sore, 4 Agustus 1811. John Leyden, penyair Inggris, turun di Cilincing, pantai utara Batavia. Ia mengenakan pakaian jubah bajak laut. Leyden mengacungkan pistol antiknya ke udara, lalu mengayunkannya seperti pedang Sinbad ke ayam-ayam yang sedang mengais makanan di kayu-kayu bekas kapal karam.
Di belakang dia kemudian 12 ribu serdadu berjubah merah dari 81 kapal Inggris mendarat di bawah arahan komandan operasi, Kolonel Rollo Gillespie, dan panglima seluruh operasi, Sir Samuel Auchmenty. Lalu tampak dua tokoh utamanya, Gubernur Jenderal India Lord Minto, dan tangan kanannya, Thomas Stamford Raffles.
Tak ada prajurit Belanda yang menghadang langkah mereka. Tak ada halangan selain ayam-ayam yang marah diganggu oleh Leyden tadi. Setelah pertempuran hampir sebulan, Batavia jatuh pada 26 Agustus dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Jan Willem Janssens kabur ke Semarang, tapi akhirnya menyerah tiga pekan kemudian. Penaklukan Jawa oleh pasukan Gillespie itu diumumkan di Inggris dan Belanda. Raffles pun diangkat sebagai Letnan Gubernur Inggris di Jawa, bagian dari kekuasaan Lord Minto, yang berpusat di India.
TIM Hannigan, penulis dan fotografer lepas Inggris, mengisahkan pendaratan pasukan Raffles itu dalam bukunya yang baru terbit, Raffles and the British Invasion of Java. "Informasi John Leyden meloncat ke pantai Cilincing dengan baju bajak laut saya dapat dari sepucuk surat seorang pejabat militer di masa itu," kata Hannigan.
Bukunya muncul tak lama setelah Victoria Glendinning, biografer dan novelis Inggris, meluncurkan Raffles and the Golden Opportunity tahun lalu. Dua buku itu hangat dibicarakan dan diulas media Inggris dan Singapura serta media berbahasa Inggris di Indonesia. Keduanya mengungkit lagi sepak terjang Raffles pada masa penjajahan Inggris di Jawa dan Malaysia.
Glendinning memaparkannya secara ringkas dan tak jauh beda dari kebanyakan biografi Raffles, yang melukiskan pria itu sebagai tokoh yang mempesona, beruntung, dan ambisius; negarawan yang lahir di atas kapal di lepas pantai Jamaika pada 6 Juli 1781; pendiri Singapura dan penakluk Jawa; penulis History of Java; orang yang menyingkap Candi Borobudur yang terkubur; dan seterusnya.
Sedangkan Hannigan sebaliknya. Ia justru secara terperinci mengurai sisi gelap perwira Inggris yang meninggal di London pada 5 Juli 1826 itu. Dia menilai ada masalah besar dengan wacana biografis mapan tentang Raffles. Semua buku sebelumnya, ujar Hannigan, berusaha menggambarkan Raffles sebagai orang baik dan terhormat, tapi hal buruk tentang dia banyak yang dihapus.
Hannigan menulis satu bab khusus soal penyerbuan dan perampokan Raffles yang kontroversial terhadap Keraton Yogyakarta. Pada 20 Juni 1812, sekitar 1.200 tentara Inggris—separuh orang Eropa dan separuh lagi Sepoi (India-Inggris)—di bawah komando Gillespie membombardir tembok Keraton. Pasukan Keraton kalah jumlah, hanya sepersepuluh dari pasukan Inggris. Yogya jatuh tanpa perlawanan yang berarti.
"Kekalahan itu bukan hanya karena kuatnya pasukan Raffles, melainkan juga situasi internal Keraton yang sedang krisis," kata guru besar sejarah Universitas Gadjah Mada, Joko Suryo. Dalam semalam, Yogyakarta dikuasai penuh. Inggris hanya kehilangan 23 tentara. Keraton mengibarkan bendera putih tanda menyerah, tapi Gillespie tetap merangsek masuk dan, menurut Babad Pakualaman, dengan ganas menebaskan pedang ke kanan-kiri terhadap prajurit yang mempertahankan Keraton. Sebagian kecil prajurit masih melawan dan Gillespie terluka di lengan kiri atas terkena tembakan bedil dari arah Masjid Suronatan di sebelah barat pondok Srimenganti, tempat sultan dan pengiringnya menunggu acara penyerahan kekuasaan secara resmi.
Sultan Hamengku Buwono II ditahan dan diasingkan ke Wisma Residen Yogyakarta. Harta Keraton disita. Raffles dan Residen Yogyakarta John Crawfurd merampas seluruh arsip dan pusaka Keraton, yang nilainya sekitar 800 ribu dolar Spanyol saat itu. Rampasan Gillespie pribadi senilai 15 ribu pound sterling dalam bentuk emas, perhiasan, dan mata uang (setara dengan 500 ribu pound sterling saat ini). Peti-peti harta itu diangkut ke Benteng Vredeburg. Manuskrip dan buku-buku diserahkan kepada Raffles dan Crawfurd.
Dengan meneteskan air mata, Sultan dan pendampingnya dipaksa menyerahkan keris dan perhiasan emas mereka. Sedangkan pedang dan belati Sultan kemudian dikirim Raffles ke Lord Minto di Kolkata, India, sebagai lambang "penyerahan menyeluruh" Keraton Yogya kepada Inggris. Bahkan kancing-kancing berlian pada jas Sultan dicopot oleh serdadu Sepoi, yang bertugas mengawalnya, tatkala ia tertidur di tahanan.
Di India, penjarahan harta taklukan adalah hal lazim. Barang jarahan merupakan imbalan besar bagi perwira Perusahaan Dagang India Timur Inggris (English East India Company/EIC), dan tentara Inggris di India berusaha memiliki semua harta di benteng, istana, dan tempat pertahanan lain yang direbut dalam penyerbuan.
Raffles menjelaskan dengan singkat perkara ini dalam suratnya kepada Lord Minto: "Semua barang berharga milik Yogyakarta jatuh ke tangan para penakluk. Tapi, dalam pembagian langsung di tempat, mereka mengambil untuk diri sendiri lebih banyak daripada sepatutnya. Saya tidak mengira mereka akan bertindak begitu cepat dan buru-buru. Tapi, karena sudah terjadi, percuma melarang atau menghukumnya."
Selama empat hari harta Keraton dipindahkan ke karesidenan dengan pedati dan kuli panggul. Yang paling banyak diangkut adalah senjata, wayang, semua gamelan keraton, serta arsip dan naskah, kecuali satu kitab Al-Quran. Naskah-naskah itu mencakup karya sastra seperti babad dan dokumen, misalnya perincian tanah jabatan milik keluarga Sultan.
Sejarawan Inggris, Pater Carey, dalam Kuasa Ramalan Jilid II mencatat bahwa Crawfurd mengangkut sedikitnya 45 naskah berbahasa Jawa dari perpustakaan Keraton, yang sebagian besar dijual ke British Museum pada 1842. Koleksi yang lebih banyak lagi (55 naskah) diambil Raffles untuk pemerintah Inggris. Naskah-naskah ini dikirim ke Bogor pada November 1814 dan menjadi inti koleksi naskah Jawa serta Nusantara milik pribadinya, yang sebagian besar kemudian diserahkan istri kedua Raffles, Sophia Hull, kepada Royal Asiatic Society pada 1830 setelah suaminya wafat.
Koleksi naskah paling banyak di tangan seorang perwira Inggris bernama Kolonel Colin Mackenzie. Sebagian besar koleksi ini dibawa pulang ke Benggala pada Juli 1813 dan kemudian dikenal sebagai The Mackenzie Private Collection, yang disimpan di London. Sekurang-kurangnya 66 dari naskah dalam koleksi itu berbahasa Jawa. Sebagian harta berharga tersebut kini disimpan di British Museum. Sebanyak 140 barang milik Raffles yang disumbangkan Sophia Hull dapat disaksikan di sana. Barang itu bermacam-macam, dari lukisan dan gamelan hingga patung dan batik, termasuk kepala patung Buddha dari Candi Borobudur.
Menurut Alexandra Green, kurator Asia Tenggara dan Selatan di museum itu, mereka memiliki 1.150 barang Raffles, yang 600 di antaranya boneka, topeng, dan instrumen musik. Dari jumlah itu, sekitar 800 dari Indonesia dengan 740 di antaranya dari Jawa. Koleksi itu kebanyakan disumbangkan oleh keponakan Raffles, William Charles Flint Raffles, pada 1859 dan cucu Flint, J.H. Drake, pada 1939. "Koleksi wayang dan boneka adalah yang paling banyak. Ada lebih dari 450 wayang dan boneka dari Raffles, seperti wayang klithik, wayang kulit, dan wayang golek," katanya.
Naskah-naskah kuno Indonesia disimpan di British Library. Mereka memiliki 500 manuskrip, yang 250 di antaranya berbahasa Jawa dan sisanya dalam berbagai bahasa, seperti Melayu, Bugis, Makassar, Batak, dan Bali. Sebanyak 66 naskah berasal dari koleksi John Crawfurd dan Colin Mackenzie. "Pada waktu itu British Museum membeli koleksi Crawfurd pada 1842 dan perpustakaan East India Company Library membeli koleksi Mackenzie pada 1823," ujar Ben Sanderson, Kepala Pers, Media Sosial, dan Komunikasi Internal British Library. Setelah EIC dibubarkan, perpustakaannya dilebur ke dalam British Library.
Nilai koleksi itu kini sukar dihitung karena British Museum dan British Library tidak pernah menjual koleksinya. Menurut P.R. Harris dalam History of the British Museum Library 1753-1973, museum pemerintah Inggris itu membeli koleksi Crawfurd, yang terdiri atas manuskrip Melayu, Bugis, dan Jawa serta buku berbahasa Cina, dengan harga 516 pound. Kalau dihitung dengan inflasi, nilainya saat ini sekitar 50 ribu pound atau lebih dari Rp 726 juta.
Adapun Royal Asiatic Society memiliki 45 naskah kuno Jawa dan 20 naskah kuno Melayu. "Pada 2004-2005, kami sudah menyerahkan mikrofilm dari seluruh naskah kuno asal Indonesia kepada Perpustakaan Nasional," kata Kathy Lazenbatt, pustakawati di sana. Duplikat mikrofilm itu bisa diperoleh lembaga mana pun yang berminat dengan biaya sebesar 80 pound atau Rp 800 ribu lebih.
Gubernur Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X pernah meminta naskah-naskah kuno Keraton Yogyakarta di Inggris dan Belanda dikembalikan, minimal dalam bentuk mikrofilm. "Kalau bisa, dalam aspek perjanjian kebudayaan, apakah boleh Daerah Istimewa Yogyakarta meminta naskah-naskah kuno di Belanda. Paling tidak diberikan dalam bentuk mikrocip jika sewaktu-waktu Keraton ingin meneliti," ujar Sultan saat bertemu dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda, Retno Lestari Priansari Marsudi, pada Mei 2012.
Perjanjian pengembalian manuskrip kuno dengan Inggris pernah dirintis pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Tapi hingga kini sebagian besar naskah kuno itu belum juga dikembalikan. Kelanjutan dari langkah Megawati juga tak terdengar. Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Inggris, Teuku Mohammad Hamzah Thayeb, menyatakan Indonesia dapat meminta barang-barang itu dikembalikan, misalnya dengan menggunakan konvensi UNESCO tahun 1970 tentang larangan ekspor-impor ilegal benda budaya, yang mewajibkan negara pemilik mengembalikan benda budaya yang diimpor secara ilegal. "Namun, untuk artefak atau naskah yang diperoleh sebelum 1970, pengembaliannya diserahkan kepada kebijaksanaan pemilik," katanya.
Dengan kata lain, pengembalian pusaka Keraton Yogyakarta di Inggris bergantung pada lembaga yang sekarang memilikinya. Persoalan bertambah karena Inggris menolak menandatangani konvensi itu. British Museum memang pernah memulangkan abu kremasi orang Aborigin di Tasmania dari masa 1838 ke Australia pada 2006. "Tapi hal itu dimungkinkan karena munculnya Undang-Undang Jaringan Manusia yang baru terbit di Inggris," ucap Hamzah.
Perkara pemulangan artefak masih tetap menjadi kontroversi di Inggris, seperti kasus batu Rosetta dari Mesir dan marmer Parthenon dari Yunani, yang berada di British Museum. "Sekarang keduanya diminta dikembalikan oleh negara-negara tersebut," kata Hamzah. Tampaknya harta rampasan Raffles dari Yogyakarta akan tetap terkatung-katung statusnya.
Kurniawan, Vishnu Juwono (London), L.N. Idayanie, Addi Mawahibun Idhom (Yogyakarta)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo