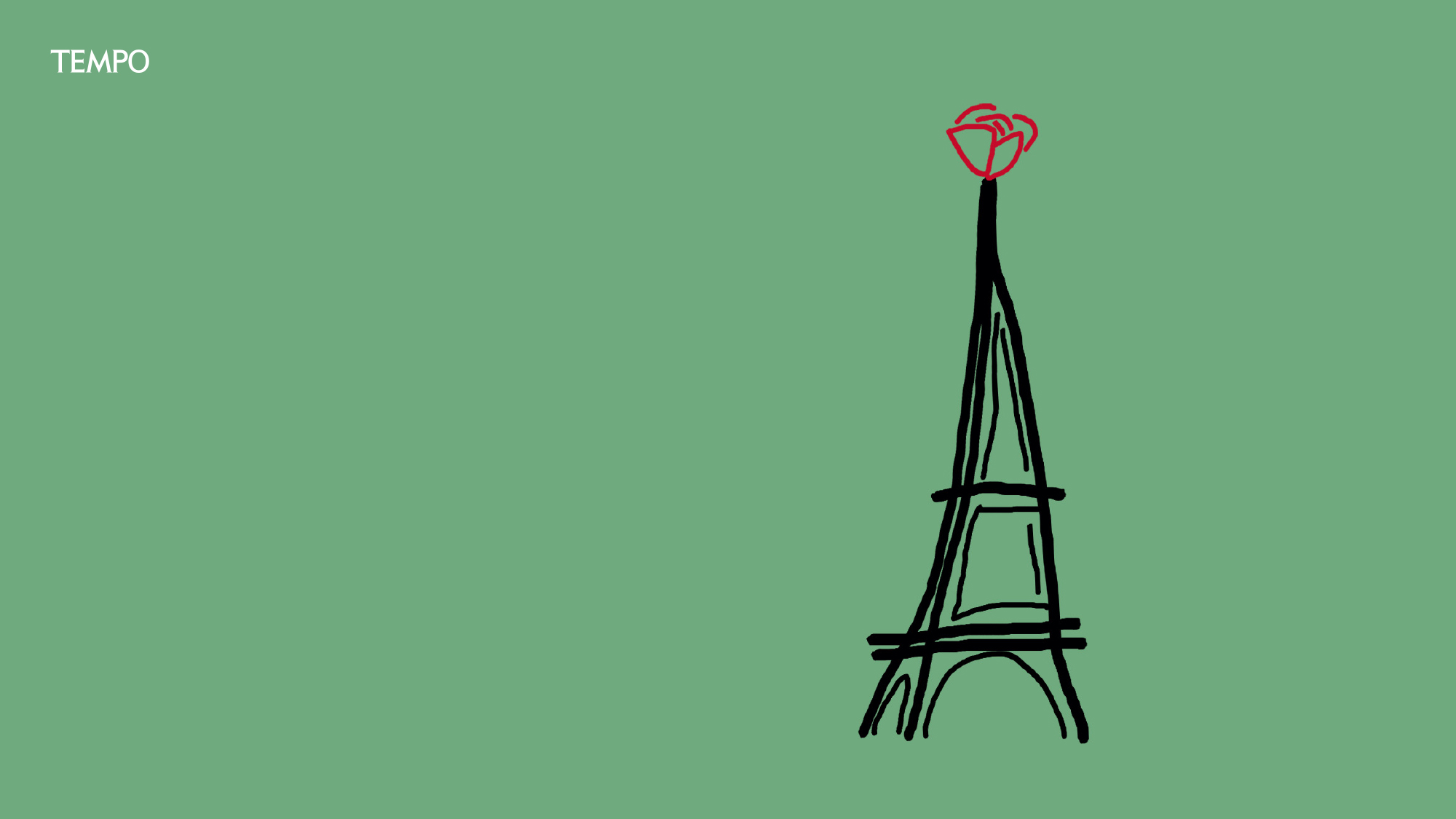Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Ritual paling sakral penganut kepercayaan Marapu, Wulla Poddu, digelar di Kampung Tarung, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur.
Wulla Poddu mengajarkan harmoni manusia, hewan, alam, dan Tuhan yang mereka sembah.
Wulla Poddu dihelat sekali dalam setahun.
SUARA kaweda terdengar sejak malam hingga pagi di perbukitan. Tambur keramat yang hanya ditabuh sekali dalam setahun itu mengiringi penari perempuan dan laki-laki di situs paling sakral penghayat Marapu, Natara Poddu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Semua warga Kampung Tarung, kampung adat tertua di Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, keluar dari rumah untuk merayakan upacara bulan suci, Wulla Poddu. Upacara adat itu berlangsung pada Oktober-November berdasarkan gejala alam dan bulan, bukan kalender Masehi. Perayaan ritual itu berpusat di kampung-kampung adat utama di seluruh Kecamatan Loli.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ritual kudus penganut Marapu setiap setahun sekali itu berlangsung khidmat ketika tetua adat utama, Rato Lado Regitera, merapal doa di Oudi Wara, kuburan leluhur. Makam itu berupa batu besar berbentuk panggung yang di atasnya diletakkan sebongkah batu segi empat besar yang menjulang ke langit. “Rato memohon agar leluhur menjauhkan warga dari mara bahaya, serta kelancaran bertani dan usaha,” kata Maria Stefani Pewali, keturunan Marapu dari suku Weelowo, Ahad, 28 November 2021.
Maria Stefani Pewali, 30 tahun, adalah anak (almarhum) Rato Lango Manu Pele, yang berperan penting dalam upacara Wulla Poddu. Ayah Fani—sapaan akrab Maria Stefani—dimakamkan melalui prosesi kubur batu.
Orang Marapu meyakini di kubur batu itu arwah leluhur yang mereka sembah, Inapapa Nuku Amapapasara atau sang juru selamat, tetap berada di sekeliling mereka. Mereka percaya roh nenek moyang tinggal di kampung, memberi perlindungan dan peringatan bila umat Marapu melanggar pantangan.
Selama perayaan hari besar Wulla Poddu, umat Marapu harus mematuhi sejumlah larangan dan menjalankan serangkaian ritual. Wulla berarti bulan dan Poddu adalah pahit.

Penari Talo Kana, tarian lompat batu kubur, tampil menutup upacara paling sakral penghayat Marapu, Wulla Poddu, di kampung Tarung, Kecamatan Loli, Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, 30 November 2021. TEMPO/Shinta Maharani
Selama Wulla Poddu, penganut Marapu tidak boleh membangun rumah, dilarang meratapi orang meninggal, serta pantang menyembelih babi dan anjing. Mereka hanya boleh makan nasi, daging ayam, dan sayur.
Berdiri di area kubur batu, saya berjejal bersama 300 orang Marapu sepanjang malam hingga dinihari. Mengenakan sarung tenun keluarga Rato Manu Pele, saya ikut menari di atas bebatuan peninggalan tradisi megalitik bersama muda-mudi.
Semua perempuan Marapu mengenakan busana adat, kain sarung terbaik, dan laki-laki memakai ikat kepala serta menyelipkan parang di pinggang bagian samping yang dililit kain.
Anak-anak, remaja, dan orang tua meneriakkan lengkingan suara suku pedalaman, terdengar seperti jeritan suku di Papua. Sembari menggerakkan jemari di atas kepala, mereka memekikkan kata “pule” yang berarti ajakan untuk berkumpul dan bersukacita.
Semua yang hadir membaur, menikmati tarian adat Kako dan Sere yang dibawakan penari perempuan. Tari Kodola dipentaskan lelaki. Mereka melantunkan Dodok, syair adat Marapu, hingga fajar terbit. Ritual dan pesta hari pertama menjadi pembuka puncak Wulla Poddu.
•••
DARI Bandar Udara Tambolaka, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, diperlukan waktu tempuh satu jam naik mobil ke Kampung Tarung. Kampung itu berjarak 9 kilometer dari Kota Waikabubak. Kota ini dikenal dengan toleransi antar-umat beragama dan kepercayaan. Selain terdapat kampung penganut Marapu, di sana berdiri gereja dan masjid yang hanya berjarak sekitar 1 kilometer. Tak jauh dari masjid itu juga berdiri pondok pesantren putri.
Untuk menuju perbukitan kampung adat Marapu itu, kita bisa menyewa jasa ojek di pinggir jalan raya. Tiga hari berturut-turut, 28-30 November 2021, adalah prosesi puncak upacara suci Wulla Poddu. Dan tiga hari berikutnya kegiatan umat Marapu di hari tenang atau nyepi.

Tetua adat Rato Amaleda membaca nasib melalui usus ayam di hari kurban ayam atau Manaa pada rangkaian ritual Wulla Poddu. TEMPO/Shinta Maharani
Saya menyatu dengan keluarga Rato Lango Manu Pele, melihat keseharian mereka selama ritual hari besar. Rumah berukuran besar keluarga itu—disebut Uma Kaka—adalah rumah adat utama yang berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan Wulla Poddu. Tak semua rumah bisa mengambil peran itu. Di Kampung Tarung terdapat 12 rumah adat dengan fungsi masing-masing.
Malam pertama, dari rumah Rato Lango Manu Pele, terdengar riuh rombongan orang yang membawa buruan babi hutan jantan dewasa. Mereka menyerahkan babi itu kepada Rato Lado Regitera sambil melantunkan pantun adat atau Kajalla.
Tangkapan pertama babi hutan itu menjadi indikator hasil panen. Menurut kepercayaan mereka, bila buruannya berupa babi jantan, berarti hasil panen akan bagus. Bila babi tangkapan sedang bunting menandakan hasil panen kurang baik. Jika babi menggigit pemburu, hama tikus akan menyerang.
Semua anggota keluarga besar Rato Lango Manu Pele berkumpul dan makan-makan. Siapa pun yang berkunjung tak boleh menolak makanan dan minuman yang disuguhkan pemilik rumah.
Keesokan harinya, tetua adat, Rato Amatuwa, merapal doa untuk menebus dosa. Sore itu, satu per satu ayam hidup dibawa masuk ke rumah adat. Duduk bersila, Rato komat-kamit di depan piring berisi sirih, pinang, dan lembaran uang. “Doa-doa untuk keikhlasan dan keberkahan,” tutur Rato Amatuwa, yang merupakan paman Maria Stefani.
Dalam tradisi Marapu, sirih dan pinang menjadi simbol penghormatan tamu terhadap tuan rumah. Saya ingin menjajal mengunyah sirih dan pinang. Tapi Fani melarang dengan alasan dua bahan alami yang lekat dengan keseharian orang Sumba itu bisa membuat mabuk dan pusing bila kita tidak terbiasa mengonsumsinya.
Hari itu setiap anggota keluarga berbondong-bondong membawa ayam untuk mengetahui nasib serta melihat tindakan baik dan buruk yang dilakukan. Ada 300 ekor ayam yang terkumpul di keluarga itu. Hari kedua puncak Wulla Poddu ini disebut Manaa atau hari raya korban ayam.
Setelah menjalani ritual doa, sanak saudara Marapu menyembelih ayam. Mereka membakar ayam-ayam itu menggunakan jerami di depan rumah. Anak-anak, orang dewasa, perempuan, serta laki-laki bersukacita membakar ayam dan mencabuti bulu-bulunya.
Bagian yang paling menarik adalah meramal nasib dan pengakuan dosa dengan cara membelah dada ayam. Fani deg-degan menyerahkan ayamnya kepada Rato Amaleda. “Seperti teka-teki nasib baik dan buruk,” kata Fani.
Rato Amaleda membelah dada ayam dengan pisau sehingga terlihat jantung, hati, dan usus. Pada usus itulah ramalan nasib ataupun tindakan baik dan buruk seseorang tergambar.
Bila di usus itu terdapat urat-urat warna merah, pemilik ayam diramalkan dalam kondisi tidak baik. Dia bisa sakit ataupun mengalami musibah lain. Tapi, jika usus terlihat bersih, pemilik ayam dalam kondisi baik.
Fani bernapas lega. Ayam yang dibelah dadanya itu memberi petunjuk baik. Rato Amaleda membaca bahwa keberkahan menghampiri Fani.

Anggota keluarga tetua adat penghayat Marapu, Rato Lango Manu Pele, memasak di dapur untuk ritual Wulla Poddu. TEMPO/Shinta Maharani
Dalam menjalankan upacara adat, penganut Marapu menggunakan ayam, babi, dan kuda sebagai bagian penting dari ritual mereka. Tanda-tanda di tubuh ayam itu menjadi petunjuk atau pedoman hidup.
Orang Marapu bergantung dan mengandalkan alam untuk menopang kebutuhan sehari-hari. Sumber pangan mereka berasal dari hasil panen di ladang, yang hanya berjarak 2 kilometer dari perkampungan. Selain dari padi dan sayuran, sumber nutrisi mereka dapatkan dari hewan ternak seperti babi, ayam, dan bebek.
Mama-mama Marapu membawa ayam yang sudah dibelah dan diberi doa Rato ke dapur untuk dipanggang di atas tungku. Dapur yang berada di bagian tengah rumah adat itu berisi wadah besar berbentuk persegi empat dari bambu untuk menyimpan ayam panggang supaya awet. Wadah yang digantung di langit-langit dapur itu berfungsi seperti tempat pengasapan.
Fani meletakkan piring-piring berisi nasi dan ayam panggang di langit-langit ruang tengah sebagai sesajen untuk leluhur. Di dekat langit-langit itu tergantung bulu-bulu ayam yang dirangkai.
Malam itu, sanak saudara Fani hilir-mudik menikmati ayam panggang, nasi hangat, dan sambal superpedas yang keluar dari dapur. Minumannya kopi khas Sumba, yang membuat mata terjaga hingga dinihari.
•••
TIBALAH saatnya hari yang ditunggu-tunggu, puncak Wollu Poddu, pada 30 November 2021. Seharian penuh, acara penutupan itu kental dengan pesta dan pertunjukan tari dari depan rumah masing-masing hingga di kubur batu megalitik.
Siang hari, rumah keluarga Rato Lango Manu Pele kembali sesak. Keluarga, handai taulan, dan tamu dari kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumba Barat hingga pejabat pemerintah datang silih berganti. Tamu yang singgah juga berasal dari beragam agama dan kepercayaan. Ada Islam, Kristen, dan Katolik.
Mama Wini Ina Lali , ibu Maria Stefani, dan mama-mama Marapu lain kembali sibuk memasak beras dan rica ayam sejak pagi. Aroma sedap masakan menguar dari dapur dengan sekat kayu besar malisu sebagai tiang penyangga rumah, berukir simbol-simbol penting Marapu. Mama Wini Ina Lali dan semua perempuan yang telah menikah dengan orang Marapu di kampung itu terlarang menyentuh tiang dan menjamah ruang tamu atau baliatonga.
Fani dan adik-adiknya bertugas membagikan makanan dalam piring hasil racikan mama-mama Marapu kepada semua keluarga dan tamu. Lagi-lagi semua orang yang datang ke rumah itu pantang menolak makanan yang disajikan.
Hujan deras beserta petir sore itu membuat semua orang berkumpul di balai-balai atau katongatana dan di dalam rumah. Kepanikan sempat menyergap penghuni rumah, terutama keluarga Manu Pele. Listrik padam sejenak saat petir menggelegar. Api di dapur memercik ke langit-langit dapur karena angin kencang menelusup masuk rumah. Saya mendekap keponakan Fani yang ketakutan.
Rato Amatuwa meminta semua orang tenang. Dengan sigap, Rato mengempaskan kain ke api yang memercik agar padam. Tiga menit setelahnya listrik menyala kembali.
Percikan api itu membuat Fani dan keluarganya mengingat kembali kebakaran yang menghanguskan 28 rumah Kampung Tarung. Sepanjang hidup, mereka tak pernah melupakan malapetaka yang terjadi pada 7 Oktober 2017 sekitar pukul 16.00 waktu setempat tersebut. “Kami mengalami trauma. Musibah itu menghancurkan seluruh kampung,” tutur Fani.
Anak tertua Rato Manu Pele ini sedang berkumpul bersama ibu dan lima adiknya di rumah ketika api menjalar dengan cepat. Sumber kebakaran berasal dari rumah besar milik Welem Wolu, berjarak kurang dari 500 meter dari rumah Fani.
Hanya benda pusaka peninggalan nenek moyang berupa kain yang bisa mereka selamatkan. Rumah Fani dan seisinya habis dilalap api dalam waktu cepat. Keluarga Fani tak mau meninggalkan kampung. Mereka mengungsi tak jauh dari kampung dengan mendirikan tenda sementara berupa terpal. Keluarga lain ada yang menumpang di rumah-rumah sanak saudara.
Kepolisian Sumba Barat menyebutkan hubungan pendek arus listrik menyebabkan kebakaran yang merembet ke semua barisan rumah. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa itu. Tapi pemerintah setempat menaksir kerugian warga mencapai miliaran rupiah. Selain rumah dan seisinya yang ludes, sebagian hewan ternak warga dan anjing mati karena terbakar.
Butuh dua tahun bagi penduduk kampung untuk pulih. Resureksi atau kebangkitan penganut Marapu, penanda identitas Sumba terpenting, berlangsung pelan-pelan. Di kabupaten ini terdapat 9.739 penganut Marapu atau 6,54 persen dari 148.916 jiwa total penduduk Sumba Barat.
Warga Kampung Tarung bangkit dengan membangun kembali rumah dari awal. Mendirikan rumah Marapu tidak bisa sembarangan karena mereka terikat dengan tatanan dan sistem kepercayaan. Rumah mereka terdiri atas tiga tingkatan. Bagian atap atau paling atas melambangkan tempat para dewa dan arwah leluhur. Ruang tengah tempat kehidupan manusia dan bagian paling bawah sebagai tempat hewan ternak.
Orang Marapu menyimpan benda pusaka peninggalan leluhur dan beras hasil panen di bagian rumah paling atas. Kamar, dapur, tikar, dan kursi panjang dari kayu di ruang tamu berada di bagian tengah. Kolong paling bawah untuk tempat tinggal babi, anjing, kuda, ayam, dan bebek.
Semua bahan rumah adat menggunakan kayu dan alang-alang dari hutan Watu Mbolo, berjarak sekitar 6 kilometer dari kampung. Untuk memperoleh bahan-bahan dari hutan itu, warga harus menunggu persetujuan dari pemerintah.
Setelah itu, mereka harus berkonsultasi dengan para rato ahli rumah adat supaya tak salah menempatkan bahan-bahan rumah. Contohnya meletakkan tali untuk mengikat kayu dan alang-alang tak boleh salah arah. Mereka percaya penempatan tali berpengaruh terhadap semua penghuni rumah. Bila salah arah, anggota keluarga bisa sakit dan terkena musibah.
Kayu yang mereka ambil harus yang berumur tua agar tak mudah lapuk dan awet. Rumah adat Marapu dikenal tahan gempa.

Warga saat pembukaan rangkaian acara ritual Wulla Poddu di kampung Tarung, Kecamatan Loli, Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, 28 November 2021. TEMPO/Shinta Maharani
Keluarga penghuni rumah adat wajib menggelar ritual selamatan dengan mengundang kerabat dan tetangga. Mereka harus menggelar upacara potong babi. “Energi dan biayanya besar. Kami kewalahan,” ujar Rato Amatuwa.
Untuk mengatasi trauma karena peristiwa itu, umat Marapu bergotong-royong dan saling menghibur. Beberapa pekan seusai kebakaran, mereka tetap menggelar upacara Wulla Poddu dengan skala kecil karena acara ini tradisi turun-temurun. Tahun itu upacara dilakukan untuk mengusir roh jahat.
Dalam upacara itu, mereka tak menyertakan tarian tombak di atas batu kubur karena sebagian hangus dan pecah. Warga berangsur-angsur mengganti bagian atas batu. Kini sebagian batu kubur masih terlihat gosong.
Ritual adat dan pesta kembali bergeliat. Hujan reda di malam pengujung Wulla Poddu atau puncak hari ketiga. Ratusan orang kembali berkumpul di Natara Poddu atau Kintal Pemali. Mereka riang gembira menyaksikan Talo Kana, tarian khas lompat batu kubur.
Dalam ritual ini, rato dan orang-orang Marapu pilihan memamerkan tombak adat di atas kuburan. Para sesepuh adat dari dua suku berhadapan, menari dengan tombak dan parang terhunus. Misalnya penari keluarga Uma Kaka berhadapan dengan keluarga Weekada.
Wolu, penari dari keluarga Uma Kaka, melompati batu kubur bersama tombak. Dia menghunus parangnya dan mengacungkan ke langit yang cerah. Wolu menghadapi Bore dari keluarga Weekada, yang tak mau kalah dalam atraksi tersebut. Bore berdiri gagah dan menggoyangkan tubuhnya dengan memainkan tombak dan parang.
Penonton yang berdiri berdesakan menyoraki keduanya dan memberikan teriakan melengking khas suku pedalaman. Remaja laki-laki dan perempuan menari di bawah batu kubur. Mereka mengentakkan kaki hingga lumpur di sekitar makam muncrat ke tubuh penari. Ada juga yang mencoreng muka penari dengan abu dan lumpur.
Di akhir ritual, tetua adat melantunkan syair tentang pencipta, alam semesta, dan manusia awal yang tiba di Pulau Sumba. Seusai penutupan Wulla Poddu, penganut Marapu tak boleh pergi ke ladang selama tiga hari. “Hingga tiba perjamuan malam terakhir bersama para rato,” ucap Maria Stefani.
Untuk perjamuan malam terakhir, semua keluarga Marapu menyembelih ayam untuk hidangan pamungkas. Air yang mereka minum berasal dari air dalam tembikar tanah liat yang disunggi mama-mama Marapu dari mata air di sekitar kampung. Satu pesan yang mereka kirim dari seluruh rangkaian upacara suci itu: keharmonisan hidup manusia, leluhur, alam, dan hewan. Filosofi hidup yang relevan diterapkan untuk mengatasi kerusakan lingkungan.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo