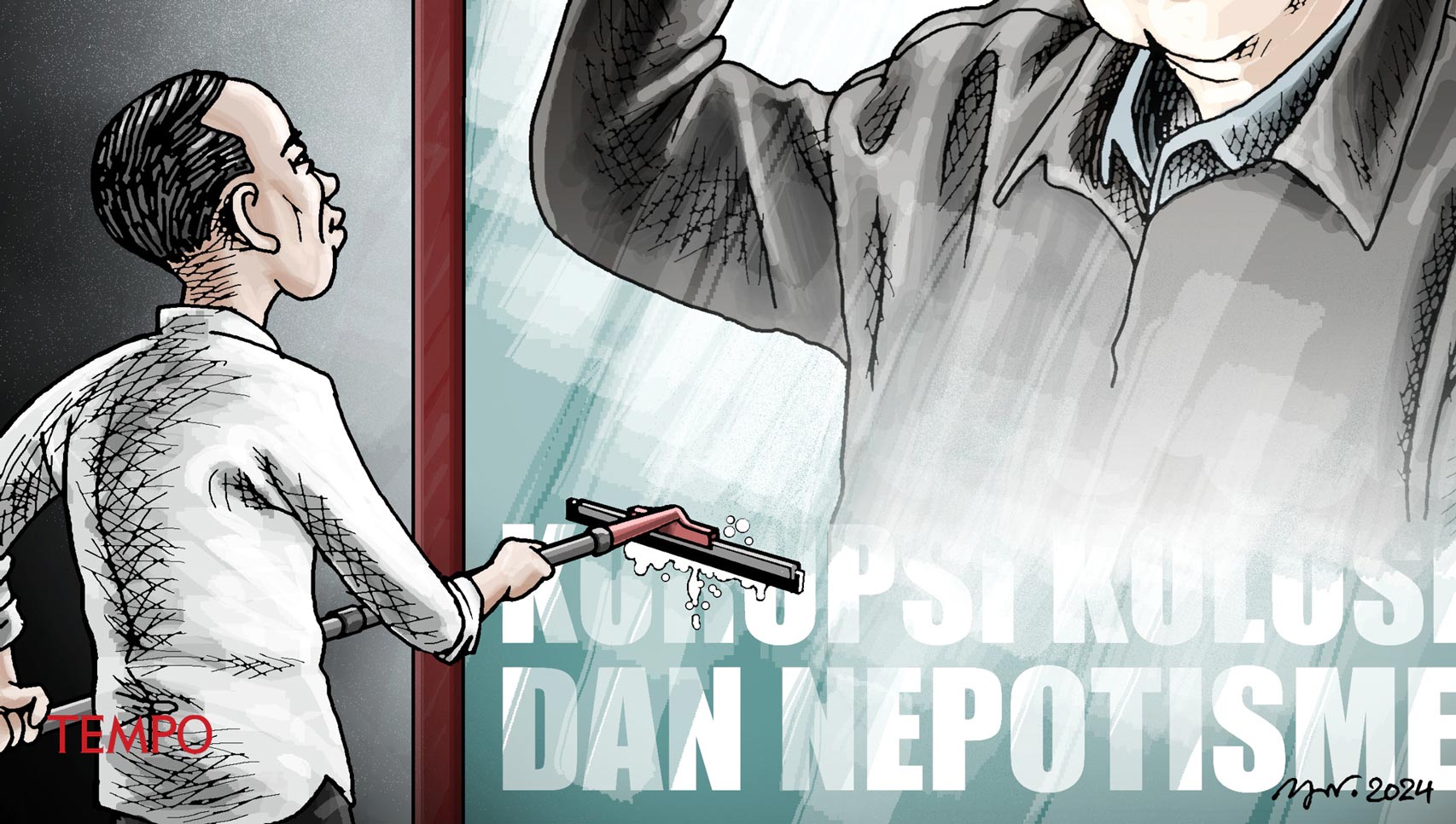Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Perbedaan sikap politik di antara mereka memperlihatkan bahwa organisasi yang berjangkar pada jaringan pesantren ini memberikan keleluasaan kepada anggotanya dalam memilih.
Cak Dur, Ketua Umum Pengurus Besar NU waktu itu, dikenal menyukai lelucon. “Saya ini seperti orang teler setelah menenggak bir Bintang, langsung nyender di beringin, kemudian diseruduk banteng,” tuturnya ketika memberikan sambutan dalam acara perayaan Isra Mikraj di markas Golkar, Slipi, Jakarta, Senin pekan ini. Dengan itu ia ingin menyatakan NU berada di atas semua golongan.
NU memang sedang jadi primadona. Sesudah semboyan kembali ke khitah yang dikumandangkan lewat Muktamar Situbondo 1984, yang melepaskan NU dari ikatan organisatoris dengan Partai Persatuan Pembangunan, “Massa NU kini menjadi floating mass seperti yang diinginkan Ali Murtopo,” ujar Cak Dur atau Abdurrahman Wahid. Suara massa mengapung inilah yang sekarang diperebutkan.
Pada Pemilihan Umum 1955, NU keluar sebagai partai nomor tiga di belakang Partai Nasional Indonesia dan Masyumi. Partai berlambang bola dunia ini berhasil meraih 18,4 persen dari hampir 38 juta suara yang masuk, sementara PNI 22,3 persen dan Masyumi 20,9 persen. Enam belas tahun kemudian, dalam pemilu pertama pada masa Orde Baru, hanya NU yang berhasil mempertahankan prestasinya.
Meski kalah jauh oleh Golkar—pendatang baru yang meraup 62,8 persen suara—NU menjadi runner-up dengan 18,6 persen. Ini membuktikan NU memiliki massa yang tahan guncangan dan tidak menyusut, bahkan justru bertambah 0,2 persen. Bandingkan dengan perolehan suara PNI yang hanya 6,9 persen atau Partai Muslimin Indonesia—yang dianggap sebagai penerus Masyumi—yang cuma 6,3 persen.
Bila diingat suara yang diperoleh semua partai Islam kala itu (NU, Parmusi, PSII, dan Perti) berjumlah 27,9 persen, “Saham NU pada partai Islam sangat dominan, sekitar 67 persen,” kata Doktor Alfian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Yang aneh, sahamnya besar, tapi jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat—sesudah fusi—terus menurun. Ketika belum bersatu, dari 360 kursi yang diperebutkan pada Pemilu 1971, 58 jatuh ke NU, 24 Parmusi, 10 PSII, dan 2 Perti. Ketika mereka mengerek bendera PPP, pada 1977, dan berhasil panen 99 kursi, NU kebagian 56 (kurang dua kursi dari pemilu sebelumnya).
Jatah kursi NU ketika itu menurun jika dibandingkan dengan organ fusi lain: Muslimin Indonesia (MI), penerus Parmusi, yang kursinya menjadi 25; Syarikat Islam (SI, dulu PSII) 14; dan Perti 4. Komposisi seperti itu merupakan keputusan Musyawarah Nasional Dewan Partai PPP 1975, resminya berdasarkan prestasi tiap-tiap unsur waktu Pemilu 1971.
Menjelang Pemilu 1982, pembagian kursi dengan rumus itu kurang disukai unsur-unsur non-NU, yang merasa organisasi mereka sudah jauh berkembang dibanding pada 1971. MI menuntut jumlah kursi untuk satu unsur tidak melebihi jumlah akumulatif dari perolehan kursi ketiga unsur lain. Kesan usaha menjegal NU menjadi kuat setelah sejumlah calon dari NU untuk DPR dicoret.
Dan sekarang, seperti yang sedang kita saksikan hari-hari ini, yang terjadi adalah penggembosan PPP. “Jurkam PPP yang masih menyatakan mereka masih partai Islam dan masih ada hubungan dengan NU seharusnya dilarang,” ujar Abdurrahman Wahid. Menurut dia, memikat massa NU dengan cara yang dilakukan PPP itu, “Tidak fair.”
Meski pernyataan Abdurrahman ataupun pucuk pimpinan NU yang lain tak tegas-tegas mengharuskan warganya memboikot partai John Naro itu, sikap kembali ke khitah ini diartikan sebagai keharusan meninggalkan PPP oleh sebagian kalangan NU. “Kami memang sangat geregetan kepada PPP,” ujar KH Imron Hamzah, Ketua I NU Jawa Timur.
Di Yogyakarta, misalnya. Tak terbayangkan sebelumnya bahwa tanda gambar beringin akan bisa tertempel di kaca jendela rumah Attabik Ali. Maklum, putra bekas Rais Am KH Ali Ma’shum—pemimpin Pesantren Krapyak—ini sebelumnya dikenal sebagai Ketua DPW PPP Yogya. “Saya beri kebebasan kepada anak-anak,” ucap Kiai Ali.
Mustasyar PB NU, KH Masjkur, mengatakan keputusan tokoh NU kala itu tak banyak dimengerti orang awam. Menurut dia, kembali ke khitah itu sebenarnya juga sebuah tindakan politik, meskipun pasti tidak untuk semua seginya. Alfian mungkin menganggapnya sebagai beyond politics, tapi—siapa tahu—NU sendiri akan suka menyebutnya “politik makrifat”.
Artikel lengkap terdapat dalam Tempo edisi 11 April 1987. Dapatkan arsip digitalnya di:
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo