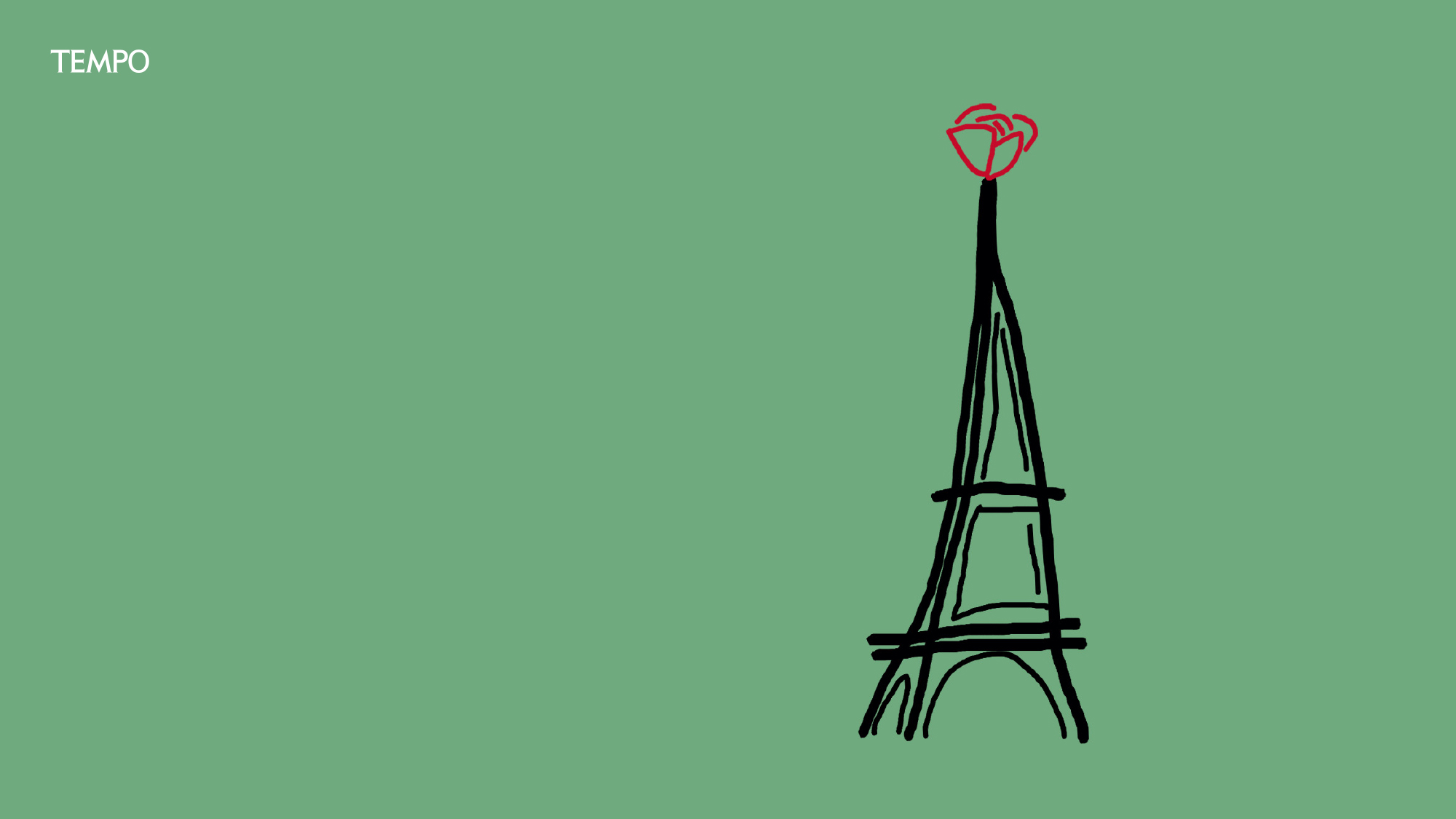Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
MELONGOK selalu dilakukan oleh Clov. Ia membawa tangga. Melihat pemandangan di luar jendela. Namun apa pun yang dilihatnya, yang dia laporkan kepada sang majikan, Hamm, selalu panorama sebentang horizon atau tak lebih dari itu. Bagi Clov, melongok adalah melongok. Suatu rutinitas. Tidak penting apakah di luar ada badai, nelayan, atau kapal-kapal lewat. Dan itu dilakukannya bertahun-tahun.
Hamm sendiri tergeletak di kursi roda, buta, lumpuh, dan penyakitan. Tapi ia mampu mengontrol mental Clov, yang secara fisik sesungguhnya sehat. Relasi mereka adalah relasi tuan dan budak. Inilah kisah orang-orang lumpuh yang hidup di sebuah ruang bawah tanah atau apa. Di samping Hamm dan Clov, di dalam kamar yang tak pernah dikunjungi orang itu, hidup juga Nag dan Nell. Mereka adalah orang tua Hamm yang juga ringkih dan sehari-hari meringkuk dalam sebuah tong bekas.
Pada Juni 2013, Landung Rusyanto Simatupang, 62 tahun, kembali mementaskan ulang lakon Endgame karya Samuel Beckett di Teater Salihara, Pasar Minggu, Jakarta. Ia berhasil menampilkan sisi lain Endgame. Lima belas tahun lalu, dia menyajikan naskah ini begitu angker, sehingga siapa saja yang menonton pertunjukannya saat itu akan merasakan pementasan begitu menekan. Tapi, apa yang disaksikan di Salihara tahun lalu, atmosfer pertunjukan Endgame terasa lebih sebagai komedi hitam.
Kemampuan menafsirkan atmosfer Endgame secara berbeda—meski tak keluar dari batas-batas kegetiran Beckett—itu yang membuat kami memilih Endgame besutan Landung sebagai pentas pilihan Tempo. Yang menarik, perbedaan atmosfer kedua Endgame tersebut, menurut Landung, karena dia merasakan perbedaan suasana Orde Baru dan pasca-Orde Baru.
Lima belas tahun lalu, menurut Landung, kita merasakan gereget besar di masyarakat untuk membebaskan diri dari Orde Baru. Di bawah Orde Baru, berbagai hal dilarang. Ketakutan ditanamkan dalam-dalam. Banyak perbuatan yang salah dianggap sebagai hal yang taken for granted—dan tak ingin dipertanyakan. Tatkala menyutradarai Endgame pertama, Landung ingin memetaforakan Hamm dan Clov seperti suasana orang-orang di zaman Orde Baru, yang mengerjakan apa saja tanpa dipikir. Ia mengarahkan aktor untuk melakukan sesuatu secara terus-menerus dan rutin sebagaimana Clov, yang selalu melongok jendela itu.
Pada era reformasi, masyarakat mengalami euforia. Lama dibungkam, kini semua orang merasa berhak berbicara, berteriak, bahkan yang tak memiliki kapabilitas. Itu yang hendak diperlihatkan Landung dalam Endgame 2013. Karakter Hamm (dimainkan Yudhi Tajuddin) menjadi sangat bawel. Ia menjadi sosok yang selalu ingin didengar cerita-ceritanya. Uraiannya cerdas, tapi tanpa arah dan tak ada kaitannya satu sama lain. Sedangkan Clov (dimainkan Whani Darmawan) menaati perintah Hamm, tapi sesekali ngeyel dan ingin mengeluarkan pendapat sendiri, walau terlihat tak jelas. Walhasil, terjadi percikan-percikan situasi lucu yang menggemaskan.
Kemampuan Landung mengeksekusi Endgame dengan nuansa berbeda ini menyajikan kepada kita bahwa teks absurd Eropa sesungguhnya bukan sebuah teks yang antah-berantah. Ia dibangun di atas suasana-suasana konkret sejarah. Inilah yang banyak disalah mengerti oleh kebanyakan kalangan seniman kita. Absurditas umumnya dipahami sebagai sesuatu yang aneh, antilogika, khayal, dan tidak ada kaitannya dengan realitas sehari-hari. Justru semua itu yang seolah-olah ditampik Landung. Lakon absurd, menurut Landung, adalah sebuah perenungan tentang makna hidup. "Kita hidup disetir oleh kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan itu yang dalam banyak naskah absurd seolah-olah dipertanyakan ulang maknanya," ucap Landung.
Yang juga harus dipuji adalah kemampuan Landung mengarahkan aktor-aktor. Dalam pentas Endgame tahun lalu, Yudhi dan Whani mampu menampilkan gerak-gerik dan diksi yang amat berlainan. Tatkala melangkah, gerak kaki Whani seperti cara berjalan tokoh Charlie Chaplin yang seperti penguin. Lalu intonasi suaranya mendadak melengking lucu. Kepekaan Landung dalam mengarahkan gestur dan artikulasi aktor menunjukkan ia mengerti betul urusan kaitan antara vokal dan ekspresi tubuh di panggung.
Titik inilah yang membuat kami memilih Landung sebagai tokoh pilihan Tempo 2013 karena ia konsisten mementaskan dramatic reading. Semenjak 1980-an, boleh dibilang ia teaterawan kita yang paling setia menggelar pentas pembacaan dramatik. Terakhir, pada 2013, ia mementaskan dramatic reading tentang penangkapan Diponegoro. Memanfaatkan teras gedung bekas kediaman Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Hendrik Merkus de Kock di Magelang—tempat Diponegoro pada 28 Maret 1830 ditangkap—Landung menceritakan kronologi penangkapan itu secara mengesankan. Seolah-olah dia menyaksikan sendiri penangkapan tersebut.
Landung menggeluti dramatic reading saat ia bergabung dengan Teater Stemka (Studi Teater Madep Karep). Pada 1970-an, di samping menjadi anggota Teater Gadjah Mada, ia bergabung dengan Teater Stemka, yang secara rutin mengisi acara di Stasiun TVRI Yogyakarta. Pada awal 1980, anggota Teater Stemka berpencar di sejumlah kota untuk mencari pekerjaan. Pentas terakhir kelompok itu berlangsung pada 1983.
"Kira-kira setelah Teater Stemka vakum itu saya mulai sering pentas dramatic reading," kata Landung. Semenjak itu, ia kerap menggelar petilan pembacaan drama, novel, dan esai. Pada 1980-an, Landung membacakan Sri Sumarah karya Umar Kayam, dan kemudian Musim Gugur Kembali di Connecticut karya pengarang yang sama. Banyak orang terkesima oleh Landung saat itu. Bahkan Umar Kayam juga. "Waktu itu Pak Kayam datang dan terkesan," ujar Landung.
Landung menekuni dramatic reading karena terilhami oleh pembacaan Kimono Biru untuk Istri karya Umar Kayam oleh Chaerul Umam. Tak pernah bertemu atau mendengar langsung pembacaan itu, ia menemukan rekaman pembacaan tersebut ketika masih bekerja di kantor Lembaga Pengkajian Kebudayaan Indonesia UGM pimpinan Umar Kayam. Kala itu, rekaman tersebut berupa kaset. "Saya tidak kenal langsung (dengan Chaerul Umam), tapi saya belajar (dramatic reading) dari beliau," ucapnya.
Boleh dibilang, saat Landung mementaskan dramatic reading, pembacaannya terasa begitu berjiwa. Suaranya memiliki watak dan karakter, sehingga imajinasi kita sebagai penonton terbawa pada sosok yang tengah diceritakannya. Saat ia menceritakan detail penangkapan Diponegoro, penonton seolah-olah bisa membayangkan sosok Diponegoro yang geram di rumah De Kock tersebut. Rencananya Landung akan mementaskan keliling kisah Pangeran Diponegoro itu. Pada 8 Januari lusa, kisah kecil sang Pangeran akan dibacakan di Ndalem Tegalrejo, Yogyakarta. Pementasan berikutnya akan digelar di Museum Fatahillah, Jakarta, pada Maret nanti. Dan ujung pembacaan dramatik akan dilangsungkan di Benteng Rotterdam, Makassar, tempat Diponegoro diasingkan, pada Juni mendatang.
Ditemui Tempo di rumahnya di Dusun Banjarsari di lereng Gunung Merapi, Yogyakarta, Landung mengatakan dramatic reading yang berpangkal pada olah vokal ini merupakan seni tersendiri. Sayangnya, dalam jagat teater kita, olah suara tak banyak mendapat perhatian. Menurut Landung, sementara teknik teater Indonesia kini berkembang sangat pesat, olah vokal cenderung tertinggal. Tak jarang ia menemui di panggung ada aktor yang memiliki kemampuan gerak bagus, tapi intonasi suaranya tak sesuai dengan tema dialognya. "Kenapa banyak aktor kita bicara ngotot sekali di atas panggung?" kata Landung.
Menurut Landung, dramatic reading sejatinya adalah seni bertutur. Dan seni tutur memiliki akar yang kuat di masyarakat. Kita, misalnya, memiliki tradisi membaca lontar. Bahkan, Landung ingat, ketika ia masih kanak-kanak, mbah buyutnya kerap mengumpulkan cucu-cucu di pendapa rumahnya di Kemetiran, Yogyakarta. Semalam suntuk, pada hari-hari tertentu, ia dan saudaranya diajak membaca sebuah babad. Keberhasilan Landung mementaskan Endgame dan perhatiannya yang terus-menerus pada dramatic reading membuat kami menjadikannya dramawan pilihan Tempo.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo