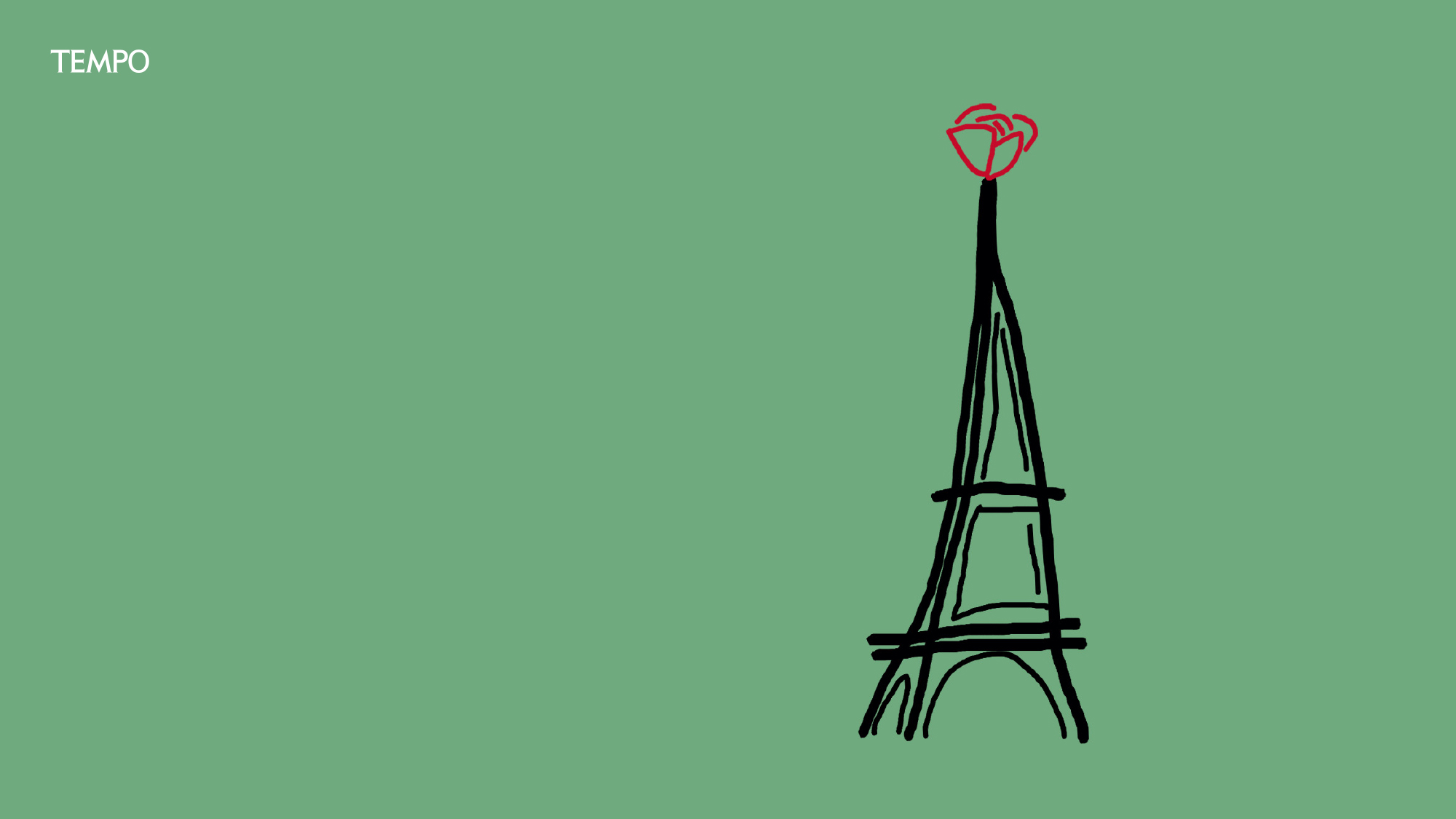Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
RATUSAN anggota jemaah tak beranjak meninggalkan Masjid al-Munawar, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selepas salat tarawih pada Senin, 1 April 2024. Mereka setia menanti kehadiran Hamid bin Abubakar Barakwan yang malam itu bakal mengisi pengajian Majelis Rasulullah. Lantunan salawat berkumandang tak putus menyambut kedatangan pria yang biasa disapa Habib Hamid itu. “Saya sudah di sini sejak sore,” ujar Shahabuddin Shahab, salah seorang anggota jemaah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Geliat jemaah Majelis Rasulullah tak padam sepeninggal pendirinya, Munzir bin Fuad al-Musawa, yang dikenal sebagai Habib Munzir. Ia meninggal saat berusia 40 tahun akibat serangan jantung pada 2013. Komunitas pengajian yang dibentuk pada 1998 itu punya ribuan anggota loyal. Hingga kini antusiasme mereka masih terpancar dari lautan manusia yang kadang tumpah ruah memadati halaman masjid hingga memakan sebagian ruas Jalan Raya Pasar Minggu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Jemaah Majelis Rasulullah juga rutin menggelar kegiatan mereka di gedung Dalail Khairat, Cidodol, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Saban Jumat malam, massa meluber hingga ruas Jalan Kompleks Hankam yang berhias baliho dan umbul-umbul. Kawasan itu juga mendadak menjadi pasar malam dengan kehadiran para pedagang yang menjajakan kebutuhan aksesori jemaah, seperti parfum dan tasbih.
Shahabuddin Shahab salah satunya. Di sela pengajian, ia memajang barang dagangan seperti siwak, tasbih, dan peci. Ia memanfaatkan pelataran masjid sebagai lapak untuk berjualan. Ia kadang menyerobot sebagian trotoar jalan jika jemaah membeludak. Ia melakoni aktivitas itu sejak lebih dari dua dasawarsa lalu. “Saya ikut pengajian sejak Habib Munzir masih hidup karena ceramahnya menyejukkan," katanya.
Munzir bin Fuad al-Musawa merupakan ulama karismatik semasa hidup. Para pembesar, seperti mantan presiden, Susilo Bambang Yudhoyono, dan eks Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, pernah menghadiri pengajiannya. Murid Umar bin Hafidz, guru besar dari Darul Mustafa, Tarim, Hadramaut, Yaman, ini juga kerap mengisi acara keagamaan di sejumlah stasiun televisi dan mengisi pengajian di banyak lembaga pemerintahan. Selepas kepergiannya, peran itu diteruskan oleh pamannya, Muhsin al-Hamid.
Seorang anggota jemaah lain, Irwan, 44 tahun, mengatakan sudah kerap mengikuti pengajian ini sejak 2008. Bagi dia, metode tablig akbar menawarkan sensasi berbeda layaknya suasana keramaian saat ia menonton konser. Komunitas ini punya daya magnet tersendiri karena dipimpin oleh ulama yang memiliki zuriah yang bermakna garis keturunan langsung dari Nabi Muhammad. “Saya orang yang meyakini adanya tabaruk, berharap keberkahan lewat mereka,” ucapnya.
Ketua Umum Rabithah Alawiyah—lembaga pencatat dan pendata keturunan Rasul—Taufiq bin Abdul Qadir bin Hussein Assegaf mengatakan dulu tak ada yang memberi gelar kepada kelompok bernasab Nabi. Kala itu, mereka hanya disebut imam. Belakangan, masyarakat memberikan gelar sayid. Istilah habib baru muncul belakangan. “Itu julukan dari masyarakat yang mencintai para tokoh dari keturunan Nabi,” tuturnya.
Keyakinan inilah yang membuat ulama zuriah Nabi mendapatkan penghormatan di tengah masyarakat. Gairah itu makin memperoleh tempat selepas 1998, saat kebebasan berekspresi makin terbuka. Selain Majelis Rasulullah, komunitas yang cukup tersohor adalah Majelis Nurul Musthofa Hasan bin Jafar Assegaf atau Majelis Kanzus Sholawat rintisan Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya atau Habib Luthfi di Pekalongan, Jawa Tengah.
Penghargaan kepada mereka sebenarnya tak bergantung pada urusan nasab. Para ulama bergelar habib tersebut juga memiliki kematangan akademis. Hasan bin Jafar Assegaf, misalnya, menimba ilmu agama sejak kecil lewat Syekh Usman Baraja. Ia menyelesaikan pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Malang, Jawa Timur. Adapun Luthfi bin Yahya pernah memimpin tarekat Mahasiswa Ahlith Thoriqoh Al-Mu’tabaroh An-Nahdliyyah.
Irwan, juga pencinta habib lain, meyakini bahwa memuliakan zuriah Nabi merupakan bentuk kepatuhan terhadap dogma agama. Sikap itu di antaranya merujuk hadis yang diriwayatkan Muslim dan Ibnu Khuzaimah: “Aku akan meninggalkan dua hal berat, yaitu Al-Qur’an.… Karena itu, laksanakanlah isi Al-Quran dan berpegang teguhlah kepadanya. Dan yang kedua adalah ahli baitku (keluargaku).” Dan Nabi mengucapkan kata “ahli bait” sebanyak tiga kali.
Nyatanya, tak semua penganut Islam patuh terhadap wasiat itu. Pengamat sosial Arya Danusiri menilai hadis ini merupakan salah satu titik pangkal yang melatari konflik berdarah yang mengorbankan sejumlah keturunan Nabi sebagai ahli waris khalifah. Tragedi itu bermula dari pemberontakan pasukan Yazid bin Muawiyah yang menentang kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ali tewas akibat tebasan pedang Abdurrahman bin Muljam alias Ibnu Muljam.

Foto-foto Habib Munzir Almusawa terpasang saat Haul Akbar ke-10 Habib Munzir Almusawa di kawasan Rawajati, Jakarta Selatan, 29 Mei 2023. Tempo/M Taufan Rengganis
Ali adalah menantu Rasul yang menikah dengan Fatimah az-Zahra, anak bungsu Nabi dari pernikahan dengan Siti Khadijah. Kedua anak mereka, yang diharapkan menjadi ahli waris takhta kekhalifahan, Hasan dan Husein, juga harus menelan pil pahit. Hasan tewas akibat diracun, sementara Husein tewas dalam Perang Karbala. Konflik kekuasaan itulah yang membuat sebagian keturunan Nabi hijrah ke berbagai tempat.
Di tanah perantauan, mereka membentuk kabilah baru. Pada abad ke-10, Bani Alawi dari garis keturunan Nabi ke-10 dari nasab Husein membentuk komunitas di lembah tandus Yaman. Kawasan itu berkontur bebatuan cadas dengan ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Orang-orang mengenalnya dengan sebutan Hadramaut. Di kemudian hari, kabilah ini berdiaspora ke banyak negara, termasuk Indonesia.
Komunitas Hadrami makin banyak datang ke Nusantara menjelang akhir abad ke-19. Mereka membentuk perkampungan muslim di banyak tempat, seperti Aceh, Palembang, Pontianak, dan sejumlah kota lain di Jawa. Pemerintah kolonial curiga kehadiran mereka merupakan bagian dari gerakan politik Pan-Islamisme yang menyerukan perlawanan terhadap praktik perbudakan. “Ada irisan dengan terhadap gerakan ini,” tutur Arya Danusiri.
Kecurigaan itu mendorong pemerintah kolonial mengawasi pergerakan mereka lewat sensus pada 1859. Buku Ulama dan Kekuasaan (2012) karangan Jajat Burhanudin menyebutkan jumlah anggota komunitas Arab di Nusantara kala itu mencapai 7.768 orang. Arus migrasi mereka makin deras setelah Terusan Suez dibuka pada 1869. Sensus lanjutan pada 1885 mencatat imigran Arab berjumlah 20.501, mayoritas berasal dari komunitas Hadrami.
Orang Arab jadi isu penting bagi pemerintah kolonial karena mereka mendapatkan tempat terhormat bagi penduduk pribumi. Khususnya mereka yang bergelar sayid, yang dianggap memiliki derajat kesalehan. Mereka adalah kelompok elite yang memainkan peran sebagai ulama pedakwah. Dari ajaran mereka lahir sejumlah pemahaman ihwal ketentuan hukum dalam Islam.
Pemujaan terhadap zuriah Nabi ada kalanya memantik masalah sosial. Jajat mengutip penelitian Van den Berg (1989) yang memotret perlakuan terhadap makam Husein bin Abu Bakar bin Abdullah bin Idrus di Luar Batang, Jakarta Utara. Gara-gara urusan berkah kuburan, orang-orang tersebut pernah bertikai memperebutkan dana dari peziarah. Sudah lama ziarah kubur memiliki nilai ekonomi. Pada 1885, nilai sumbangan peziarah mencapai 8.000 gulden. Sebagai perbandingan, di masa itu harga tanah seluas lapangan sepak bola di Jakarta Pusat sebesar 2.000 gulden.
Tragedi sengketa lahan makam Mbah Priok di Jakarta Utara pada 2010 diduga tak lepas dari motif itu. Bagi sebagian kalangan, makam Mbah Priok atau Hassan Al Haddad merupakan tempat petilasan yang harus dirawat peziarah. Hassan diyakini sebagai orang suci yang berperan besar menyebarkan agama Islam di Jakarta, khususnya Koja dan Tanjung Priok. Padahal jasad Mbah Priok sudah dipindahkan ke Tempat Pemakaman Umum Budidharma, Semper, Jakarta Utara, pada 1997.
Penghargaan terhadap para sayid tak hanya berlaku bagi ulama Hadrami. Tradisi serupa tergambar dari praktik ziarah makam Wali Sanga, ulama penyebar Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15 hingga ke-16. Berbagai kajian sejarah menyebutkan Wali Sanga memiliki garis nasab yang sama dengan Bani Alawi. Bedanya, nenek moyang mereka umumnya turun dari nasab Muhammad Shahib Marbad bin Ali bin Alwi.
Jejak manuskrip itu di antaranya merujuk pada kitab Syamsudz Dzahirah yang ditulis Abdurrahman Muhammad bin Husein al-Masyhur pada pertengahan abad ke-19. Dalam kitab itu disebutkan Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati tercatat sebagai keturunan Alwi Amul Faqih, kakek Muhammad Shahib Marbad. “Beliau adalah Raja Cirebon,” ujar pustakawan Keraton Kanoman, Cirebon, Farihin Niskala.
Menurut Farihin, riwayat semua keturunan Sunan Gunung Jati terdokumentasi dengan lengkap karena menyangkut suksesi kekuasaan. Termasuk Maulana Hasanuddin, anak Sunan Gunung Jati yang mendirikan Kesultanan Banten. Pencatatan itu punya arti penting karena tradisi ziarah makam saat perayaan haul hanya boleh dilakukan orang tertentu. “Hanya sayid keturunan Sunan yang boleh memasuki area makam,” katanya.
Boleh jadi karena keistimewaan itulah banyak orang berburu gelar sayid dan habib. Sebagian dari mereka bahkan menjadi korban penipuan lembaga audit nasab abal-abal yang mencomot nama Rabithah Alawiyah. Penangkapan Janes Meliawan Wibowo oleh Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya pada Februari 2024 menjadi contoh. “Kasus seperti itu banyak. Baru sekarang kami laporkan untuk memberikan pelajaran,” ucap Taufiq bin Abdul Qadir bin Hussein Assegaf.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul "Pemburu Berkah Para Sayid"