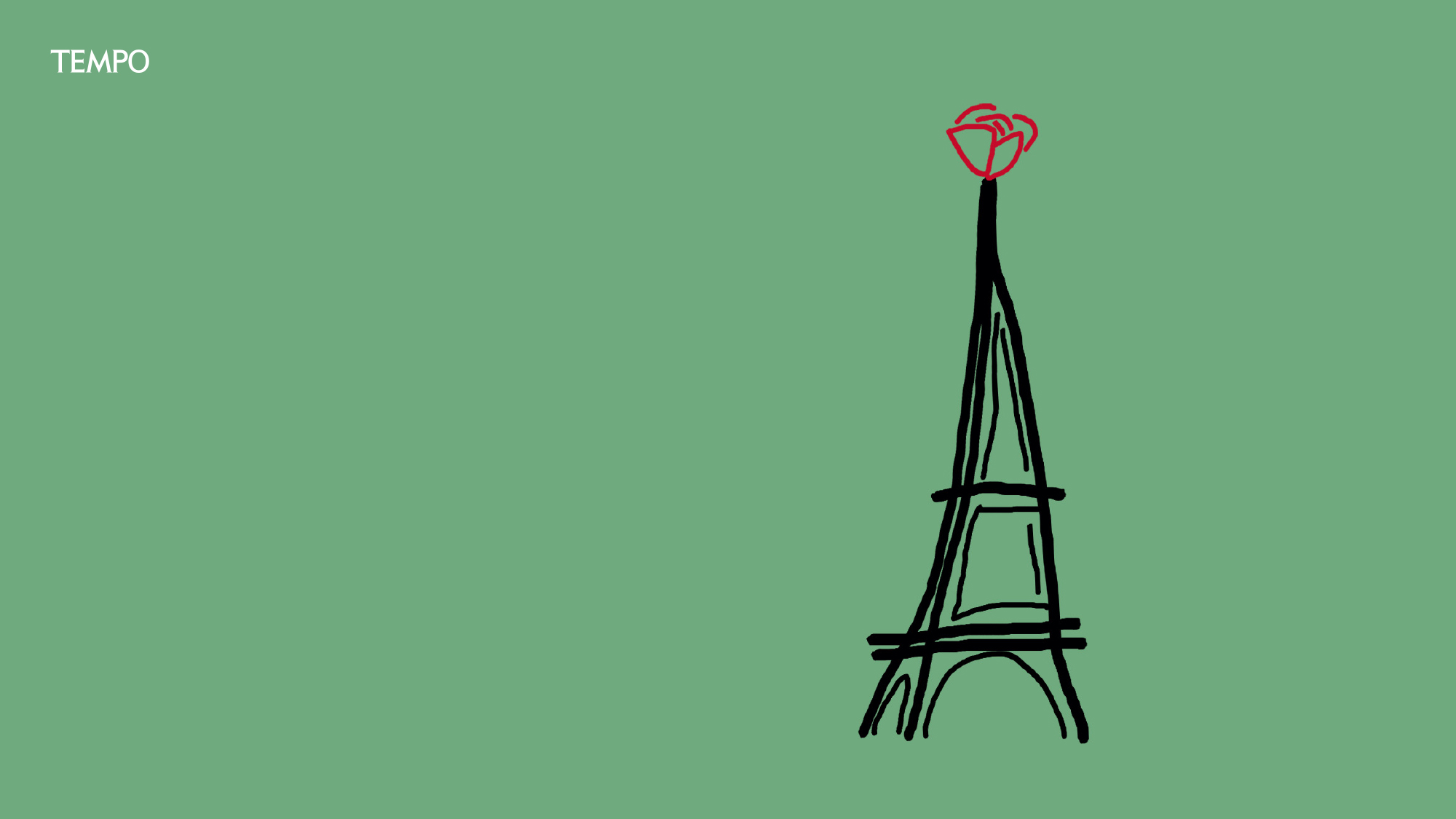Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hari terakhir muktamar Partai Masyumi IV di Yogyakarta, Desember 1949, berlangsung panas. Silang pendapat terjadi dalam pembahasan anggaran dasar rumah tangga. Ketegangan disebabkan juga oleh adanya wacana untuk mendesak Nahdlatul Ulama keluar dari partai. Jumlah peserta waktu itu terbilang banyak. Sekitar dua ratus. Salah satu yang hadir adalah Ernest Franois Eugne Douwes Dekker. "Dalam buku tamu tercatat nama dia," kata Yusril Ihza Mahendra kepada Tempo, Selasa akhir Juli lalu.
Yusril tidak mengetahui keberadaan dokumen buku tamu itu. Dia hanya mendapat keterangan itu dari Slamet Imam Santoso (almarhum), sesepuh Partai Masyumi. Yang terang, Douwes Dekker datang ke muktamar dengan gaya khasnya, yaitu memakai jas dan peci hitam. "Dia sudah tampak tua waktu itu," ujar Yusril, yang didapuk sebagai ahli waris Masyumi oleh Anwar Harjono (almarhum), mantan juru bicara Masyumi. Meski hadir, Douwes Dekker tidak angkat bicara saat muktamar.
Bisa dipahami jika dia diundang muktamar. Douwes Dekker cukup aktif di Masyumi. Yusril mencatat, dia sempat menjadi anggota dewan mewakili fraksi Masyumi di parlemen sementara setelah kemerdekaan, sekitar 1947, di Yogyakarta. "Dia diangkat menjadi anggota parlemen dari fraksi Masyumi sebagai wakil golongan Indo Belanda," kata penulis disertasi perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jama'at-i-Islami (Pakistan) ini. Namun hal itu berlangsung tidak terlalu lama. Hanya beberapa bulan.
Dalam bukunya, The Lion and the Gadfly: Dutch Colonialism and the Spirit of E.F.E. Douwes Dekker, Paul W. van der Veur menulis, Douwes Dekker bergabung dengan partai Masyumi pada 1947, dua tahun sebelum muktamar. Kesahihannya sebagai anggota Masyumi diperkuat dengan adanya surat resmi partai yang ditemukan pada 8 Maret 1954 atas namanya. Surat itu ditandatangani pimpinan Masyumi. Namun Veur tidak menyebutkan siapa nama pimpinannya.
Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), sebagai transformasi gerakan sosial keagamaan Masyumi, juga tidak memiliki dokumen itu. Tempo pun tidak menemukan literaturnya di Arsip Nasional Republik Indonesia dan di Perpustakaan Nasional. Anggota DDII, Ramlan Marjoned, mengatakan dokumen tentang Douwes Dekker sebagai anggota Masyumi itu pasti ada, meski perpustakaan DDII yang ada di Kramat Raya, Jakarta, tidak menyimpannya. "Cukup sulit mencarinya. Bisa jadi di daerah," kata Ramlan pada akhir Juli lalu.
Hal ini dikuatkan oleh penelitian Yusril. Menurut dia, nama Douwes Dekker tidak pernah tercatat di Dewan Pimpinan Pusat Masyumi. Ia lebih banyak aktif di Masyumi Bandung, setelah kembali dari Yogyakarta bersama sang istri, Nelly Alberta Kruymel alias Harumi Wanasita, yang dinikahinya secara Islam pada 8 Maret 1947 di Masjid Agung Yogyakarta.
Sejarawan Ridwan Saidi mengatakan masuknya Douwes Dekker ke Masyumi tidak aneh karena memang banyak Indo Belanda yang masuk partai politik. Apalagi dia bagian "Geng Bandung" bersama Moehammad Natsir, Sutan Sjahrir, dan Sjafruddin Prawiranegara, sebelum Jepang masuk Indonesia. Mereka aktif di Bandung Debating Club, tempat kaum intelektual dan terpelajar bergaul. Natsir akhirnya menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Masyumi pada 1949. "Ernest dekat dengan Natsir. Jadi dia masuk Masyumi," kata Ridwan saat ditemui di kediamannya di Bintaro, Jakarta Selatan, 27 Juli lalu.
Soal kedekatan Douwes Dekker dan Natsir juga diyakini oleh Malam Sambat Kaban. Ide-ide Natsir tentang perjuangan, demokrasi, dan keadilan klop dengan Douwes Dekker. Ketertarikan Douwes Dekker pada Masyumi juga karena kebesaran partai ini. Ada delapan unsur organisasi pendukung Masyumi saat itu, di antaranya NU, Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), dan Persatuan Umat Islam. "Ia amat tertarik dengan pergerakan Islam modern yang besar," ujar Kaban, bekas Ketua Umum Partai Bulan Bintang—partai Islam yang diklaim merupakan "anak kandung" Masyumi—akhir Juli lalu.
Sejarawan Anhar Gonggong sependapat dengan Kaban. Menurut Anhar, Douwes Dekker sudah lama dekat dengan para intelektual Islam di Bandung, seperti Natsir dan Sjahrir. Sejak Kementerian Agama dibentuk di Kabinet Sjahrir II, isu Islam menguat. Maka pergerakan partai Islam juga semakin menggeliat. "Masuknya Ernest ke Masyumi amat dimungkinkan karena Natsir," tutur Anhar.
Selain soal ide-ide besar, Douwes Dekker merasa orang-orang Masyumi cukup berbudaya. Ridwan menggambarkan, elite partai yang berdiri pada 7 November 1945 di Yogyakarta itu sering berbicara memakai bahasa Belanda dengan Douwes Dekker. Mereka membicarakan musik sekelas Ludwig van Beethoven dan novel sekelas Boris Leonidovich Pasternak, novelis kenamaan Rusia kala itu.
Mereka juga pandai bermain musik. Natsir, misalnya, pandai bermain biola klasik. Sedangkan Douwes Dekker mampu memainkan gitar. Tradisi intelektual ini ternyata membuat orang NU gerah. Kulturnya, kata Ridwan, tidak ketemu. Maka NU memutuskan keluar dari Masyumi pada 1952. "Branding Masyumi waktu itu benar-benar Islam modern. Ingat Masyumi, ingat intelektualitas, ujar Ridwan.
Douwes Dekker juga aktif menulis soal pendidikan yang bertuhan. Dia banyak menulis di majalah Hikmah, majalah Partai Masyumi saat itu. Pengaruhnya di Jakarta cukup kuat. Kemenangan Masyumi dalam Pemilu 1955 di Jakarta dinilai Ridwan juga karena Dekker. Itu lantaran sekolah yang didirikannya, yakni Institut Ksatrian, di Kemayoran cukup populer saat itu. "Banyak pemuda mengidolakan Ernest," tutur Ridwan.
Sebelum masuk Masyumi, pada awal 1947, Douwes Dekker mengganti namanya menjadi Danudirja Setiabudi, bersamaan ketika dirinya masuk Islam. Nama itu diberikan oleh Presiden Sukarno. Artinya banteng berjiwa kuat dan setia. Nama itu sengaja dibuat Sukarno serupa dengan nama Belandanya yang juga memakai dobel D. "Danudirja dan Douwes Dekker, biar sama-sama DD," ujar Ridwan.
Ikrar dua kalimat syahadat dilakukan secara sederhana di Yogyakarta. Prosesi itu disaksikan langsung Sukarno dan kerabat dekat. Informasi ini diterima Van der Veur dari Harsono Tjokroaminoto, Wakil Menteri Negara dalam kabinet Natsir yang ikut hadir dalam ritual itu. Veur menerima informasi itu pada 14 Juni 1957 di Honolulu, Hawaii. "Sejak menjadi mualaf, Ernest berpakaian seperti muslim pribumi, di antaranya dengan mengenakan kopiah hitam," tulis Veur dalam makalahnya di Cambridge Journal Online.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo