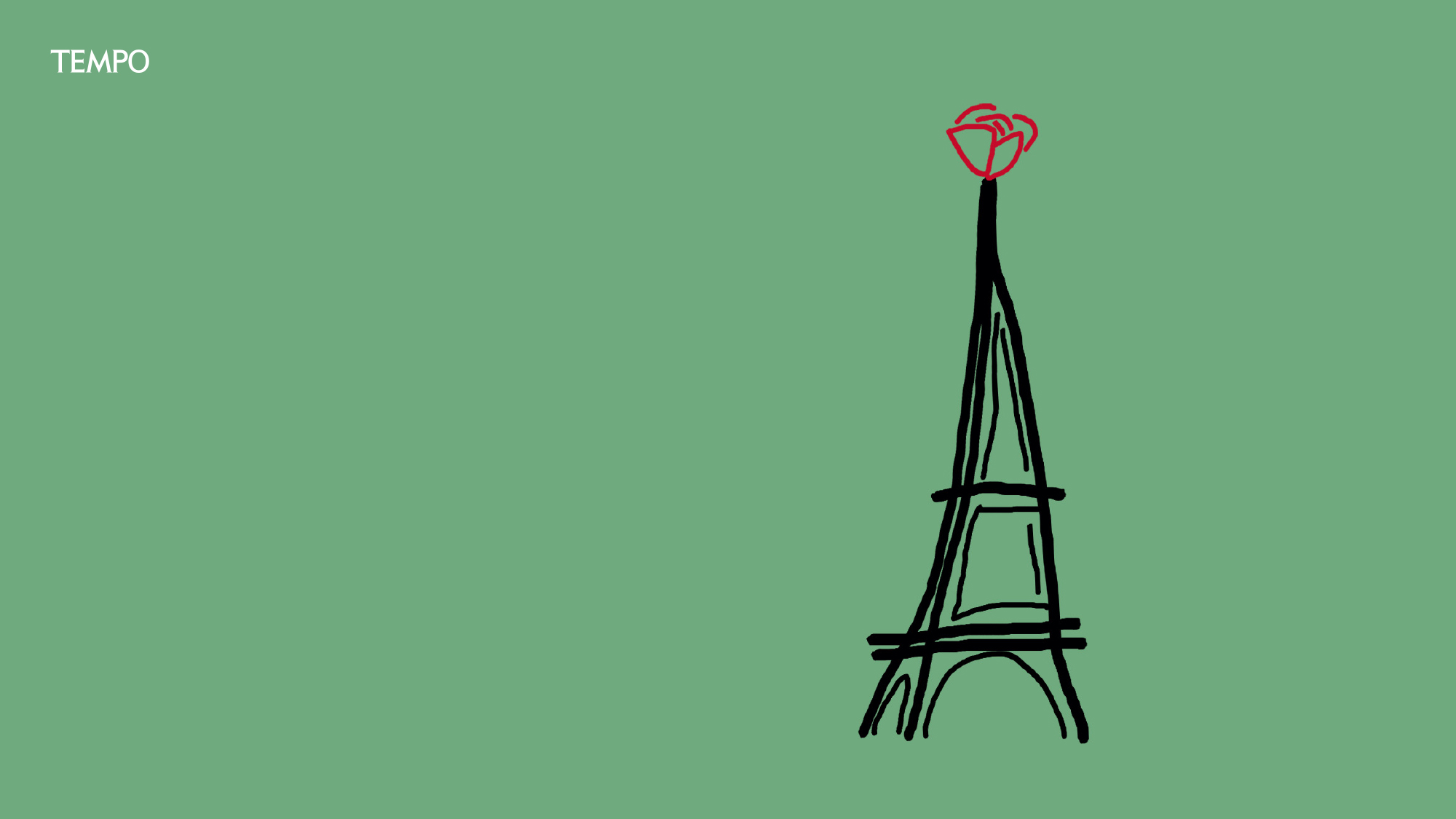Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kereta api itu akhirnya tiba di Den Haag pada 2 Oktober 1913. Tiga orang turun dan disambut sekitar lima puluh orang pendukung mereka, yang menyanyikan lagu mars Indische Partij. Para tamu itu adalah Ernest François Eugéne Douwes Dekker, Tjipto Mangoenkoesoemo, dan Soewardi Soerjaningrat.
Tiga Serangkai baru saja dibuang ke Belanda setelah membuat kehebohan di Batavia dengan menolak merayakan seabad lepasnya Belanda dari jajahan Prancis, menerbitkan artikel terkenal Soewardi, "Als ik eens Nederlander was...". Mereka meminta Ratu Belanda Wilhelmina mencabut larangan pendirian partai politik oleh orang Hindia-Belanda.
Selama di Den Haag, mereka dapat tempat tinggal atas dukungan Tado Fund (Tot aan de Onafhankelijkheid), yayasan Indische Partij yang didanai anggota dan simpatisannya. Tapi Douwes Dekker agaknya sedikit istimewa. Menurut harian De Expres, seorang sahabat kaya telah menyewakan untuknya sebuah kamar di lantai tiga sebuah gedung di pinggir kota. Kamar itu dilengkapi dua meja, satu kursi, pemanas gas, dan lampu. Tapi harian itu merahasiakan alamatnya dengan alasan agar Douwes Dekker tak diganggu dalam menyelesaikan proyeknya, sebuah "buku politik" tentang sejarah evolusi Hindia-Belanda. Kala itu Douwes Dekker dan Tjipto tercatat sebagai editor De Expres di Belanda.
Tjipto kuliah kedokteran di Universitas Amsterdam. Adapun Soewardi dan istrinya, Soetartinah, masuk sekolah guru. Dia juga aktif menulis untuk koran dan mingguan di Hindia-Belanda dan Belanda, termasuk De Indiër. Belakangan dia menjadi Direktur Indonesisch Persbureau, sebuah kantor berita yang tidak dimaksudkan untuk menghubungkan media Belanda dan media Hindia-Belanda. Soewardi, tulis Kees van Dijk dalam The Netherlands Indies and the Great War, 1914-1918, percaya bahwa dengan menyuguhi masyarakat Belanda dengan informasi tentang Hindia-Belanda, politikus Belanda pelan-pelan akan menyadari dan bersimpati kepada gerakan kaum nasionalis. Untuk mencapai maksud itu, Soewardi menerbitkan bermacam brosur tentang Hindia-Belanda, termasuk, tentu saja, soal Indische Partij dan pembuangan tiga pemimpinnya.
Selama di sana, tiga tokoh itu sering menghadiri pertemuan dan berpidato di hadapan berbagai partai politik dan organisasi. Kehadiran mereka memicu debat, baik di kalangan orang Belanda maupun mahasiswa. Saat itu, organisasi mahasiswa Hindia Belanda yang aktif adalah Indische Vereeniging, yang didirikan Noto Soeroto pada 1908.
Tapi Noto sejak awal sudah berbeda pendapat dengan Indische Partij. "Indische Partij melawan Belanda, sedangkan Indische Vereeniging setia. Yang pertama punya benih-benih pertikaian dan hasutan, sedangkan yang terakhir mencoba mencapai gagasan bersama yang didukung banyak orang unggul," tulis Noto dalam Nieuwe Courant.
Rupanya gagasan kemerdekaan Hindia yang diusung Indische Partij masih terlalu radikal bagi Noto, cucu Pakualam V di Yogyakarta. Ayahnya, Pangeran Notodiredjo, salah satu pendiri Boedi Oetomo. Sebagaimana diuraikan Madelon Djajadiningrat-Nieuwenhuis dalam "Noto Soeroto: His Ideas and the Late Colonial Intellectual Climate" di jurnal Indonesia edisi April 1993, Noto melihat masalah Hindia-Belanda sebagai perbenturan budaya Timur dan Barat, sehingga dia mengangankan perpaduan di antara dua budaya itu dalam suatu kesatuan.
Ketika Indische Partij menolak merayakan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari Prancis, Indische Vereeniging memutuskan ikut serta. Ketika Belanda melakukan mobilisasi untuk menghadapi perang pada 1914, Noto bergabung sebagai sukarelawan pasukan kavaleri.
Terjadilah pertentangan tajam antara Noto dan Tiga Serangkai, khususnya Dekker dan Tjipto. Pertentangan itu dipicu pandangan Noto tentang konsep kerja sama bangsa Hindia dan Belanda berdasarkan perbedaan dan persamaan kedua bangsa. Konsep itu menjadi dasar ambisi dan tulisannya, gagasan yang menyatukan norma-norma Jawa dan nilai-nilai yang dipinjam dari filsuf Yunani kuno, Plato. Pandangannya cenderung pada Kerajaan Belanda Raya, yang mengarahkan negara induk (Belanda) dan koloni-koloninya menjadi suatu bentuk politik kolonial ideal.
Perbedaan pendapat itu berpuncak pada konfrontasi langsung ketika Tiga Serangkai hadir dalam peringatan ulang tahun kelima Indische Vereeniging pada November 1913. Dalam acara itu, Noto berpidato menyampaikan pandangannya tentang "asosiasi" dan milisi. Douwes Dekker mengkritik keras pandangan Noto tentang perlunya perlindungan militer dari Belanda. Namun saat itu pandangan Noto masih didukung rekan-rekannya. Tapi, menurut Parakitri T. Simbolon dalam buku Menjadi Indonesia, keadaan berubah ketika tongkat kepemimpinan organisasi beralih ke Gerungan S.S.J. Ratulangie, mahasiswa asal Tondano, Sulawesi Selatan, yang belajar matematika di Universitas Amsterdam, pada 1915. Di bawah Ratulangie, organisasi itu berubah menjadi pusat pengkajian dan bersiap terjun ke ranah politik.
Sejarawan Akira Nagazumi mencatat bahwa kehadiran Tiga Serangkai kemudian mampu mengubah suasana Indische Vereeniging. Mereka mampu mendorong mahasiswa perantauan itu menerbitkan jurnal Hindia Poetra pada 1916. Dalam seri kedua penerbitannya, jurnal itu dibubuhi subjudul "Organ (media) dari Ikatan Pelajar-pelajar Indonesia". Ikatan pelajar itu mencakup lebih dari sepuluh organisasi, termasuk Indische Vereeniging. Inilah untuk pertama kalinya mereka memakai istilah "Indonesia". Pada 1922, ikatan pelajar itu pecah. Indische Vereeniging, yang kemudian berganti nama menjadi Indonesische Vereeniging, mengganti nama jurnal itu menjadi Indonesia Merdeka.
Pada masa itu, gelombang baru mahasiswa Hindia tiba di Belanda, termasuk Mohammad Hatta, yang kemudian bergabung ke Indonesische Vereeniging sebagai bendahara. Menurut Hatta dalam Permulaan Pergerakan Nasional, yang diangkat dari ceramahnya di Gedung Kebangkitan Nasional Jakarta pada 22 Mei 1974, nama "Indonesia" baru muncul pada 1920-1921. Sewaktu Douwes Dekker mampir di Belanda pada 1923, ia banyak berdiskusi dengan Hatta dan orang-orang Indonesische Vereeniging. Dia menentang nama itu. "Ah, Indonesia itu golongan primitif," katanya.
Hatta menangkis. "Hindia tidak mungkin. Sebab, ada Hindia jajahan Inggris, namanya India. Inggris tidak pernah menamakan British-India. Itu hanya orang Belanda yang mengatakannya. Biarlah kata 'Indonesia' itu primitif asalkan kita sendiri yang menciptakannya," ujar Hatta.
Pada 1925, saat dipimpin Soekiman Wirjosandjojo, Indonesische Vereeniging berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Pada tahun itu pula mereka mengeluarkan manifesto politik "Indonesia Merdeka, Sekarang Juga" yang menyatakan, antara lain, bahwa "Hanya ada satu Indonesia yang bersatu dan mengesampingkan perbedaan-perbedaan antarkelompok yang dapat mematahkan kekuatan penjajahan. Tujuan bersama—kemerdekaan Indonesia—menuntut terwujudnya suatu aksi massa nasionalis yang sadar dan berdiri di atas kekuatan sendiri". Sejarawan Sartono Kartodirdjo, yang mengkritik pengagungan Sumpah Pemuda 1928 oleh penguasa Orde Baru dan Orde Lama, menilai manifesto itu merupakan tonggak sejarah yang lebih penting daripada Sumpah Pemuda.
Setahun kemudian Soekiman menyerahkan tongkat komando kepada Hatta, yang memimpin organisasi itu menjadi lebih radikal.
Tiga Serangkai telah menyulutkan api perjuangan di dada para mahasiswa perantau. Tapi mereka butuh dua dekade lagi untuk benar-benar mewujudkan manifesto politik itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo