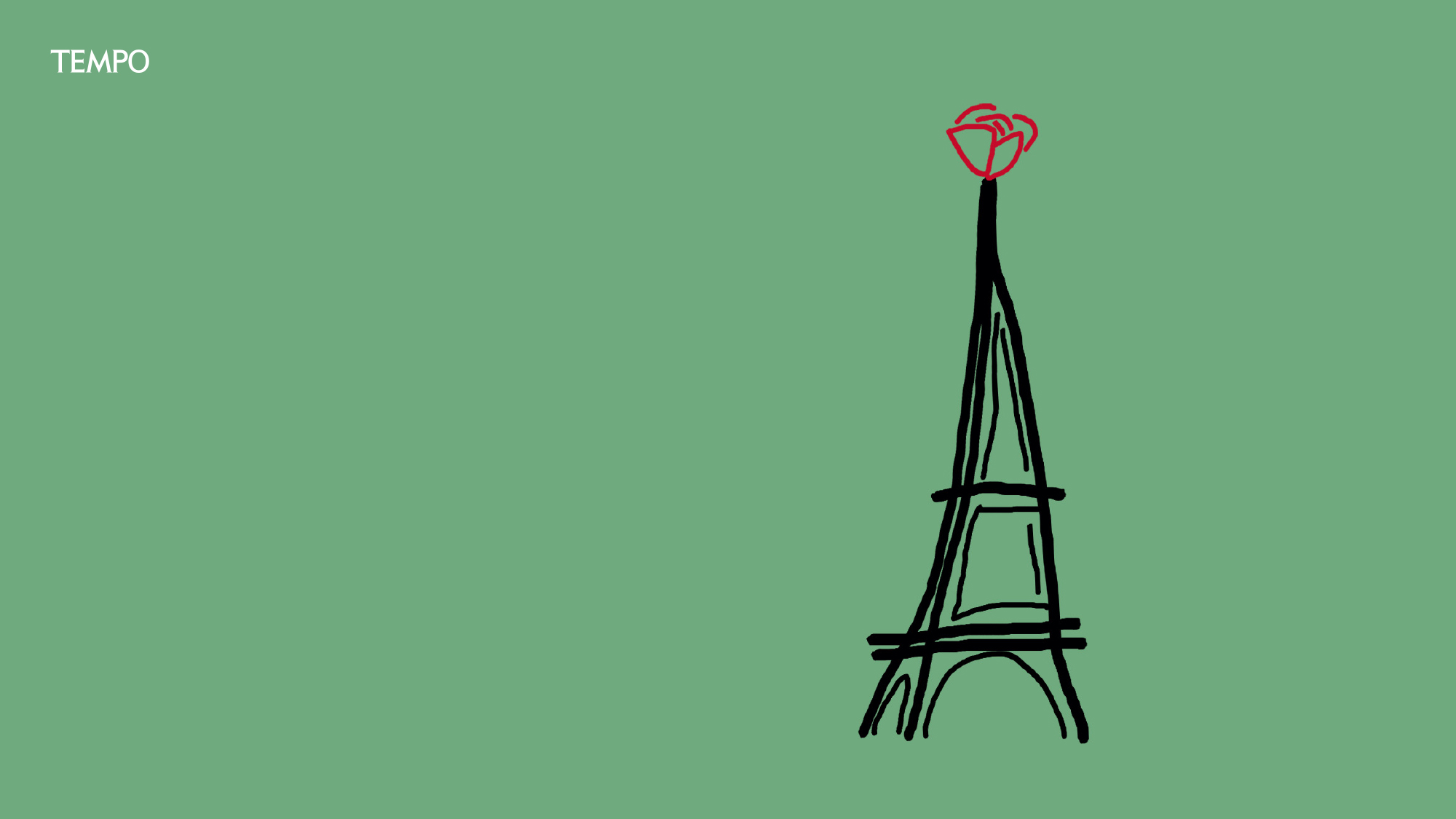Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
MESKI berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain di perkebunan kopi dan tebu di Jawa, minat Ernest Franois Eugne Douwes Dekker tertambat pada jurnalistik. Pada 1883, ketika usianya 14 tahun dan bersekolah di Hogere Burger School Batavia, ia menulis buku Gedenkboek van Lombok (Buku Peringatan dari Lombok).
Douwes Dekker bercerita tentang tanah Lombok dengan pantai nan indah. Bahannya ia sarikan dari isi telegram seorang teman, yang menuturkan perjalanan menengok sang kakak dan meninggal di pulau itu. Meski buku itu tak pernah diterbitkan, ibunya amat bangga. Membaca tulisan anaknya, sang ibu berkata, "Dari tulisanmu, akan lahir seorang penulis, anakku."
Frans Glissenaar, penulis biografi Het leven van E.F.E. Douwes Dekker, mencatat Douwes Dekker mulai senang bercerita lewat tulisan sejak usia sembilan tahun. "Ia memulai kegemaran menulis sejak bisa membaca," tulis Glissenaar. Sejarawan ini menduga kegemaran Douwes Dekker itu karena pengaruh Eduard Douwes Dekker, penulis novel Max Havelaar, yang terkenal dengan nama pena Multatuli. Eduard adalah adik kakek Douwes Dekker.
Bakat menulisnya terus ia asah ketika merantau ke Afrika Selatan pada 1899 saat menjadi sukarelawan dalam Perang Boer. Douwes Dekker menulis surat kepada teman-temannya di Batavia. Perjalanannya ikut mengusir pendudukan Inggris itu kelak mempengaruhi sikapnya dalam memandang penjajahan.
Surat-surat panjang Douwes Dekker yang mereportasekan kondisi orang Boer; perjalanan melintasi India, Eden, dan Afrika Timur; serta tentang para petani yang ditindas kemudian diterbitkan Bataviaasch Nieuwsblad, koran berbahasa Belanda yang terbit di Indonesia dan Belanda. Tulisan-tulisannya itu menarik minat Pieter Brooshooft dan Vierhout.
Dua pemimpin koran De Locomotief itu menawari Douwes Dekker bekerja di kantor mereka. Waktu itu, 1902, dia baru pulang dari Afrika Selatan. Karena koran itu terbit di Semarang, Douwes Dekker ditawari menjadi koresponden di Batavia. Dia menerima tawaran itu karena Brooshooft terkenal sebagai wartawan senior yang banyak mengkritik politik penjajahan Belanda, cocok dengan sikapnya. "Brooshoft yang pertama kali menjadi mentor saya di dunia jurnalistik," kata Douwes Dekker seperti tertulis dalam The Lion and the Gadfly karya Paul van der Veur.
Maka segera saja ia menjadi gunjingan di Belanda karena tulisan-tulisan yang pedas menentang penjajahan di Hindia. Douwes Dekker, misalnya, mengkritik politik etis yang memecah belah penduduk pribumi, Indo, dan priayi. Tokoh-tokoh politik di Belanda menyerang balik lewat pelbagai tulisan dengan menyebut Douwes Dekker sebagai avonturir, oportunis, bahkan schoelje atau "si bangsat".
Menurut sejarawan Universitas Indonesia, Rushdy Hoesein, profesi wartawan adalah pekerjaan umum dan favorit para aktivis pergerakan waktu itu. Koran atau majalah dijadikan alat propaganda menyampaikan pemikiran yang umumnya antipenjajahan. "Karena itu, dia ikut-ikutan mencoba jurnalistik," kata Rushdy. Dan Douwes Dekker punya ciri yang sempurna untuk itu: bahasanya lugas, menonjok, dengan sikap yang jelas.
Misalnya serangkaian tulisan di Nieuwe Arnhemsche Courant, yang terbit pada 1908. Douwes Dekker memberi judul sangat provokatif: "Bagaimana Belanda Paling Cepat Bisa Kehilangan Tanah Jajahannya?". Tulisan itu mengingatkan Belanda, yang menerapkan politik etis, akan mendapat perlawanan seperti orang Amerika Serikat melawan Inggris seabad sebelumnya. Douwes Dekker mengakui ia terinspirasi oleh tulisan Benjamin Franklin, Bapak Bangsa Amerika Serikat, berjudul Seni Menghilangkan Jajahan.
Meski jelas kapan Douwes Dekker memulai karier menulisnya, menurut Frans Glissenaar, tak pernah terlacak kapan ia mempublikasikan tulisan pertamanya. Glissenaar hanya mencatat tulisan di Bataviaasch Nieuwsblad begitu menyita perhatian intelektual di Jawa dan keturunan Eropa yang tinggal di Indonesia. Karena itu, penguasa Belanda amat membenci Douwes Dekker.
Sadar dengan ancaman itu, jika menulis untuk koran yang terbit di Belanda, Douwes Dekker memakai nama samaran dengan menuliskan inisialnya: DD. Inisial ini kemudian melekat terus hingga keluarganya sendiri mengubah panggilan "Nest" menjadi "DD".
Karier Douwes Dekker di dunia jurnalistik yang moncer membuat jabatannya juga terkerek. Setelah dari Locomotief, ia pindah ke Soerabaia Handelsblad sebagai redaktur. Tapi di sini pun tak lama. Sikap kerasnya membuat ia mundur karena bertengkar dengan pemilik koran, M. van Geuns. Douwes Dekker menuding Geuns dibeli penjajah dalam memutuskan sikap redaksi.
Sejak itu, Douwes Dekker menjadi koresponden beberapa koran yang terbit di Bandung dan Sumatera, sebelum ditampung Bataviaasch Nieuwsblad sebagai korektor. Kariernya terus moncer hingga ia menjadi redaktur utama pada usia 28 tahun. Hidupnya juga tergolong sejahtera.
Dalam puncak kariernya ini, Douwes Dekker kerap berinteraksi dengan intelektual pribumi, terutama mahasiswa sekolah kedokteran di Batavia. Lewat dua korannya itu, dia dianggap perwakilan semangat pribumi menentang penjajah. "Dua surat kabar ini tak kenal menyerah melawan Belanda," kata Margono Djojohadikusumo, yang menulis biografi Douwes Dekker.
Pemerintah kolonial pun menyebut Douwes Dekker sebagai "pembakar semangat antikolonialisme". Tapi, di Bataviaasch, ia juga tak lama. Dia hengkang karena bertengkar dengan pemimpin redaksi, Zaalberg. Tak punya pekerjaan, Douwes Dekker memutuskan hijrah ke Belanda. Tapi itu tak lama karena kabar tentang penjajahan selalu mengusiknya.
Pulang ke Batavia, ia menerbitkan Het Tijdschrift. Koran dwimingguan ini ia isi dengan tulisan tentang nasionalisme pertumbuhan nasionalisme di kalangan anak muda Jawa. Pada Maret 1912, dengan pergaulannya yang luas, Douwes Dekker berhasil menggalang dana 200 ribu franc. "Uang ini saya pakai untuk menerbitkan De Expres," ujarnya.
Koran terakhir ini kemudian ia pakai sebagai media resmi Indische Partij, partai politik pertama di Hindia yang ia dirikan bersama aktivis mahasiswa kedokteran, Tjipto Mangoenkoesoemo dan Ki Hadjar Dewantara, pada 25 Desember 1912. Douwes Dekker kemudian mengubah namanya menjadi Danudirja Setiabudi.
Tiga anak muda ini secara bergiliran menulis di De Expres, mengecam Belanda dan membangkitkan nasionalisme. Akibatnya, pada tahun pertama koran itu, Douwes Dekker mendapat lima gugatan hukum.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo