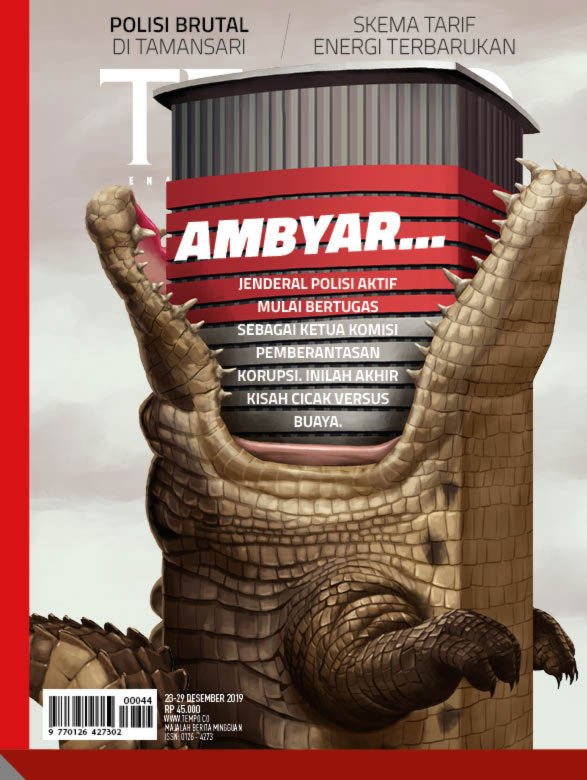Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Media sosial, menjadi titik awal kemunduran hidup Clemmie Hooper, bidan yang dikenal juga sebagai "Mother of Daughters" oleh para pengikutnya di Instagram. Meski menerima banyak sokongan iklan untuk terus menjadi blogger soal pengasuhan anak, Hooper memutuskan menutup akunnya setelah secara publik mengaku sering berkomentar tak pantas pada unggahan blogger saingannya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dia berada di ujung tanduk setelah Dewan Keperawatan dan Kebidanan (NMC) Inggris didesak publik untuk mencabut izin prakteknya. NMC merespon tekanan ini dengan mengatakan bahwa keresahan publik tersebut sudah diteruskan kepada “pihak-pihak yang relevan.”
Lain hal dengan Hooper yang menaruh dirinya sendiri pada posisi tersebut, influencer lainnya bernasib sama setelah karir mereka terhalang berbagai tekanan yang datang dari pengguna internet.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menurut profesor marketing sekolah bisnis Universitas Loyola Chicago, Jenna Drenten, “Platform seperti Instagram mungkin tidak secara langsung mendorong penggunanya untuk berkomunikasi dengan para para pengusik ini, tetapi interaksi tersebut secara tidak langsung didorong oleh keterlibatan para pengguna dan kemampuan mereka menjadikan sorotan ini sebuah potensi untuk monetisasi.”
Daripada menghapus unggahan, sebuah penelitian memperlihatkan beberapa influencer perempuan di medsos memilih membalas kritikan dengan emoji-emoji ceria atau “lol,” (akronim untuk ‘tertawa terbahak-bahak’). Karena membalas komentar negatif tersebut justru mendorong visibilitas akun mereka dan membuka peluang monetisasi lebih besar.
Tapi itu bukan hal yang mudah. Bahkan mereka yang bukan influencer era digital pun kerap merasa karir mereka ternodai oleh media sosial. Di tahun 2013, Justine Sacco, seorang humas eksekutif di Amerika Serikat, kehilangan pekerjaannya setelah Tweet dia dianggap menghina.
***
Pada 2016, Angela Gibbins dikeluarkan dari pekerjaannya di Inggris setelah mengunggah status Facebook yang menjelekkan Pangeran George. Komentar Angela pada akhirnya diberitakan oleh pers meski dia sudah memperketat tingkat privasi akun Facebook-nya. Pengadilan ketenagakerjaan menguatkan pemecatan dia setelah membuktikan Angela tidak mengindahkan nasihat perusahaan untuk berhati-hati dalam dalam berkomentar di media sosial. 
Sebuah server farm milik situs pencarian Google. Situs ini berkembang dari sebuah garasi di Silicon Valley, oleh Larry Page dan Sergey Brin, dengan tujuan mengembangkan sistem untuk menghubungkan server komputer secara murah dan mewujudkan ambisi untuk membangun digital roadmap bagi semua informasi dunia. Dailymail.co.uk
Profesor hak asasi manusia dan hukum ketenagakerjaan Virginia Mantouvalou dari University College London ini menulis jurnal akademis berjudul “Saya Kehilangan Pekerjaan Karena Status Facebook - Apakah Adil?” Di dalamnya tertuang alasan-alasan mengapa perusahaan berwenang untuk memeriksa konten media sosial para pekerjanya, terlebih untuk menghindari potensi terganggunya performa pekerjaan, relasi di kantor, dan reputasi bisnis perusahaan.
Namun, menurut Mantouvalou, argumen bahwa perusahaan berhak untuk menjaga reputasinya melalui pengawasan media sosial beririsan dengan hak privasi para pekerja dan “pandangan moral tentang bagaimana para pekerja diatur cara menjalani hidup mereka sendiri.” Kuasa berlebih ini juga dapat menguatkan alasan pemecatan seseorang dengan alasan performa pekerjaan buruk - yang sebetulnya tidak berkaitan.
Media sosial yang berakhir menjadi penghalang pekerjaan dialami juga oleh penyanyi dengan 108 juta lebih pengikut Instagram, Nicki Minaj. Dia mengumumkan tak akan mengunggah konten di platform tersebut setelah Instagram menguji sistem baru dengan membuat jumlah “likes” tidak terlihat secara publik. Rapper tersebut juga angkat suara untuk pengikutnya yang terdistraksi dengan Tweet-nya, “Hmmm, apa yang harus saya lakukan sekarang? Bayangkan waktu yang bisa saya habiskan dengan kehidupan baruku.”
Penulis The Curious Incident of the Dog in the Night-Time, Mark Haddon, menulis di Financial Times tahun ini bahwa ia akan rehat dari Twitter setelah menyadari waktunya terlalu banyak dihabiskan untuk memikirkan komentar-komentar rancak dan dipusingkan oleh perkataan orang. “Singkatnya, saya telah membuang waktu, energi, dan emosi. Interaksi dengan mereka di sekeliling saya mulai berkurang, dan kebebasan saya dalam berpikir juga menjadi korban.”
Banyak pengguna mengaku menjadi kelewat berhati-hati dalam berkomentar di media sosial. Ini berujung menjadi sifat sensor-diri yang berefek pada pola pikir mereka. Asisten profesor manajemen di California State University, Lorenzo Bizzi, mengatakan bahwa kita cenderung memiliki pandangan sederhana mengenai media sosial dalam hal pekerjaan. Menurutnya, pengguna seringkali tidak dapat membedakan antara aktivitas pasif, seperti menggulir beranda, dengan aktivitas aktif seperti mengunggah konten.
“Perilaku media sosial yang berbeda akan memancing reaksi yang berbeda pula,” kata Bizzi. 
Media Center yang difasilitasi oleh panitia Muktamar Muhammadiyah ke-46 di kantor BPPTK, Jalan Cendana, Yogyakarta, Minggu (4/7). Belasan komputer baru dan konsumsi disediakan untuk wartawan yang meliput kegiatan muktamar. Tempo/Arif Wibowo
Bizzi menekankan bahwa penggunaan media sosial bisa beragam tatkala difungsikan dalam bidang pekerjaan tertentu. Seperti di bidang kreatif yang dapat beristirahat sejenak dengan berselancar di media sosial dan mendorong orang bekerja lebih produktif. Akan tetapi efeknya bisa berbeda untuk bidang pekerjaan yang repetitif yang memungkinkan penggunanya untuk mengubah bermedia sosial menjadi cyberloafing, yaitu berselancar di internet tapi berpura-pura sedang bekerja.
Hanya saja, bisa jadi bidang pekerjaan itu sendiri yang salah. Apabila pekerjaan anda kurang memuaskan, godaan Instagram akan lebih menarik dibandingkan dengan spreadsheets. Profesor studi organisasi di Departemen Administrasi Bisnis Universitas Lund, Roland Paulsen, meriset tentang kerja kosong (empty labour) yang didefinisikan olehnya sebagai “aktivitas pribadi dalam pekerjaan.”
Profesor Paulsen berargumen bahwa; “Meski sudah ada banyak penelitian sosiologis membuktikan bahwa ketatnya kompetisi globalisasi mengarah ke prekarisasi dan bertambahnya gejala patologi sosial seperti “burnout” (stress fisik atau mental akibat pekerjaan), beberapa studi mengungkap bahwa pekerja rata-rata menghabiskan 1,5 hingga tiga jam saat jam kerja untuk melakukan aktivitas yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan mereka.”
Tapi negativitas tersebut tidak berlaku bagi beberapa orang yang melihat manfaat media sosial bagi karir mereka. Contohnya seperti pekerja lepas untuk melawan rasa kesendirian dan menggunakannya sebagai medium interaksi sosial karena tidak bekerja di sebuah kantor.
Beberapa pekerja memuji peran media sosial saat menjawab pertanyaan Financial Times di Twitter, terutama dalam konteks lingkungan pekerjaan. Seorang konsultan dari layanan kesehatan umum Inggris mengungkap peran platform tersebut untuk mengedukasi khalayak global. “Saya bisa menyebarkan pengetahuan tentang studi kasus medis ke puluhan ribu orang, lintas batas negara, waktu, hirarki profesional dan sosial. Daripada saya berurusan dengan lusinan orang di sebuah ruangan.”
Aktivitasnya di media sosial juga mempertemukan dia dengan berbagai kenalan baru di luar Inggris yang kemudian malah menjadi kolaborasi profesional. Topik pembicaraan pengguna Twitter ini menyangkut hal-hal yang bersifat pekerjaan, dari hal ringan seperti fitur deteksi suara hingga soal pajak pensiunan.
Media sosial juga bisa menjadi platform untuk mereka yang suaranya kurang terdengar. Asisten profesor bidang tanggung-jawab sosial korporasi dan etika di Trinity College Dublin, Tanusree Jain, mengatakan: “Sebagai perempuan berkulit hitam, saya tahu betapa mudahnya kita terpapar komentator biang keladi (troll) di media sosial.”
Jain menggaris-bawahi bahwa media sosial dapat memperkuat suara dan opini seseorang “yang sayangnya tidak terwakilkan oleh platform arus utama” dan menciptakan tokoh-tokoh panutan yang sebelumnya tidak ada. “Hal ini mendorong kita untuk memberikan perhatian lebih ke komunitas global.”
Jawaban atas pertanyaan Twitter kami juga datang dari seorang perempuan yang bekerja di industri penerbangan. Dia menemukan bahwa media sosial menjadi perangkat penting untuk memperkuat aktivitas serikat para pekerja, seperti yang pernah terjadi di industri teknologi saat pekerja Google berbondong-bondong menggunakan tagar #Googlewalkout untuk mengkoordinir demonstrasi beberapa waktu silam.
Namun, dia menyayangkan banjirnya perselisihan dan maraknya berita-berita palsu (fake news) di grup-grup Facebook. “Media sosial telah sudah menjadi bagian dari kehidupan kita yang bisa membawa hal-hal positif seperti pertemanan dan informasi, terutama bagi tenaga kerja. Sayangnya, itu juga bisa membawa efek negatif dengan menyita kesejahteraan emosi dan waktu kita, juga pada apa yang kita rasakan terhadap perusahaan dan kolega-kolega kita. 
Deklarasi antihoaks yang diselenggarakan Kepolisian Daerah Metro Jaya di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, April 2018. TEMPO/Muhammad Hidayat
***
Michelle Phan, "Ketika dapat banyak likes, rasanya seperti memakai narkoba."
Sebagai pionir beauty vlogging dengan nyaris 9 Juta pengikut di Youtube, Phan mulai membuat konten di platform medsos berbasis video tersebut pada 2007. Phan menghilang sesaat selama dua tahun belakangan dari Youtube sebelum kembali di bulan September. Selain seorang beauty influencer, Phan kini juga duta untuk Bitcoin.
Phan mengungkap bahwa dia terus-menerus secara konstan memproduksi konten sebelum mengambil “cuti” dua tahunnya. “Saya kelelahan karenanya. Saya mulai kehilangan motivasi dan tidak lagi menikmati apa yang saya lakukan. Sebagai konten kreator online, kita melepaskan endorfin ke tubuh saat diganjar banyak likes dan respon. Online dan mendapat validasi tiada henti itu seperti narkoba.
Ada kalanya aktivitas online tersebut menjadi sumber stres; “Dada saya sesak dan seringkali bermasalah dengan pernafasan saya.”
Sejenak melepaskan diri dari produksi video memungkinkan dia untuk mengurangi waktunya di Twitter dan Instagram. “Saya tidak lagi memikirkan bagaimana mengelabui algoritma. Saya fokus dengan kehidupan di luar kehidupan medsos.”
Phan ingin mencicipi kehidupan normal lagi dan setelah satu tahun, dia berhasil mencapainya. “Saya dilupakan. Terlalu banyak “suara” yang dihasilkan media sosial malah menimbulkan rasa kesunyian dalam hidupku. Saya terpaksa membungkam bunyi-bunyian tersebut untuk memulihkan pikiran batinku.”
Sebagai pionir di dunia vlogging, atau blogger berbasis video, Phan tidak yakin arah karirnya akan menuju ke mana. “Saya enggan berlama-lama hanya untuk menyaksikan akhir hidup saya. Sebuah bintang juga lama - lama akan terbakar dan menghilang. Hal tersebut menjadi tombol atur ulang egoku yang memaksa membuat batasan pribadi dan mengevaluasi ulang arah tujuanku.”
Kala itu, gosip dan kritik online mempengaruhinya. “Kamu harus antipati agar tidak terluka oleh troll dan komentar - komentar negatif. Banyak yang menyebarkan gosip tentangku yang pada akhirnya jadi pembahasan di vlog gosip karena itu adalah infotainment dan orang - orang suka dengan hiburan. Hal itu mencerminkan diri mereka - melihat orang terkenal tidak sendiri. Mereka akan merasa lebih baik dengan adanya itu," katanya.
"Gosip itu seperti makanan cepat saji yang rasanya enak tapi buruk bagi kesehatan. Saya juga terpancing pada clickbait. Aku tidak bisa kontrol apa yang orang pikirkan tentang aku dan satu-satunya yang di bawah kuasaku adalah bagaimana aku harus bereaksi.”
Namun, orang jarang menyuarakan kritikan mereka saat bertemu langsung dengannya. “Orang akan menjadi sangat baik padaku di setiap meet and greet, internet tidak mencerminkan kehidupan nyata.”
Masa rehat yang dia lalui memberi Phan waktu untuk mempelajari lebih dalam tentang cryptocurrencies.
“Dari semua komunitas yang saya ikuti, komunitas bitcoin adalah salah satu yang paling informatif secara politis dan finansial. Troll tentu saja akan tetap ada, tapi mereka lebih marah kepada dunia finansial.” Phan juga gemar dengan anggota komunitasnya yang terdiri dari berbagai kalangan umur dan latar belakang. “Ada sopir truk, ada mereka yang mencampakkan Wall Street. Komunitasnya sangat beraneka - ragam.”
Di luar ekspektasinya, video Youtube yang dia muat mendapat sambutan hangat.
“Lebih baik orang merindukanmu daripada orang yang lama - lama jengah akan dirimu.”
---------------------------------------------------------------------------------
Heidi Allen, "Platform medsos sudah dikuasai para Troll."
Anggota parlemen (MP) perempuan ini adalah salah satu figur publik yang lantang menyuarakan betapa beracunnya media sosial. Analisa terbaru Financial Times menemukan bahwa MP perempuan ini sering menjadi target dari serangan online terutama setelah debat parlemen Desember 2019 lalu di mana Perdana Menteri Boris Johnson menganggap ancaman kematian pada dirinya sebagai omong - kosong.
Sebuah penelitian oleh Amnesty International menguak kenyataan bahwa anggota parlemen perempuan berkulit hitam dan Asia lebih sering menjadi target serangan online ketimbang anggota lainnya yang berkulit putih. Diane Abbott, anggota parlemen berkulit hitam, menjadi subyek serangan Twitter pada masa kampanye dirinya pada pemilihan tahun 2017.
Sayangnya, Heidi Allen, anggota parlemen dari kubu Konservatif yang pindah haluan ke Demokrat dari Cambridgeshire Selatan, tidak bertahan lama di pemilihan Inggris yang terakhir. Dia mengutip “pelecehan yang tidak manusiawi” yang dia hadapi.
Meski menjadi salah satu faktor, media sosial bukan satu-satunya alasan Allen membatalkan pencalonan dirinya. “Untukku, dorongan utamanya adalah ancaman di kehidupan nyata yang makin parah dan email-email yang yang aku terima. Media sosial menjadi titik akhirnya. Berbagai cacian utamanya datang dari “pejuang online” menyedihkan hingga troll yang sengaja membuyarkan wacana publik.”
“Mimpi buruk tersebut lebih parah dialami oleh perempuan dan saya tidak melihat para pria berempati setelah melihat ancaman pemerkosaan di media sosial. Perempuan mendapat perlakuan lebih buruk daripada laki-laki.”
Sifat anonimitas online berujung pada dampratan. “Hal itu tambah parah apabila kita baca komentar - komentarnya selama lima menit.” Menurutnya, sikap trolling mempengaruhi wacana online. “Media sosial mengubah mereka yang normal di Twitter. Entah hal itu menjadikan mereka a) OK, b) mengotak-ngotakkan mereka, dan itu hal terakhir yang kita inginkan tentunya. Masyarakat modern seperti kita harus bisa menyuarakan pandangan tanpa perlu agresif.”
Di kala beberapa MP memilih vakum dari media sosial dan memilih komunikasi langsung dengan konstituennya, Allen merasa peran anggota parlemen adalah untuk berpartisipasi dalam debat nasional, yang juga termasuk di media sosial.
Menurutnya, tanggapan dari Twitter sebagai figur otoritas juga kurang memadai saat dia melaporkan apa yang ia alami. “Setiap aku mendapat ancaman di Twitter, saya melaporkannya tapi dibalas oleh bot. Platform ini tidak pas lagi untuk seorang anggota parlemen. Mungkin dulu pernah berhasil sebagai alat komunikasi, tapi akhir - akhir ini sudah dikuasai oleh para troll yang menghabiskan waktu kami dalam mengkurasi pengikut yang dapat menjadi koneksi berharga. Anda tidak bisa selalu menghadapi semua sampah itu untuk menggapai yang berguna."
Dia menyarankan para anggota parlemen baru untuk “berbicara dengan sesama anggota baru yang juga memakai platform ini dan bersiap untuk memanfaatkannya sebagai media siaran hingga Twitter bisa mencari solusi atas masalah anonimitas.
---------------------------------------------------------------------------------
Marian Keyes, "Medsos membantu saya mengikuti tren terkini."
Keyes penyumbang pertama arsip digital pribadinya kepada Perpustakaan Nasional Irlandia yang sedang mengumpulkan video, surat-surat elektronik, dan media sosial. “Pertama terjun ke Twitter kesehatan mental saya sedang tidak baik, ditambah saya pengangguran. Saya menghabiskan banyak waktu di Twitter. Semuanya berisi tentang apa yang kupikirkan saat melalui masa-masa itu. Tidak hanya sebagian, tapi semuanya.” Keyes juga mendonasikan draft awal beberapa novelnya, uang juga beserta komentar dari editor.
Dulu, Keyes sering dihampiri oleh orang-orang yang tidak ia kenali yang hanya ingin mengungkap kesukaan mereka terhadap karyanya. Namun kini, orang-orang tersebut lebih menyukai apa yang Keyes tulis di Twitter.
“Twitter punya efek buruk terhadap karya-karya tulisan saya, terlebih karena saya menghabiskan terlalu banyak waktu. Platform ini adalah cara terbaik untuk menunda pekerjaan, terbaik, dalam hal ini, adalah cara yang buruk sekali.” Keyes mulai masuk Twitter di tahun 2012 setelah didorong oleh penerbit dengan alasan sebagai platform untuk mempromosikan karyanya. “Saya terlalu menyukainya. Terlalu menyenangkan bagiku.” Dia bisa lebih santai menulis saat dia sedang berada di suasana hati yang tepat.” Sekalinya saya terbenam ke dalam pekerjaan saya, saya menikmatinya. Medsos tidak masuk ke gambaran ini.”
Keyes melihat Facebook tidak seperti dirinya melihat Twitter. “Pada saat saya membuat akun Facebook bertahun-tahun lalu, tetiba perempuan-perempuan jalang zaman sekolah ingin menjadi temanku. Kupikir mereka sudah pergi dari hidupku. Saya membenci semua ‘like’ dan ‘dislike’ yang kudapatkan. Menurutku itu sangat jahat.”
Keyes memandang Instagram “kurang interaktif dan mengecewakan karena tidak bisa membuka obrolan.” Yang paling dia benci adalah gaya hidup terkurasi tanpa cela yang diperlihatkan teman-teman Instagramnya.
“Twitter sangat meletihkan. Banyak pengguna yang sedang dipenuhi amarah dan hanya menunggu alasan untuk mengeluarkannya. Twitter menjadi tempat yang mereka paling suka habiskan. Ada kalanya saya mengatakan sesuatu yang mungkin biasa saja, tapi kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain menerimanya. Manusia itu spesies yang sangat beragam dan dengan titik amarah yang berbeda-beda. Selalu ada saja kesempatan di mana kamu memantik amarah seseorang.”
Twitter terkadang membuatnya merasa depresi. “Ini seperti pedang bermata dua. Saya bisa senang karena Twitter, tapi saya pemalu dan saya akan ambil hati apabila ada yang menegurku keras.”
Media sosial membantunya mengikuti tren-tren terkini, terutama cara orang berbicara bahasa slang maupun sintaksis. Dia melihat ini berguna untuk buku terbarunya yang berjudul Grown Ups tentang dua karakter berumur 30 dan 22, yang siap tayang di bulan Februari 2020.
Medsos menginspirasi bukunya yang berjudul The Break yang menceritakan karakter yang bekerja di bidang hubungan masyarakat, dan satunya bekerja sebagai vlogger kecantikan dengan nenek yang tiba-tiba terkenal di seantero internet.
Secara keseluruhan, media sosial membantunya menjadi lebih mawas diri dalam hal bahasa dan representasi. “Tujuh karakter utama di buku baru saya berkulit putih semua. Memang, ada karakter dengan ras lain di dalamnya, tapi media sosial membuatku berpikir apakah seharusnya saya membuatnya ke arah yang lebih baik.” Awalnya Keyes mendeskripsikan dirinya sebagai orang dengan gangguan batin (Keyes pernah mengalami depresi). “Tapi aku sekarang lebih perhatian dan bijaksana dan ini bukan hal yang buruk kok. Saya berkulit putih dan mengenyam pendidikan. Saya jadi sadar akan hak istimewa saya yang tidak saya sadari selama hidup.”
Media sosial membantu menaikkan profilnya di antara kaum laki yang mungkin dulunya tidak menghiraukannya. “Untungnya, laki-laki yang dulunya tidak akan membaca buku saya meskipun dipaksa, saat ini mengikutiku di medsos karena selera humor saya, dan hal ini membuatku senang. Platform ini membuatku lebih terekspos dan membantu meyakinkan mereka untuk membeli buku saya.” Ditanya apakah itu tidak menyebalkan? “Saya tidak tersinggung sama sekali. Satu hal menyenangkan saat beranjak lebih tua adalah saya bisa mengatakan bahwa mereka salah.”
---------------------------------------------------------------------------------
Ketika sebuah perusahaan menutup semua akun media sosial
Pada bulan April, brand kecantikan Lush menutup akun media sosial mereka di seantero Inggris. Sebelumnya, pada platform Instagram, Facebook, dan Twitter, brand ini mengunggah “Kami lelah melawan algoritma media sosial dan kami enggan mengeluarkan uang lagi untuk muncul dalam beranda anda.” Hal tersebut didorong oleh kenyataan bahwa hanya 6 persen pengikutnya yang terpapar konten mereka sebelumnya, Lush menolak untuk mengeluarkan uang guna mengiklankan produknya di medsos. Saat ini, Lush lebih fokus pada platform yang mereka buat sendiri, termasuk di e-commerce dan situs konten.
Kepala digital Lush, Jack Constantine, mengatakan; “Anda bisa tertipu anggapan akan jutaan pengikut tapi hanya mampu mencapai 6 persen dari angka itu. Namun, sekarang ada perantara, yaitu platform media sosial yang memutuskan sendiri cara menggapai para pelanggan. Kami terus bereksperimen untuk menemukan formula yang berhasil.”
Lush percaya bahwa pelanggan mereka akan lebih peduli pada konten cerita yang baik mengenai manfaat produk yang dirasakan sendiri oleh para pelanggan. Constantine mengutip contoh unggahan seorang pelanggan perempuan tentang produknya, Lush’s Dream Cream, pada eksim kulitnya. Meskipun Lush bekerja sama dengan influencer, namun mereka tidak mengeluarkan uang untuk jasa mereka.
Penggunaan tanda pagar, atau hashtag, #lushcommunity justru tumbuh hingga 42 persen setelah Lush menutup akun medsos mereka. Suara para pengguna Lush pada platformnya sendiri terbukti lebih populer ketimbang di Twitter ataupun Instagram.
Akan tetapi, sisi lain dari model bisnis ini adalah menurunnya jangkauan paparan mereka pada pelanggan potensial. “Kami memperparah tren penurunan yang sudah terdeteksi sebelumnya.”
Perusahaan mau tidak mau harus bekerja lebih keras untuk memperbaiki optimasi pencariannya. “Anda harus menanam bibitnya,” kata Constantine. “Sudah ada subkanal di Reddit tentang kami, tapi itu dikelola oleh para pengguna situs itu sendiri. Kami bisa diusir kalau kami mempromosikan sesuatu di dalamnya.”
Menariknya, Lush mengatakan bahwa penjualan mereka tidak mengalami penurunan semenjak menutup mereka akun-akun medsos. (*)
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo