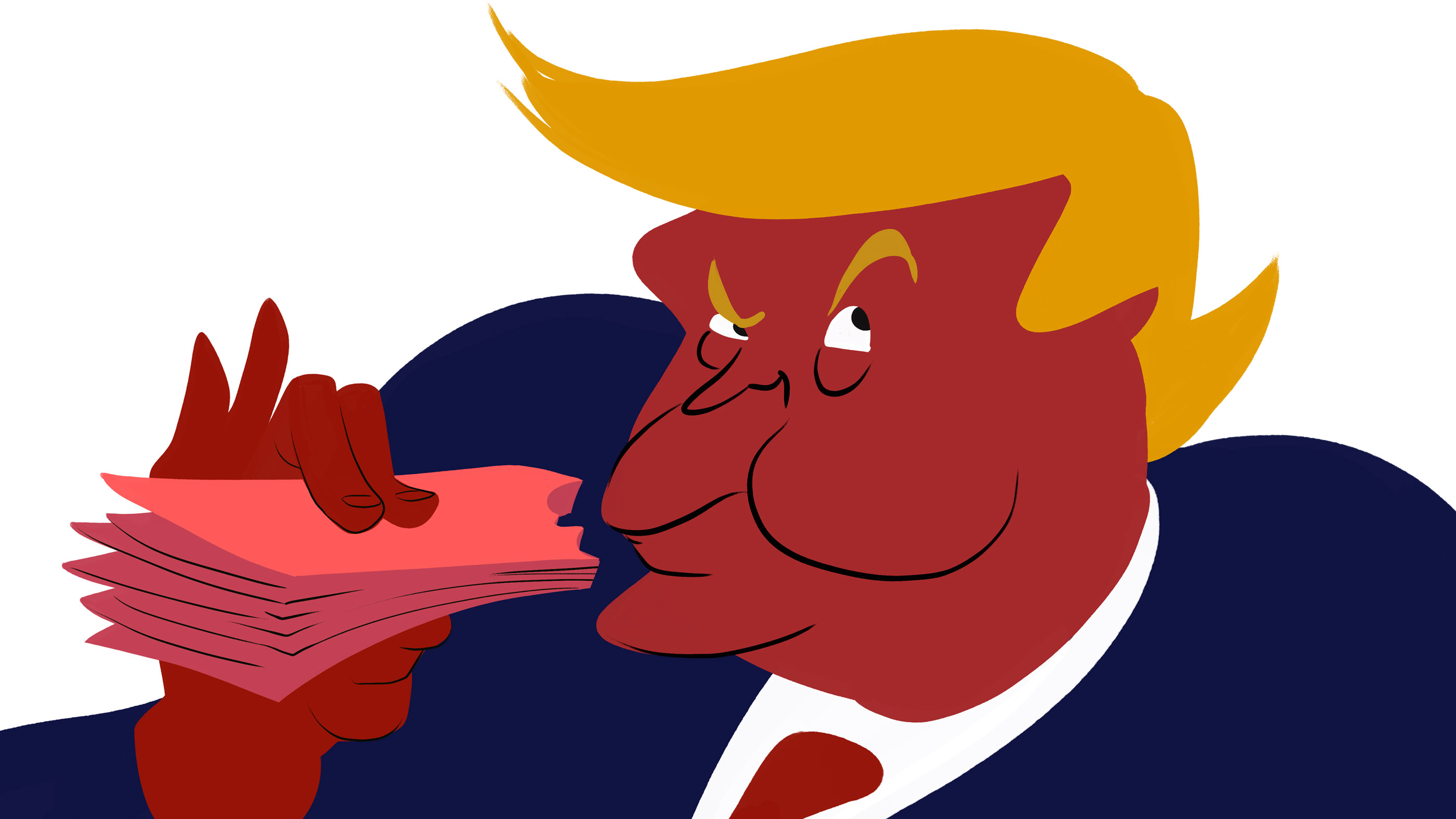Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Banyak proyek pembangkit listrik tenaga sampah yang mandek.
Sejumlah daerah megap-megap memenuhi biaya pengolahan yang mahal.
KPK dan PLN mendorong pengolahan sampah jadi co-firing PLTU yang lebih murah.
PAHALA Nainggolan, Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, langsung lesu ketika Pemerintah Kota Tangerang, Banten, meneken perjanjian kerja sama pengolahan sampah energi listrik (PSEL) dengan PT Oligo Infra Swarna Nusantara pada pertengahan Maret lalu. Oligo sebetulnya sudah memenangi tender proyek itu dua tahun lalu. Tapi pemerintah Tangerang tak kunjung menandatangani perjanjiannya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dua tahun terakhir, Wali Kota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah meminta bantuan KPK agar bisa membatalkan tender itu. Dalam hitung-hitungan pemerintah Tangerang, permintaan biaya pengolahan sampah (tipping fee) yang diajukan Oligo kelewat mahal dan tidak detail.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kantong anggaran pemerintah daerah tak cukup buat menanggung biaya pengolahan sampah sebesar Rp 310 ribu per ton yang diajukan Oligo—termurah dibanding peserta tender lain. Dengan produksi sampah mencapai 1.400 ton per hari, pemerintah kota setidaknya harus menyediakan anggaran sampai Rp 434 juta per hari atau Rp 13 miliar per bulan. “Arief sudah bolak-balik minta perlindungan agar tender dibatalkan,” kata Pahala, Rabu malam, 20 April lalu.
Maju-mundurnya langkah Pemerintah Kota Tangerang dalam mengeksekusi proposal Oligo itu buntut dari kajian KPK pada 2020, yang menyimpulkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik dalam bentuk pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) berpotensi terlalu mahal. Dalam skema bisnis itu, investor swasta punya dua sumber pemasukan untuk mengembalikan investasi dan mengeruk keuntungan.
Pundi-pundi pertama berasal dari tipping fee dari pemerintah daerah. Agar tidak memberatkan, pemerintah pusat menyediakan subsidi, maksimal Rp 500 ribu per ton. Sumber pemasukan kedua adalah PT Pembangkit Listrik Negara (Persero), yang bakal membeli setrum dari sampah itu dengan harga yang sudah dikunci pemerintah, maksimal US$ 13,35 sen per kilowatt-jam untuk pembangkit berkapasitas maksimal 20 megawatt.

Walikota Tangerang Arief R Wismansyah (kedua kanan), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan (tengah), dan Komisaris PT Oligo Infra Swarna Nusantara (Oligo) Bambang Brodjonegoro (kedua tengah), saat penandatanganan perjanjian kerja sama antara Oligo dan pemerintah Kota Tangerang untuk membangun pengolahan sampah menjadi energi listrik, 9 Maret 2022. Tangerangkota.go.id
Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Jadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. “Kontraknya take or pay semua. Take or pay ke kiri (dengan pemerintah daerah), take or pay ke kanan (PLN). Kok, kontrak begini bisa hidup?” ujar Pahala.
Ketika menyimpulkan potensi kemahalan proyek PSEL tersebut, KPK sebetulnya menyodorkan opsi. Mereka mendorong pengolahan sampah menggunakan teknologi yang lebih murah, yaitu dengan mengubah sampah menjadi jumputan padat alias refused-derived fuel (RDF). Jumputan ini nantinya dibakar bersama (co-firing) di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.
Kota Tangerang menjadi yang pertama mencoba teknologi RDF sejak April 2021, bekerja sama dengan PT Indonesia Power, anak perusahaan PLN. Pemerintah kota memproduksi jumputan padat dari tumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Rawa Kucing, lalu menjualnya ke PLTU Lontar milik Indonesia Power yang berjarak 30 kilometer dari TPA. “Setelah dicoba, eh, dia (Arief) diomelin sama Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi,” tutur Pahala.
Percobaan tersebut akhirnya berakhir. Tangerang tak sampai meningkatkan proyek itu ke skala komersial.
Setelah tertunda beberapa tahun, penandatanganan kontrak PLTSa dengan Oligo akhirnya tetap dilakoni Pemerintah Kota Tangerang. Gara-gara lokasi TPA Rawa Kucing berdekatan dengan Bandar Udara Soekarno-Hatta, proyek digarap dengan dua langkah: memproduksi RDF di TPA, lalu mentransfernya ke PLTSa Oligo yang agak jauh dari bandara. “Kementerian Koordinator Kemaritiman tetap mendorong Tangerang melaksanakan PLTSa tersebut,” ucap Pahala. “Bolehlah mendorong PLTSa, tapi RDF didorong juga. Saya berharap pemerintah daerah waras sendiri.”
Tertundanya penandatanganan kontrak PLTSa Tangerang sempat membuat panas-dingin hubungan KPK dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Pemenang tender seperti Oligo—investor asal Prancis—juga ikut senewen.
Oligo meminta bantuan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro. Mantan Menteri Riset dan Teknologi ini didapuk menjadi komisaris utama perusahaan sejak Juli 2021. Bambang mengontak Basilio Dias Araujo, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves), untuk menanyakan status kemenangan tender Oligo di Tangerang.
Dalam pertemuan virtual pada akhir tahun lalu, Bambang menanyakan apa yang menghambat penandatanganan kontrak Oligo. “Saya mengingatkan Kemenkomarves, swasta sudah menang tender tapi enggak ada kepastian,” kata Bambang pada Kamis, 21 April lalu. “Coba diselesaikan, minta kepastian saja, ini mau jalan terus atau tidak?”

Foto udara lapisan geomembran menutup hamparan lahan bekas timbunan sampah untuk menghasilkan metana pada proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Landfill Gas di Tempat Pembuangan Akhir Jatibarang, Kota Semarang, Jawa Tengah, 17 April 2021. ANTARA/Aji Styawan
Basilio mengaku mendorong Pemerintah Kota Tangerang segera meneken kontrak dengan Oligo. Namun Basilio menjelaskan, penandatanganan itu dilakukan atas kemauan Pemerintah Kota Tangerang sendiri.
Pemerintah kota, menurut Basilio, kesal lantaran biaya pengolahan sampah menjadi RDF, yang mencapai Rp 350 ribu per ton, lebih mahal daripada tawaran Oligo. Jika mengambil skema RDF, Tangerang tidak bisa mendapat subsidi dari pemerintah karena bantuan biaya pengolahan layanan sampah (BBLPS) hanya berlaku bagi PLTSa yang menggunakan teknologi pemanasan—dari pembakaran (insinerasi) hingga pemanasan dengan gas (gasifikasi)—yang juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018. “Akhirnya Wali Kota Tangerang putuskan kembali ke fasilitas BBLPS yang diberikan dalam Perpres Nomor 35 Tahun 2018,” ujar Basilio pada Jumat, 22 April lalu.
Dihubungi Ayu Cipta dari Tempo sejak Jumat, 22 April lalu, Wali Kota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah tak menjawab pertanyaan tentang keputusannya menandatangani kontrak dengan Oligo. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kota Tangerang Buceu Gartina sempat berjanji menghubungkan Tempo dengan Arief lewat ajudannya. Namun hingga Sabtu, 23 April lalu, tak ada respons lanjutan dari pemerintah daerah. Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Tangerang Tihar Sophian juga tak menjawab pertanyaan Tempo.
•••
PENANDATANGANAN kontrak pembangkit listrik tenaga sampah Kota Tangerang menjadi titik balik proyek serupa di kota lain. Sejak pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Jadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan pada 16 April 2018, dari 12 kota percontohan, baru Surabaya yang berhasil membangun PLTSa.
PLTSa di Surakarta, Jawa Tengah, sudah mulai dibangun, tapi prosesnya tertahan gara-gara pandemi Covid-19. Proyek di kota besar lain, yaitu Jakarta, Tangerang Selatan, Bekasi, Bandung, Semarang, Makassar, Denpasar, Palembang, dan Manado, belum memberikan kabar perkembangan berarti. Pengembang proyek di Jakarta, yang lebih dulu menggelar tender, malah mundur, yaitu Fortum dari Swedia.
Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 diterbitkan untuk mengatasi produksi sampah yang terus menggunung, hingga 64 juta ton per tahun, yang selama ini digelontorkan begitu saja ke tempat pembuangan akhir—sebagian bahkan mengotori laut atau lingkungan warga. Penanganan sampah dengan model demikian melahirkan banyak efek buruk. Kebutuhan lahan TPA terus meningkat. Lingkungan sekitar TPA pun tercemar, termasuk akibat emisi gas metana yang dilepaskan sampah ke udara.
Perpres itu menargetkan paling tidak 5,8 juta ton sampah per tahun, dari 12 kota tersebut, dapat diolah menjadi listrik. Hitung-hitungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, belanja modal untuk proyek sampah menjadi listrik itu mencapai US$ 5,3 juta atau sekitar Rp 76 miliar per megawatt. Dibutuhkan dana setidaknya US$ 1,16 miliar atau sekitar Rp 16,75 triliun untuk membangun PLTSa di 12 kota dengan kapasitas total 219,5 megawatt. Asumsi biaya itu didasari teknologi yang digunakan, dari insinerasi hingga gasifikasi.
Agar menarik minat pemodal berinvestasi di PLTSa, pemerintah menyusun skema bisnis yang aduhai. Pemodal diiming-imingi dua sumber pemasukan sekaligus, yakni biaya pengolahan layanan sampah (tipping fee) dan harga jual listrik ke PLN yang sudah dikunci. Konsesinya berlaku selama 25 tahun. “Kalau pengolahan sampah saja, tidak layak secara ekonomi,” kata Basilio Dias Araujo, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi. “Maka pemerintah cari tambahan (bisnis) supaya perusahaan bisa hidup, yaitu listrik, sebagai produk akhirnya.”
Skema bisnis ini memunculkan sejumlah investor dadakan. Salah satunya Bobby Gafur Umar. Mantan Direktur Utama PT Bakrie and Brothers Tbk ini sekarang memimpin Indoplas Energy Group, yang menggarap Fasilitas Pengolahan Sampah Antara Wilayah Barat DKI Jakarta di Cakung. Bersama PT Wijaya Karya (Persero), Bobby membentuk konsorsium untuk menggarap proyek yang ditugaskan kepada PT Jakarta Propertindo tersebut—badan usaha milik DKI Jakarta. “Kami membawa teknologi insinerasi dari Jerman,” ujar Bobby di kantornya di Jakarta pada Senin, 14 Maret lalu.
Bobby mengaku tak mempertaruhkan modal sendiri. Dia mengemas proyek dari fasilitas kredit ekspor plus asuransi pemerintah Jerman. “Ada campuran modal investor dan teknologi dari penyedia, yang dipaket oleh pembiayaan,” ucapnya. “Jerman mau jualan barang. Jadi barang mahalnya terkompensasi dengan pembiayaan murah mereka.” Setelah memenangi tender di Jakarta, Bobby mengaku mengincar dua tender PLTSa lain.

Pemulung memilah sampah di Tempat Pembuangan Akhir Rawa Kucing di Tangerang, Banten, 23 April 2022. TEMPO/Febri Angga Palguna
Kendati model bisnis PLTSa sudah dijamin menguntungkan buat pengembang, seperti yang dikatakan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, rupanya sejumlah daerah masih maju-mundur untuk menjalankan proyek itu. Menurut Basilio, proyek PLTSa molor terus lantaran sejumlah daerah masih berharap proyek digarap dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha. Artinya, pemerintah pusat yang berinvestasi di daerah, seperti lewat PT Sarana Multi Infrastruktur—skema yang disiapkan di Kota Semarang.
Banyak pula proyek yang tak berjalan karena pemerintah daerah mengambil skema kerja sama sejumlah pemerintah daerah dengan swasta. “Bayangkan, swasta harus deal satu-satu dengan pemerintah daerah,” ujar Basilio. Hambatan lain ada pada kemampuan keuangan daerah untuk membayar biaya pengolahan sampah kepada pengembang yang mencapai miliaran rupiah per bulan.
Dari sederet masalah itu, kata Basilio, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi akhirnya mendorong pemerintah daerah mengambil skema kerja sama daerah dengan pihak swasta saja, seperti yang dilakukan Surabaya, Surakarta, dan kini Tangerang. Pemerintah daerah juga tak perlu repot-repot menentukan teknologi yang akan digunakan. Pemerintah cukup memasang parameter dalam tender, seperti volume sampah yang harus dikurangi minimal 85 persen, dengan tingkat emisi yang sudah diikat. Tawaran termurah yang bisa memenuhi standar itulah yang menjadi teknologi pemenangnya. “Akhirnya terjadi tanda tangan tender antara Kota Palembang dan PT Indogreen Power,” ujar Basilio.
Basilio mengaku menyodorkan skema ini kepada sejumlah daerah, seperti Manado, yang kini sedang memperluas proyeknya mencakup sejumlah kota besar di sekitarnya dengan Provinsi Sulawesi Utara sebagai pemilik proyek. Ia juga menyodorkan skema ini kepada Provinsi Jawa Barat, yang akan menggandeng kota/kabupaten di Bandung Raya. “Tiga minggu lalu DKI Jakarta juga bilang ada investor yang mau bangun PLTSa dengan skema build, own, operate,” tutur Basilio. “Di lahan swasta itu sendiri.”
•••
BAGI Pahala Nainggolan, skema bisnis yang disiapkan pemerintah dalam proyek pembangkit listrik tenaga sampah di 12 kota percontohan sama seperti menciptakan sistem rente. Negara memberikan bisnis yang dijamin untung. “Enak benar jadi pengembang PLTSa. Investasi Rp 2 triliun, dapat pembayaran pasti,” ujar Pahala.
Menurut Basilio Dias Araujo, justru semua risiko ada di swasta. “You bangun, you olah, kita bayar,” katanya. “Kalau you enggak olah, kita enggak bayar. We have nothing to do.”
Untuk meredam potensi kemahalan dalam proyek tersebut, sejak dua tahun lalu KPK mendorong PLN menggencarkan uji coba pemanfaatan jumputan padat dari olahan sampah, sebagai teman pembakaran batu bara di PLTU milik mereka. Dengan refused -derived fuel atau RDF, pemerintah daerah hanya mengolah sampah menjadi jumputan, lalu menjualnya ke PLN sebagai pembeli. Atau menjualnya ke industri lain yang menggunakan bahan bakar padat dalam operasinya, seperti tekstil dan semen. Hasil penjualan RDF tersebut bisa digunakan untuk menutup biaya operasional pengolahan RDF.
Tangerang menjadi kota pertama yang digandeng PT Indonesia Power—anak usaha PLN pengelola sejumlah PLTU—untuk mengembangkan jumputan tersebut. Dimulai pada April 2021, proyek riset itu menghasilkan 10 ton RDF. Setiap 3 ton sampah menghasilkan 1 ton jumputan.
PLN telah mencoba membakar RDF itu di PLTU Lontar dan Suralaya di Banten. “Nilai kalornya memenuhi spesifikasi, 3.400 kilokalori per kilogram,” ucap Agung Murdifi, Executive Vice President Corporate Communication and Corporate Social Responsibility PLN, pada Jumat, 22 April lalu. “Hasil uji bakar secara umum tidak ada parameter operasi PLTU yang anomali.”
Lantaran Tangerang tidak melanjutkan proyek ke skala komersial, PLN membopong alat pengolah sampah menjadi RDF itu ke Kota Cilegon, yang hendak menjalankan uji coba tersebut. Di Cilegon, fasilitas RDF bikinan PLN kini mengolah 5 ton sampah per hari dari kapasitas 100 ton per hari. “Di luar lahan, biaya investasinya Rp 35 miliar untuk kapasitas 100 ton per hari,” Agung menambahkan.
PLN sejauh ini sudah mendesain pengolahan kapasitas 30 ton per hari buat sejumlah kota, di antaranya Bandung, Karawang, dan Purwakarta di Jawa Barat. Untuk kapasitas sebesar itu, biaya investasinya Rp 12-14 miliar. Adapun untuk skala komersial di Cilegon dan Lombok, Nusa Tenggara Barat, PLN sudah mengajukan permintaan pendanaan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang memiliki anggaran dari pinjaman lunak luar negeri. Sebab, sejauh ini PLN mengongkosi uji coba tersebut dengan dana tanggung jawab sosial perusahaan.
Basilio mengungkapkan, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi sudah memeriksa teknologi pengolahan sampah menjadi RDF yang diklaim lebih murah dibanding PLTSa tersebut. Klaim itu, menurut Basilio, berasal dari studi banding pengolahan RDF di Cilacap, Jawa Tengah. Biaya RDF di sana, kata Basilio, bisa murah karena mayoritas didanai oleh Denmark sebagai donor. “Ketika saya tanya ke Wakil Bupati Cilacap, kalau pakai uang sendiri, feasible enggak? Enggak feasible. Berarti informasi RDF lebih murah itu enggak bener.”
Bagi Pahala, RDF Cilacap mahal karena peralatannya mengikuti standar pemberi donor. Alat pencacah sampah diimpor dari Swedia, sementara lahan dibeli oleh pemerintah daerah. Adapun Semen Cibinong, sebagai pembeli RDF, ikut mengelola fasilitas tersebut dengan menempatkan sejumlah pegawainya di situ, yang juga digaji. “Ini jadi kemahalan satu lagi,” ucap Pahala Nainggolan. “Indonesia Power itu pakai alat pencacah dari Cina. RDF Cilegon contoh ideal.”
Mantan Menteri Riset dan Teknologi yang kini menjabat Komisaris Utama Oligo, Bambang Brodjonegoro, meminta pembandingan harga RDF dengan PLTSa disudahi. Tidak adil, tutur Bambang, jika PLTSa yang masih mahal dibandingkan dengan RDF. “RDF itu bagus bersyarat.”
Maksudnya, RDF menjadi ideal jika lokasi pembuatannya dekat dengan PLTU atau industri pengguna. Selain itu, menurut Bambang, RDF hanya bisa dihasilkan dari sampah organik. “Padahal jenis sampah kita macam-macam,” ujar Bambang. “PLTSa bisa mengolah sampah jenis apa saja.”
Berdasarkan hasil uji coba PLN di beberapa PLTU, fasilitas RDF perusahaan sanggup mengubah 80 persen volume sampah yang ada menjadi jumputan padat. Hanya 20 persen volume sampah yang tak bisa diolah menjadi RDF, seperti beling dan logam. Ada pula sampah jenis lain yang masih punya nilai ekonomis, seperti botol bekas, yang diambil pemulung. Praktis, dari 1.000 ton yang ada, misalnya, 800 ton bisa diolah menjadi RDF.
Ihwal prasyarat jarak, Agung membenarkan jika RDF disebut hanya akan ekonomis bila jarak antara fasilitas pengolahan RDF dan PLTU tidak lebih dari 100 kilometer. Itu sebabnya daerah seperti Jakarta, yang jauh dari PLTU, tak cocok menerapkan RDF karena akan berat di ongkos perjalanan. “Karena PLN beli di harga lokasi PLTU,” ucap Agung. Kini PLN menghargai jumputan padat setara dengan harga batu bara—sebelumnya hanya 80 persen dari harga batu bara.
Sambil menunggu komersialisasi RDF, PLN kini menjalankan bisnis pembelian RDF berskala kecil. Jauh di timur sana, di Ende, Nusa Tenggara Timur, ada sebuah koperasi yang mengumpulkan sampah dari rumah ke rumah. Sampah-sampah itu kemudian mereka olah menjadi RDF, lalu menjualnya ke PLTU Ropa berkapasitas 14 megawatt, sekitar 62 kilometer dari lokasi pengolahan. “Itu sudah dari Oktober 2021. Kapasitasnya kecil, 1 ton per hari,” kata Agung. “Kami punya kontrak pembelian RDF jangka panjang.”
Menurut Basilio, pemerintah pusat tidak melarang penggunaan model RDF. “Itu bisnis murni di antara mereka, terserah,” ujarnya. Namun Basilio mengingatkan, jika ingin mendapatkan bantuan layanan pengolahan sampah dari pemerintah pusat, pemerintah daerah mesti mengikuti skema Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018, yaitu membangun pembangkit listrik tenaga sampah. Tak bisa ditawar.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo