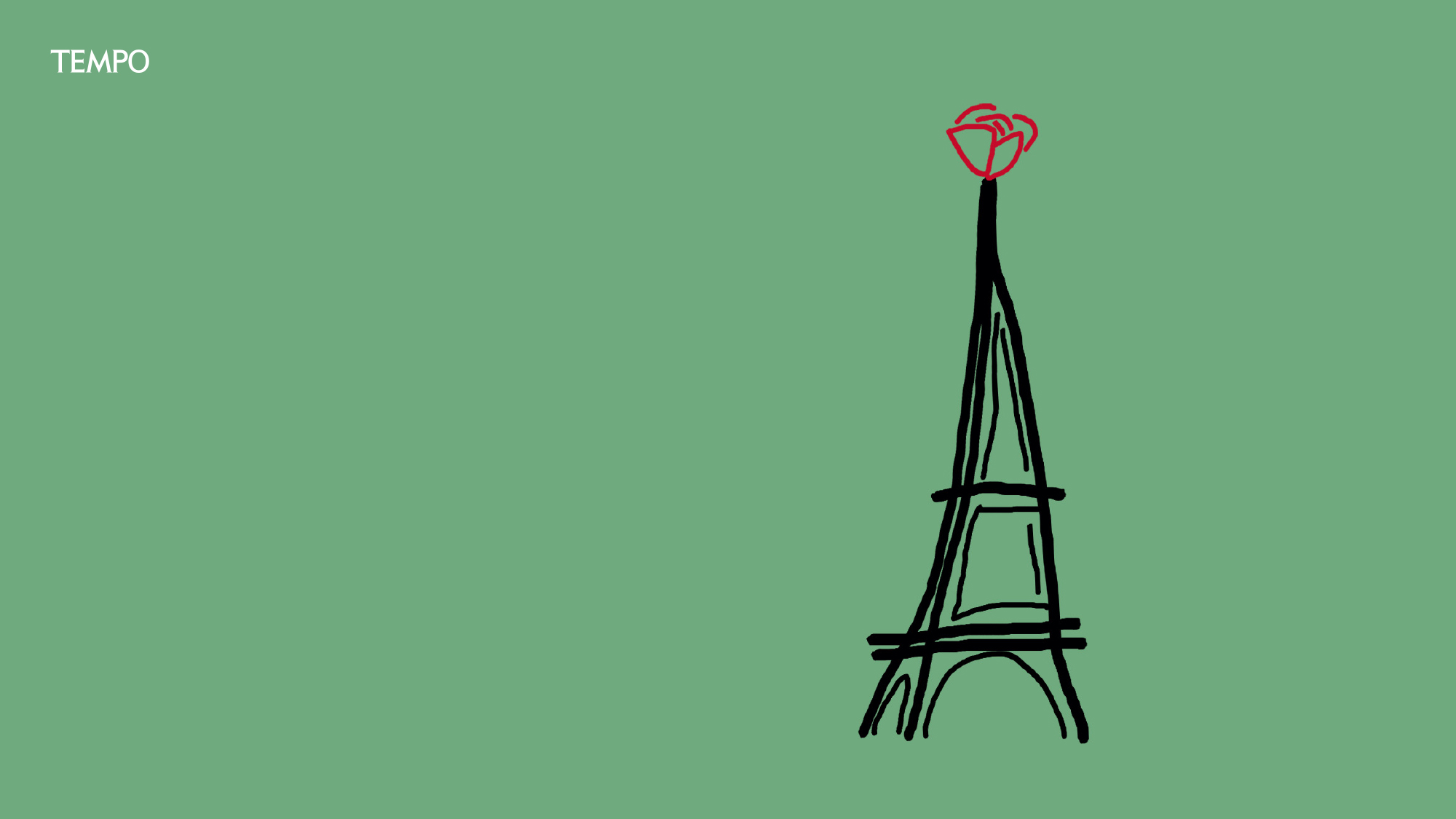Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kampung Wardo, Pulau Biak, 10 Oktober 1921.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
FRANS Kaisiepo lahir di desa subur yang dikepung ngarai dan sungai, buah cinta Alberth Kaisiepo dan Alberthina Maker. Bagi sejoli Alberth dan Alberthina, kehadiran anak ketiga ini begitu istimewa. Frans menjadi anak laki-laki pertama dalam keluarga ini. Frans Kaisiepo punya dua kakak perempuan dan dua adik laki-laki.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Frans datang dari keluarga terpandang di Wardo. Alberth, papanya, adalah kepala suku Biak Numfor yang pekerjaan sehari-harinya menempa besi. Pandai besi atau pandhe bukan pekerjaan sembarangan di sana. Mereka dihormati layaknya para tetua adat dan dianggap sebagai kaum cerdik pandai.
Menjadi orang berilmu, Alberth ingin anak-anaknya mengenyam pendidikan terbaik, termasuk Frans. “Kakek mendorong Bapak bersekolah,” kata putra bungsu Frans, Antonius Victor Kaisiepo, di Merauke, Papua Selatan, pada Rabu, 26 Juli lalu.
Frans masuk ke Sekolah Desa Klas 3 di Wardo. Sekolah desa juga dikenal sebagai dorpsschool B atau volkschool alias sekolah rakyat. Saat menempuh pendidikan dasar, Frans menumpang di rumah kerabat sang ayah yang tinggal di kota.
Menurut buku Pahlawan Nasional Frans Kaisiepo yang terbit pada 1996, Alberth menitipkan Frans kepada adik perempuannya. Sebab, Alberth kehilangan istrinya, Alberthina, yang meninggal saat Frans belum genap berumur 2 tahun. Bagi anggota suku Biak Numfor, perempuan punya peran kunci dalam keluarga. Anak laki-laki baru disapih dari ibunya untuk menjalani upacara inisiasi sebagai pria pada usia 12 tahun.
Bersama keluarga tantenya, Frans mempelajari tata upacara adat, religi, serta mitologi yang hidup di tengah masyarakat Biak Numfor. Dia juga berlatih tarian perang dan menggunakan senjata tradisional, di antaranya panah, tombak, serta perisai.

Frans Kaisiepo (kedua dari kiri) saat berada di Malaysia, Maret 1977. Dok Keluarga
Menurut Victor, bapaknya selalu antusias pergi ke sekolah, meski perjalanan ke sana harus ditempuh dengan menyeberangi sungai. “Semangatnya untuk belajar sangat tinggi,” ujarnya.
Setelah lulus dari sekolah rakyat, Frans pergi ke vervolgschool atau sekolah lanjutan di Kampung Korido, Kecamatan Supiori—sekitar 70 kilometer di sisi barat laut Wardo. Korido terkenal sebagai pusat pendidikan pada era pemerintahan Hindia Belanda. Frans, pada 1934, lulus dari vervolgschool dan masuk ke sekolah pendidikan guru di Kampung Miei—kini masuk wilayah Kabupaten Manokwari, Papua Barat.
Sekolah guru di Miei punya sejarah penting bagi Papua. Dikelola Nederlandsch Zendeling Genootschap—organisasi penginjilan yang berpusat di Rotterdam, Belanda, sekolah guru Miei merupakan lembaga pendidikan pertama yang khusus menerima anak-anak Papua. Sekolah ini didirikan pada 1925.
Setelah menamatkan sekolah guru, pada 1936, Frans mudik ke kampung halamannya di Wardo. Di sana dia menjadi guru pembantu sekaligus penginjil. Dia berkhotbah ke rumah-rumah anggota jemaat di kampung. “Para guru menjadi penginjil setelah mengajar di kelas,” tutur Samuel Manggaprouw, menantu Frans. Samuel kawin dengan Susana Kaisiepo—anak kedua Frans dari istri pertamanya, Anthomina Arwam.
Tingkat pendidikan yang lebih tinggi justru membawa Frans masuk ke dunia politik. Mendekati Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Frans mengikuti sekolah bestuur, institusi pendidikan kepamongan pencetak pegawai pemerintahan yang memberikan layanan administrasi kependudukan. Berlokasi di Kota Nica, sekolah bestuur didirikan pemerintah Hindia Belanda.
Sejarawan Universitas Cenderawasih, Albert Rumbekwan, menyebutkan Frans adalah generasi pertama pemuda Papua yang mengenyam pendidikan di sekolah bestuur. Pemerintah Hinda Belanda waktu itu memilih orang Belanda menjadi pamong praja di wilayah Papua. "Pamong dari orang asli Papua baru diberi kesempatan setelah 1945,” ujar Albert.
Di sekolah inilah Frans bertemu dengan tokoh pergerakan Papua lain seperti Silas Papare, Marthen Indey, dan Corinus Marselus Krey. Frans juga berjumpa dengan Soegoro Atmoprasodjo, bekas tahanan politik di Boven Digoel—sekarang masuk Provinsi Papua Selatan. Soegoro menanamkan pengetahuan politik kepada siswa sekolah bestuur.
Pengaruh Soegoro terhadap aktivitas politik pemuda Papua diakui Frans dalam risalah berjudul “Catatan Mengenai Irian Barat” yang ditulis pada 1 Oktober 1962. Catatan itu kini tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia. Frans menulis bahwa Soegoro membangun kesadaran untuk mendidik anak-anak Papua. “Supaya mereka menjadi pemimpin dan penggembala Irian,” tulis Frans.
Frans jadi sering berinteraksi dengan warga setempat karena berstatus pegawai pamong praja. Dia memanfaatkan kesempatan itu untuk mempengaruhi masyarakat lokal agar Nederlands Nieuw-Guinea—nama awal Papua—bergabung dengan pemerintahan Republik Indonesia. Frans menyampaikan pesan itu ketika berkeliling kampung, dari Warsa sampai Biak Utara.
Dolfina Kaisiepo, 79 tahun, mengatakan rumah Frans di Warsa selalu dipenuhi kerabat dan masyarakat yang beranjangsana. Salah satunya keluarga Dolfina yang kerap mampir ke sana. Menurut Dolfina, Frans punya panggilan akrab dari warga Warsa karena saking lamanya berdinas di wilayah itu. “Panggilannya Papa Warsa,” kata istri bekas Bupati Biak Numfor, Amandus Mansenmbra, ini.
Gara-gara tekun menyebarkan pesan persatuan, Frans ditugasi pemerintah Hindia Belanda ke Kampung Kokonao, Kabupaten Mimika. Kokonao adalah kampung terpencil yang hanya bisa diakses dengan perahu. Sekretaris Jenderal Presidium Dewan Papua Mohammad Thaha Alhamid mengatakan penugasan Frans ke Kokonao merupakan hukuman dari pemerintah kolonial.
Menurut Thaha, pamong praja yang ditempatkan di daerah terpencil adalah pegawai yang dicap sebagai pemberontak. “Mereka dikeluarkan dari basis pengaruhnya, lalu disebar ke pedalaman," tutur Thaha.
Tinggal jauh di pedalaman, aktivitas politik Frans tak terhentikan. Dia makin aktif mengajar dengan menjadi guru dan penginjil di Kokonao. Dia bahkan kerap membawa keluarga dalam aktivitasnya. "Kakek tak hanya mengajar, tapi juga menampung orang yang kesulitan," ucap Frans Ajani Wanma, cucu Frans.
Paulus Rey, warga Kokonao, menyebut Frans Kaisiepo meninggalkan kesan mendalam bagi warga lokal. Masyarakat senang ada pemuda Papua yang bisa menjadi pamong untuk Kampung Kokonao. Selain itu, Frans tak hanya menjalankan tugas pemerintahan, tapi juga berkenan mengajar dan menyebarkan ajaran Injil. “Pamong sebelum Frans selalu orang luar Papua atau orang Belanda,” kata Paulus, 67 tahun.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul "Anak Pandhe Musuh Kompeni"