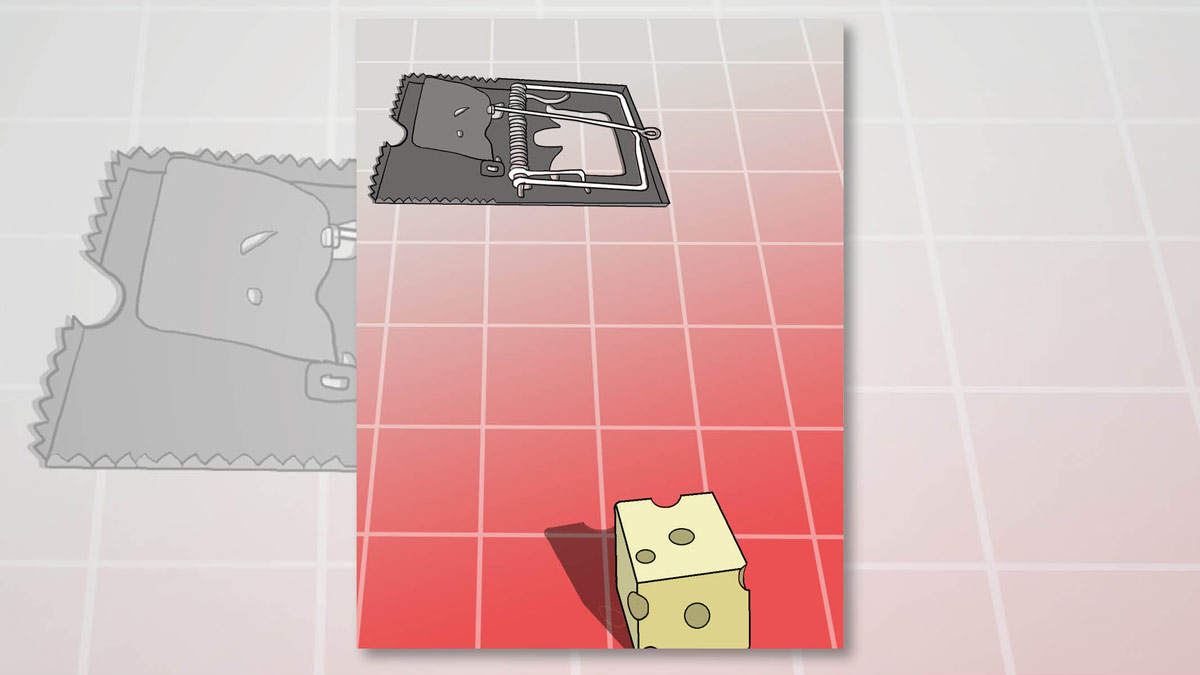Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Mengapa korupsi di Indonesia susah diberantas?
Mengapa demokrasi tak membawa tata pemerintahan yang baik.
Suatu analisis terhadap korupsi sistemik di Indonesia.
MENGAPA korupsi nyaris tak mungkin diberantas di Indonesia? Mengapa para pejabat di Indonesia dengan mudah membangun tatanan kelembagaan yang longgar, berintegritas rendah, nepotis, dan gemuk dengan konflik kepentingan? Mengapa demokrasi tidak mendorong tata pemerintahan yang baik, malah atas nama dan melalui infrastruktur serta peristiwa-peristiwa demokrasi (partai, pemilihan umum) korupsi justru merajalela?
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kita bisa menambah daftar pertanyaan lebih panjang mengapa korupsi begitu mudah terjadi di Indonesia. Menurut saya, itu karena ada elemen kuasi-ideologis yang relatif kuat dan bertahan dalam tradisi politik Indonesia yang bersifat “korupsiogenik”.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dalam kuliah pengukuhan guru besarnya pada 11 November 2021, ahli politik dari Belanda, Ward Berenschot, mengemukakan apa yang ia sebut jebakan informalitas (the informality trap) sebagai “logika” dasar praktik kebijakan di negara seperti Indonesia. Informalitas adalah hubungan antara warga negara, dunia bisnis, dan negara yang ditandai dengan kuatnya koneksi personal, yang didayagunakan untuk menjadi alat pemengaruh implementasi kebijakan negara.
Informalitas merentang dari praktik politik terbawah, seperti pemilihan kepala daerah, hingga pembuatan kebijakan di level atas. Ia mengakar pada relasi klientelistik yang mengandalkan kelenturan transaksional antara elite dan pemilih, satu politikus dengan politikus lain, hingga melampaui aturan-aturan hukum. Informalitas dan klientelisme juga ditandai longgarnya komitmen etis elite dengan partai dan sesama politikus. Dengan kata lain, bukan prosedur, institusi, apalagi aturan yang menjadi jantung kinerja demokrasi kita, melainkan jalinan koneksi informal klientelistik yang hidup dan merebak di dalam institusi-institusi itu.
Yang menjadi pertanyaan, dari mana akar informalitas klientelistik ini tumbuh? Dalam studi bersama Edward Aspinall (Democracy for Sale, 2019) Berenschot mengungkap karakter yang khas dari klientelisme yang merentang dari satu rezim ke rezim berikutnya dalam sejarah Indonesia. Namun mereka tidak menjawab pertanyaan mengapa informalitas selalu mengungguli prosedur dan menekuk cita-cita pemerintahan yang baik di Indonesia.
Untuk menjawab persoalan ini, kita perlu meminjam pandangan Nadia Urbinati mengenai populisme dalam Democracy Disfigured (2014). Menurut dia, sistem demokrasi perwakilan yang baik dicirikan oleh keseimbangan antara will dan opinion. Will adalah keseluruhan instansi demokrasi yang menaungi hak, regulasi, institusi pemungutan suara, serta pelbagai mekanisme keputusan otoritatif. Sedangkan opini adalah domain politik ekstra-institusional tempat warga negara saling mempengaruhi. Menurut Urbinati, demokrasi representatif yang sehat mengukuhkan pentingnya will dan opinion sambil tetap mempertahankan pemisahan atas keduanya.
Populisme, kata Urbinati, adalah suatu keadaan tatkala aspek prosedural dalam demokrasi ditekan dan dihancurkan oleh mobilisasi opini dan elemen-elemen ekstra-institusional. Benar bahwa demokrasi tidak bisa hanya terdiri atas institusi, prosedur, mekanisme, dan hak. Ia juga mesti diisi kompetisi gagasan serta partisipasi yang terbuka, luas, otonom, dan spontan. Namun prosedur perlu dijaga sebagai kerangka dasar demokrasi representatif yang kuat. Pengakuan terhadap yang formal hanya mungkin apabila pemisahan yang rigid antara yang prosedural dan nonprosedural diakui secara kuat.
Ciri umum populisme adalah mobilisasi propagandis pelbagai kelompok sosial sebagai kekuatan ekstra-institusional politik. Dengan begitu, populisme selalu diarahkan untuk membatalkan dan merusak yang formal atas nama “kehendak dan pendapat” rakyat. Populisme menjadikan opini publik sebagai permainan yang digerakkan untuk mentransformasi politik ke dalam proses vertikalisasi. Di sini politikus populis mengklaim membawa politik kepada rakyat dan membawa rakyat kepada politik. Dengan cara seperti itu populisme merusak dan mengaburkan batas-batas yang formal dan yang informal, yang prosedural dan nonprosedural.
Dari sononya, populisme adalah kuasi-ideologi yang mendasari politik sejak Indonesia mengukuhkan diri sebagai republik merdeka. Kuatnya populisme dan informalitas vis-à-vis tata pemerintahan yang baik (good governance) berakar panjang dalam tradisi politik di Indonesia.
Pembedaan yang dibuat Herbert Feith (1930-2001) mengenai Sukarno yang bertipe “solidarity maker” dan Hatta yang lebih merupakan administrator ulung boleh dibilang sebagai bentuk eufemistik untuk menyembunyikan kontradiksi populisme vis-à-vis proseduralisme atau “informalisme vis-à-vis good governance”.
Feith juga mengistilahkan rezim Orde Lama sebagai rezim populisme otoritarian, sementara Orde Baru adalah rezim populisme pembangunan. Dari sini kita bisa paham bahwa populisme telah meresap ke dalam sari pati politik Indonesia dari dulu hingga kini. Dengan kata lain, populisme dan informalitas mendapatkan basis dan sumber justifikasinya dalam bangunan sosio-antropologi dari diskursus nasionalisme Indonesia.
Di Indonesia, konsep warga negara sebagai citizen tidak pernah memiliki akar filosofis yang memadai, kalah oleh konsepsi umat dan rakyat. Umat merupakan konsep antropologi politik aktif yang digerakkan oleh agama, sementara konsep rakyat yang khas Indonesia dihidupi oleh sentimen nasionalis-populis yang dipakai dan diakui sebagai subyek politik oleh semua kelompok politik sekuler di Indonesia.
Tarikan populisme dalam konsep rakyat membuat ia dengan mudah ditekuk ke luar dari pemaknaan demokratisnya, dan dengan gampang dimanipulasi oleh kaum populis. Populisme mengambil untung dari opini publik, dan tak jarang kaumnya menangguk kesetiaan dari rakyat melebihi kesetiaan kepada demokrasi.
Dari sini jelas bahwa populisme, informalitas-klientelisme dan korupsi, memiliki denominator yang sama: ketiganya berbasis pada penghapusan etika publik yang menekankan batas-batas yang publik dan yang privat. Ketiganya membuka jalan bagi invasi yang privat ke dalam semua lembaga politik, mentransformasi pranata politik formal menjadi ruang kongko elite mengakumulasi kekayaan.
Indonesia kontemporer adalah Indonesia-nya para populis. Polarisasi politik warisan pemilihan presiden 2019 adalah polarisasi dua populis yang sama-sama mengklaim monopoli autentik atas bangsa dan karena itu merasa berhak berada di urutan pertama perolehan sumber daya pembangunan.
Prinsip-prinsip dasar populisme bertolak belakang dengan prinsip dasar demokrasi dan konstitusionalisme. Demokrasi perwakilan memposisikan rakyat sebagai pemilik kebijaksanaan, sementara populisme memposisikan rakyat sebagai agen mobilisasi. Demokrasi memposisikan rakyat sebagai semacam hakim yang mengambil putusan dalam rasionalitas dan deliberatif, sementara populisme memposisikan rakyat sebagai “kami” yang diintegrasikan secara hegemonik ke dalam personifikasi pemimpin. Dalam demokrasi, lembaga-lembaga publik disterilkan sebisa mungkin dari intervensi kepentingan dan bias ideologi, sementara di dalam populisme kepentingan dan ideologisasi adalah mekanisme dasar untuk mengintegrasikan orang dan tatanan.
Dengan itu, tak mengherankan populisme tidak menghitung dan menaruh penghargaan terhadap etika personal seperti kejujuran dan integritas. Populisme berupaya menotalkan semua ruang dalam politik. Ia mengukuhkan peleburan rakyat dengan personalisasi pemimpin di atas yang formal dan yang publik. Lenyapnya batas-batas etis antara yang publik dan yang privat secara paradoksal memperluas informalitas di dalam pusat-pusat pembuatan kebijakan. Korupsi inheren di dalam semua rezim populis.
Reformasi Indonesia didorong oleh penolakan atas korupsi-kolusi-nepotisme. Dengan itu sebenarnya demokrasi dimulai secara harmonis dengan ideal good republic and good governance. Hal-hal yang ideal ini sekarang rontok. Sentimen purba para populis dengan mudah merayap dan merusak demokrasi serta institusi-institusi Republik. Kelak Indonesia memerlukan satu jenis reformasi lagi: reformasi republikan untuk membebaskan demokrasi dari penaklukan kaum populis.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo