Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
SEJARAH puisi Indonesia tergolong sangat dinamis dengan kebaruan-kebaruan yang muncul dengan cepat. Karena itu, periodisasi sastra Indonesia pun berusia pendek. Konon setiap sekitar dua puluh tahun sudah terbentuk babak baru. Jarak angkatan Poedjangga Baroe yang dikatakan romantik dengan angkatan 45 yang dibilang ekspresif hanya sekitar 12 tahun.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Begitu juga jarak angkatan 45 dengan angkatan yang disebut Ajip Rosidi sebagai angkatan baru yang bersifat kedaerahan dengan puisi balada sebagai model atau kanonnya, yaitu angkatan 50. Begitulah seterusnya, berturut-turut muncul babak-babak baru, dari yang dinamakan angkatan 66, angkatan 70, angkatan 80, angkatan 90, hingga angkatan 2000. Belum lagi perdebatan yang muncul dalam setiap periode, seperti perdebatan yang disebut oleh Aoh Kartahadimadja sebagai paham-paham angkatan 45, polemik antara realisme sosialis dan Manifes Kebudayaan, angkatan 70, serta pertentangan paham yang berpusat di majalah Horison dan Taman Ismail Marzuki dengan puisi mbeling yang berbasis di majalah Aktuil. Akhir-akhir ini bahkan muncul gagasan yang juga polemik mengenai puisi siber, digital, atau elektronik yang berbasis di Internet.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bila diperhatikan secara komprehensif, sejarah sastra Indonesia yang dinamikanya cepat tidak bisa dilepaskan dari perkembangan dalam sejarah sastra, katakanlah, dunia. Kecepatan perubahan dalam sastra Indonesia itu bukan tidak mungkin berhubungan dengan keterlambatan kelahiran sastra Indonesia itu sendiri. Pada saat awal pertumbuhannya, sastra Indonesia sudah berhadapan dengan begitu banyaknya paham yang muncul dalam sejarah sastra dunia. Karena itu, apabila perkembangan sastra dunia bergerak secara sekuensial, berurutan mengikuti waktu, perkembangan sastra Indonesia lebih cenderung spasial, simultan, dengan berbagai paham yang sudah ada dan bersaing. Dalam batas tertentu, kondisi sastra Indonesia yang demikian tidak juga dapat dilepaskan dari kondisi pascakolonialnya. Sejak awal, sastra Indonesia, yang dengan demikian modern, menjadikan sastra Barat sebagai kanonnya. Karena itu, perubahan yang terjadi dalam sastra Barat, termasuk penyangkalannya terhadap diri sendiri dan akomodasinya terhadap sastra lokal, berpengaruh langsung terhadap sastra Indonesia.
Namun, seperti yang antara lain dikemukakan oleh Rene Wellek dan Austin Warren, teori dan sejarah sastra yang bersifat general adalah satu hal, kritik sastra yang berurusan dengan karya-karya sastra yang partikular adalah hal lain. Dalam hal ini, sastra Indonesia pun penuh dengan perburuan akan munculnya karya-karya sastra yang memperlihatkan kebaruan, yang dapat membuat masyarakat, setidaknya masyarakat sastra Indonesia, menemukan cara baru dalam memandang, memahami, dan menjelaskan kehidupan, dunia, dan sekaligus cara baru dalam mengungkapkan atau bahkan membentuknya. Di samping berbagai media massa cetak, digital, dan penerbit, berkembang pesat pula kegiatan lomba dan pemberian penghargaan terhadap karya-karya sastra yang dianggap memenuhi kebutuhan tersebut. Di antaranya kegiatan Buku Pilihan Tempo yang diselenggarakan setiap tahun ini. Pilihan Tempo atas buku kumpulan puisi terbaik 2022 adalah Dua Marga karya Nirwan Dewanto.

Nirwan Dewanto, di Palmerah, Jakarta, 31 Desember 2022. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Tentu saja pilihan tersebut diambil dengan pertimbangan yang relatif, yaitu terbatas pada perbandingannya dengan buku-buku puisi yang terbit pada waktu yang bersangkutan. Sebagian besar buku puisi yang ada cenderung semacam penulisan kembali tradisi lokal atau primordial yang sudah ada sebelumnya, baik yang berupa mitos-mitos, paham-paham keagamaan, ataupun adat-istiadat setempat. Dengan demikian, buku-buku puisi itu tampaknya sudah meninggalkan konsep penciptaan modern, khususnya romantik, yang menganggap puisi sebagai karya yang sepenuhnya orisinal, asli, dan lahir dari ketiadaan atau kekosongan, seperti alam semesta dalam penciptaan Tuhan. Dan, sebagaimana halnya Tuhan yang mencipta dalam kesendirian, penyair pun mencipta hanya dalam hubungan dirinya dengan obyek ciptaannya, mencipta dalam suasana yang sepenuhnya reflektif atau kontemplatif. Puisi-puisi 2022, sebagaimana yang terlihat dalam buku-buku yang dinilai, cenderung tidak mengingkari keberadaan karya-karya yang terdahulu, bahkan tidak khawatir menjadi reproduktif. Reproduksi bukanlah suatu cela dalam penciptaan karena hasilnya tidak sama persis dengan yang direproduksi. Penciptaan puisi tidak berlangsung dalam suasana kontemplatif, melainkan dialogis.
Dilihat dari judulnya saja, Dua Marga sudah memperlihatkan kecenderungan yang demikian. Kata marga sudah membawa asosiasi pembaca kepada kesan mengenai komunitas etnis atau lokalitas yang sudah ada sebelumnya. Dari subjudul dua bab yang menjadi bagian isinya, yaitu “Samudana: Sajak-sajak Halima Puti Djamhari” dan “Alinggana: Sajak-sajak Nyoman Hambulu Adwaita”, kumpulan puisi tersebut mempertegas kesan sifat reproduktif dirinya, posisinya sebagai penuturan kembali puisi-puisi orang lain yang terkesan berasal dari masa lalu yang mungkin jauh seperti yang terlihat dari penggunaan ejaan lama pada nama yang pertama, “Djamhuri”. Dua nama itu sendiri menunjukkan tidak hanya dua asal etnik, melainkan juga dua paham keagamaan dan gender yang yang berbeda. Yang pertama terkesan seperti nama Melayu, Islam, dan perempuan, sedangkan yang kedua Bali, Hindu, dan laki-laki. Dengan demikian, di dalam ruang yang sama, sampai di sini, kita menemukan empat kategori subyek yang terjalin dalam hubungan dialogis.
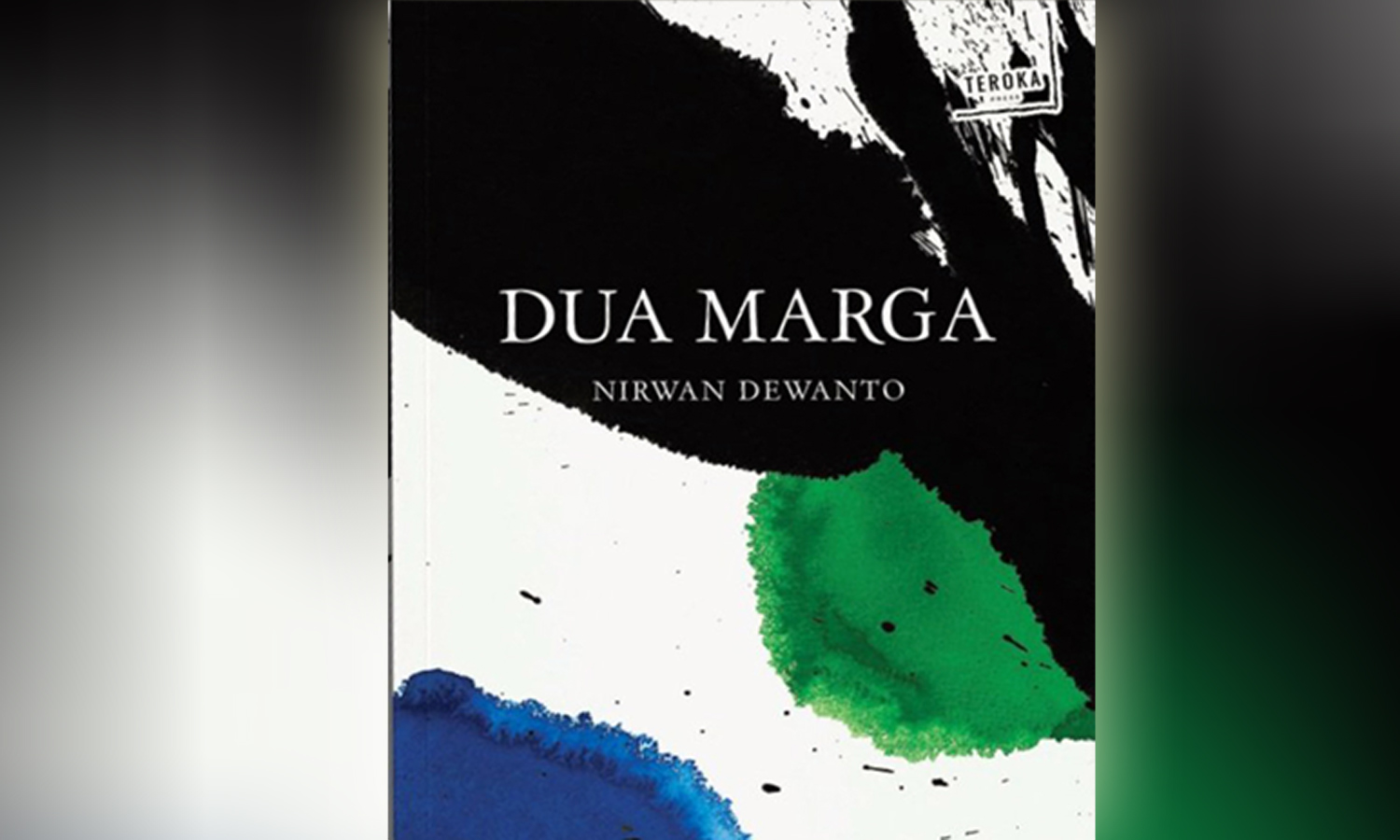
Buku puisi Dua Marga Nirwan Dewanto
Dalam puisi-puisinya sendiri yang segera tampak adalah dua gender berbeda yang pada umumnya terlibat dalam hubungan cinta dan erotik, tapi sekaligus bergerak melampauinya dan tetap terikat padanya. Sejajar dengan kecenderungan yang kuat pada gambaran mengenai hubungan ketubuhan yang bisa dikatakan mendekati pornografi, “film biru”, puisi-puisi dalam kumpulan ini juga memperlihatkan pilihan kata yang sangat cermat yang terarah pada citra-citra kekayaan kehidupan flora dan fauna serta yang bersifat visual. Kombinasinya sering kali mengejutkan dan memberi tenaga pada kata dan citraan. Berbeda dengan puisi-puisi lain yang cenderung panjang dan naratif, puisi dalam kumpulan ini memperlihatkan kepadatan liris yang modernis, tapi tanpa terperangkap pada lirisisme yang memusat. Memang, terasa pengaruh perkembangan sastra dunia di dalamnya, misalnya Oktavio Paz, tapi subyek yang kemudian ini pun merupakan bagian dari partner dialog dalam hubungan dengan puisi ini. Sebuah cinta lama yang terus hidup menggelora, mungkin karena tak pernah sampai.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo




























