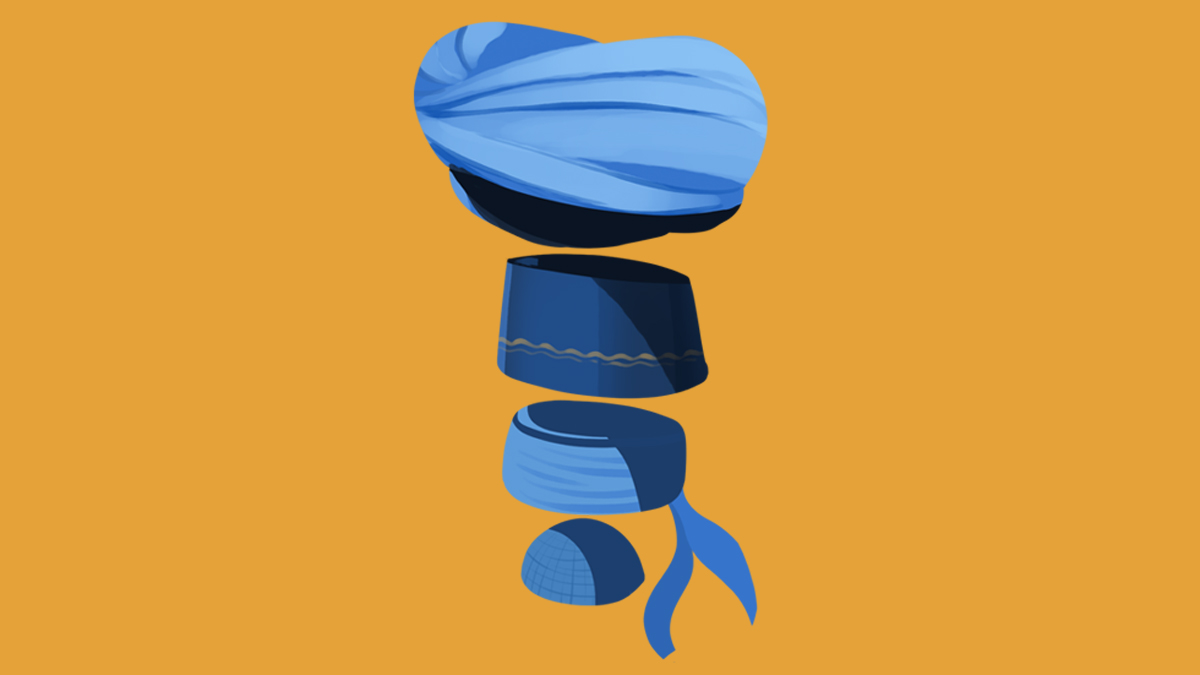Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
KEMUNCULAN habib yang memiliki banyak pengikut, meski tindak tanduknya tercela, dalam beberapa tahun belakangan menuai respons dari sejumlah kalangan. Pada 2022, seorang ulama Banten, Kiai Haji Imaduddin Utsman, yang geram melihat fenomena itu menerbitkan buku yang menyimpulkan nasab para habib tidak tersambung ke Nabi Muhammad.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Beberapa tahun sebelumnya, cendekiawan Muhammadiyah, Buya Syafi’i Maarif, mengatakan mendewa-dewakan keturunan Nabi merupakan bentuk perbudakan spiritual. Media sosial juga ramai membincangkan persoalan itu. Ada pro dan kontra. Keprihatinan terhadap maraknya feodalisme agama dan perbudakan spiritual juga disuarakan oleh majalah Tempo melalui liputan khusus pada edisi 8-14 April 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dalam editorial liputan khusus Lebaran itu, Tempo mengaitkan pemujaan terhadap mereka yang dianggap sebagai habib dengan otokritik Mochtar Lubis tentang karakter masyarakat kita dalam Manusia Indonesia (1977), yaitu berjiwa lemah dan berwatak feodal. Opini itu menilai sebagian masyarakat menerima doktrin begitu saja, menganggap mereka yang menyandang gelar habib memiliki kedudukan sosial atau derajat lebih mulia. Sikap itu yang menjelaskan alasan para habib tersebut memiliki banyak pengikut meskipun tindak tanduknya tercela dan bahkan bertentangan dengan hukum positif.
Di tengah riuh rendah percakapan publik mengenai persoalan itu, kita bisa menemukan sejumlah kerumpangan yang layak diungkap agar kita dapat melihat masalah secara lebih jernih dan terhindar dari kesalahan penyimpulan yang berpotensi melukai perasaan kelompok etnis tertentu, bahkan tradisi keagamaan, yang bisa merusak kebangsaan.
Pertama, dalam seluruh perbincangan itu sama sekali tidak diungkap jumlah habib yang mendapat privilese. Padahal ini penting untuk membedakan antara citraan dan persepsi yang ada di benak kita serta realitas tentang fenomena itu. Faktanya, selama ini kita melihat hanya beberapa gelintir habib yang “memiliki banyak pengikut meskipun tindak tanduknya tercela dan bahkan bertentangan dengan hukum positif” itu. Ada puluhan atau mungkin ratusan habib yang memiliki banyak pengikut tapi tindak tanduknya baik. Lalu ada ratusan ribu lain yang tidak mempunyai pengikut sama sekali, dan sama dengan keturunan-keturunan lain, mereka ada yang baik, ada yang tercela, bahkan melanggar hukum positif.
Yang disebut terakhir itu adalah para habib yang hidup dan bekerja di tengah-tengah masyarakat, dengan beragam tingkat ekonomi dan pendidikan, juga bermacam pekerjaan serta profesi, yang sama sekali tidak berhubungan dengan kedudukan sosial atau derajat mulia. Jadi hanya ada sedikit sekali habib yang “sukses mendapatkan privilese”. Maka patut dipertanyakan apa yang menjadi dasar pemikiran yang menempatkan habib secara umum sebagai pangkal persoalan perbudakan spiritual.
Kedua, dengan merenungi kata-kata Buya Syafi’i Maarif soal perbudakan spiritual dan editorial Tempo bahwa fanatisme terhadap keturunan Nabi patut dikritik lantaran melestarikan sifat rendah diri dan mengingkari kodrat manusia yang terlahir setara, kita akan menemukan kerumpangan berikutnya: rasa-rasanya, mendewa-dewakan apa saja dan keturunan siapa saja merupakan perbudakan spiritual.
Mendewa-dewakan adalah menganggap sesuatu sebagai dewa, atau dengan kata lain menuhankan. Perbuatan seperti itu adalah bentuk kemusyrikan. Mengapa hanya fanatisme terhadap “keturunan” Nabi yang patut dikritik? Bukankah semua sikap fanatik—terhadap apa pun dan keturunan siapa pun—adalah buruk? Jika fanatisme terhadap “keturunan” Nabi patut dikritik, orang bisa juga berpikir bahwa fanatisme terhadap “keturunan” lain, misalnya para kiai dan gus (yang selama ini pada dasarnya sama seperti habib, yaitu diyakini dan meyakini sebagai “keturunan” Nabi dari jalur Wali Sanga) tentu patut dikritik pula.
Maka persoalannya terletak pada “fanatisme” dan perbuatan “mendewa-dewakan” apa saja dan keturunan siapa saja, bukan hanya keturunan Nabi. Ihwal batasan mana yang tergolong fanatisme dan mendewa-dewakan dan mana yang tidak, setiap orang bisa berdebat panjang. Semua itu tergantung pemikiran, ideologi, tradisi, dan keyakinan teologi masing-masing.
Contohnya, bagi seorang muslim modernis, budaya santri yang berjalan merangkak di hadapan kiai atau gus dan menciumi tangannya mungkin akan dipandang sebagai sikap fanatik dan mendewa-dewakan. Sebaliknya, oleh kalangan tradisionalis, hal itu dianggap wajar sebagai bentuk penghormatan dan tabaruk kepada ulama panutannya. Begitu pula kebiasaan menziarahi makam para habib, kiai, dan gus yang dikeramatkan.
Di titik ini, banyak pihak yang gagal memetakan dan memahami persoalan. Akibatnya, kompleksitas relasi otoritas keagamaan yang terbentuk melalui proses interaksi yang panjang dan mentradisi, yaitu hubungan sukarela berdimensi spiritual dan sosial antara umat dan pemimpin komunitas agama, baik itu habib, kiai, gus, maupun para wali, direduksi menjadi perbudakan spiritual belaka.
Fakta sosial adanya kesamaan pola relasi antara habib panutan dan jemaahnya dan kiai atau gus panutan dan jemaahnya juga terabaikan. Sesungguhnya figur yang dianggap sebagai representasi ahli waris kenabian itu sama-sama merawat mata rantai nasab mereka, baik sebagai “keturunan” Nabi melalui trah habib maupun “keturunan” Nabi dari trah Wali Sanga.
Perlu digarisbawahi, umat yang mendatangi majelis taklim, mengalap berkah, menghormati, mencium tangan para habib, kiai, dan gus panutan itu, tidak hadir sebagai orang-orang pasif yang tereksploitasi oleh nasab mereka, melainkan termotivasi oleh kesadaran pemikiran, dan secara sukarela terangkai dalam sebuah jemaah. Jemaah ini dibangun dan dibina melalui kerja artikulasi (articulatory labor); praktik mengaitkan masyarakat dengan sejarah kenabian (riwayat, hadis, dan sunah) yang dilakukan secara berkesinambungan oleh para tokoh agama itu—terlepas dari baik atau buruk, kita setuju atau tidak.
Para pemuka agama itu dengan tekun memberikan layanan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat sehingga terbentuk ikatan jemaah yang terhubung dengan masa lalu kenabian (prophetic past). Bentuknya bisa berbeda-beda antara otoritas agama yang satu dan yang lain. Profesor Ismail Fajrie Alatas menelaah secara detail relasi otoritas agama ini dalam bukunya, What Is Religious Authority? Cultivating Islamic Communities in Indonesia (Princeton University Press, 2021).
Jadi tidak serta-merta orang yang terlahir dengan “nasab emas” seperti yang dimiliki habib, kiai, dan gus itu akan otoritatif. Tanpa kerja pembangunan dan pembinaan, para “bangsawan keagamaan” itu akan sama dengan “orang biasa” yang tak punya pengikut dan tak memiliki status sosial tinggi atau derajat mulia.
Kita tahu Mbah Benu dari Gunungkidul yang mengaku memperoleh informasi langsung dari Allah tentang Idul Fitri lima hari lebih awal dari mayoritas umat Islam memiliki banyak pengikut. Meski bukan dari trah habib, kiai, atau gus, ia memiliki kedudukan sosial tinggi dan derajat mulia di daerahnya. Semua itu ia raih berkat kerja membangun dan membina jemaah selama bertahun-tahun. Begitu pula ustad-ustad kondang yang tak memiliki trah habib ataupun gus seperti Aa Gym, Adi Hidayat, dan Syafiq Basalamah.
Becermin pada kenyataan itu, kita bisa melihat bahwa nasab habib, kiai, dan gus bukanlah faktor yang esensial. Keberhasilan menjadi tokoh umat yang otoritatif, yang memiliki banyak pengikut, memperoleh kedudukan sosial tinggi dan kemuliaan derajat, ditentukan oleh banyak hal, terutama konsistensi dalam membangun dan merawat jemaah.
Sebagaimana bisa tercipta dari apa pun dan oleh siapa pun, fanatisme dan pendewa-dewaan juga bisa muncul dari jemaah yang dibangun dan dirawat sedemikian rupa itu, termasuk yang dikerjakan oleh kalangan habib, kiai, dan gus yang kebetulan terlahir sebagai “bangsawan keagamaan”. Namun menghakimi nasab mereka sebagai faktor terbentuknya feodalisme agama dan perbudakan spiritual itu—terlebih jika hanya habib yang dijadikan sebagai “pesakitan”—saya kira merupakan sebentuk penyederhanaan masalah.
Penyederhanaan masalah dan pilih-pilih pihak yang didudukkan di kursi terdakwa akan menghasilkan kesimpulan yang rumpang dan tak berimbang.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo