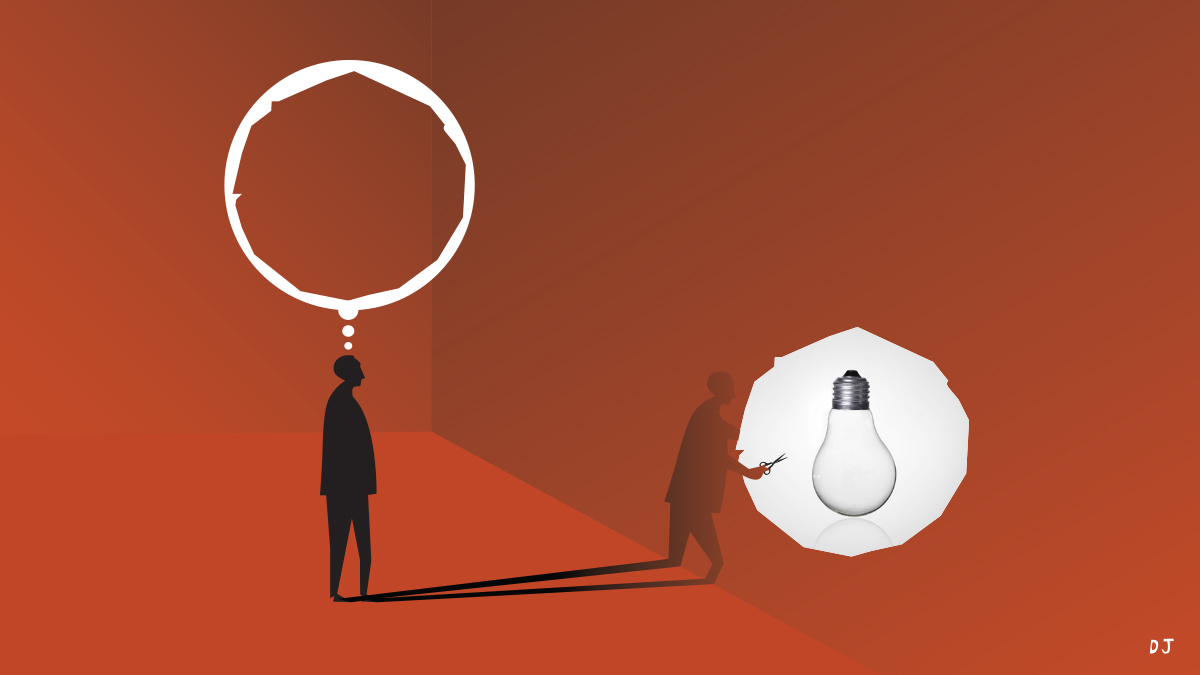Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Rohman Budijanto*
Bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia banyak bersimpang jalan, meski berakar dari bahasa puak Melayu. Berbagai reaksi mewarnai pergeseran makna dalam satu kata yang sama-sama digunakan oleh kedua bahasa. Persis seperti yang digambarkan Saudara Ahmad Sahidah dalam ulasannya tentang jarak makna antara bahasa Indonesia dan Malaysia ("Menemukan Kata Bersama", Tempo, 9-15 September 2013).
Tak jarang jarak makna ini memang jungkir-balik. Simak contoh kabar di Berita Harian, Malaysia, edisi 25 Juni lalu, berjudul "Presiden Indonesia Minta Maaf", tentang asap (jerebu) akibat kebakaran hutan yang mengotori udara jiran.
"Pada sidang media itu, Presiden Indonesia turut menyindir beberapa pegawai kerajaan republik itu yang menyebut nama syarikat perladangan yang dipercayai menyebabkan kebakaran, yang tidak seharusnya mereka lakukan." Beberapa diksi terasa ganjil di telinga kita karena, meski satu rumpun, bahasa Malaysia tetap bahasa asing. Cermati khusus kata kerajaan republik di kalimat tidak langsung tentang berita jumpa pers (sidang media) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.
Malaysia lazim menyebut "kerajaan Republik Indonesia" untuk negara kita. Bukan hanya bahasa media, bahasa resmi pun begitu. Dalam dokumen tahun 1970 ada judul seperti ini: "Perjanjian Persahabatan antara Kerajaan Malaysia dan Kerajaan Republik Indonesia". Uniknya, sebelum Malaysia merdeka dari Inggris, perjanjian serupa pada 1959 disebut "Perjanjian Persahabatan antara Persekutuan Tanah Melayu dengan Republik Indonesia" (Johan Saravanamuttu, 2010).
Rupanya, Malaysia tak menganggap diri memiliki "kerajaan" sebelum merdeka, padahal dipimpin raja-raja kecil. Anehnya, setelah merdeka, lahirlah sebutan "Kerajaan Malaysia" dan Malaysia seakan-akan mengajak semua negara di dunia, baik republik maupun persemakmuran, jadi kerajaan.
Jika Indonesia disebut "kerajaan" oleh Malaysia, lalu siapa gerangan rajanya? Jelas tak ada. Bung Karno, meski pernah dijunjung dengan sebutan Paduka Jang Mulia (PJM) dan diangkat Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara (MPRS) sebagai presiden seumur hidup, tentu saja bukan raja. Kerajaan dalam bahasa Malaysia tersebut memang sebagai kata ganti pemerintah.
Istilah kerajaan itu seakan-akan terlepas dari kata dasarnya, raja. Yang diambil hanya spiritnya, yakni kekuasaan atau penguasa. Terasa lucu atau ganjil bagi kita pengistilahan ala Malaysia itu, karena kita yang mengenal kerajaan sebagai bentuk pemerintahan yang biasanya dipimpin raja disandingkan dengan republik, pemerintahan yang umumnya dipimpin presiden.
Bila dipikir agak kritis, istilah pemerintah yang kita pakai bisa terasa ganjil juga. Ini juga agak terlepas dari kata dasarnya, perintah. Kita sangat jarang mendengar sikap yang dikeluarkan pemerintah sebagai perintah (paling-paling Surat Perintah 11 Maret yang dikeluarkan dalam keadaan kepepet itu). Maklumat pemerintah kita berbentuk keputusan dan peraturan. Penguasa yang benar-benar rutin mengeluarkan perintah malah tak disebut pemerintah, melainkan komandan atau kepala (di dunia kemiliteran atau kepolisian, misalnya).
Bukan hanya Malaysia, Indonesia juga memberi julukan kepada negara lain dengan istilah yang bisa membuat kita sendiri bekernyit dahi. Dalam dunia diplomasi, kita tak hanya menjalin hubungan dengan negara republik, kerajaan, atau persemakmuran, tapi juga dengan keharyapatihan. Sebutan agak teatrikal dan Indonesia banget ini disematkan pada Liechtenstein dan Luksemburg, negara mini di jantung Eropa.
Istilah keharyapatihan untuk Liechtenstein ini merupakan penafsiran dari sebutan principality (Inggris) dan Fürstentum (Jerman). Liechtenstein, seluas 160 kilometer persegi dengan 35 ribu penduduk, adalah negara monarki berdaulat, tapi mengurus kepentingan luar negerinya dengan menitip pada Swiss. Karena itulah Kedutaan Besar Republik Indonesia di Konfederasi Swiss dirangkapkan dengan Keharyapatihan Liechtenstein (kini dijabat Duta Besar Djoko Susilo).
Kalau dilihat dari istilah principality, tafsir yang lebih mendekati sebenarnya adalah kepangeranan, wilayah yang dipimpin prince (pangeran), seperti Monako dan Andorra. Memang di dalam khazanah kita dikenal harya patih atau patih agung. Yang paling terkenal adalah Harya Patih Gajah Mada (historis) dan Harya Patih Sangkuni (imajiner). Tapi harya patih tak punya kedaulatan. Seagung-agungnya patih, dia adalah pembantu raja, semacam perdana menteri. Bahkan para pangeran kerap punya kekuasaan lebih besar.
Negara lain yang dijuluki keharyapatihan adalah Luksemburg (Inggris: grand duchy; Prancis: grand-duché; Jerman: Großherzogtum; Luksemburg: Groussherzogtum). Meskipun status asli Luksemburg berbeda dengan Liechtenstein, Indonesia resmi menyebutnya sama-sama keharyapatihan. Padahal akar katanya, duchy, lebih dekat ke kadipaten, yaitu wilayah besar (seperti provinsi) yang dipimpin duke atau adipati. Tapi memang lebih terasa seperti pertunjukan ketoprak kalau Luksemburg dijuluki kadipaten agung.
Sebagai bahan pemikiran, akan lebih aman jika baik Luksemburg maupun Liechtenstein (juga Monako dan Andorra) disebut saja kerajaan. Toh, pemimpinnya tetap seperti raja, turun-temurun di negara berdaulat. Seperti kita menerima julukan raja Malaysia, yakni Yang Dipertuan Agung. Bukankah kita tak perlu menyebut ke-yang-dipertuan-agung-an untuk Malaysia? Kita tetap menyebut Kerajaan Malaysia, meski penangkapan atas istilah kerajaan itu bisa berbeda di Malaysia.
Bahasa memang penuh tikungan tafsir yang mengejutkan. Lebih dari itu semua, apa pun julukannya, yang terpenting dari berbahasa adalah efektivitas komunikasi.
*) Wartawan Jawa Pos
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo