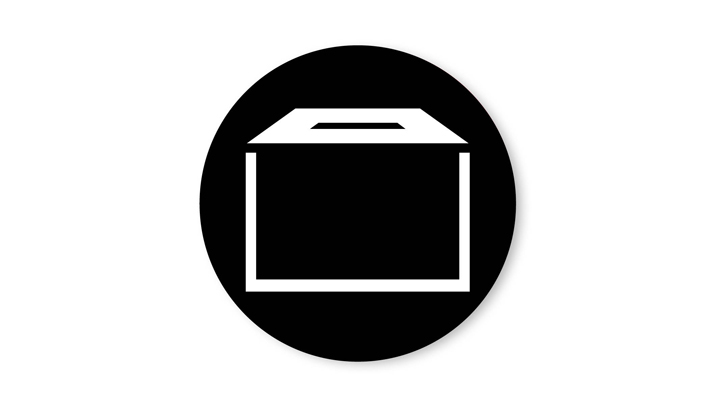Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
JIka jadi diselenggarakan, pemilihan kepala daerah tahun ini boleh jadi akan menjadi pilkada berdarah dalam sejarah Republik.
Kecemasan ini beralasan karena pilkada berlangsung pada saat pandemi Covid-19 mengganas.
Alih-alih mampu mengendalikan, pemerintah dan siapa saja saat ini sedang kalang-kabut.
PEMILIHAN kepala daerah 9 Desember tahun ini boleh jadi akan menjadi pilkada berdarah. Di tengah pandemi Covid-19 yang terus mengganas, pesta demokrasi itu mudah berubah menjadi pesta penularan virus.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pegiat survei politik Muhammad Qudori memperkirakan ada 1,04 juta kerumunan sepanjang pilkada serentak di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota di Indonesia. Banyaknya jumlah kerumunan didasari 1.468 calon kepala daerah yang bakal bertarung. Asumsinya, setiap calon berkampanye di minimal 10 titik per hari, selama 71 hari masa kampanye, sejak 26 September hingga 5 Desember mendatang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dengan asumsi itu, setidaknya akan ada 50,2 juta orang yang terlibat. Dengan 3,8 persen tingkat kematian akibat corona di Indonesia, diperkirakan 1,76 juta orang akan meninggal. Berlebihan? Potonglah asumsi itu hingga 50 persen, angkanya akan tetap mengerikan.
Komisi Pemilihan Umum memang telah mengeluarkan peraturan baru untuk memastikan pilkada aman. Dalam aturan KPU sebelumnya, kampanye tatap muka boleh diikuti maksimal 100 orang, sedangkan kini hanya boleh diikuti separuhnya. Peraturan KPU juga melarang penyelenggaraan rapat umum, konser musik, pertunjukan seni, jalan dan sepeda santai, perlombaan, serta aneka kegiatan sosial yang memungkinkan terjadinya pengumpulan orang.
Di lapangan, tak ada jaminan peraturan dipatuhi. Di Tegal, Jawa Tengah, sebuah konser dangdut digelar dan penyelenggaranya tidak diberi sanksi. Ketua KPU Arief Budiman dan sejumlah komisioner terinfeksi Covid-19 jauh sebelum hari pencoblosan. Sejumlah calon kepala daerah juga positif, bahkan ada yang meninggal.
Menutup mata dan telinga, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan pilkada jalan terus. Setidaknya ada tiga alasan yang diajukan: ketidakjelasan kapan pandemi berakhir, efek ekonomi pilkada, dan argumentasi pilkada sebagai hak konstitusional warga.
Benar belaka: tak ada yang tahu kapan pandemi berakhir. Tapi penundaan pilkada bisa disesuaikan dengan penurunan grafik pandemi. Artinya, lewat kajian epidemiologis, pilkada dapat diselenggarakan jika keadaan dianggap aman. Namun, untuk itu, pemerintah harus mendasarkan penanganan pandemi pada fakta dan ilmu pengetahuan—bukan mengambil langkah serampangan sambil menunggu vaksin. Tak menunda pilkada karena tak jelas kapan pandemi berakhir juga terkesan dibuat-buat karena belakangan Kementerian Dalam Negeri menunda pemilihan kepala desa dengan dalih wabah yang mengganas.
Menggunakan alasan ekonomi untuk meneruskan pilkada jelas tak bertanggung jawab. Memang betul ada uang berputar dalam pilkada. Tapi itu sementara: roda ekonomi tak pernah benar-benar berjalan jika pandemi tak dapat dikendalikan.
Meneruskan pilkada untuk menjamin hak konstitusional warga negara sepintas terdengar logis. Tapi, hendaknya diingat, kesehatan juga merupakan hak konstitusi orang banyak. Memberikan hak konstitusi politik tapi melupakan hak kesehatan merupakan kejahatan besar.
Pemerintah dan DPR harus menunda pilkada. Ancaman kematian orang ramai tak boleh diabaikan demi dahaga kekuasaan segelintir orang. Jika berlanjut, giliran publik yang mesti mengambil tindakan: ketimbang mati sia-sia, lebih baik tidak memilih dan menolak terlibat dalam setiap tahap pilkada.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo