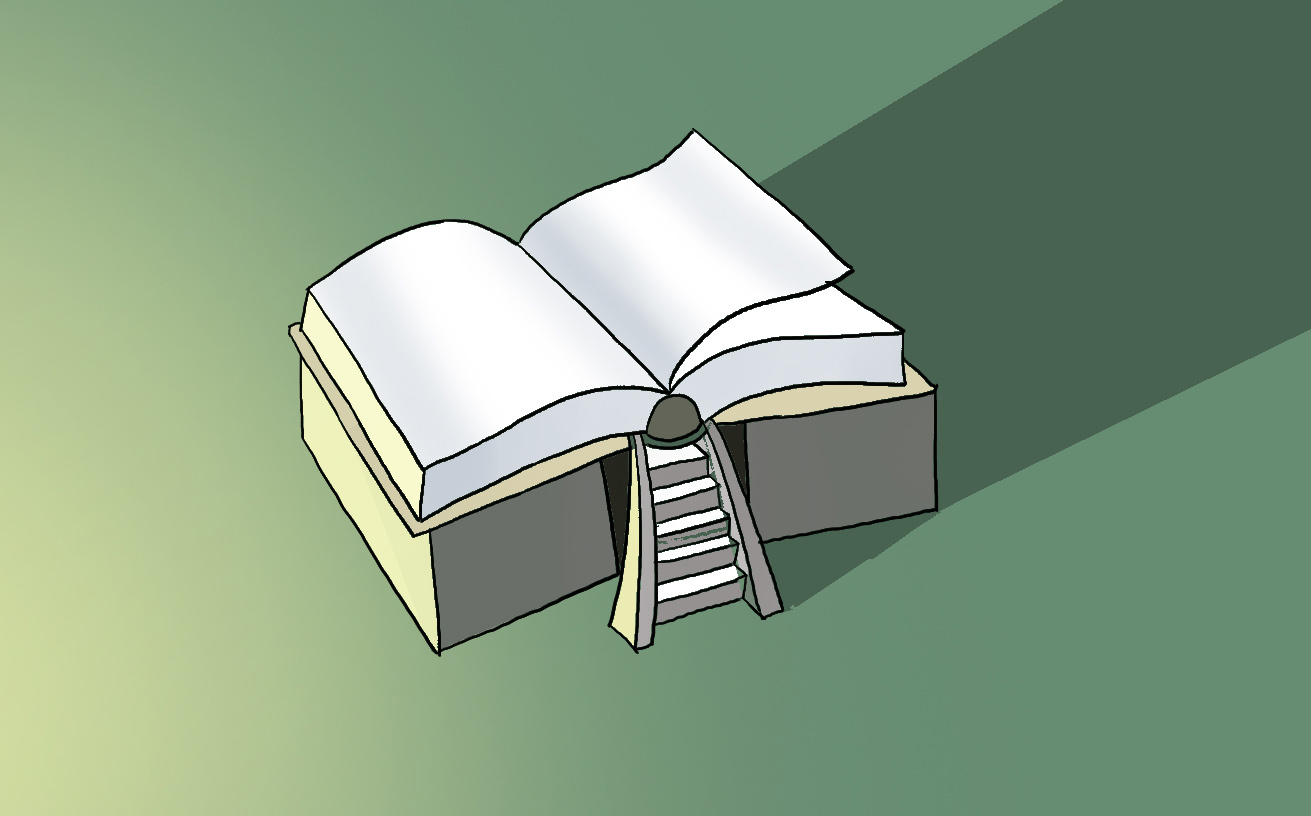Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
DPR mengesahkan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang.
Cipta Kerja didominasi pendekatan ekonomi yang mengeksploitasi sumber daya alam.
Mengabaikan tujuan kesejahteraan dan pelindungan bagi yang lemah.
Eko Cahyono
Peneliti Sajogyo Institute dan Papua Study Center serta Mahasiswa Doktoral Sosiologi Pedesaan IPB University
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang pada 21 Maret 2023. Undang-Undang Cipta Kerja lama dan Perpu Cipta Kerja dikritik serta ditolak oleh sebagian besar jaringan gerakan sosial di hampir seluruh Indonesia. Meskipun demikian, regulasi itu tetap saja bisa diloloskan dan disahkan DPR. Bisa dibayangkan bagaimana dengan peraturan dan perundang-undangan lain yang sepi kritik dan penolakan masyarakat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sejak peraturan itu disahkan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja, tampaknya semakin penting untuk merefleksikan pendulum kebijakan pembangunan nasional. Setidaknya ada dua pertanyaan dasar. Pertama, mandat konstitusional berbangsa dan bernegara yang bagaimana yang menjadi landasannya? Kedua, tujuan akhir pembangunan nasional itu untuk apa dan melayani kelompok "rakyat" yang mana?
Merujuk pada legasi para pendiri bangsa, misalnya pandangan Moh. Hatta dkk, dalam buku Penjabaran Pasal 33 UUD 1945 (1977) dijelaskan bahwa sendi utama politik pembangunan Indonesia adalah demokrasi ekonomi berbasis semangat "sosialisme-kerakyatan". Demokrasi ini didasarkan pada kebersamaan dan asas kekeluargaan, sedangkan demokrasi Barat didasari asas perorangan. Demokrasi Indonesia didasarkan pada konsensus atau kesepakatan yang disebut “Vertrag”, sedangkan demokrasi Barat didasari kontrak sosial (social contract).
Ayat 4 Pasal 33 UUD 1945 menjelaskan bahwa tujuan demokrasi ekonomi tidak harus sepenuhnya diartikan sebagai prinsip "perlakuan setara" secara mutlak. Sebab, cita-cita akhirnya adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (keadilan sosial, fairness, equity, equality) sehingga menyandang pemihakan (parsialisme, special favour) terhadap yang lemah, miskin, dan terbelakang untuk mendapat perhatian serta perlakuan khusus ke arah pemberdayaan. Parsialisme terhadap yang tertinggal ini bukanlah sikap diskriminatif, apalagi yang berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), melainkan bermakna positif pada doktrin kebersamaan dalam asas kekeluargaan.
Penjelasan Pasal 33 tersebut, menurut Hatta, akan berimplikasi pada model pembangunan ekonomi nasional yang harus dilaksanakan dengan dua cara. Pertama, pembangunan yang besar dikerjakan oleh pemerintah atau dipercayakan kepada badan hukum tertentu di bawah penguasaan atau penguasaan pemerintah. Pedomannya adalah mencapai "sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".
Kedua, pembangunan yang kecil-kecil dan sedang dikerjakan rakyat melalui koperasi. Koperasi dapat berkembang berangsur-angsur, dari kecil dan sedang menjadi besar, dari pertukangan atau kerajinan menjadi industri.
Lalu, apa yang dimaksud dengan "cabang-cabang penting bagi negara"? Ini adalah cabang-cabang produksi strategis. Adapun "dikuasai" diinterpretasikan bahwa dikuasai oleh negara tapi tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan, atau ondernemer. “Dikuasai” mengandung arti bahwa kekuasaan negara terdapat dalam membuat peraturan guna melancarkan perekonomian, peraturan yang melarang pengisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal (Kusuma, 2009). Artinya, tidak boleh terjadi pemihakan yang menimbulkan hubungan majikan-buruh sebagaimana terjadi dalam cultuurstelsel. Hal inilah yang menjadi dasar pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945, yang menegaskan bahwa demokrasi yang dikehendaki adalah permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politiek-economische democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial.
Merujuk pada jantung "cita-cita" awal pembangunan nasional di atas, penolakan gerakan masyarakat sipil terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (lama) dan bentuk barunya sekarang tetaplah sama, tepat di titik "ruh dasar"-nya, yakni pengingkaran dan pengkhianatan terhadap cita-cita awal tujuan demokrasi ekonomi berdasarkan asas kerakyatan.
Undang-undang itu berbasis model ekonomi-politik yang berwatak kapitalistis-neoliberal. Akibatnya, sumber-sumber ekonomi vital negara, baik pertambangan, kehutanan, perkebunan, kelautan, maupun sumber-sumber agraria lainnya, lewat regulasi itu, mendapat lapak (baru) dan karpet merah untuk diperjual-belikan seluas-luasnya kepada pihak swasta melalui sirkuit kapital-pasar global atas nama investasi.
Sulit diterima akal sehat bahwa para pengusaha dan korporasi yang mau berinvestasi di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan mendapat secara gratis pajak dan hak guna usaha (HGU) di atas hak penggunaan lahan (HPL) IKN hingga dua siklus, dengan masing-masing 95 tahun atau total 190 tahun. Ini jauh melebihi politik perizinan agraria di era kolonial sekalipun. Undang-Undang Agraria Kolonial (Agrarische Wet 1870) saja hanya memberikan hak konsesi perkebunan kepada investor atau perkebunan kolonial paling lama 75 tahun.
Jika kembali pada semangat dasar cita-cita demokrasi ekonomi berjiwa sosialisme kerakyatan itu, jelas tujuan akhir kebijakan pembangunan harus ditegaskan untuk mencegah kembalinya praktik ekonomi kolonial yang membolehkan pengisapan manusia lemah oleh mereka yang bermodal serta memastikan "penguasaan negara" dalam seluruh produksi regulasi dan kebijakannya untuk diabdikan demi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan jelas mengingkari tujuan ini. Promosi dan undangan investasi lebih kuat pesannya untuk membuka "lapak dagang" dan menutup mata terhadap beragam ketimpangan struktural agraria (penguasaan, kepemilikan, distribusi, akses, dan pemanfaatan) dari sumber-sumber agraria nasional.
Laporan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada 2019 menyatakan 1 persen orang kaya di Indonesia menguasai 50 persen aset nasional. Akibatnya, Undang-Undang Cipta Kerja semakin kuat memberi legitimasi dan pelanggengan bagi kuasa kelompok oligarki dan korporasi yang selama ini menikmati kue terbesar kekayaan alam Indonesia.
Guru besar politik agraria, Endriatmo Soetarto, dalam pidato purnabaktinya pada 19 Maret 2023, menyebutkan akar masalah sengkarut agraria nasional sekarang bersumber dari salah asuh negara yang ahistoris menjalankan konsep "berbangsa-bernegara" dan justru semakin menjauh dari tujuan konstitusionalnya. Geliat lahirnya perjuangan masyarakat adat, menurut dia, bukan semata sebagai respons atas keterbukaan "keran demokrasi", tapi juga penanda penting koreksi salah asuh negara dalam mengurus hak rakyat atas tanah airnya sendiri. Maka, mengasuh bangsa dan negara pada hakikatnya terletak pada pendekatan kesejahteraan yang dilengkapi pendekatan kultural yang memihak (afirmatif) kepada kelompok lapis sosial terlemah di perdesaan, termasuk masyarakat adat dan kaum marginal lain.
Pandemi Covid-19 sebenarnya memberi pelajaran penting tentang "kegagalan" model-model paradigma kebijakan pembangunan global, terutama kebijakan pembangunan berwatak pertumbuhan (growth), kapitalistis, dan antroposentris. Kebijakan itu tidak hanya berdampak pada beragam krisis ekosistem yang jelas kini diwariskannya, tapi juga minus nilai-nilai intrinsik sekaligus abadi dari tujuan hidup manusia, yakni kebahagiaan.
Indikator makroekonomi berbasis produk domestik bruto (PDB) dan ukuran ekonomi sejenis dengan doktrin "angka yang mahakuasa" lainnya telah dianggap gagal. Joseph E. Stiglitz dkk dalam buku Mengukur Kesejahteraan: Mengapa Produk Domestik Bruto Bukan Tolak Ukur yang Tepat untuk Menilai Kemajuan? (2011) menegaskan bahwa indikator PDB telah gagal memenuhi janji kesejahteraannya karena mengabaikan dimensi kualitas hidup, perasaan sejahtera, dan pengukuran "keberlanjutan masa depan" di tengah ancaman krisis sosial-ekologis kontemporer.
Maka, tak boleh lagi ada "penyeragaman dan ukuran tunggal indikator" kesejahteraan suatu negara. Sebaliknya, diperlukan ukuran-ukuran kesejahteraan yang plural dan kontekstual dengan kondisi historis-empiris suatu negara.
Gagasan inilah yang memicu lahirnya beragam alternatif ukuran kesejahteraan di banyak negara. Bhutan, misalnya, menggunakan indeks kebahagiaan nasional bruto (GNH) yang merujuk pada analisis ekstensif Indeks GNH (Karma Ura, 2012). Pengukuran GNH ini mencakup sembilan aspek dan terdiri atas 33 indikator yang diambil dari 124 variabel. Kesembilan aspek tersebut adalah kesejahteraan psikologis, kesehatan, penggunaan waktu, pendidikan, keragaman budaya, tata kelola yang baik (good governance), vitalitas masyarakat, keragaman ekologi, dan standar hidup.
Undang-Undang Cipta Kerja yang sejak awal menyemai lahan subur investasi jelas masih dominan dengan nalar kapitalisme yang berwatak mengeruk serta mengkomodifikasi sumber-sumber agraria nasional demi memenuhi indeks agregat makroekonomi pertumbuhan dan pelipatgandaan keuntungan. Hal itu tak hanya akan melanjutkan salah asuh politik kebijakan pembangunan dan agraria nasional, tapi juga akan makin menjauhkan tujuan kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan bagi rakyat Indonesia.
PENGUMUMAN
Redaksi menerima tulisan opini dari luar dengan syarat: panjang sekitar 5.000 karakter (termasuk spasi) atau 600 kata dan tidak sedang dikirim ke media lain. Kirim tulisan Anda ke email pendapat@tempo.co.id disertai dengan foto profil, nomor kontak, dan CV ringkas.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo