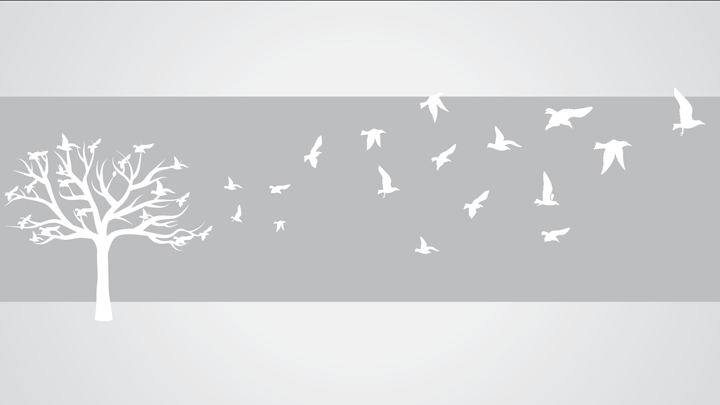Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam rapat kabinet terbatas pada 26 Februari 2019, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kementerian yang terkait dengan urusan pertanahan segera melakukan perbaikan data guna mempercepat reforma agraria di kawasan hutan. Menurut Presiden, tujuan penataan dipercepat itu agar masyarakat hukum adat mendapat manfaat dari hutan di sekitar mereka.
Imbauan Presiden ini harus disambut dan ditindaklanjuti tidak hanya oleh kementerian. Sebab, meski sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012, perkembangan pengakuan hak masyarakat adat atas hutan di tingkat lapangan sangat minim. Hal ini terjadi karena adanya sesat pikir dalam kebijakan pengakuan hak masyarakat adat, termasuk putusan hakim konstitusi itu.
Sesat pikir itu kemudian berkembang ke dalam tiga persoalan akut yang harus segera diatasi. Jika tidak, niat pengakuan hak masyarakat adat itu hanya akan terus menjadi lip service. Apalagi ada janji Presiden dalam Nawacita terkait dengan masyarakat adat ini. Jangan sampai janji itu berlalu sebagaimana janji pemerintah terdahulu.
Silang-sengkarut
Meski merujuk pada Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, kriteria pengakuan ada-tidaknya masyarakat adat dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 dan Nomor 10 Tahun 2012 tidak sama. Ketidaksinkronan yang sama terjadi dalam kebijakan tentang pengelolaan hutan.
Misalnya, Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 67 ayat 3 dengan tegas menyatakan bahwa, “Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan peraturan pemerintah.” Namun, setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012, yang muncul adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2015 jo Peraturan Direktur Jenderal P.1/PSKL/SET/KUM.1/2/2016.
Perbedaan antarkebijakan akan terlihat makin lebar jika mencermati mekanisme/proses verifikasi dan validasi—berikut produk hukum yang diperlukan—untuk menetapkan keberadaan masyarakat adat tertentu itu. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 adalah satu-satunya instrumen yang bertujuan khusus menetapkan keberadaan suatu masyarakat adat. Namun kriteria, mekanisme, dan produk hukum hasil akhir proses yang digunakan dalam peraturan ini berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 dan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.
Hasil akhir peraturan Menteri Dalam Negeri ini pun tidak sesuai dengan Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 cq. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2015, Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 2016, dan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017. Padahal dalam tiap kebijakan itu tidak diatur mekanisme pengakuan terhadap masyarakat adat. Di sana hanya disebutkan “… sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Langkah mundur
Sekilas, Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 2016 terlihat seperti keluar dari pakem kerja lama. Aturan itu telah digunakan untuk memberikan sertifikat hak milik bersama kepada desa pakraman. Ini dimungkinkan dengan adanya Keputusan Menteri Agraria Nomor 276/Kep 19.2/X/2017 tentang Penunjukan Desa Pakraman di Provinsi Bali sebagai subyek hak kepemilikan bersama (komunal) atas tanah.
Sebagaimana yang terungkap dalam suatu semiloka yang diselenggarakan di Balige, akhir Juli tahun lalu, yang antara lain melibatkan Badan Pertanahan Nasional, pembicara dari lembaga itu secara tegas menolak mengurus kasus-kasus konflik tanah adat yang berada di kawasan hutan.
Logika hukum Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 jauh lebih progresif ketimbang logika hukum yang diperkenalkan oleh Undang-Undang Kehutanan. Pasal 5 ayat 2 menyebutkan, “Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi dan, apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah.”
Artinya, tidak ada klausul yang menyatakan bahwa ada proses penetapan keberadaan masyarakat adat yang bersangkutan. Namun, dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi itu, logika hukum bidang agraria pun berubah. Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 2016 lebih merujuk pada kriteria yang digunakan dalam putusan Mahkamah dan Undang-Undang Kehutanan.
Realitas sosio-antropologis
Setidaknya ada tiga masalah sosio-antropologis dalam menerapkan berbagai kebijakan tentang pengakuan hak masyarakat adat. Masalah pertama adalah persoalan kuantitas. Jenis tanah ulayat sangat beragam. Selain itu, tidak tersedia mekanisme yang berbeda untuk mengakomodasi realitas perbedaan hak ulayat yang bersifat publik dan yang bersifat privat.
Dalam masyarakat Minangkabau, misalnya, ada ulayat (tanah adat) kaum, ulayat suku/buek, atau ulayat nagari. Dua jenis pertama bersifat privat, sedangkan ulayat nagari bersifat publik. Tiap tanah ulayat itu memiliki organisasi pengurusnya sendiri-sendiri (Warman, 2010). Di Sentani, Jayapura, ada hierarki suku, kampung, ondofolo, dan khoselo (Karuwai, 2004). Bahkan ada yang mengatakan unit terkecilnya adalah tanah keluarga (akona). Dua unit yang disebut pertama bersifat publik, sedangkan selebihnya bersifat privat. Sesuai dengan kebijakan yang ada, unit mana yang butuh diatur dalam peraturan daerah?
Masalah kedua menyangkut kapasitas subyek hak untuk masuk ke proses-proses politik untuk menghasilkan produk peraturan hukum daerah yang disyaratkan. Seperti yang terjadi dalam masyarakat Batak Toba (Sjahrir-Pandjaitan & Zakaria, 2017), susunan masyarakat adat yang memiliki kecakapan urusan publik semacam bius dan huta relatif telah memudar jika tidak dikatakan telah hilang.
Kecuali pada beberapa masyarakat adat yang bisa dikategorikan sebagai masyarakat traibal, atau oleh pemerintah disebut Komunitas Adat Terpencil, dalam konteks kelompok etnis dalam ukuran yang besar, susunan masyarakat adat yang memiliki kecakapan pengaturan publik ini mungkin hanya tersisa di beberapa daerah. Di samping di Minangkabau dan Bali (Windia, 2018), masih ada di Maluku (Matuankotta, 2018) dan Papua (Karuwai, 2004 dan Hammar, 2011). Dalam kelompok etnis besar lain umumnya sudah memudar atau hilang sama sekali.
Lebih dari itu, dalam masyarakat Batak Toba, sudah sejak awal penguasaan tanah berada dalam susunan masyarakat adat yang mendasarkan pada hubungan darah (marga) yang cakupannya sebatas keluarga luas, bukan terletak pada susunan masyarakat adat yang berkecakapan publik. Hal yang sama terjadi di Sentani, Jayapura (Karuwai, 2004). Bisa dibayangkan apa yang terjadi jika unit sosial ini dipaksa terlibat dalam proses penyusunan produk hukum daerah yang akan mengatur mereka.
Masalah kapasitas akan terasa makin terbatas jika dikaitkan dengan biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk hukum daerah itu. Menurut pengamatan saya, serangkaian kegiatan untuk menghasilkan produk hukum daerah itu dibutuhkan waktu enam bulan hingga dua tahun. Konon, biaya yang dibutuhkan untuk melahirkan suatu peraturan daerah tentang penetapan hutan adat tersebut berkisar Rp 200 juta-2 miliar.
Hambatan ketiga menyangkut persoalan kualitas. Akumulasi pengetahuan aparat pemerintahan di tingkat daerah tentang subyek dan obyek tanah/hutan adat relatif terbatas, bahkan buta sama sekali. Dari puluhan peraturan daerah yang telah dihasilkan, hanya sedikit yang memuat rincian subyek dan obyek hak masyarakat adat dengan nama lokalnya. Akibatnya, upaya, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit itu menjadi tidak operasional ketika diterapkan.
Butuh peraturan pengganti undang-undang
Dalam situasi silang-sengkarut kebijakan itu, juga karena Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat tidak kunjung ditetapkan, saatnya Presiden mengambil tindakan. Tindakan itu bisa dengan menghapus biang kerok permasalahan ini, yakni Pasal 67 Undang-Undang Kehutanan yang khusus mengatur hak-hak masyarakat adat terhadap hutan di sekitarnya.
Konon, penyebab permohonan Aliansi Masyarakat Adat Nasional dan dua komunitas pendukung untuk mencabut pasal ini ditolak Mahkamah Konstitusi adalah lembaga konstitusi tertinggi itu tidak mau terjadi kekosongan hukum. Di sinilah letak penting lahirnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) yang mengatur pengakuan hak masyarakat adat. Tentu perpu harus sekaligus berisi pengaturan lebih lanjut yang lebih bersahabat dengan kapasitas masyarakat adat.
Toh,peraturan pengganti undang-undang dalam ranah pengelolaan hutan bukan barang baru. Pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri juga pernah terjadi. Jika untuk kepentingan investasi perpu dimungkinkan, mengapa tidak untuk kepentingan masyarakat adat?
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo